“Al-Quran punya zahir, batin, batas dan tempat naik,” demikian diriwayatkan Kanjeng Nabi saw bersabda. Berdasarkan hadis ini, para sufi menafsir al-Quran dengan cara yang khas. Dan sebagaimana aspek lain dari tasawuf, tafsir sufi seringkali dianggap menyimpang dari syariat. Pertanyaannya, bagaimana tafsir sufi bisa dinilai valid secara syariat atau eksoterik? Melalui buku ini, Darmawan mencoba menjawabnya.
Darmawan memilih kitab Ta’wīlat Al Kasyani sebagai fokus penyelidikan. Dalam Bab I, Darmawan berulang kali menegaskan bahwa buku ini hendak mencoba (1) membangun metode takwil al-Kasyani dan (2) membuktikan bahwa metode tersebut selogis dan sevalid tafsir eksoterik (9, 14-15, 18).
Dalam Bab II, Darmawan berupaya menelusuri perkembangan takwil sufi, validitasnya, dan fondasinya. Dengan “takwil sufi”, dia memaksudkan “interpretasi esoteris al-Qur’an yang dilakukan oleh kaum sufi” (32). Dia berkesimpulan bahwa Al Kasyani yang pertama membedakan takwil dan tafsir: tafsir untuk penjelasan eksoterik pada umumnya; takwil khusus untuk penjelasan sufi secara esoteris (47). Darmawan tidak menampik sudah ada sufi sebelum al-Kasyani yang menulis komentar terhadap al-Qur’an, tetapi menurutnya itu bercorak ‘tasawuf ‘amali’ atau tasawuf Sunni (46).
Asumsi esoteris Darmawan itu tampaknya bertentangan dengan observasi James W. Morris dalam “Ibn ‘Arabi and His Interpreters, Part II” (1987: 102). Morris mencatat bahwa karya al-Kasyani itu bukanlah takwil dalam arti sufi yang melibatkan kesadaran langsung akan implikasi spiritual ayat-ayat al-Qur’an. Sebaliknya, kitab itu, lanjut Morris, adalah penerapan suatu sistem metafisika yang koheren terhadap al-Quran, metafisika yang berisikan unsur-unsur dari ajaran Ibn ‘Arabi dan Ibn Sina. Memang, Darmawan menyinggung sekilas, tanpa identifikasi dan analisis lebih jauh, bahwa al-Kasyani menggunakan bahasa atau istilah filsafat dalam takwilnya. Tetapi, jika Morris benar, maka ada setidaknya dua pilihan: menunjukkan bahwa aspek Sinaian itu ‘hanya sebatas bahasa’, atau merevisi asumsi bahwa takwil Al Kasyani adalah murni sufi.
Baca Juga: Dua Dimensi Makna Wali Menurut Imam Al-Qusyairiy
Mengenai fondasi takwil sufi, Darmawan membaginya ke dalam fondasi kebahasaan, epistemologis dan ontologis. Yang terpenting bagi saya sekarang adalah dua fondasi pertama. Darmawan menekankan ciri simbolik bahasa sufi, ciri yang hanya bisa dipahami oleh si pendengar sesuai dengan maqam rohaninya. Itu artinya, pembaca atau pendengar perlu menjalani pula suluk rohani sebagaimana si sufi, kalau mau memahaminya (71). Sementara itu, yang terpenting dari fondasi epistemologis tampaknya adalah teori rūḥ al-maʻnā (“roh makna”), yang menurut Darmawan embrionya berasal dari al-Ghazali (94), sedangkan istilahnya berasal dari Mulla Sadra.
Sampai di sini, saya mau memberikan beberapa catatan. Pertama, jika bahasa sufi hanya bisa dipahami oleh seseorang sesuai dengan tahap rohaninya, maka ini akan jadi pertanyaan besar: apa yang kajian akademis bisa lakukan terhadapnya? Atau malah apa status kajian akademik tentang tasawuf pada umumnya?
Kedua, konsep rūḥ al-maʻnā, menurut saya, memang bisa menjadi kunci yang efektif untuk membaca takwil sufi, walau masih banyak aspek epistemologisnya yang perlu digali lebih jauh. Yang terpenting barangkali adalah bagaimana “roh makna” al-Quran diketahui. Menurut Darmawan, “roh makna” diperoleh melalui “abstraksi makna (tajrīd al-maʻānī) dari unsur-unsur tambahan yang terdapat dari konsep tersebut”, yang kemudian dia jelaskan sebagai perujukan pada “kamus-kamus bahasa induk untuk menarik sebuah makna kata yang paling asli” (95).
Saya meragukan apakah perujukan kamus itu adalah langkah yang al-Ghazali atau Sadra anjurkan untuk menggapai “roh makna”. Dalam Jawāhir al-Qur’ān, Al-Ghazali cenderung mengidentifikasi “makna rohani” (maʻnan rūḥāniyyan) itu dengan esensi (ḥaqīqah) atau definisi (ḥadd) sesuatu—istilah-istilah yang juga al-Ghazali pakai dalam bagian mantik al-Mustaṣfā. Jadi, al-Ghazali tidak berbicara tentang roh makna suatu kata, melainkan tentang makna rohani dari alam atau kenyataan inderawi (Jawāhir, 51).
Ketiga, Darmawan tidak menjelaskan apa kaitan teori rūḥ al-maʻnā dengan fondasi kebahasaan yang coba direkonstruksi sebelumnya, tidak pula dengan ciri simbolik bahasa sufi. Tidak diterangkan, misalnya, apa kaitan metode rūḥ al-maʻnā yang, menurut Darmawan, leksikal itu dengan mekanisme haqīqī-majāzī (“denotasi-konotasi”). Agaknya Darmawan berasumsi bahwa mekanisme haqīqī-majāzī adalah (salah satu) mekanisme kebahasaan yang sah menurut para pendukung tafsir eksoterik, sehingga jika bisa ditunjukkan bahwa takwil sufi-esoterik juga bekerja dengan mekanisme tersebut, maka takwil ini harus diakui juga validitasnya. Menariknya, rūḥ al-maʻnā bagi Mulla Sadra bukanlah aplikasi istiʻārah atau majas (Mafātīh al-Ghayb, ed. Khajawi, 89.7-8), melainkan semacam abstraksi logis yang diperoleh melalui ‘penyingkapan’ (mukāsyafah) (ibid, 92.3-8).
Selanjutnya, dalam Bab III, Darmawan mendiskusikan, salah satunya, apa yang dia sebut “paradigma takwil sufi al-Kasyani”. Sayangnya, dia tidak menjelaskan dalam arti apa ia menggunakan istilah ‘paradigma’ di sini. Barangkali dengan ‘paradigma’ Darmawan memaksudkan dasar-dasar epistemologis al-Kasyani dalam takwilnya. Akan tetapi, tidak jelas bagaimana paradigma ini berkaitan dengan fondasi takwil sufi yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.
Dalam bab IV, Darmawan secara khusus mengambil beberapa topik ini dari takwil al-Kasyani untuk dianalisis: kafir, air, khamr, Nabi Ayyub, imra’ah Firʻaun. Pendekatan yang digunakan ialah teori rūḥ al-maʻnā yang telah disinggung itu Dalam praktiknya, Darmawan senantiasa menggunakan konsep istiʻārah dan konsep ‘relasi logis’ sebagai pisau analisis paling inti (181). Ini, sekali lagi, menunjukkan dengan terang bahwa dengan teori rūḥ al-maʻnā itu Darmawan memaksudkan pendekatan kebahasaan atau kesusastraan.
Masih dalam bab yang sama, Darmawan menyebutkan beberapa hal yang dia anggap sebagai kelemahan al-Kasyani. Al Kasyani, sebagai contoh, menakwil ayat “… dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu” (Q.S. al-Rahman [55]:19) sebagai lautan jisim dan lautan roh yang bertemu dalam wujud manusia. Tanpa percobaan analisis sebagaimana sebelumnya, Darmawan menilai bahwa takwil ini tidak mengandung kesesuaian dan relasi logis, dan bahwa al-Kasyani dalam hal ini jatuh pada subjektivisme dirinya sebagai penganut Wahdatul Wujud yang mau memaksakan makna batin ayat demi membela ‘paham’ tersebut. ‘Pemaksaan’ ini, dalam kata-kata Darmawan, “tidak bisa dibiarkan secara akademik” (226-227, 230).
Baca Juga: Mengenal Lataif Al-Isyarat, Tafsir Bernuansa Isyari (Sufi) Karya al-Qusyairi
Membaca penilaian tersebut saya tidak bisa menghindar untuk mengajukan pertanyaan metodologis: jika bahasa sufi adalah bahasa simbol, dan jika si pembaca hanya akan dapat memahami sesuai maqām rohaninya sendiri—yang berarti bahwa apa yang dia baca pada dasarnya adalah dirinya sendiri—apakah, mengapa dan bagaimana penilaian ‘akademis’ ini adalah sebuah pengecualian?
Akhirulkalam, takwil sufi seperti karya al-Kasyani sangatlah kompleks. Pembacanya perlu keakraban dengan dua tradisi besar intelektual Islam: tradisi filsafat al-Syekh al-Ra’is Ibn Sina dan tradisi tasawuf al-Syekh al-Akbar Ibn ‘Arabi. Terlepas dari beberapa catatan di atas, Darmawan telah menyumbangkan ‘ijtihad’ pertama untuk memahaminya. Ijtihad-ijtihad selanjutnya tentulah ditunggu.[]
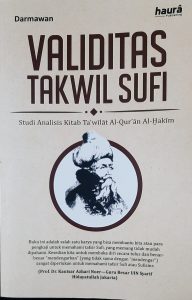
Judul Buku : Validitas Takwil Sufi: Studi Analisis Kitab Taʻwīlāt al-Qur’ān al-Ḥakīm
Penulis : Darmawan
Cetakan : I, November 2021
Penerbit : Haura
Ketebalan : xxii+283
ISBN : 978-623-320-609-9


![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)
![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)













![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-100x70.png)