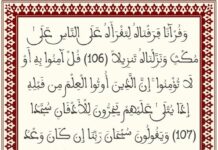Al-Qurṭubī tahu bahwa sejak lama perdebatan tentang tafsir ayat-ayat mutasyābihāt, khususnya yang menyinggung sifat-sifat antropomorfisme (seperti yad atau wajh), telah memecah belah teologi Islam menjadi dua kubuh utama: tafwid dan ta’wil. Tafwid adalah ciri khas ulama salaf, dan ta’wil adalah ciri khas ulama khalaf. Tulisan ini akan membahas Penafsiran ayat antropomorfisme ala Al-Qurṭubī.
Melalui tafwid, ulama salaf lebih memilih menetapkan lafazh secara literal namun menyerahkan sepenuhnya makna dan hakikatnya kepada Allah, sebagai pengakuan atas keterbatasan akal manusia. Di sisi lain, ta’wil yang banyak dianut oleh ulama khalaf terutama dalam tradisi Asy’ariyah berpendapat bahwa makna harfiah harus dialihkan ke makna kiasan, misalnya menafsirkan “tangan” Allah sebagai kekuasaan-Nya, demi menjaga kesucian Allah (tanzīh) dari kesan penyerupaan dengan makhluk (tasybīh).
Dalam pusaran kontestasi metodologis inilah kita menemukan posisi unik Imam Abū ‘Abdullāh Muḥammad Al-Qurṭubī. Sebagai seorang mufassir yang masyhur dengan corak fikihnya dalam al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān. Al-Qurṭubī justru mengambil jalur eklektik yang berani. Beliau tidak memilih salah satu melainkan berupaya menjembatani kedua pendekatan tersebut. Pendekatan eklektik ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana Al-Qurṭubī, dengan latar belakang fikih Maliki dan akidah Asy’ariyah menafsirkan ayat – ayat mutasyābihāt seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 115.
Baca juga: Sikap al-Qurṭubī Terhadap Riwayat Isrāīliyyāt
Tiga Langkah Al-Qurṭubī dalam Menafsirkan Ayat Antropomorfisme
Dalam urusan akidah, khususnya saat menafsirkan ayat-ayat antropomorfisme, Imam Al-Qurṭubī tidak terperangkap dalam dikotomi tafwid (salaf) dan ta’wil (khalaf), melainkan mengembangkan metode eklektik tiga langkah yang cerdas.
Pertama, beliau menetapkan lafazh sifat (seperti yad atau wajh) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah.
Kedua, beliau beralih ke langkah ta’wil dengan menyajikan berbagai pendapat ulama yang memalingkan makna literal ke makna kiasan. Kecenderungan ta’wil ini adalah manifestasi dari teologi Asy’ariyah yang dianutnya, yang mengutamakan tanzīh (penyucian Allah) dari kesan tasybīh (penyerupaan), di mana ta’wil diarahkan pada konsep kekuasaan, keagungan, atau nikmat Allah, bukan makna fisik.
Ketiga, untuk memperkuat ta’wil tersebut dan meredam kritik dari kubu Salaf, Al-Qurṭubī secara krusial menekankan bahwa ta’wil yang ia sajikan bukanlah pendapat pribadinya, melainkan kutipan dari ulama generasi awal, seperti Ibnu Abbas atau Al-Hasan Al-Bashri. Dengan cara ini, beliau berhasil mendemonstrasikan bahwa ta’wil memiliki legitimasi historis dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan tradisi salaf.
Contoh Penafsiran Ayat Wajhullah
Pendekatan eklektik Al-Qurṭubī menjadi sangat jelas ketika beliau menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 115, yang mengandung isu fikih dan akidah dalam satu redaksi:
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
“Hanya milik Allah timur dan barat. Kemana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”
Imam Al-Qurṭubī, dengan corak fikihnya, memulai pembahasan dengan dimensi hukum. Ayat tersebut awalnya berfungsi untuk membolehkan salat sunnah di atas kendaraan saat bepergian ke mana pun arah hadapannya, tanpa terikat kiblat. Namun, beliau segera menegaskan bahwa hukum ini telah dinasakh (dihapus) oleh ayat penetapan kiblat (QS. Al-Baqarah [2]: 144) yang lebih umum dan mengikat. Pembahasan nasakh ini adalah upaya Al-Qurṭubī untuk menjaga keteraturan dan konsistensi syari’ah sebelum beralih ke pembahasan teologi yang lebih samar.
Setelah menyelesaikan isu fikih, Al-Qurṭubī beralih ke isu akidah, yaitu lafazh antropomorfisme wajhullāh. Di sini, beliau menerapkan metode ta’wil dengan mengutip berbagai otoritas untuk memalingkan makna literal “wajah” ke makna kiasan demi menjaga tanzīh (kesucian Allah).
Dalam penafsirannya, Al-Ḥaddāq berpendapat bahwa wajh merujuk pada eksistensi keberadaan Allah. Penggunaan kata wajh adalah ucapan kiasan. Ibnu Fūrak juga menegaskan bahwa penyebutan suatu deskripsi boleh disebutkan. Ketika wajh disebutkan, yang dimaksud adalah Eksistensi Allah. Analogi ini digunakan pula dalam ayat lain seperti QS. Al-Insan [76]: 9) dan QS. Al-Lail [92]: 20), yang secara umum ditafsirkan sebagai mencari keridhaan Allah. Dengan mengutip ulama-ulama khalaf seperti Ibnu Fūrak dan ulama lainnya, Al-Qurṭubī menempatkan ta’wil sebagai solusi rasional yang memiliki legitimasi teologis kuat, sejalan dengan keyakinan asy’ariyahnya bahwa akal harus digunakan untuk menyucikan Tuhan dari kesan penyerupaan dengan makhluk.
Baca juga: Penafsiran al-Qurtubi atas Surah an-Nisa Ayat 34
Untuk mengukuhkan posisi ta’wil nya, Al-Qurṭubī tidak hanya mengutip ulama khalaf, tetapi juga mencari legitimasi historis dari generasi awal. Beliau mengutip pendapat dari Ibnu Abbas, yang menafsirkan wajh sebagai ekspresi bagi Allah SWT, sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya QS. Ar-Rahman [55] : 27. Dengan memasukkan kutipan dari sahabat Nabi ini, Al-Qurṭubī secara halus menunjukkan bahwa ta’wil tidak sepenuhnya asing bagi salaf, sehingga semakin memperkuat penerimaan metode khalaf dalam tafsirnya.
Selain itu, Al-Qurṭubī juga menyajikan spektrum penafsiran yang lebih luas, termasuk pandangan yang menolak menetapkan sifat tanpa kaifiyah seperti Ibnu ‘Aṭiyya yang mengikuti Abu al-Ma’āli, serta pandangan Mu’tazilah yang menafsirkan “wajh” sebagai kehadiran Tuhan dan mengaitkannya dengan firman Allah QS. Al-Ḥadīd [57]: 4. Penyertaan pandangan yang beragam ini menegaskan bahwa Al-Qurṭubī bertindak sebagai seorang mufassir yang menyajikan berbagai opsi kepada pembacanya.
Sebagai penutup pembahasan ayat, Imam Al-Qurṭubī menafsirkan sifat al-wāsi’ (Maha Luas) yang menyertai ayat tersebut dengan cakupan tak terbatas dari ketuhanan-Nya. Penafsiran ini mencakup tiga aspek utama diantaranya luas dalam hukum, di mana Allah memudahkan urusan agama hamba-Nya dan tidak membebani di luar kemampuan. Kemudian luas dalam ilmu, di mana Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Serta luas dalam rahmat, di mana Dia adalah Maha Dermawan yang kedermawanan dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu (menurut Al-Farrā’ dan lainnya).
Secara ringkas, al-wāsi’ menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pemurah yang tidak bergantung pada amal hamba-Nya. Penafsiran ini berfungsi untuk menjauhkan sifat Allah dari keterbatasan fisik dan mengukuhkan kesempurnaan-Nya. Wallahu a’lam.