Dalam tradisi tafsir, kita mengenal istilah asbābun nuzūl: sebab turunnya ayat. Dengan menelusuri latar belakang turunnya wahyu, penafsir bisa menangkap maksud ayat lebih jernih, tidak terjebak pada pemahaman kaku atau sepotong-sepotong. Hal yang sama berlaku untuk hadis Nabi ﷺ. Ia pun lahir dari peristiwa nyata yang disebut asbāb al-wurūd. Tanpa memperhatikan konteks ini, makna hadis bisa menyempit, bahkan disalahgunakan.
Sayangnya, di zaman media sosial, hadis sering diperlakukan layaknya quotes/kutipan instan. Begitu ada label “sahih” atau disebut dalam Shahih Bukhari–Muslim, banyak orang langsung merasa aman untuk menekan tombol share. Padahal, sebagaimana al-Qur’an tidak bisa dilepaskan dari asbābun nuzūl-nya, hadis pun harus dibaca tuntas dengan asbābul wurūd-nya.
Acar/Cuka adalah Makanan Favorit Nabi?
Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
“Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka.”
(HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Ashriba, Bab Faḍl al-Khall wa’l-Laban, no. 2052, juz 3 hlm. 1623)
Apabila hadis ini dibaca tanpa konteks—tanpa memperhatikan zaman, tempat, situasi, dan kondisi—barangkali kita akan menyimpulkan bahwa makanan favorit Nabi adalah makanan yang memakai cuka, atau bahwa sunnah dalam urusan makan adalah selalu mengonsumsi cuka.
Namun, lain ceritanya bila hadis tersebut dibaca dengan memperhatikan asbāb al-wurūd-nya, yakni peristiwa yang melatarbelakangi sabda Nabi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertamu ke rumah seorang sahabat yang hidupnya sederhana. Sang sahabat hanya mampu menghidangkan roti dengan cuka, karena memang tidak ada makanan lain yang lebih layak. Seandainya ia memiliki daging atau makanan yang lebih mewah, tentu ia akan menyajikannya, mengingat tamu agung yang datang adalah Nabi Muhammad ﷺ.
Dalam kondisi itu, Rasulullah ﷺ tetap menghormati jamuan yang sederhana tersebut. Bahkan beliau memuji makanan itu dengan sabdanya: “Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka.” Dengan sikap itu, Nabi bukan sekadar menyampaikan komentar tentang rasa cuka, melainkan memberikan teladan moral: bagaimana menghargai jamuan sederhana dari seorang tuan rumah, dan bagaimana memuliakan sahabatnya yang telah berusaha menjamu dengan kemampuan terbaik.
Baca juga: Pembacaan Ulang Hadis Larangan Istri Puasa Tanpa Izin Suami
Jika kita memahami konteks hadis ini, pelajaran (‘ibrah) yang bisa diambil jauh lebih dalam dibanding sekadar “cuka adalah makanan favorit Nabi”. Ada dua nilai moral utama: pertama, anjuran untuk menghormati tamu; kedua, pentingnya menghargai setiap jamuan, betapapun sederhana.
Di sinilah pentingnya membaca hadis dengan konteks. Baik al-Qur’an maupun hadis Nabi ﷺ bukanlah teks yang muncul dari ruang hampa. Firman Allah dan sabda Rasul selalu lahir dari peristiwa, pengalaman, dan kondisi sosial tertentu.
Sayangnya, di zaman kiwari masih banyak dari kita yang menerima hadis begitu saja, membacanya bulat-bulat tanpa memperhatikan asbāb al-wurūd. Setiap ungkapan yang diawali qāla Rasūlullāh segera dianggap sebagai aturan universal, lalu disebarkan begitu saja. Teknologi informasi membuat hadis-hadis yang belum tentu siap pakai ini tersebar masif lewat WhatsApp, Facebook, Telegram, dan media sosial lainnya.
Fatalnya Hadis “Perang” Tanpa Konteks
Dalam contoh hadis tentang cuka tadi, yang dibicarakan hanyalah soal makanan: roti dan cuka (atau acar). Dampaknya relatif ringan, bahkan bisa membuat orang hanya sibuk membicarakan “menu sunah Nabi”.
Namun, bayangkan jika yang tersebar dan diyakini secara kolektif adalah hadis Nabi ﷺ yang terdengar jauh lebih keras. Misalnya sabda beliau:
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى.
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan alasan Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah Ta‘ala.” (HR. al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, no. 25, Juz 1 hlm. 14)
Baca juga: Pakaian Isbal, Indikator Kesombongan, dan Tafsir Ayat-Ayat Takabur dalam Al-Quran
Jika hadis ini dibaca secara literal, tanpa mempertimbangkan asbāb al-wurūd dan konteks sejarahnya, maka bisa muncul kesimpulan yang sangat berbahaya: seolah-olah Nabi ﷺ diperintahkan untuk membunuh semua manusia yang bukan muslim. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa hadis ini turun dalam konteks perang mempertahankan eksistensi Islam di jazirah Arab, khususnya terhadap kelompok musyrik Quraisy yang saat itu memerangi kaum muslimin.
Membaca hadis semacam ini tanpa konteks bukan hanya menimbulkan salah paham, tetapi juga bisa menjadi catastrophic: legitimasi teologis bagi tindak kekerasan dan radikalisme. Inilah yang sering terjadi ketika hadis-hadis populer beredar di media sosial hanya dalam bentuk potongan terjemahan singkat.
Kesimpulan
Dua contoh di atas—hadis tentang cuka dan hadis tentang perintah memerangi manusia—menunjukkan betapa pentingnya membaca hadis dengan konteks. Tanpa konteks, pesan moral bisa menyempit hanya pada soal makanan, atau lebih buruk lagi, melahirkan justifikasi bagi kekerasan atas nama agama.
Hadis, sebagaimana al-Qur’an bukanlah teks mati. Ia lahir dari ruang dan waktu tertentu, dari peristiwa nyata yang dihadapi Nabi ﷺ bersama para sahabatnya. Karena itu, membacanya memerlukan ilmu, ketelitian, dan kehati-hatian.
Sebelum membagikan sebuah hadis di jagat maya, setidaknya ada dua hal yang perlu dipastikan: (1) kesahihannya, dan (2) konteks atau asbāb al-wurūd-nya. Dengan cara ini, hadis akan tetap menjadi sumber inspirasi moral dan spiritual, bukan sumber salah paham yang menjerumuskan.


![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)
![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)

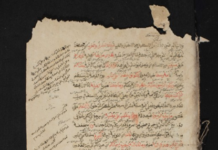








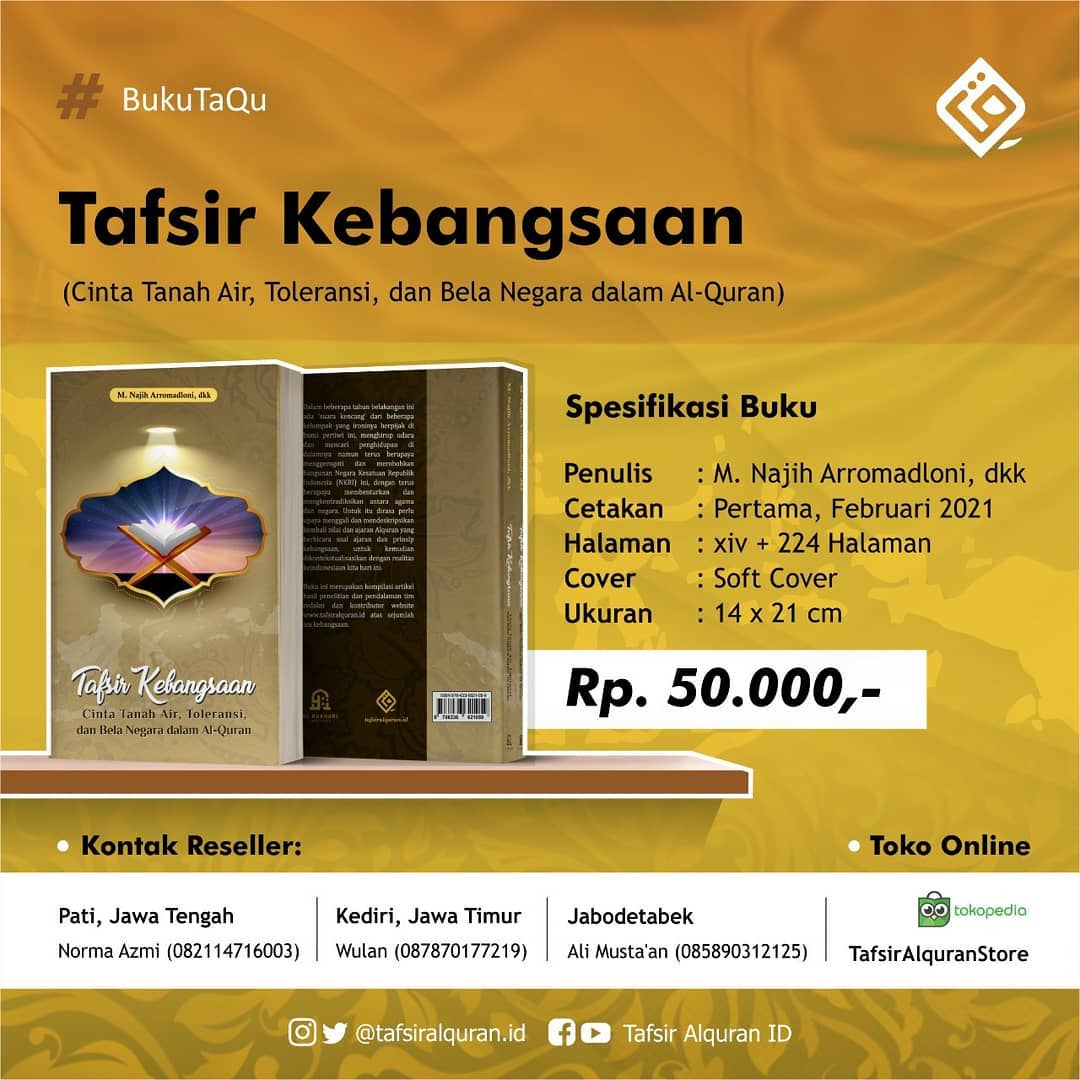
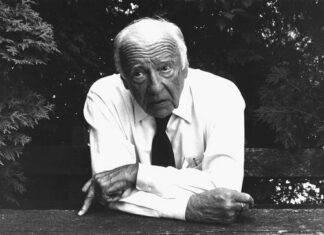

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-100x70.png)