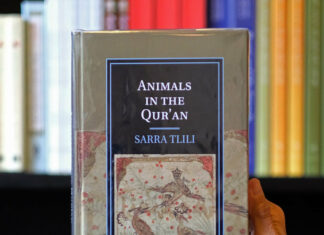Otoritas mufassir berperan signifikan dalam produksi makna-makna Al-Qur’an yang plural dan kontradiktif dibandingkan otoritas teks itu sendiri. Secara lebih khusus, sumber utama di balik pluralisme dan kontradiksi makna Al-Qur’an berasal bukan dari watak teks yang sekalipun bersifat polisemik, karena tidak ada makna yang inheren dalam teks itu sendiri, tetapi justru dari pikiran mufassir-nya (the mind of interpreter). Dapat disimpulkan bahwa pikiran mufassir lah yang berperan penting di balik produksi makna Al-Qur’an yang plural dan terkadang kontradiktif.
Bukti nyata peran mufassir dalam memproduksi makna Al-Qur’an secara beragam, plural, dan bahkan kontradiktif terekam misalnya dalam penafsiran atas kosakata wahy, najm, qur’ān, dan furqān. Dalam penafsiran atas empat kosakata wahyu (the vocabulary of revelation) ini, sejak dahulu hingga sekarang, tidak ada makna yang stabil, tetap, dan inheren dalam teks-teks wahyu itu sendiri.
Setiap kosakata wahyu dimaknai secara berbeda-beda, plural dan kontradiktif oleh sejumlah mufassir yang selalu berikhtiar untuk mengeksplorasi dan memproduksi makna Al-Qur’an yang tidak univokal, tetapi multivokal. Inilah yang memotivasi saya untuk berargumen bahwa otoritas penafsir, daripada otoritas teks wahyu itu sendiri, yang berperan signifikan dalam memproduksi makna Al-Qur’an yang multivokal. Dus, konsekuensi logisnya adalah bahwa makna Al-Qur’an yang plural tersebut menjadi karakteristik utama dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an, terutama di fase awal maupun pertengahan Islam.
Baca juga: Eksplorasi Makna Furqan yang Plural dan Kontradiktif
Tiga Argumen Multivokalitas Tafsir Al-Qur’an
Penafsiran makna Al-Qur’an yang multivokal memberikan inspirasi para intelektual untuk mengajukan pertanyaan yang sering terabaikan dalam diskursus pemikiran Islam. Mengapa Al-Qur’an, yang diyakini berasal dari sumber yang sama, yakni Tuhan, dapat ditafsirkan secara multivokal? Saya ingin mengajukan tiga jawaban atas pertanyaan yang kritis ini.
- Iklim intelektual yang mendukung paska masa Nabi
Tidak ada otoritas tunggal dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an paska profetik dan pewahyuan dalam Islam (post prophetic-revelatory event). Saat pewahyuan masih aktif dan misi profetik sedang berlangsung secara gradual, Nabi Muhammad berperan sentral bukan saja sebagai pembawa wahyu (bearer of revelation), tetapi juga sekaligus sebagai mufassir tunggal Al-Qur’an (sole interpreter of the Qur’ān). Karena itu, Nabi memegang otoritas sentral dalam penafsiran makna Al-Qur’an.
Para sahabat terbiasa bertanya langsung kepada Nabi atas suatu makna wahyu yang ambigu dan bagaimana konteks pewahyuannya. Seiring dengan berakhirnya era pewahyuan dan misi profetik Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi otoritas tunggal dan sentral yang dijadikan rujukan pertama dan utama, yang bersifat otoritatif dan konklusif, atas suatu makna Al-Qur’an dan Islam secara umum.
Sepeninggal Nabi, mufassir demi mufassir mulai bermunculan, terutama di kalangan sahabat, tābi’in, atbā’ at-tābi’in dan mereka yang datang beberapa dekade setelah generasi awal Islam. Inilah generasi awal yang shalih yang sering dirujuk dalam diskursus pemikiran Islam sebagai as-salaf as-sālih. Mereka dipandang istimewa karena hidup lebih dekat dari segi waktu dengan zaman Nabi dan era pewahyuan. Mereka muncul secara gradual dan sporadis dalam sejarah Islam, berasal dari berbagai lokasi geografis dunia Islam yang berbeda-beda, dan menguasai tradisi kesarjanaan Islam secara kompeten (the scholarly traditions of Islam).
Dengan kompetensinya dalam Ulum Al-Qur’an, bahasa Arab, konteks sosial-keagamaan proses pewahyuan, dan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan wahyu itu sendiri, komunitas mufassir secara gradual memperoleh pengakuan dan otoritas dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an.
Mereka sendiri terpanggil bukan sekadar untuk merawat wahyu yang terfragmentasi, yang hanya dihafal melalui ingatan kolektif (collective memory) dan membacanya secara kreatif, variatif, dan dengan penuh keimanan, tetapi juga sekaligus menjaga wahyu yang terfragmentasi itu dalam kultur penafsiran, baik lisan dan tulisan (oral and writerly culture of interpretation), memproduksi makna atas teks-teks Al-Qur’an secara parsial maupun komprehensif, memberikan konteks atas teks-teks wahyu yang kadang ambigu, penuh referensi sejarah masa silam, terutama sejarah nabi-nabi dan berbagai peristiwa dalam tradisi monoteisme pra-Islam, serta memaknai berbagai peristiwa pewahyuan dan kenabian (prophetic-revelatory event) yang tidak direkam dalam Kitab Suci itu sendiri.
Dalam konteks inilah, tradisi penafsiran wahyu menjadi kesadaran kolektif di kalangan komunitas mufassir Al-Qur’an yang berlokasi di berbagai wilayah baru dunia Islam. Sepeninggal Nabi, otoritas dalam menafsirkan makna Al-Qur’an tidak lagi terpusat pada sosok Nabi, melainkan terpencar pada para mufassir Al-Qur’an yang berasal dari berbagai lokasi geografis di dunia Islam. Dengan demikian, tidak ada hierarki otoritas dalam penafsiran Al-Qur’an, terutama dalam tradisi Islam Sunni.
Di tengah absennya hierarki otoritas (hierarchy of authority) inilah, maka setiap mufassir menikmati kebebasan berpikir untuk menafsirkan makna Al-Qur’an dalam iklim intelektual yang sarat polemik. Seiring dengan munculnya banyak mufassir Al-Qur’an dan tersebarnya lokasi geografis mufassir di berbagai dunia Islam yang baru, maka suatu kemustahilan bagi mufassir yang beragam di berbagai lokasi geografis yang berbeda pula itu memiliki penafsiran Al-Qur’an yang tunggal dan seragam.
Faktanya, tradisi penafsiran Al-Qur’an pada periode Islam formatif justru merefleksikan pemikiran mufassir yang multivokal, yang berhasil bukan sekadar menghadirkan wajah Al-Qur’an sebagai kitab suci yang multivokal, tetapi juga mengeksplorasi makna-makna Al-Qur’an yang beragam, plural, dan kontradiktif.
Baca juga: Makna Qur’an yang Plural dan Kontradiktif, Makna Awal Qur’an yang Terlupakan
- Keragaman orientasi keislaman mufassir
Penafsiran makna Al-Qur’an yang multivokal tak terlepas dari orientasi keislaman mufassir yang cukup beragam. Salah satunya adalah mufassir yang berorientasi mistik-sufistik. Tren ini terefleksikan dalam dua mufassir dalam dua tradisi Islam yang berbeda: Islam Shi’ah dan Sunni.
Pada Islam Shi’ah, figur utama yang menjadi rujukan adalah Ja‘far Ash-Shādiq (w. 148/765). Ja‘far Ash-Shādiq menafsirkan An-Najm secara mistik dan metaforis dengan mempertautkan makna An-Najm; pertama, dengan pengalaman mistik-spiritual Nabi Muhammad ketika dia turun dari perjalanan mi’rāj sehingga cahaya-cahaya terpancar dari dirinya; dan kedua, dengan rujukan pada hati Nabi Muhammad yang terputus dari segala bentuk ikatan apa pun kecuali hanya ikatan dirinya yang spiritual dengan Tuhan (Ja‘far Ash-Shādiq, Kāmil al-Tafsīr al-Shūfī al-‘Irfānī li al-Qur’ān 2002: 159).
Corak mistik-sufistik ini juga tampak pada teolog Islam Sunnī Sahl ‘Abd Allāh At-Tustarī (w. 283/896) yang menafsirkan makna An-Najm dengan merujuk pada pengalaman mistik-sufistik Nabi Muhammad ketika ia turun dari langit seusai mengalami perjumpaan spiritual dengan melihat secara langsung figur suci yang berada di langit (At-Tustarī, Tafsir al-Qur’ān al-‘Azhīm 1908: 145). Dengan demikian, orientasi sektarian-keagamaan mufassir merupakan salah satu faktor utama di balik penafsiran makna Al-Qur’an yang multivokal.
Baca juga: Mengenal Corak Tafsir Sufistik (1): Definisi, Klasifikasi dan Prasyarat yang Harus Dipenuhi
- Watak tafsir Al-Qur’an itu sendiri
Tradisi penafsiran Al-Qur’an itu sendiri, sejak awal, tidak pernah bersifat statis dan monolitik, seperti diasumsikan sejumlah sarjana Barat, tetapi selalu dinamis dan multivokal. Hal ini terefleksikan pada publikasi tafsīr Al-Qur’an itu sendiri yang semakin produktif dan variatif, yang menjadi bukti kuat atas tradisi penafsiran yang dinamis dan produksi makna Al-Qur’an yang multivokal.
Jika dibaca dan ditafsirkan secara kreatif, tradisi penafsiran Al-Qur’an menyediakan ruang terbuka untuk proses pemaknaan teks wahyu yang multivokal. Konsekuensinya, makna Al-Qur’an yang multivokal menjadi karakteristik utama dalam tafsir Islam Sunni. Menjadi Muslim Sunni, secara otomatis, harus mengakui keragaman penafsiran dan multivokalitas makna wahyu.
Baca juga: Kenapa Hasil Penafsiran itu Berbeda-beda? Ini Salah Satu Alasannya