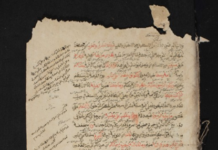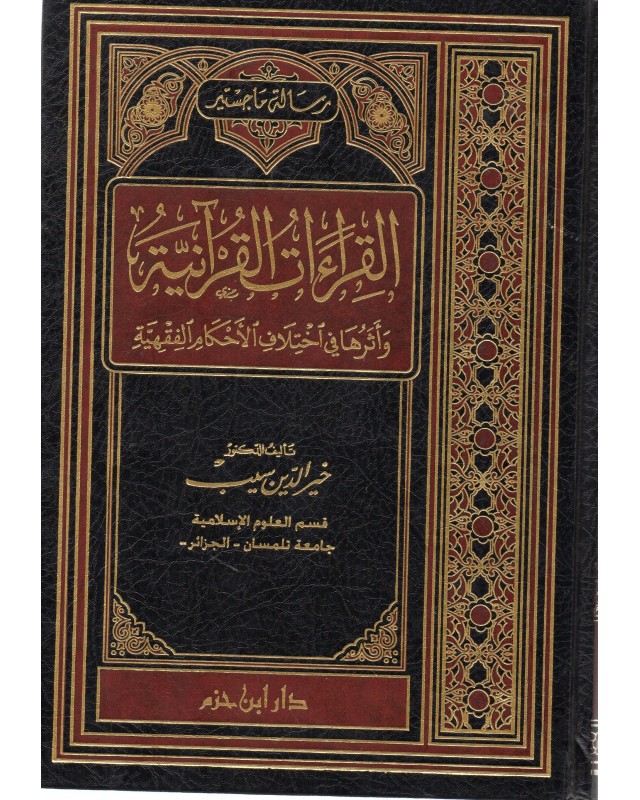Alquran, sedari masa Nabi Muhammad saw. mempunyai bacaan yang beragam yang keragaman itu diafirmasi oleh beliau. Pasca wafat Nabi Muhammad saw. keragaman bacaan itu berkembang menjadi satu bagian dari bahasan ilmu Al-Qur’an yang dikenal dengan ilmu Qira’at Alquran.
Ada satu kitab khusus yang membahas persoalan ini, berjudul al-Qira’at al-Qur’aniyyah wa Atsaruha fi Ikhtilaf al-Ahkam al-Fiqhiyyah, karya Khairuddin Sayyib. Kitab ini merupakan tesis beliau saat menempuh studi di Universitas Islamiyyah, jurusan Usul Fiqh, sekitar tahun 2001/2002. Dalam kitab tersebut dijelaskan betapa besar pengaruh perbedaan bacaan al-Qur’an terhadap kesimpulan hukum yang dirumuskan oleh fuqaha.
Salah satu riwayat yang sering dijadikan dasar tentang adanya ragam qira’at Alquran disampaikan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab hadisnya,
Al-Miswar bin al-Mukhramah dan Abdurrahman bin Abd al-Qari menceritakan bahwa mereka pernah mendengar Umar bin Khatab berkata,
“Aku pernah mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan pada masa Rasulullah masih hidup. Aku pun menyimak bacaannya, dan ternyata dia membaca dengan cara yang berbeda, dengan beberapa variasi bacaan yang belum pernah diajarkan kepadaku oleh Rasulullah.
Aku hampir saja menegurnya saat itu juga di tengah salat, tapi aku masih sabar menungu sampai dia selesai. Setelah salat, aku langsung menegurnya dan bertanya: siapa yang mengajarkan bacaan ini kepadamu?
Dia menjawab: Rasulullah yang mengajarkannya kepadaku.
Aku berkata: Kamu keliru! Rasulullah mengajarkan surah ini kepadaku dengan bacaan yang berbeda dari yang kamu baca.
Akhirnya, aku membawa Hisyam menghadap Rasulullah saw. Sesampainya di sana, Nabi meminta Hisyam membaca surah al-Furqan seperti yang dia baca sebelumnya, dan Nabi pun membenarkan bacaannya. Kemudian Rasulullah memintaku membaca sesuai bacaan yang aku pelajari darinya, dan beliau juga membenarkan bacaanku. Kemudian beliau bersabda:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
“Sesungguhnya al-Qur’an ini diturunkan dengan tujuh macam dialek. Maka bacalah yang mudah untuk kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim)
Baca Juga: Menelisik Pengertian, Sejarah dan Macam-Macam Qira’at
Imam az-Zarkasyi mendefinisikan ilmu qira’at sebagai perbedaan dalam lafal-lafal wahyu (al-Qur’an), baik dalam bentuk huruf maupun cara membacanya. Perbedaan ini mencakup hal-hal seperti takhfif (pelafalan ringan), tatsqil (pelafalan penekanan), penambahan, pengurangan, penggantian lafal, atau perbedaan harakat. (al-Burhan fi Ulum al-Qur’an, jilid 1, 138)
Menariknya, perbedaan qira’at ini tidak cuma berpengaruh pada cara membaca, tetapi juga bisa berdampak pada pemahaman makna ayat. Dari sinilah sebagian fuqaha kadang punya pandangan hukum yang berbeda, padahal dalilnya sama-sama diambil dari satu ayat. Dengan kata lain, perbedaan dalam qira’at sering kali menjadi faktor yang melahirkan perbedaan dalam kesimpulan hukum fikih.
Contoh Perbedaan Qira’at yang Berpengaruh pada Hukum
Pertama, surah al-Ma’idah ayat 89:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۗ
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang sengaja. Maka kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya).”
Ayat ini menjelaskan ketentuan bagi seseorang yang melanggar sumpahnya. Sebagai sanksi atau kafarat karena pelanggaran tersebut, Allah memberikan tiga pilihan. Pertama, memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang lazim ia konsumsi, atau pakaian yang setara dengan pakaian yang ia kenakan. Kedua, memerdekakan budak. Ketiga, apabila tidak mampu melakukan keduanya, maka diwajibkan berpuasa sebanyak tiga hari.
Dalam versi bacaan lain, seperti Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, dan Qais al-Nakha’i membaca potongan ayat di atas dengan tambahan lafal “al-mutatabi’at”, sehingga berbunyi:فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. Dengan demikian, makna ayat tersebut menjadi: “Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa tiga hari berturut-turut”.
Dari kalangan Mazhab Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan minoritas Hanabilah berpendapat bahwa puasa tiga hari sebagai sanksi karena melanggar sumpah tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Alasannya, karena lafal “al-mutatabi’at” memang tidak disebutkan dalam al-Qur’an menurut mayoritas ulama qira’ah.
Sementara dari ulama Mazhab Hanafiyyah dan mayoritas Hanabilah mengatakan bahwa puasa berturut-turut adalah syarat untuk keabsahan kafarat sumpah. Mereka berargumen dengan qira’ahnya Ibnu Mas’ud yang menyebut tambahan lafal “al-mutatabi’at”. Meskipun qira’at tersebut tidak diakui oleh mayoritas ulama qira’ah sebagai bacaan mutawatir, ulama Hanafiyyah tetap menganggapnya memiliki kedudukan seperti hadis ahad, sehingga bisa dijadikan hujjah.
Baca Juga: Variasi Qiraat Al-Quran dan Contohnya dalam Surat Al-Fatihah Ayat 4
Kedua, surah al-Baqarah ayat 196:
وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ
“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Swt.”
Perbedaan bacaan terletak pada lafal “al-umrata”. Dalam qira’ah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Umar, lafal tersebut dibaca “al-umratu” dengan harakat dammah pada huruf ta’, menjadikannya sebagai mubtada. Sedangkan mayoritas qurra’ membacanya dengan harakat fathah (al-umrata).
Bagi yang membaca lafal al-umrah dengan harakat fathah, berarti menjadikannya sebagai ma’tuf, sedangkan ma’tuf alaih-nya adalah lafal al-hajj. Lafal al-hajj sendiri berkedudukan maf’ul dari kata atimmu. Makna dari atimmu adalah datangkanlah secara sempurna. Kata ini berbentuk amar (perintah) yang menunjukkan mewajibkan. Dengan demikian, makna ‘sempurnakanlah ibadah haji dan umrah’ adalah bahwa keduanya wajib dilaksanakan. Pendapat ini dipegang oleh ulama Mazhab Syafi’iyyah dan Hanabilah.
Sedangkan dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa umrah tidak wajib, melainkan sunnah. Sebab, menurut bacaan mereka, lafal al-umrah bukan sebagai ma’tuf dari al-hajj, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda.
Wallah a’lam.