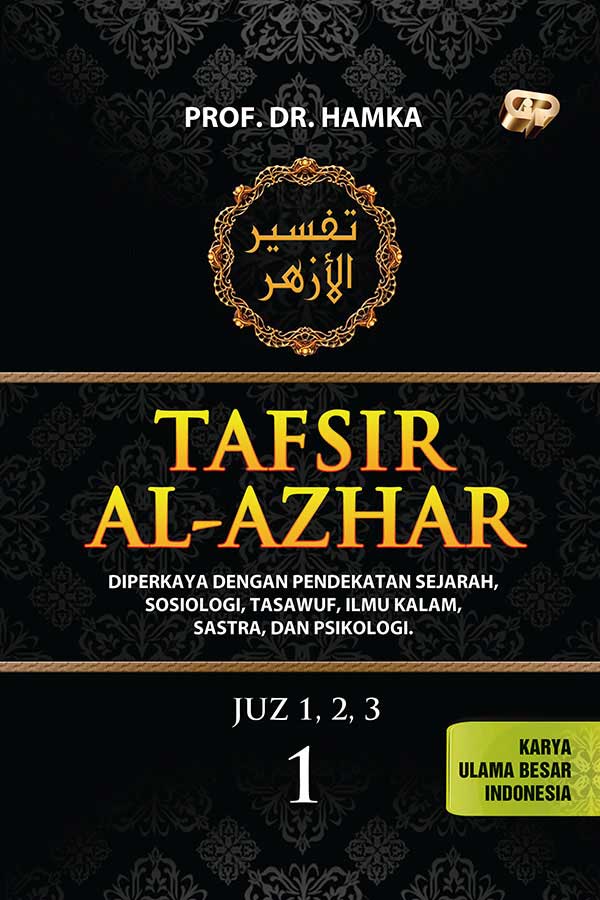Seperti dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Tafsir Al-Azhar lekat dengan keadaan Indonesia yang terjadi saat itu. Sentuhan sisi ke-Indonesiaan yang disuguhkan oleh Buya Hamka diawali dengan pembahasan penggunaan bahasa lokal yang mengiringi nama “Allah” sebagai bentuk pengagungan. Pembahasan tersebut disinggung oleh Buya Hamka dalam menafsirkan Surat al-Fatihah ayat 1, yakni pembahasan terkait kata “Allah”.
Untuk memulai penjelasannya, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengutip pendapat dari Raghib al-Isfahani, Buya Hamka menguraikan kalimat “Allah” dari segi bahasa. Menurut Raghib, “Allah” merupakan sebutan yang ditujukan kepada Dzat Yang Maha Kuasa. Kata ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh bangsa Arab untuk menyatakan “Yang Maha Esa”.
Kata “Allah” adalah perkembangan dari kata “Al-Ilah” yang bermakna Tuhan atau Dewa. Maka, setiap apa yang mereka puja serta dianggap sakti, mereka sebut dengan “Al-Ilah”. Jika mereka hendak menyebutkan banyak Tuhan, mereka menggunakan bentuk jamak dari kata “Al-Ilah” yakni “Al-Alihah”.
Namun dalam tahap selanjutnya, pikiran mereka berakhir pada kesimpulan, bahwa dari semua tuhan atau dewa yang mereka yang sembah hanya ada satu Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, untuk merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka, digunakanlah kata “Ilah” sebagai pengkhususan kepada Dia Yang Esa.
Baca juga: Alasan Tafsir Jalalain Jadi Tafsir Favorit di Pesantren
Supaya lebih khusus lagi, mereka menambahkan kata “Al” di depannya, sehingga menjadi “Al-Ilah”. Kemudian, mereka membuang huruf hamzah yang di tengah, maka jadilah “Allah”. Dengan menyebut nama “Allah” tersebut, berarti tidak ada lagi yang dimaksud, kecuali Yang Maha Esa.
Maka, dari penjelasan Raghib al-Isfahani tersebut, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengambil kesimpulan bahwa dari sejak dahulu orang Arab sudah mengakui adanya tauhid uluhiyah. Sebab, mereka sekali-kali tidak menggunakan kata “Allah” itu untuk yang selain dari Yang Maha Esa. Dan, tidak mau menyebut ratusan berhala yang ada dengan sebutan “Allah”. Hanya saja, dalam aspek tauhid rububiyahnya yang masih musyrik.
Setelah menguraikan hal itu, Buya Hamka menyinggung terkait penggunaan bahasa lokal dalam Tafsir Al-Azhar-nya. Dalam bahasa Melayu, Ilah diartikan dengan dewa atau tuhan. Sehingga, kalimat Allah Subhanahu wa Ta’ala dibahasakan dengan Dewata Mulia Raya. Ini bisa dilihat di batu bersurat Trengganu yang ditulis dengan huruf Arab, kira-kira tahun 1303 M.
Baca juga: Mufasir-Mufasir Indonesia: Biografi Abdurrauf As-Singkili
Sedangkan di Jawa, digunakan kata “Gusti” untuk mengiringi kata “Allah”, yang dalam bahasa Melayu Banjar “Gusti” berarti gelar bangsawan. Demikian halnya di Sunda, yang menggunakan kata “Pangeran”. Padahal, “Pangeran” juga memiliki arti gelar bangsawan atau anak raja.
Buya Hamka juga menyinggung kepercayaan orang Bali. Bahwa meskipun mereka beragama Hindu, mereka tetap percaya kepada “Sang Hyang Widhi”, yang berarti Yang Maha Esa. Bahkan hingga mencapai puncaknya, yakni “Sang Hyang Tunggal”.