Dalam empat tahun terakhir ini, saya sedang fokus mengkaji penerjemahan al-Quran. Ternyata cakupan kajiannya amat luas, dan banyak hal yang menarik untuk diteliti. Melalui tulisan singkat ini, saya ingin berbagi tentang hal tersebut. Selain karena lagi gandrung pada kajian terjemah al-Quran, saya juga sering menyimak artikel-artikel terkait penerjemahan al-Quran di portal ini, tafsiralquran.id. Artikel-artikel tersebut memantik saya untuk turut sharing gagasan, bacaan dan berdiskusi. Tulisan kali ini akan berfokus pada apakah terjemah al-Quran adalah tafsir al-Qur’an.
Awalnya, saya tertarik membaca tulisan Ulin Nuha dalam portal ini dengan tajuk Apakah Terjemahan Al-Quran Dapat Disebut Karya Tafsir? Inilah Pemetaan Levelisasi Mufasir Menurut Para Ahli. Sekilas, saya berharap menemukan jawaban yang memuaskan dari judul tulisan tersebut. Alih-alih mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya malah terpancing untuk ikut menambahkan.
***
Mari berangkat dari definisi terjemah yang diusung para sarjana Ulumul Qur’an. Pertama, Muhammad Abd al-Azim az-Zarqani (w. 1367 H/1948) dalam Manahil al-Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, menyebutkan bahwa tarjamah al-Quran memiliki makna tafsiruhu bi lughatihi al-‘arabiyya (tafsir al-Qur’an dengan bahasa Arab) dan juga memiliki makna tafsiruhu bi lughatin ajnabiyyah (tafsir al-Qur’an dengan bahasa lain). Kedua, Jalaluddin Ibn at-Tahir al-‘Alusi, dalam Ahkam Tarjamah al-Qur’an al-Karim menyebutkan bahwa tarjamah adalah tafsiru al-kalam bi lughatihi al-asliyyah allati ja’a biha (penjelasan berita dengan bahasa aslinya) atau yang sering disebut dengan istilah tafsir. Tarjemah juga didefinisikan dengan tafsiru al-kalam bi lughatin ukhra ghairi al-lughati allati ja’a biha (penjelasan berita dengan bahasa lain selain bahasa asli) atau yang sering disebut dengan at-tarjamah al-ma’nawiyyah.
Ketiga, Najdah Ramadan dalam Tarjamah al-Qur’an al-karim wa asaruha fi ma’aniha menyebutkan bahwa terjemah adalah tafsiru al-kalam wa bayanuhu bi lughatihi allati ja’a bih (penjelasan berita dan penjelasannya dengan bahasa asli) dan tafsiru al-kalam bi lughatin ghairi lughatihi (penjelasan dengan bahasa selain bahasa asli).
Tiga sarjana Ulumul Qur’an tersebut, pada dasarnya menguatkan gagasan bahwa terjemah al-Qur’an adalah tafsir al-Qur’an. Bahwa apa yang dilakukan oleh penerjemah, yakni memindahkan kata, frasa, kalimat, atau pesan dari bahasa sumber ke bahasa target merupakan tindakan penafsiran. Keputusan yang diambil dalam menentukan pilihan kata, frasa dan kalimat adalah—meminjam istilah dari Johanna Pink—exegetical decision (keputusan tafsiriyah).
Contoh, kata qawwamun dalam QS. An-Nisa [4]:34 dalam al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama edisi 1990 atau sebelumnya diterjemahkan dengan pemimpin. Pada edisi penyempurnaan 2002 diterjemahkan pelindung. Sedangkan pada edisi penyempurnaan 2019, qawwamun diterjemahkan dengan penanggung jawab. Pemilihan pemimpin, pelindung dan penanggung jawab pasti didasarkan pada proses penafsiran.
Namun, dalam kenyatannya, meskipun memiliki pengertian yang mirip, terjemah al-Quran dan tafsir al-Quran itu berbeda. Perbedaan mendasarnya terletak pada luas-lebarnya penjelasannya. Tafsir memiliki ruang yang luas dalam menjelaskan berbagai sisi ayat-ayat al-Qur’an. Maka, tak heran jika kitab tafsir itu tebal-tebal dan berjilid-jilid. Sedangkan terjemah memiliki ruang yang terbatas dalam menjelaskan kata-kata dalam al-Qur’an.
Jadi, tugas penerjemah al-Qur’an itu pada dasarnya lebih berat. Ia harus memilih di antara pilihan-pilihan kata bahasa target yang tersedia, yang bisa mewakili maksud dari kata-kata pada bahasa aslinya. Karena penerjemah tidak bisa ruang yang luas untuk menyediakan banyak pilihan, maka ia harus mengambil salah satu atau dua.
Konsekuensinya, keputusannya dalam mengambil pilihan tersebut bisa jadi dipandang salah, kurang tepat atau tidak memuaskan oleh pembacanya. Inilah yang dalam studi penerjemahan disebut dengan lost in translation. Akan selalu ada yang hilang dalam penerjemahan.
Lost in translation yang dimunculkan karena kei’jazan al-Qur’an (Inimitability of Qur’an) ini yang menjadi alasan utama para ulama generasi awal (hingga abad ke-5 H) untuk menolak keterjemahan al-Qur’an (Translatability of Qur’an). Usaha-usaha untuk memindahkan bahasa al-Qur’an (Arab) ke bahasa selain Arab tidak mungkin bisa dilakukan dan hanya akan menimbulkan masalah.
Di sinilah penerjemahan al-Qur’an selalu menghadapi tantangan dan tidak menemukan solusi yang memuaskan. Kebuntuan ini menurut Fred Lemhuis—sebagaimana ia tuliskan dalam buku The Cambridge Companion to The Qur’an (2006)—karena kata tarjamah sejak dari awal dimaknai sebagai literal translation (tarjamah harfiyyah).
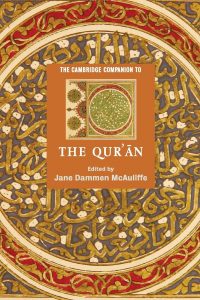
Terjemah harfiyyah inilah yang sejak awal ditolak. Seiring dengan menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah non-Arab dan proses vernakularisasi (pembahasalokalan teks-teks keagamaan), sikap para ulama dan sarjana mulai melentur dan mencari jalan keluar, yakni menawarkan tarjamah tafsiriyyah dan juga menawarkan gagasan bahwa yang diterjemahkan bukanlah al-Qur’an tetapi makna dari kata-kata al-Qur’an. Gagasan yang terakhir ini terihat misalnya dari judul-judul karya terjemahan seperti karya Muhammad Marmaduke Pickthall yang berjudul The Meaning of the Glorious Koran: an explanatory translation (1930), Abul A’la Al Maududi, yang berjudul The Meaning of The Qur’an (1967), dan M. Quraish Shihab dengan judul Al—Qur’an dan Maknanya (2010).
***
Singkat kata, penerjemah al-Qur’an akan menghadapi banyak masalah. Hussein Abdul-Rouf dalam Qur’an Translation: Discourse, Texture and Exegesis (2001) mendaftar berbagai fitur al-Qur’an yang bakalan hilang bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Hussein memberikan yang cukup memadai daam buku tersebut. Misalnya, kata gulibat ar-rum (غلبت الروم) dalam pembuka surah Ar-Rum. Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan ayat tersebut dengan The Roman Empire has been defeated. M. Quraish Shihab menerjemahkan (Kerajaan) Rum telah dikalahkan. Apa yang hilang dari terjemahan tersebut?
Perhatikan kata gulibat adalah verb dalam bentuk mu’annas (feminine form), padahal ar-rum adalah isim mudzakar (masculine form). Secara semantik, bentuk seperti ini menunjukkan humiliation (penghinaan). Sedangkan secara retorik fitur ini berfungsi sebagai sarcasm (sindiran tajam). Fungsi semantik dan retorik inilah yang tidak muncul atau hilang (lost) dalam terjemah Inggris dan Indonesia. Contoh lainnya yang sering disebut-sebut adalah kata nazzala dan anzala yang sama-sama diterjemahkan menurunkan. Padahal keduanya berbeda, memiliki tekanan makna yang beda. Kalau nazzala itu turun secara berangsur-angsur, sedangkan anzala, turun secara sekaligus.
Begitu berat dan banyaknya tantangan seorang penerjemah al-Qur’an, sampai-sampai, Tarif Khalidi—dalam sebuah makalahnya berjudul Reflection of a Qur’an Translation (2013)—mengibaratkan seorang penerjemah al-Qur’an itu bagaikan sebagai seorang yang berpisah dengan kekasihnya. Setelah perpisahan, seseorang itu menyesali dirinya sebab pada saat berpisah, ia seharusnya mengatakan banyak hal, ini dan itu. Begitulah dengan para penerjemah al-Qur’an. Begitu terjemahnya sudah selesai dan dicetak, ia merasakan banyak hal yang seharusnya ia jelaskan tetapi tidak bisa. Hingga akhirnya menyadari kekurangan atas terjemahnya tersebut.
Untuk membenahi penyesalan tersebut, beberapa karya terjemah mengalami biasanya direvisi. Seperti al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI yang direvisi sebanyak empat kali (1970, 1990, 2002 dan 2019). Tentu ini langkah yang baik sebagai usaha penyempurnaan terjemah tersebut. Meskipun begitu, selalu ada ‘penyesalan’ (karena ada yang terlewatkan dari revisi) pada edisi penyempurnaan yang terakhir, yakni tahun 2019.
Beberapa bulan setelah al-Qur’an dan Terjemahnya edisi penyempurnaan 2019 di-launching, saya mewawancarai salah satu panitia penyempurnaan. Dalam wawancara tersebut, ia mengakui ada yang terlewatkan, misalnya terjemah kata ‘alaqah. ‘Alaqah di QS. Al-‘Alaq [96]:2, al-Hajj [22]:5, Ghafir [40]:67 masih diterjemahkan dengan segumpal darah. Sedangkan ‘alaqah pada Al-Qiyamah [75]:38 dan al-Mu’minun [23]:14 diterjemahkan dengan sesuatu yang menggantung (darah). Menurut panitia ini, yang lebih tepat adalah sesuatu yang menggantung.
***
Dari penjelasan di atas, rasanya tidak berlebihan bila saya berkesimpulan pada dasarnya terjemah al-Quran adalah tafsir yang terbatas. Karena keterbatasannya itulah, pembaca sudah seharusnya berhati-hati dalam membacanya dan melengkapinya dengan membaca kitab tafsir. Memang, kita harus mengakui bahwa terjemah al-Quran sangat membantu dalam memahami al-Qur’an terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab.
KH. Ahsin Sakho Muhammad—ketika saya wawancarai—berpendapat bahwa terjemah al-Qur’an hanyalah salah satu pintu awal memahami al-Qur’an, bukan satu-satunya cara untuk memahami al-Qur’an. Maka, saya setuju dengan apa yang dikatakan Ahmad Rafiq—Direktur LSQH UIN Sunan Kalijaga—the worst way to read the Qur’an is stop it on the translation. Cara terburuk membaca/memahami al-Qur’an adalah hanya dengan berhenti pada terjemahnya.[]



![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)









