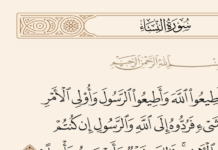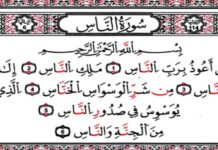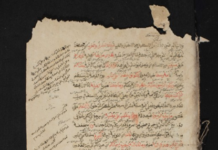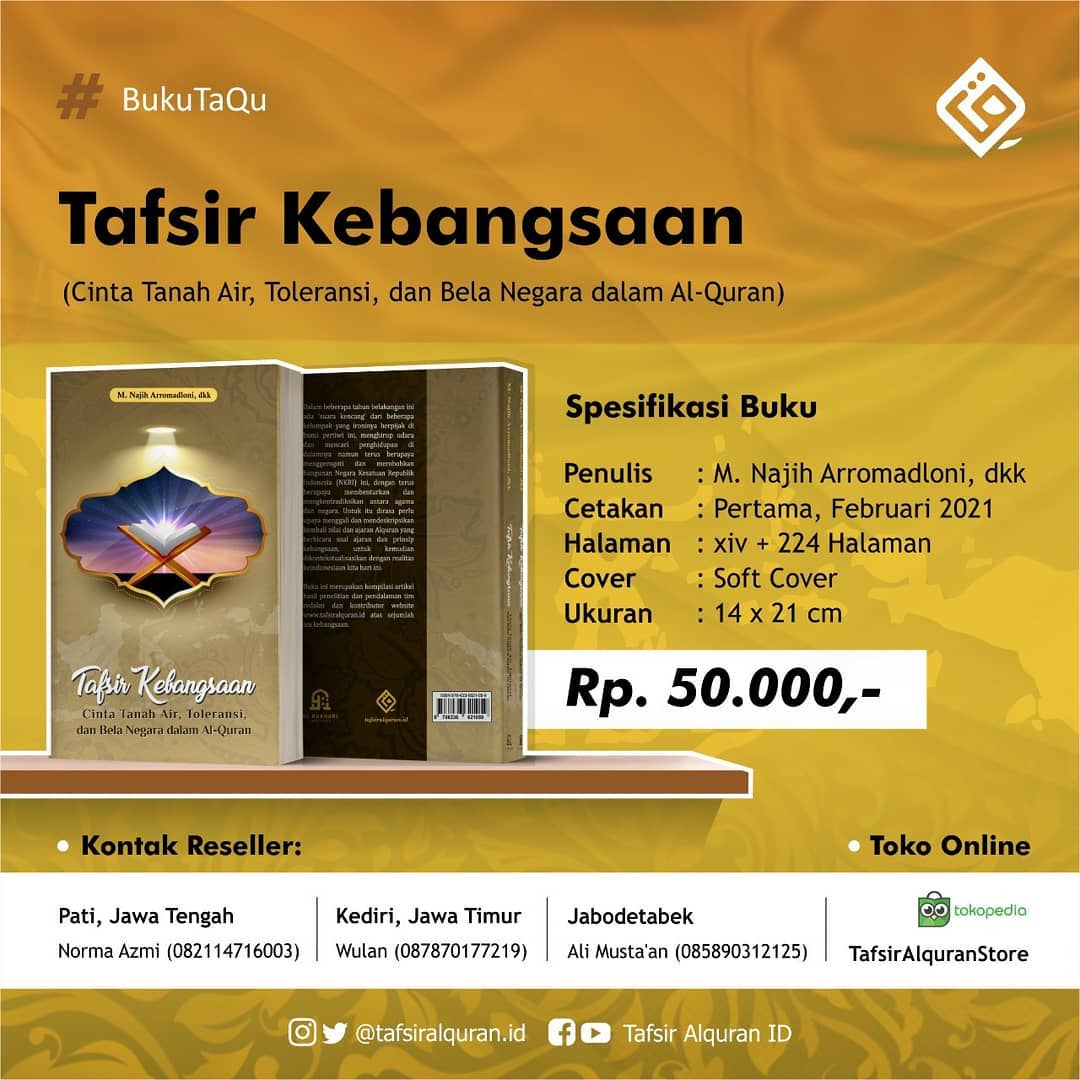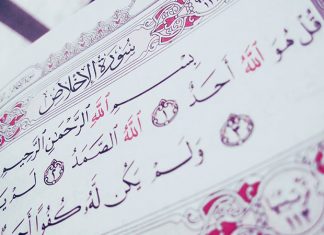Alquran turun sebagai hudan lin-nas (petunjuk bagi manusia) sebagaimana disebutkan dalam surah Albaqarah ayat 185. Lafaz an-naas atau manusia di sini tidak terbatas pada mereka yang telah memeluk Islam, melainkan mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali.
Namun, sebuah paradoks menarik sering terjadi dalam pemahaman tentang hidayah: ketika seseorang masuk Islam, masyarakat sering berkata “dia mendapat hidayah,” seakan-akan petunjuk itu diturunkan kepadanya tanpa usaha. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, orang tersebut biasanya telah melalui proses panjang mencari-cari apa itu Islam, apa itu iman, dan belajar hingga akhirnya menjemput petunjuk tersebut.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar yang mengarah pada dilema spiritual: apakah hidayah itu dicari atau diberi? Apakah manusia berperan aktif ataukah pasif dalam memperoleh petunjuk Ilahi? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan penggalian mendalam terhadap makna linguistik dan konseptual hidayah dalam Alquran.
Baca Juga: Tafsir Surat Al-Qashash Ayat 56: Memahami Hikmah, Ragam dan Proses Hidayah
Dua Sisi Petunjuk: Yang Diberi dan Yang Dicari
Menelusuri jejak makna hidayah dalam Alquran, ternyata ada kedalaman linguistik yang mengagumkan. Al-Râghib al-Ashfahânî,, seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami kosakata Alquran, memberikan pencerahan yang luar biasa tentang hal ini.
Menurut Al-Ashfahânî, meskipun secara bahasa al-huda dan al-hidayah memiliki makna yang sama, namun Allah telah mengkhususkan lafaz al-huda untuk petunjuk yang ditangani dan diberikan-Nya, sementara istilah lain digunakan untuk yang diserahkan kepada manusia.
Perbedaan halus ini ternyata membawa implikasi teologis yang mendalam, menunjukkan bahwa Alquran membedakan secara tegas antara petunjuk yang bersifat pemberian dan petunjuk yang memerlukan pencarian aktif (Al-Râghib al-Ashfahânî, 1431 H, 838).
Ketika merenungkan penggunaan al-huda (الهُدَى) dalam Alquran, akan ditemukan bahwa istilah ini secara khusus merujuk pada petunjuk yang Allah berikan dan kuasai sepenuhnya. Penggunaan istilah ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat seperti “hudan lil-muttaqin”, “ula’ika ‘ala hudan min rabbihim”, dan “qul inna huda Allah huwal huda”. Konsistensi penggunaan ini menunjukkan bahwa ada dimensi hidayah yang sepenuhnya merupakan prerogatif Allah, tanpa campur tangan manusia.
Berbeda halnya dengan al-ihtida (الاهْتِدَاءُ), yang secara khusus berhubungan dengan apa yang dicari manusia melalui jalan pilihan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Keindahan konsep ini terlihat dalam firman Allah: “wa huwal ladzi ja’ala lakumun nujuma li tahtadu biha”, yang dengan jelas menunjukkan peran aktif manusia dalam menggunakan sarana yang telah disediakan untuk memperoleh petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam proses memperoleh petunjuk, bukan hanya menunggu secara pasif.
Yang lebih menarik lagi, al-ihtida mencakup spektrum usaha yang luas: pencarian petunjuk (talab al-hidayah), mengikuti orang yang berilmu, dan berusaha mencari dengan sungguh-sungguh (taharri). Kedalaman makna ini tergambar indah dalam QS. Taha: 82, dimana frasa thumma ihtada bermakna “kemudian ia terus-menerus mencari petunjuk, tidak berhenti dari usahanya, dan tidak kembali kepada kemaksiatan” (Al-Râghib al-Ashfahânî, 1431 H, 839). Makna yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa hidayah bukanlah pencapaian sekali jadi yang bisa dianggap selesai, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen jangka panjang dan ketekunan yang tidak mengenal lelah.
Baca Juga: Baca Ayat Ini Sebagai Doa Agar Orang Mendapatkan Hidayah Islam
Tingkatan Hidayah: dari Umum hingga Khusus
Setelah memahami perbedaan mendasar antara al-huda dan al-ihtida, muncul pertanyaan yang lebih kompleks tentang aplikasi konsep ini dalam realitas. Imam Ar-Razi, dengan kecerdasan analitisnya yang tajam, mengangkat pertanyaan yang menggelitik: mengapa Al-Qur’an disebutkan sebagai hudan lil-muttaqin di satu tempat, namun di tempat lain disebutkan sebagai hudan lin-nas? (Mafâtîẖ Ghayb, 5/254).
Pertanyaan sederhana ini ternyata membuka pintu pemahaman yang luas tentang hierarki hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa ada struktur berlapis dalam konsep hidayah yang perlu dipahami secara komprehensif, bukan sekadar dipandang sebagai konsep tunggal yang homogen.
Menjawab kegelisahan intelektual ini, Ar-Razi menjelaskan bahwa hidayah terbagi dalam beberapa tingkatan yang saling terkait namun berbeda kualitasnya. Allah menyebut Al-Qur’an sebagai hidayah secara umum, kemudian hidayah itu sendiri terbagi dua: terkadang menjadi petunjuk yang jelas dan terang bagi manusia, terkadang memerlukan usaha lebih untuk memahaminya (Mafâtîẖ Ghayb, 5/254). Stratifikasi ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek hidayah dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang, melainkan memerlukan kesiapan spiritual dan intelektual yang berbeda-beda.
Dimensi historis juga menambah kekayaan pemahaman ini. Al-Qur’an, selain menjadi hidayah dalam dirinya sendiri, juga mengandung bayyinat min al-huda wal-furqan, penjelasan penjelasan dari hidayah dan furqan yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil (Mafâtîẖ Ghayb, 5/254). Kesinambungan ini menunjukkan kontinuitas dan universalitas pesan ilahi yang melampaui batas-batas temporal dan kultural, menegaskan bahwa kebenaran memiliki benang merah yang menghubungkan seluruh peradaban dan zaman.
Aspek sosiologis juga tidak kalah menarik untuk dicermati. Al-Ashfahânî dengan jeli mencatat bahwa lafaz an-nas dalam Al-Qur’an terkadang dimaksudkan untuk orang-orang utama, bukan semua yang disebut manusia secara umum. Spesifikasi ini terjadi ketika dipertimbangkan makna kemanusiaan yang sesungguhnya, yaitu adanya akal yang berfungsi, ingatan yang aktif, dan akhlak-akhlak terpuji serta makna-makna khusus yang menjadi ciri khas manusia (Al-Râghib al-Ashfahânî, 1431, hlm. 829). Selektivitas ini menunjukkan bahwa responsivitas terhadap hidayah sangat bergantung pada kualitas kemanusiaan seseorang, bukan sekadar status biologis sebagai homo sapiens.
Melengkapi gambaran yang kompleks ini, Ar-Razi menjelaskan fenomena psikologis yang sering dialami manusia: dorongan kuat yang tiba-tiba muncul dalam hati tanpa sebab yang jelas, yang kemudian terbukti membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dorongan yang membawa kebaikan berasal dari malaikat yang memberi petunjuk, sementara yang membawa kerusakan berasal dari setan yang menyesatkan (Mafâtîẖ Ghayb 19/18–19). Kompleksitas dinamika internal ini menunjukkan bahwa proses pencarian hidayah melibatkan pertarungan spiritual yang tidak kasat mata, memerlukan kemampuan membedakan antara bisikan positif dan negatif yang silih berganti dalam sanubari manusia.
Baca Juga: Petunjuk Al-Quran tentang Tiga Hal Untuk Memperkuat Keyakinan
Hukum Perubahan: Usaha Manusia Mendahului Pertolongan Allah
Dari pemahaman tentang kompleksitas hidayah, perjalanan pencarian makna sampai pada prinsip universal yang dinyatakan dalam QS. Ar-Ra`d: 11. Ayat ini bagaikan kunci emas yang membuka rahasia hubungan antara usaha manusia dan respons Ilahi.
Al-Maraghi, dengan gaya tafsir yang aplikatif, menjelaskan bahwa Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum berupa nikmat dan kesejahteraan sehingga menghilangkannya dari mereka, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka dengan saling berbuat zalim, saling menyerang, dan melakukan keburukan-keburukan yang merusak tatanan masyarakat (Tafsir Al-Marâghî, 13/78–79). Prinsip kausalitas ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi eksternal, baik positif maupun negatif, selalu dimulai dari transformasi kondisi internal, menciptakan pola hubungan sebab-akibat yang dapat diprediksi dan dipahami.
Memperkuat pemahaman ini, Ar-Razi dengan tegas menegaskan bahwa seluruh mufasir bersepakat bahwa Allah tidak mengubah apa yang dimiliki suatu kaum berupa nikmat-nikmat dengan menurunkan hukuman, kecuali setelah ada kemaksiatan dan kerusakan dari mereka (Mafâtîẖ Ghayb, 19/20). Konsensus ulama ini menunjukkan bahwa hukuman ilahi bukanlah tindakan sewenang-wenang atau takdir buta, melainkan konsekuensi logis dan adil dari pilihan moral yang dibuat manusia secara sadar.
Transisi dari prinsip sosial ke dimensi individual terlihat jelas dalam penjelasan Ibnu Ashur. Ketika seseorang berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah (jaahadu fiina), Allah memberikan jaminan akan menunjukkan jalan-jalan-Nya kepada mereka (lanahdiyannahum subulana).
Hidayah dalam konteks ini mencakup bimbingan spiritual dan kemudahan praktis dari Allah melalui penyiapan hati dan petunjuk syariat (Al-Tahrîr wa al-Tanwîr, 21/ 36–37). Jaminan ilahi ini menunjukkan bahwa ada kepastian matematis dalam hubungan antara usaha spiritual dan respons Allah, meskipun bentuk dan waktu respons tersebut tidak selalu dapat diprediksi oleh manusia.
Aspek psikologis dari prinsip ini dijelaskan Ar-Razi dengan sangat menarik. Mengetahui bahwa malaikat mencatat setiap amal perbuatan memiliki efek transformatif: ketika seseorang yang beriman hendak melakukan kemaksiatan dan ia meyakini bahwa malaikat menyaksikannya, rasa malu kepada mereka akan menghalanginya dari melakukan kemaksiatan tersebut (Mafâtîẖ Ghayb 19/18–19).
Mekanisme psikologis ini menunjukkan bahwa kesadaran spiritual dapat menjadi sistem kontrol diri yang sangat efektif, mengubah perilaku dari dalam tanpa paksaan eksternal, menciptakan transformasi yang autentik dan berkelanjutan.
Keharmonisan Ikhtiar dan Taufiq
Setelah menelusuri berbagai aspek hidayah dari dimensi linguistik, teologis, hingga psikologis, sampailah pada sintesis yang mengubah paradigma pemahaman. Hidayah ternyata bukanlah konsep dikotomi yang mempertentangkan “mencari” versus “diberi,” melainkan simfoni harmonis antara usaha manusia dan pertolongan Allah yang saling melengkapi dan memperkuat.
Transformasi pemahaman ini membawa implikasi praktis yang revolusioner. Pemahaman baru ini mengembalikan dignitas dan peran aktif manusia dalam proses spiritual, mengubah mentalitas dari penerima pasif menjadi pencari aktif, tanpa mengabaikan aspek fundamental ketergantungan kepada Allah. Manusia bukan robot yang menunggu program dari langit, tetapi juga bukan makhluk yang bisa meraih segalanya dengan kekuatan sendiri.
Dalam konteks dakwah, revolusi pemahaman ini mengubah paradigma dari “memberi hidayah” menjadi “memfasilitasi pencarian hidayah.” Perubahan sudut pandang ini sangat signifikan karena menyadarkan bahwa seorang pendakwah bukanlah pemberi hidayah -karena itu hak prerogatif Allah semata- melainkan fasilitator yang bertugas menyediakan akses informasi dan menciptakan kondisi yang mendukung pencarian kebenaran. Pendekatan ini menghilangkan arogansi spiritual yang sering muncul dan mengembalikan kerendahan hati dalam berdakwah.
Bagi mereka yang merasa “belum mendapat hidayah,” konsep ini memberikan harapan yang sangat konkret. Kondisi tersebut bukan karena Allah tidak mau memberi atau ada diskriminasi ilahi, tetapi karena proses pencarian yang mungkin belum optimal atau belum menemukan metode yang tepat. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kapasitas inheren untuk menjemput petunjuk melalui usaha yang sungguh-sungguh, doa yang khusyuk, dan pembersihan jiwa yang konsisten.
Dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan multikultural, pemahaman ini juga menghilangkan rasa superioritas agama yang seringkali merusak harmoni sosial. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budayanya, memiliki akses yang sama terhadap petunjuk universal Alquran. Yang membedakan hanyalah intensitas pencarian, metode yang digunakan, dan kesiapan menerima, bukan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diubah.
Alquran sebagai hudan lin-nas telah tersedia seperti mata air yang jernih, tinggal bagaimana setiap individu menjemputnya dengan sungguh-sungguh melalui keseimbangan yang indah antara ikhtiar dan taufiq, antara usaha maksimal dan penyerahan total kepada Allah. Wallahu a’lam.