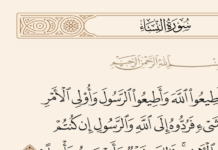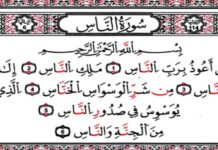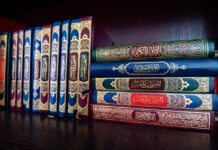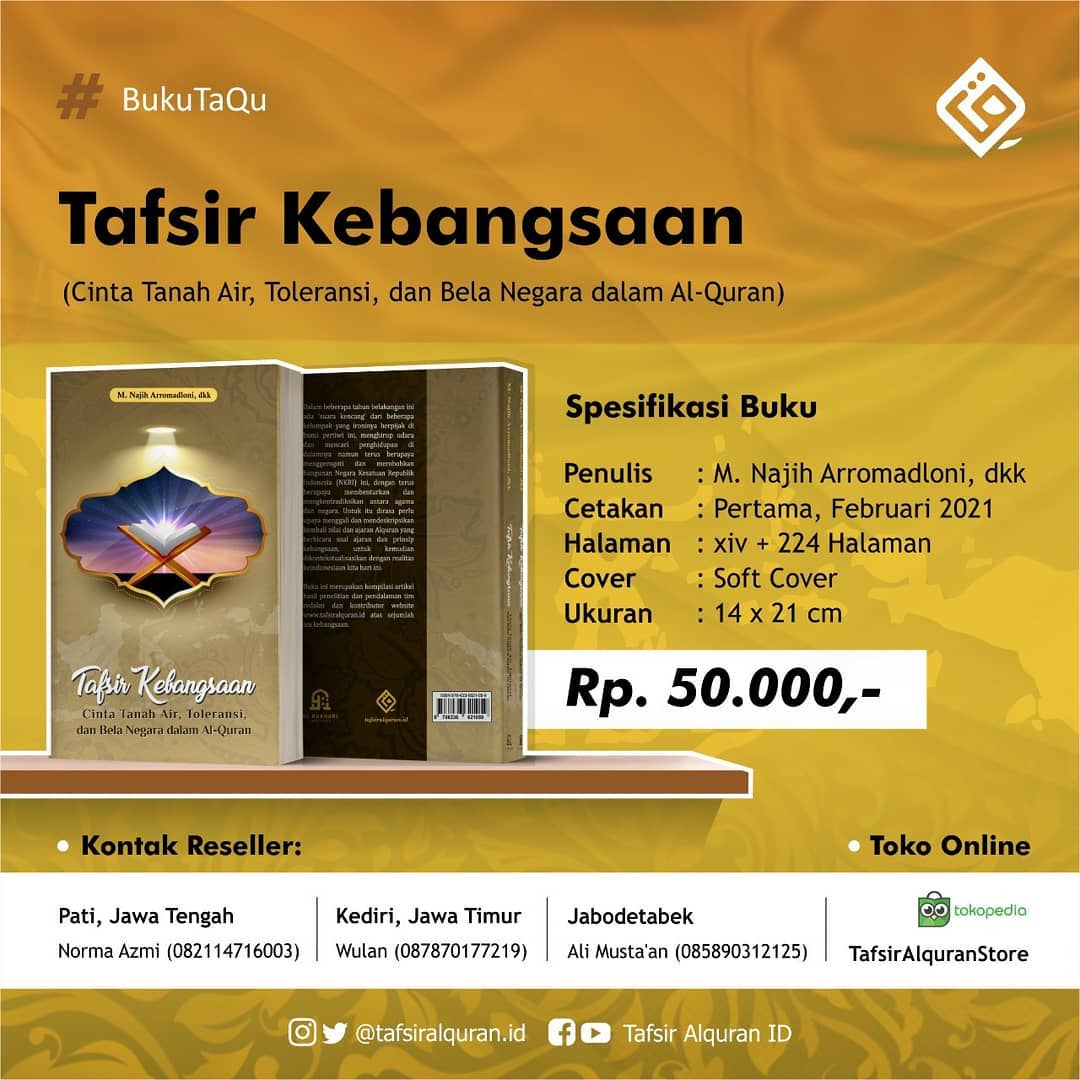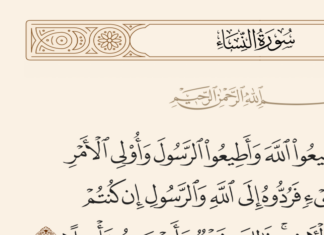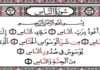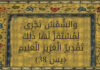Di era digital yang menuntut setiap orang untuk terus bersuara dan mengomentari, keheningan menjadi sebuah kemewahan yang langka. Di tengah hiruk pikuk informasi, sebuah sunnah yang sering terlupakan justru menawarkan kekuatan: keutamaan diam (الصمت, ash-shamt). Jauh dari anggapan sebagai sikap pasif, disiplin spiritual ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ini bukanlah ajakan untuk membisu total, melainkan undangan untuk menemukan kembali kebijaksanaan dalam memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam.
Baca Juga: Menjaga Lisan di Era Digital: Etika Komentar dan Kritik Menurut Alquran
Fondasi Iman dan Lisan
Landasan utama dari etika lisan dalam Islam tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Analisis Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) terhadap hadis ini menyoroti statusnya sebagai jawami’ al-kalim (kalimat ringkas namun padat makna). Logikanya sangat kuat: hadis ini memberikan dua pilihan utama bagi seorang mukmin. Pilihan pertama dan utama adalah “berkata baik” dan pilihan kedua, jika yang pertama tidak dapat dipenuhi, adalah “diam”. Tidak ada pilihan ketiga untuk perkataan yang sia-sia atau batil (Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hlm. 455).
Kaidah biner yang tajam ini—berkata baik atau diam—berfungsi sebagai sebuah filter spiritual yang sangat relevan. Jika diterapkan pada linimasa media sosial, berapa banyak ucapan, komentar, atau status yang akan lolos dari saringan ini? Prinsip ini secara tidak langsung mendefinisikan “kebisingan digital” sebagai segala sesuatu yang berada di luar dua pilihan tersebut: ucapan yang tidak mengandung kebaikan.
Baca Juga: Lahwul Hadits dan Krisis Standar Hidup di Era Digital
Perintah untuk ‘Berkata Baik’
Sebelum menyelami keutamaan diam, penting untuk menggarisbawahi pilihan pertama yang diperintahkan oleh hadis tersebut: “berkata baik”. Ibn Hajar menegaskan bahwa kategori “kebaikan” ini mencakup “setiap perkataan yang dituntut oleh syariat, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah” (Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hlm. 447).
Ini adalah ranah di mana diam justru menjadi sebuah kesalahan. Termasuk dalam kategori “berkata baik” adalah menyuarakan kebenaran, memberikan kesaksian yang adil, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, serta menyuarakan kritik atau protes terhadap kezaliman secara beradab. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan hal ini dalam Surah An-Nisa’, ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah…”. Dengan demikian, sunnah diam tidak berlaku saat kebenaran perlu ditegakkan.
Rasionalitas Keutamaan Diam
Lantas, jika berkata baik begitu utama, mengapa diam seringkali disandingkan sebagai pilihan yang setara?
Al-Ghazali (w. 505 H) menawarkan sebuah rasionalitas yang mendalam. Beliau memaparkan betapa banyaknya “penyakit lisan” (afat al-lisan), yang mencakup kesalahan, kebohongan, ghibah, namimah (adu domba), riya, nifak, perkataan keji, perdebatan, dan berbicara dalam kebatilan. Semua ini, menurut Al-Ghazali, terasa ringan di lisan dan manis di hati (Abû Hâmid, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, hlm. 111).
Analisis Al-Ghazali ini seolah menjadi sebuah diagnosis dini bagi penyakit era digital, di mana “penyakit lisan” kini termutasi menjadi “penyakit jari” di papan ketik. Beliau lantas menyimpulkan dengan sebuah kaidah emas: “Maka dalam berbicara ada bahaya, dan dalam diam ada keselamatan.”
Baca Juga: Tafaqquh fi Digital dan Pedoman Bermedia Sosial dalam Alquran
Menjauhi Laghw sebagai Kriteria Falah
Al-Qur’an secara spesifik memuji hamba-hamba-Nya yang berhasil menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna atau sia-sia (اللغو, al-laghw). Sifat ini bahkan disebutkan sebagai salah satu karakteristik utama orang beriman yang akan meraih falah (keberuntungan).
Allah berfirman dalam Surah Al-Mu’minun, ayat 1-3: “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna…”
Ibn ‘Ashur (w. 1393 H) dalam analisisnya terhadap ayat ini, mendefinisikan laghw sebagai “perkataan yang batil” (al-kalam al-bathil). Beliau juga menyoroti hubungan indah antara khusyuk dalam salat dengan menjauhi laghw. Salat adalah bentuk perkataan terbaik (doa), maka orang yang terbiasa dengannya secara alami akan menjauhi perkataan yang batil (Ibnu ’Âsyûr, Al-Tahrîr wa al-Tanwîr, hlm. 10). Dalam konteks hari ini, laghw dapat berupa perdebatan tak berujung di kolom komentar. Kemampuan untuk “berpaling” dari kebisingan digital ini, menurut Al-Qur’an, adalah sebuah pencapaian spiritual.
Akuntabilitas Ucapan dan Konsekuensi Ukhrawi
Mekanisme internal untuk mampu menahan lisan adalah kesadaran akan akuntabilitas total. Allah SWT menegaskan prinsip ini dalam Surah Qaf, ayat 18: “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).”
Ibn ‘Ashur menjelaskan bahwa ayat ini mencakup setiap ucapan, sekecil apapun (Ibnu ’Âsyûr, Al-Tahrîr wa al-Tanwîr, hlm. 303). Prinsip akuntabilitas ini—bahwa setiap ‘tweet’ dan ‘comment’ akan ditimbang—menjadi rem paling kuat bagi lisan dan jari. Kesadaran ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi ad-Dunya (w. 281 H), di mana Rasulullah saw. ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, beliau menjawab: “Dua rongga: mulut dan kemaluan.” (Ibn Abī ad-Dunyā, Kitāb aṣ-Ṣamt wa Ādāb al-Lisān, hlm. 44).
Ini ditutup dengan hadis panjang kepada Mu’adz bin Jabal, di mana Rasulullah saw bersabda: “…Bukankah manusia tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka… tidak lain karena hasil (panen) lisan mereka?” (HR. Tirmidzi No. 2004).
Baca Juga: Penyakit Hati di Era Media Sosial: Hasad dan Terapinya
Penutup
Menghidupkan sunnah diam di era digital bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi apatis atau membisu di hadapan kezaliman. Sebaliknya, ia adalah sebuah disiplin untuk menguasai lisan. Hadis fundamental “berkata baik atau diam” mengajarkan sebuah filter spiritual: jika sebuah ucapan tidak termasuk dalam kategori “kebaikan”—seperti menegakkan keadilan atau memberi nasihat—maka diam menjadi pilihan yang lebih bijaksana dan menyelamatkan. Ini adalah tentang mengalihkan energi dari kebisingan laghw yang tak berkesudahan, agar saat benar-benar perlu bicara, suara yang keluar adalah suara kebaikan yang bergema dan bermakna. Wallahu a’lam.