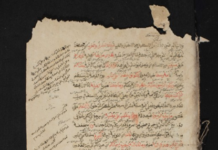Dalam perjalanan panjang sejarah tafsir, para mufassir sering hadir bagaikan para penjelajah yang membawa lentera masing-masing. Ada yang datang dengan cahaya bahasa, ada yang memegang lentera fikih, dan ada pula yang membawa cahaya teologi. Lentera itu bukan sekadar alat penerang, namun menjadi cara pandang, sudut melihat, dan pintu masuk untuk memahami ayat-ayat Alquran. Sepertinya halnya al-Zamakhsyari dan al-Dhahabi.
Baca Juga: Pertemuan Unik Najmuddin al-Nasafi dengan al-Zamakhsyari
Al-Zamakhsyari menjadi sosok yang menonjol karena ketajaman analisis kebahasaannya dan kecemerlangannya dalam balaghah. Namun lentera yang ia bawa bukan hanya bahasa, tetapi juga keyakinan teologis Mu’tazilah, yang memengaruhi cara ia memahami ayat-ayat tentang sifat Tuhan dan hubungan kuasa antara manusia dan Sang Pencipta.
Berabad-abad setelahnya, Husayn al-Dhahabi muncul sebagai pengamat tajam dalam al-Tafsir wa al-Mufassirun. Ia menguliti tafsir para ulama klasik, menimbang seberapa besar warna mazhab mereka mewarnai pemahaman terhadap Alquran. Ketika matanya tertuju pada Al-Kashshaf, ia mendapati al-Zamakhsyari sebagai mufassir brilian yang, menurutnya, terlalu sering membiarkan akidah Mu’tazilah mendikte arah tafsirnya.
Di titik inilah muncul pertanyaan penting, apakah kritik al-Dhahabi benar-benar objektif? Ataukah ia sendiri membawa bias teologis yang membuat penilaiannya tidak sepenuhnya netral? Untuk memahami persoalan ini, kita perlu masuk ke dalam dinamika tafsir itu sendiri.
Baca Juga: Melihat Respon Adz-Dzahabi atas Perdebatan Tafsir Nabi
Al-Zamakhsyari memulai langkahnya dengan prinsip yang sangat indah dan luas diakui, bahwa ayat-ayat mutasyabih harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam. Prinsip yang terdengar sederhana ini ternyata bisa menghasilkan ragam tafsir ketika bertemu teologi. Dalam kasus ayat-ayat ru’yatullah, misalnya, al-Zamakhsyari memandang bahwa ayat “Tidak dapat dicapai oleh penglihatan” adalah ayat muhkam yang menegaskan ketidakmungkinan melihat Tuhan. (Al-Zamakhsyari, Al-Kashshaf, 340-341)
Ia kemudian menafsirkan ayat “memandang kepada Tuhannya” sebagai bentuk “menanti karunia”. Dari sudut pandangnya, ini menjaga kemurnian konsep tanzih bahwa Tuhan tidak serupa makhluk. Namun al-Dhahabi melihat langkah ini sebagai bentuk keberpihakan teologis. Ia memandang bahwa al-Zamakhsyari memilih mana yang muhkam dan mana yang mutasyabih berdasarkan prinsip akidah, bukan berdasarkan nash semata. (al-Dhahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, juz 1, 321-322)
Namun ketika kita melihat tradisi tafsir yang lebih luas, kita justru menemukan ironi yang menarik. Para mufassir Sunni pun menafsirkan ayat ru’yatullah dengan warna akidah mereka. Mereka menerima ru’yatullah sebagai hakikat yang pasti, tetapi misterius tanpa kaifiyah. Bagi mereka, ayat itu adalah muhkam, bukan mutasyabih. Pada titik inilah terlihat bahwa bukan hanya al-Zamakhsyari yang memakai kacamata teologis, namun hampir semua mufassir melakukannya. Teologi bukan lapisan tambahan yang datang belakangan, ia adalah kacamata yang dipakai sebelum mereka membaca ayat-ayat dalam Alquran.
Baca Juga: Biografi Al-Zamakhsyari: Sang Kreator Kitab Tafsir Al-Kasysyaf
Perjumpaan tafsir dan teologi kembali terlihat ketika kita membaca ayat tentang apakah Allah memerintahkan perbuatan buruk. Di satu sisi, ada ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah tidak memerintahkan kekejian.[QS. al-A’raf/7: 28] Namun di sisi lain, ayat yang menggambarkan Allah “memerintahkan” para pembesar suatu negeri lalu mereka berbuat fasik memberi kesan sebaliknya.[QS al-Isra’/17: 16]
Al-Zamakhsyari, dengan teologi keadilan Tuhan yang menjadi nadi Mu’tazilah, memahami kata Amarna> dalam ayat tersebut sebagai pemberian nikmat yang membuat mereka sombong, bukan perintah moral untuk berbuat buruk. (Al-Zamakhsyari, Al-Kashshaf, 592-593) Di mata al-Dhahabi, ini adalah takwil yang terlalu jauh.
Namun dalam sejarah kalam, takwil seperti ini bukan hal asing. Para mufassir dari berbagai mazhab juga melakukan hal serupa ketika ayat tampak bersinggungan dengan prinsip teologis mereka. Maka pertanyaan itu kembali muncul: apakah al-Dhahabi membaca teks atau membaca teologi aliran lain melalui standar Sunni yang ia yakini?
Di sinilah bagian menarik dari dialog panjang antara kedua tokoh ini. Kritik al-Dhahabi kepada al-Zamakhsyari memang memiliki dasar yang kuat. Ia benar bahwa al-Zamakhsyari sering kali menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan kerangka Mu’tazilah. Namun pada saat yang sama, al-Dhahabi juga membawa lenteranya sendiri, yaitu lenteranya Ahlus Sunnah yang membuatnya melihat al-Zamakhsyari dari sudut tertentu. Dua bias bertemu, dan justru dari pertemuan itulah lahir pemahaman yang lebih jernih tentang bagaimana tafsir bekerja.
Baca Juga: Inilah Perbedaan Periodesasi Tafsir Al-Qur’an Husain Al-Dzahabi dan Ignaz Goldziher
Ketika kita menyingkap tirai tebal ini, kita menemukan kenyataan yang sudah lama hadir tetapi jarang diakui, bahwa tidak ada tafsir yang benar-benar netral. Setiap mufassir datang dengan pengalaman, kepercayaan, asumsi, pendidikan, dan cara pandang tertentu. Bahkan ketika mereka ingin objektif, cahaya dari lenteranya tetap memengaruhi cara mereka membaca teks. Tetapi ketidaknetralan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari keberagaman inilah tafsir Alquran tumbuh menjadi bidang yang kaya, luas, dan penuh dinamika.
Al-Zamakhsyari memberi kita ketekunan dalam bahasa dan keberanian dalam logika. Al-Dhahabi memberi kita kewaspadaan dalam membaca dan kesadaran bahwa setiap tafsir lahir dari kecenderungan tertentu. Keduanya, dengan perbedaan yang tajam sekalipun, sama-sama menunjukkan bahwa perjalanan memahami Alquran adalah perjalanan manusia mendekati wahyu dengan segala perangkat yang ia miliki. Tafsir, pada akhirnya, bukan arena siapa yang menang atau kalah. Ia adalah ruang dialog, ruang perjumpaan antara teks yang suci dan akal yang terus mencari. Dan mungkin justru dalam perbedaan itulah kita menemukan keluasan rahmat Alquran. Rahmat yang terus hidup, bergerak, dan menyinari siapa pun yang datang dengan hati yang ingin memahami.