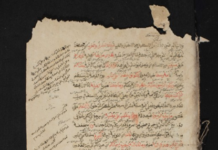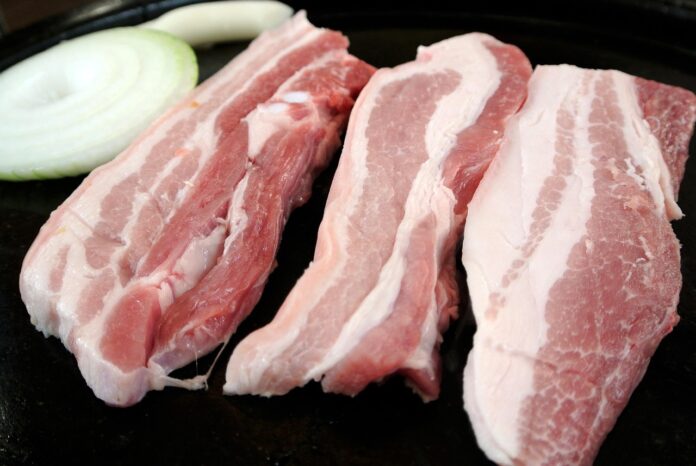Tulisan ini bermula dari keresahan yang menghantui penulis beberapa hari terakhir. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyimpan kompleksitas teologis: mengapa babi diharamkan dalam Al-Qur’an? Lebih jauh lagi, apakah benar kata khinzir yang termaktub di dalamnya benar-benar menunjuk pada makna “babi” sebagaimana kita pahami kini? Apakah bangsa Arab abad ke-6 M, yang hidup di lingkungan semi-gurun dan nyaris tanpa habitat babi, memahami hewan ini secara konseptual dan empiris?
Pertanyaan pertama muncul saat penulis berbelanja di sebuah supermarket di Freiburg, Jerman. Daging babi dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan sapi, kerbau, bahkan ayam. Sebagai seorang santri yang berpegang pada prinsip frugal living, tentu muncul godaan batin sederhana, “Andai babi itu halal, betapa hemat pengeluaran saya.” Hehehe.
Namun keresahan itu berlanjut pada tataran linguistik dan teologis. Bahasa Al-Qur’an adalah bahasa Arab abad ke-6, yang senantiasa mengalami pergeseran makna (semantic shift). Sebagaimana kata sayyārah yang dalam Al-Qur’an bermakna “kafilah dagang” (Yūsuf: 19), tetapi kini berarti “mobil,” demikian pula kata khinzīr perlu diuji: apakah ia sudah bermakna “babi” di masa pewahyuan, ataukah makna itu hasil interpretasi pasca-Qur’anik yang terbentuk melalui tradisi tafsir?
Baca juga: Apakah Bulu Babi Juga Diharamkan? Begini Pendapat Ulama Tafsir
Pertanyaan berikutnya menyangkut kapasitas kognitif audiens pertama Al-Qur’an. Jika khinzīr memang merujuk pada babi, sejauh mana bangsa Arab pada masa itu mengenal hewan tersebut? Adakah relevansi sosial dari larangan itu bagi komunitas Hijaz yang bahkan tidak berinteraksi langsung dengan spesies ini?
Tulisan ini berangkat dari tiga pertanyaan itu—linguistik, historis, dan teologis—dengan upaya memahami khinzīr bukan sekadar sebagai “babi,” melainkan sebagai tanda (signifier) dalam jaringan makna yang lebih luas dalam wacana Qur’anik.
Keharaman khinzir dalam Al-Qur’an
Kata khinzīr muncul empat kali dalam Al-Qur’an, selalu dalam konteks keharaman (2:173, 5:3, 6:145, dan 16:115). Semua ayat ini berasosiasi dengan verba ḥarrama (mengharamkan) atau turunannya (ḥurrimat, muḥarraman), menegaskan satu posisi tegas Al-Qur’an terhadap hewan ini.
Menariknya, tiga dari empat ayat tersebut tidak memiliki sabab al-nuzūl spesifik, melainkan berupa prinsip umum penyucian makanan (ṭayyibāt) dan penegasan batas halal-haram. Hanya QS. al-An‘ām: 145 yang memiliki konteks polemis: ia turun untuk menegur kaum musyrikin Arab yang mengharamkan sebagian makanan tanpa dasar wahyu.
Baca juga: Pro Kontra Tentang Hukum Babi Laut Menurut Ulama Tafsir
Artinya, larangan khinzīr muncul dalam wacana penyucian moral dan identitas keagamaan, bukan dalam konteks reaksi terhadap praktik memakan babi yang nyata di masyarakat. Hal ini memberi indikasi kuat bahwa keharaman babi bukan respons sosial, melainkan penegasan teologis—suatu indikasi bahwa memang “tradisi” mengkonsumsi babi sangat minor dalam realitas bangsa Arab kala itu.
Dalam perkembangan hukum Islam, para ulama menegaskan larangan itu sebagai ‘azīmah (ketentuan pokok) dan qaṭ‘iyy al-dalālah. Hampir tidak ada suara alternatif. Di tataran kultural, “keharaman babi” bahkan menempati posisi paling tinggi dalam kesadaran umat Islam—tergambar dalam ungkapan satir populer, “semua halal kecuali babi.” Larangan ini hidup bukan sekadar sebagai norma fikih, tetapi sebagai simbol identitas kolektif umat Islam terhadap dunia nonmuslim.
“Membayangkan” khinzir di era pewahyuan
Pertanyaan berikutnya: apakah bangsa Arab mengenal babi?
Secara ekologis, hewan ini memang tidak hidup di jantung Hijaz atau Najd. Namun, babi liar (Sus scrofa) telah lama hidup di wilayah Syro-Palestina, Yordania, dan Levant—kawasan yang memiliki relasi dagang, budaya, dan religi yang intens dengan Hijaz. Sejarawan zoologi dan arkeozoologi mencatat bahwa babi liar merupakan satwa umum di Levant sejak milenium pertama SM.
Maka, kemungkinan besar pengetahuan tentang babi diimpor melalui kontak kultural antara Arab dan masyarakat Syam. Dengan demikian, khinzīr dalam Al-Qur’an bisa jadi merepresentasikan pengetahuan pinjaman (borrowed knowledge) yang sudah cukup dikenal secara konseptual, meski tidak berakar dalam pengalaman hidup masyarakat Hijaz.
Khinzīr sebagai penegasan teologis: “Syar‘u Man Qablanā”
Dari perspektif teologi wahyu, boleh jadi (asumsi penulis) larangan khinzir dalam Al-Qur’an bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari hukum Abrahamik terdahulu (syar‘u man qablana).
Dalam Taurat, larangan itu bersifat eksplisit:
וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה וְהוּא גֵרָה לֹא־יִגָּר טָמֵא הוּא לָכֶם
“Dan babi (ḥăzîr), karena berkuku belah dua tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.”
(Imamat 11:7)
Begitu pula dalam Yesaya 65:4:
הָאֹכְלִים בְּשַׂר הַחֲזִיר וְהַמַּרְק פִּגּוּלִים כְּלֵיהֶם
“Mereka makan daging babi (bĕśar ha-ḥăzîr), dan kuah yang najis ada dalam bejana mereka.”
Baca juga: “Unta Masuk Lubang Jarum” dalam Tradisi Yudaisme dan Kristen
Kata ḥăzîr berakar dari akar Semitik ḥ–z–r yang berarti “mengendus/menggali tanah,” sesuai perilaku babi mencari makanan dengan moncong.
Kata Ibrani ḥăzîr (חזיר) berasal dari akar Semitik ḥ–z–r yang berarti “menggali atau mengendus tanah,” sesuai perilaku babi mencari makanan.
Dalam Aram (bahasa Yesus) disebut ḥazīrā, dan dalam Arab menjadi khinzīr—pergeseran fonetik dari ḥ ke kh yang umum dalam evolusi bahasa Semitik Barat.
Korelasi etimologis ini menunjukkan bahwa larangan terhadap babi merupakan tradisi hukum lintas wahyu, bukan monopoli Islam. Maka, kehadiran kata khinzīr dalam Al-Qur’an bukan sekadar hukum makanan, tetapi pernyataan teologis bahwa Islam berdiri dalam kesinambungan dengan risalah-risalah sebelumnya.
Dimensi identitas dan simbolisme
Larangan khinzīr dapat dibaca sebagai tanda identitas dan diferensiasi (symbolic boundary marker) antara komunitas Muslim dan komunitas non-Muslim.
Sebagaimana disampaikan Fredrik Barth dalam teorinya tentang batas etnis, identitas kelompok dipelihara bukan oleh keseragaman internal, tetapi oleh garis batas yang membedakan “kita” dari “mereka.”
Dengan demikian, khinzīr dalam Al-Qur’an tidak semata larangan biologis, tetapi juga penegasan perbedaan epistemik—antara yang ṭayyib (bersih) dan khabīṯ (najis), antara umat wahyu baru dan warisan hukum lama yang disalahpahami.
Dari perspektif semiotika Qur’an, khinzīr berfungsi sebagai metasign—tanda yang menunjuk pada dunia simbolik kebersihan, ketaatan, dan loyalitas teologis terhadap sumber wahyu yang satu. Ia bukan sekadar hewan, tetapi sebuah konsep yang menandai kesucian moral dan keutuhan identitas iman.
Penutup
Berdasarkan telaah filologis, historis, dan teologis, khinzīr dalam Al-Qur’an hadir bukan sekadar sebagai nama hewan, melainkan sebagai tanda teologis dalam wacana wahyu. Meskipun babi tidak hidup di jantung Hijaz, istilah ini tidak asing bagi masyarakat Arab karena dikenali secara konseptual melalui interaksi budaya dengan wilayah Syam dan Levant.
Larangan terhadapnya tidak bersifat ekologis atau medis, tetapi merupakan penegasan kesinambungan risalah ilahi—kelanjutan hukum Abrahamik yang ditegaskan kembali oleh Al-Qur’an. Dengan demikian, khinzir menjadi simbol identitas yang membedakan yang suci dari yang profan, ṭayyib dari khabīṯ, serta menandai loyalitas teologis umat terhadap Tuhan. Ia adalah tanda linguistik yang menjembatani bahasa antarwahyu, simbol kesucian moral, dan representasi kontinuitas kenabian dalam sejarah tauhid.




![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)