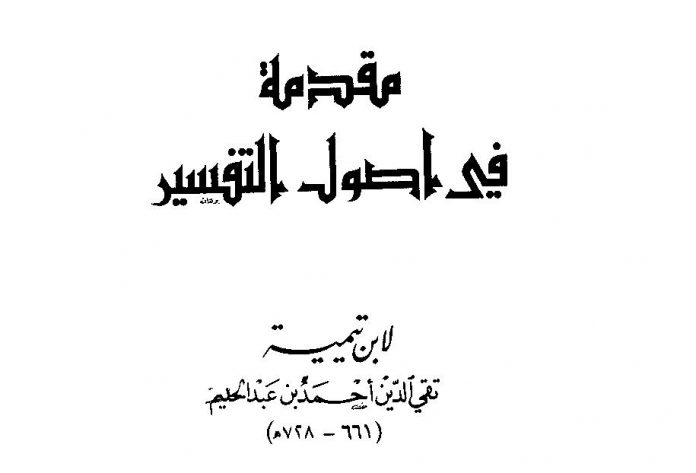Tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya menguak makna, maksud, hikmah yang terdapat dalam Alquran. Namun, ternyata tidak semua penafsiran juga bisa dijadikan acuan dalam memahami Alquran. Sebab, kadang ditemukan penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan rambu-rambu ilmu tafsir dengan segala perangkatnya, bahkan terkadang bertentangan dengan akal manusia. Oleh karenanya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mencoba mencari jalan tengah dalam masalah ini dengan cara mengklasifikasikan tingkatan kredibelitas Alquran dalam tiga tingkatan sebagaimana yang dituangkannya dalam kitabnya yang berjudul, Muqaddimah fi Usul al-Tafsir.
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tafsir yang paling bisa dipertanggungjawabkan ada tiga. Pertama, “an yufassara al-Qur’an bi al-Qur’an” Alquran dijelaskan dengan dirinya sendiri. Kedua, “an yufassara al-Qur’an bi al-Sunnah” Alquran dijelaskan dengan al-Sunnah. Ketiga, “bi aqwal al-Sahabat” Alquran dijelaskan dengan perkataan para sahabat nabi. (Taqiyuddin Ibn Taimiyah, Muqaddimah fi Usul al-Tafsir, hlm. 20-21)
An Yufassara al-Qur’an bi al-Qur’an
Ibnu Taimiyah meletakkan metode penafsiran ini pada predikat pertama bukan tanpa alasan. Paling tidak, dapat dijumpai beberapa argumentasinya -baik berasal dari internal maupun eksternal pengetahuannya- yang mendukung metode ini sebagai pemegang predikat pertama. Dalam disertasi yang ditulish oleh Nurcholish Madjid misalnya. Ibn Taimiyah mengatakan, bahwa satu-satunya hujjah yang akan mengantarkan kepada kebenaran hanyalah Alquran.
Meski terbilang sangat ekstrim, dan memberi kesan bahwa Ibnu Taimiyah menampik penggunaan rasio dalam penafsiran. Justru argumentasi yang disodorkannya memang benar adanya. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa argumen. Pertama, Ia memandang, bahwa sakralitas Alquran sebagai kalamullah patut diakui kredibelitasnya sebagai kitab yang akan mengantar kepada kebenaran. Karena, Alquran dianggapnya sebagai wahyu yang diturunkan kepada orang yang dikehendaki (yang dalam hal ini adalah nabi Muhammad saw). Jadi, dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an yang disampaikan oleh nabi Muhammad kepada umatnya merupakan firman Allah juga bukan merupakan karyanya sendiri dan jelas terlepas dari segala kepentingan. (Taqiyuddin Ibn Taimiyah, al-Tafsir al-Kabir, juz.5, hlm. 175).
Baca Juga: Kritik Ignaz Goldzhiher Terhadap al-Tafsir bi al-Ma’tsur
Kedua, apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah memberi pesan bahwa sebenarnya kebenaran itu merupakan hal yang potensi subjektivitasnya lebih dominan daripada potensi objektivitasnya. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Farag Fouda, seorang aktivis Mesir yang mati terbunuh. Dalam magnum opus nya, al-Haqiqah al-Ga’ibah (kebenaran yang hilang), Fouda mengatakan “bahwa manusia hari ini lebih memilih mendengarkan, setuju dengan apa yang mereka sukai”. (lihat, Farag Fouda, al-Haqiqah al-Ga’ibah, hlm. 5). Apa yang disampaikan oleh Fouda jelas menggambarkan bahwa kebenaran di mata manusia sangatlah subjektif, karena hanya berbasis perasaan dan justru mengesampingkan objektivitas. Dan ini semakin mendukung pernyataan Ibn Taimiyah, bahwa al-Qur’an yang merupakan kalam Allah merupakan sumber kebenaran yang mutlak.
An Yufassara al-Qur’a>n bi al-Sunnah
Sebagai utusan yang diamanati menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, ini menjadikan nabi Muhammad mempunyai intensitas “kedekatan” dengan Allah. Karena itu pula, tindak-tanduk nabi selalu dalam naungan ila>hiyah. Sehingga, tak jarang Alquran sendiri juga menyatakan hal yang senada dengan narasi tersebut, seperti yang teretera dalam QS. Al-Najm : 3-4.
Sunnah, secara bahasa adalah jalan. Sedangkan, sunnah dalam perspektif terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad baik dari perkataan ucapan maupun ketetapan. (lihat, Muhammad ibn Alwi al-Maliki, al-Qawa’id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadis, hlm. 10). Kedekatan yang “intens” dengan Tuhannya, ditambah lagi mengemban amanah untuk menyampaikan Alquran kepada umatnya menjadikan pribadi nabi Muhammad harus mempunyai dimensi keselarasan dengan apa yang dibawanya. Sehingga, begitu Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak nabi Muhammad, ia menjawabnya dengan “ka>na khuluquhu al-Qur’an” (akhlaknya nabi Muhammad adalah al-Qur’an).
Senada dengan pernyataan diatas, ada anggapan yang menyatakan bahwa sunnah nabi merupakan wahyu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Musa’id Sulayman al-Tayyar dalam kitab syarah nya terhadap kitab Muqaddimah nya Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan, bahwa al-Sunnah merupakan wahyu. Sebab, manakala al-Qur’an itu disebut dengan wahyu, harusnya al-Sunnah juga disebut dengan wahyu, karena apa yang tertera dalam al-Qur’an termanifestasi dalam akhlak nabi Muhammad. (Musa’id Sulayman al-Tayyar, Syarh Muqaddimah fi Usul al-Tafsir li Ibn Taimiyah, hlm. 253).
An Yufassara al-Qur’an bi Aqwal al-Sahabat/bi al-Ijtihad
Suatu ketika, sahabat Mu’az ibn Jabal ditanya oleh Rasulullah, dengan (landasan) apa kamu menghukumi sesuatu? Mu’az menjawab, dengan al-Qur’an. Rasul bertanya lagi, jika kamu tidak menemukannya dalam al-Qur’an? Mu’az menjawab, dengan al-Sunnah. Rasul kembali bertanya, jika kamu tidak menemukannya dalam al-Sunnah? Aku akan menggunakan ijtihad melalui akal ku. (Musa’id Sulayman al-Tayyar, Syarh Muqaddimah fi Usul al-Tafsir li Ibn Taimiyah, hlm. 253-254).
Dialog nabi Muhammad dengan sahabat Mu’uz ibn Jabal memberi pesan bahwa akal mempunyai peranan penting dalam mengambil sebuah tindakan. Ditambah lagi, dalam narasi tersebut, penggunaan akal dalam memutuskan sesuatu diapresiasi dengan memasukkannya setelah sumber primer umat Islam dalam bertindak-tanduk, yakni, al-Qur’an dan al-Sunnah. Dari apa yang disampaikan oleh sahabat Mu’a>z} ibn Jabal juga menghadirkan rumus turunan yang juga diakui oleh al-Qunawi (w.1195 H).
Dalam kitabnya, Hasyiyah al-Qunawi, ia mengatakan “sesungguhnya teks-teks (al-Qur’an dan al-Sunnah termasuk di dalamnya) itu berkata, sedangkan akal itu memberi persaksian” redaksi aslinya : “Anna al-Nususa Natiqah, wa al-‘Uqul Syahidah”. Apa yang diungkapkan oleh al-Qunawi sangat metaforis. Sebab, seharusnya perkataan itu disambut dengan pendengaran, bukan persaksian. Lantas, apa maksud al-Qunawi menganalogikannya seperti demikian? (Ismail ibn Muhammad al-Qunawi, Hasyiyah al-Qunawi, juz.1, hlm. 22)
Baca Juga: Pemahaman Anak Allah dalam Perspektif Alkitab dan Al-Qur’an
Tidak ada salahnya jika al-Qunawi menganalogikannya seperti demikian. Justru, al-Qunawi semakin mempertegas vitalitas posisi akal dalam memutuskan sesuatu. Hal ini tergambarkan dalam ungkapannya yang berbunyi “sedangkan akal itu menyaksikan”. Ini memberi pesan, bahwa untuk memahami makna tersirat dalam sebuah teks, alat cerna yang mampu mengurainya secara jelas dan gamblang adalah akal, bukan telinga atau indera yang lain.
Selain itu, penggunaan akal dalam mengurai sesuatu juga diapresiasi penuh oleh Ibn Taimiyah. Hal ini diungkapkannya dalam kitabnya yang berjudul Dar’ Ta’arudl al-‘Aql wa al-Naql. Di bagian awal kitabnya, ia menceritakan motif dibalik pembuatan kitab ini. Ia mengatakan, bahwa kitab ini dibuat sebagai kritik terhadap internal umat muslim yang begitu mendewakan penggunaan akal, tetapi mengesampingkan penggunaan teks-teks keagamaan. Oleh karenanya, Ibn Taimiyah menyerupakan mereka dengan kaum Nasrani yang juga begitu mendewakan akalnya, sehingga menolak teks-teks keagamaan mereka, yang dalam hal ini adalah Injil. (Ibn Taimiyah, Dar’ Ta’arudl al-‘Aql wa al-Naql, juz.1, hlm. 6)
Baik al-Qunawi maupun Ibn Taimiyah maksudnya sama, sama-sama mempertimbangkan akal sebagai landasan dalam mengurai, memutuskan, menafsirkan sesuatu. Namun, keduanya juga menggarisbawahi, bahwa penggunaan akal harus dibarengi dengan teks-teks keagamaan. Ini menurut Ibn Taimiyah, akan mengantarkan kepada kebenaran yang hakiki (tidak bercampur dengan hawa nafsu manusia). (Nurcholish Madjid, Ibn Taimiyah tentang Kalam dan Falsafah, hlm. 72) Wallahu A’lam.