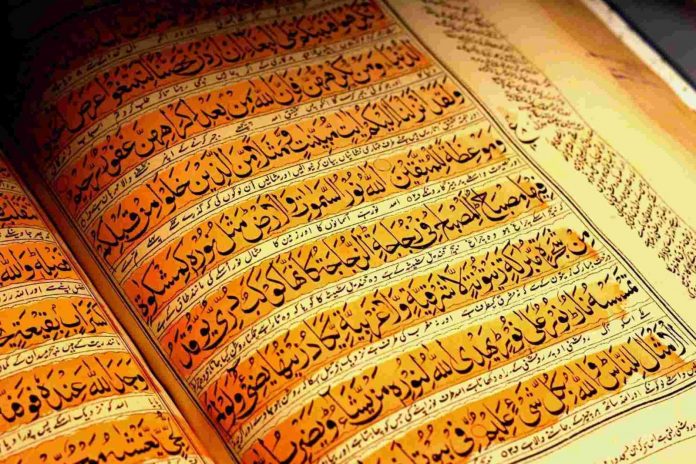Dalam lima tahun terakhir ini, sepanjang studi saya tentang penerjemahan al-Qur’an, saya merasakan betapa menjadi penerjemah al-Qur’an adalah pekerjaan yang berat. Apa yang menjadikannya berat? Yang membuat berat adalah teks yang diterjemahkan, yakni kitab suci. Pemeluk agama yang memiliki kitab suci, di satu sisi, menyakini misi penyebarkan firman Tuhan. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi kebingungan. Kata-kata atau firman di dalam kitab tersebut bersifat suci (holy). Tidak mungkin menggantikannya atau mencarikan padanannya (equivalency).
Padahal penerjemahan itu pada hakikatnya tidak hanya sekadar mengganti makna-kata dari bahasa asli ke makna-kata bahasa sasaran. Tetapi juga melakukan rekonstruksi struktural di mana makna-makna-kata bahasa sumber tersebut melekat. Di dalam kitab suci, pilihan kata, struktur kalimat, gaya bertutur, dan sebagainya dinilai suci. Sehingga menggantikan pilihan kata, struktur kalimat, gaya bertutur teks kitab suci beresiko mendapatkan kritik dan bahkan hujatan.
Dalam studi penerjemahan al-Qur’an sering muncul frasa “translating the untranslatable” atau “menerjemahkan yang tak-bisa-diterjemahkan”. Sebab ada incompatibility (tidak kompatible) antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Makanya, tidak semua agama menyukai penerjemahan atas kitab sucinya sebab aspek kesucian bahasa kitab tersebut. Di sinilah menerjemahkan kitab suci menjadi pekerjaan yang berat.
Baca Juga: Al-Qur’an Terjemah Bahasa Bali Pertama: Cakepan Suci Al-Qur’an Salinan Ring Basa Bali
Tarif Khalidi, seorang penerjemah al-Qur’an ke dalam bahasa Inggris, membagikan pengalamannya sebagai penerjemah al-Qur’an. Pengalaman tersebut, ia tuangkan dalam sebuah tulisan berjudul Reflections of Qur’an Translator (2013). Menurutnya, ada tiga beban berat dalam menerjemahkan al-Qur’an.
Pertama, adalah menentukan pilihan kata atau frasa pengganti kata atau frasa bahasa sumber. Memilih yang terbaik dari beberapa pilihan kata yang ada. Dalam konteks Indonesia misalkan, tim penerjemah al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama, pasti melakukan perdebatan yang sengit ketika menerjemahkan kata qawwamun (QS. An-Nisa [4]:34). Edisi-edisi awal (1965, 1971 hingga 1990) menerjemahkan qawwamun dengan pemimpin. Sedangkan edisi 2002, mengganti terjemah pemimpin dengan pelindung. Dan di edisi terakhir (2019), mengganti pelindung dengan penanggungjawab. Untuk menentukan pemimpin, pelindung dan penanggungjawab tentu melewati sekian perdebatan (dispute), apalagi al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama ini disusun oleh tim (terdiri dari banyak orang). Pilihan kata yang tidak tepat (tidak yang terbaik) hanya mengakibatkan kritik dan bahkan hujatan. Pilihan kata pemimpin, dihujat oleh generasi reformis sebagai bentuk terjemah bias gender.
Kedua, menerjemahkan, khususnya menerjemahkan al-Qur’an itu seperti legenda Sisyphus (Sisyphean activity). Kisah Sisyphus dalam mitologi Yunani mengajarkan tentang aktivitas kesia-sian dan absurditas (sesuatu yang mustahil). Jadi, menerjemahkan al-Qur’an itu sia-sia atau pasti akan selalu ada yang kurang.
Kata Tarif Khalidi: “akan selalu ada rasa sesal setelah menyerahkan draft terjemah al-Qur’an ke penerbit untuk dicetak.” Sama seperti perpisahan dengan orang yang kita cintai, kita selalu menyesal dan merasa ada yang kurang dalam pembicaraan terakhir setelah perpisahan itu terjadi. “Oh, harusnya tadi saya bilang begini, begitu….” “Oh harusnya saya memberikan ini dan itu.” Selalu ada penyesalan dan kekecewaan setelah berpisah.
Ketiga, beban yang bersifat filologi. Filologi dalam makna kajian bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, terutama terkait dengan maknanya. Sudah banyak kamus-kamus tentang kosa-kata al-Qur’an yang ditulis dan sudah menjelaskan secara baik bagaimana term-term al-Qur’an dipahami jika dilacak dari bahasa aslinya seperti Syiriac, Ethiopic, Yunani dan lain-lain. Dan ini akan terus berkembang, menghasilkan makna-makna yang baru dalam memahami pesan al-Qur’an.
Misalnya, Tarif Khalidi, menceritakan temannya yang ahli Bio-Kimia, bahwa Tairan Ababil bukan bermakna burung yang berbondong-bondong, tetapi sesuatu yang mirip dengan benda-benda berapi yang berterbangan, yakni erupsi vulkanik akibat dari Ashabul Fiil (tentara gajah) tersebut. Dan masih banyak contoh yang lainnya.
Dari tiga beban tersebut, tampaklah bahwa pekerjaan menerjemahkan al-Qur’an adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang harus dikerjakan dalam “kesunyian”. Artinya: penerjemah akan bergelut, berdinamika di dalam dirinya sendiri untuk memilih makna, struktur dan gaya bahasa yang terbaik. Setelah pilihan ditentukan dan terjemahan selesai, penerjemah masih harus menghadapi banyak penilaian dan kritik. Dan yang paling parah, terkadang penerjemah itu tidak begitu dikenal, misalnya, bila dibandingkan dengan mufassir. Padahal, menerjemahkan pada hakikatnya juga menafsirkan.
Di sinilah penerjemah al-Qur’an sedang menempuh “jalan sunyi.” Dan biasanya, karya terjemah itu adalah karya puncak dari seseorang intelektual/sarjana, contoh saja Muhammad Marmaduke Piktchall dan Abdullah Yusuf Ali, karya terjemah mereka adalah karya puncak sebelum mereka meninggal. Di Indonesia, mungkin ada Djohan Effendi yang menerjemahkan Juz Amma secara puitis dan diterbitkan bersamaan dengan karya tafsir ijmalinya, beberapa tahun sebelum wafatnya di Australia.
Selain itu, perkembangan penerjemahan yang semakin membludak di abad ke-20 ini menuntut banyak penerjemahan al-Qur’an untuk pandai-pandai menyuguhkan banyak hal dalam terjemahnya. Mengingat penerjemah al-Qur’an tidak memiliki ruang yang banyak dalam menjelaskan hal-hal yang kontroversial dan sebagainya, sebagaimana yang mufassir miliki, maka penerjemah harus mencari cara, meskipun cara ini ada kelebihan dan kekurangannya.
Menurut Johanna Pink, penerjemah bisa membubuhkan keterangan penting di bodytext dengan memberikan tanda kurung (brecket) atau tanda hubung. Namun strategi ini terkadang bisa mengurangi keterbacaan (legibility) teks. Sebagai gantinya—masih menurut Johanna Pink—penerjemah bisa membubuhkan catatan kaki sebagai informasi tambahan atau alternatif terjemahan.
Namun, lagi-lagi ini tetap berisiko sebab pembaca biasanya mengabaikan catatan kaki tersebut. Jadi, serba salah. Belum lagi jika kemudian penerjemah dihadapkan pada klaim-klaim kebenaran atas kenyakinan tertentu dan juga dihadapkan pada konteks penafsiran yang lebih luas dan posisi loyalitasnya terhadap teks asli al-Qur’an. Jadi semakin ribet.
Baca Juga: Mengulas The Message of the Qur’an, Sebuah Karya Terjemah Sekaligus Tafsir
Walhasil, baik para penerjemah, maupun pengkaji penerjemah al-Qur’an, semua berkesimpulan bahwa menerjemahkan al-Qur’an itu tidak mudah. Namun, harus terus dilakukan dengan pertimbangan dakwah dan penyebaran ajaran-ajaran Islam. Dan Alhamdulillah, karya-karya terjemah al-Qur’an belakangan ditulis oleh para penerjemah yang menyadari akan hal tersebut: menyadari kekurangannya, menyadari betapapun bagusnya terjemahan tidak akan bisa menggantikan al-Qur’an, dan menyadari bahwa terjemahannya bukanlah yang terbaik.
Tulisan singkat ini, sebenarnya, akan menjadi pengantar bagi tulisan serial saya di portal tafsiralquran.id tentang sejumlah biografi pada penerjemah al-Qur’an. Saya merasakan betapa masih jarangnya tokoh-tokoh penerjemah al-Qur’an ini diangkat, dikenang, dikaji dan diapresiasi di hadapan sidang pembaca (publik), padahal kerja-kerja mereka merupakan amal jariyah bagi peradaban umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Silahkan simak, tulisan serial tentang tokoh-tokoh penerjemah al-Qur’an berikutnya. []



![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)