Salah seorang orientalis, Ignaz Goldziher dalam sebuah karyanya berjudul Madzahib al-Tafsir al-Islamiy, menyampaikan kritiknya terhadap Al-Qur’an. Menurutnya, sebagai sebuah kitab panduan syari’at yang diperoleh melalui proses pewahyuan, sudah semestinya tidak ditemukan ‘cacat’ ketidakserasian dan ketidakseragaman (idlthirab wa ‘adam al-tatsabbut) dalam narasi-narasinya.
Dalam ulasan panjangnya, kritik ini ia sampaikan seiring dengan adanya varian dialek (huruf), bacaan (qira’ah) dan cara penulisan (rasm) dalam Al-Qur’an. Ia lantas menyimpulkan bahwa akar permasalahannya terletak pada model dan pola penulisan Arab yang diikuti Al-Qur’an ternyata tidak disertai dengan titik dan harakat (al-naqth wa al-dlabth).
Menanggapi kritik ini, ‘Abd al-Fattah Isma‘il Syalabiy dalam Rasm al-Mushaf al-‘Utsmaniy mengungkapkan bahwa kritik Ignaz Goldziher ini merupakan kritik ahistoris terhadap Al-Qur’an. Dalam pengantar ulasannya, Syalabiy menekankan pentingnya mengetahui akar tradisi qira’ah Al-Qur’an, yaitu sunnah muttaba‘ah, untuk memahami konteks masalah yang tengah dikaji Goldziher.
Baca juga: Al-Quran dalam Pandangan Orientalis dan 3 Ajaran Islam yang Diadopsi dari Yahudi menurut Geiger
Sehingga menurutnya, qira’ah bukan sesuatu yang bisa dianalogikan satu dengan yang lainnya. Melainkan mengacu pada bagaimana Rasulullah Saw. memberikan pengajaran. Ketiadaan analogi dalam pembacaan ini juga memberikan pengertian bahwa teks Al-Qur’an yang tertulis bukan menjadi pondasi utama, tetapi sekali lagi, sunnah muttaba‘ah.
Mungkin pembaca menjadi bertanya-tanya. Jika demikian, mengapa dalam sebuah qira’ah shahihah terdapat syarat persesuaian terhadap rasm? Jawaban pertanyaan ini akan memberikan gambaran relasi antara qira’ah dan rasm Al-Qur’an sekaligus menjelaskan mengapa kritik yang disampaikan Ignaz Goldziher adalah ahistoris sebagaiman counter Syalabiy.
Sejarah Terbentuknya Relasi Qira’ah dan Rasm
Selisih pendapat umat Islam di Azerbaijan mengharuskan Khalifah ‘Utsman mengambil tindakan. Perpecahan yang pernah menimpa umat terdahulu tidak boleh terjadi pada umat Muhammad ini. Dibentuklah lajnah kodifikasi Al-Qur’an edisi kedua dengan Zaid bin Tsabit masih sebagai ketuanya.
Dalam melakukan tugasnya, lajnah anyar ini mempunyai panduan tersendiri. Diantaranya menyebutkan bahwa kodifikasi yang nantinya akan dilakukan ditulis berdasarkan rasm yang telah ditetapkan (taqrir) oleh Rasulullah Saw., dengan langkah tertentu yang mampu mengakumulasi semua model bacaan yang sah kewarid darinya. Dan menghilangkan segala atribut yang menempel pada huruf, seperti titik dan harakat, adalah salah satu ekspresi pengejawantahannya.
Namun demikian, hal ini belum cukup menghindarkan dari varian produk mushaf yang dihasilkan tim lajnah. Karena nyatanya tidak semua model bacaan mampu terakumulasi dalam satu bentuk penulisan. Paling tidak sejarah mencatat bahwa ada sedikitnya 4 hingga 6 mushaf yang akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam kala itu. Dan masing-masing mushaf, dikirim beserta satu sahabat qari’ sebagai agent of sunnah muttaba‘ah.
Dari delegasi dan mushaf ‘Utsmaniy ini lah kajian mengenai qira’ah dan rasm menjadi trending. Muncul pakar dan ahli dari berbagai wilayah yang menjadi pusat peradaban Islam kala itu, di Madinah ada Mu‘adz Al-Qari’ dan Ibn Syihab al-Zuhri; di Mekah ada ‘Ubaid bin ‘Umair dan ‘Atha’; di Kufah ada Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulamiy dan Zir bin Hubaisy; di Syam ada Al-Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumiy, dan tokoh laih di berbagai wilayah lainnya.
Di tengah meningkatnya jumlah kajian qira’ah dan rasm, konsistensi dan kualitas kajian harus dihadapkan pada masalah luasnya wilayah ekspansi Islam. Kemurnian lughat Arab mulai terkontaminasi dengan banyaknya penduduk non-Arab yang masuk Islam. Sebagai dampak nyata dari ini, dilakukan lah upaya pemberian titik dan harakat dalam Al-Qur’an (ulasannya dapat dibaca pada Sejarah Harakat dalam Mushaf Al-Qur’an Bagian 1 dan Bagian 2).
Entah bagaimana kemudian muncul varian qira’ah yang tidak sesuai dengan rasm mushaf ‘Utsmaniy. Para pakar dan ahli kemudian mencoba melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada dan menyepakati bahwa qira’ah dianggap sah apabila sesuai dengan rasm mushaf ‘Utsmaniy.
Kualifikasi ini ditetapkan mengingat penulisan yang dilakukan ‘Utsman dulu berisi klausul atas kompilasi terhadap seluruh qira’ah shahihah dari Rasulullah Saw. Sehingga ketika kini terjadi chaos terhadap orisinalitas qira’ah, giliran rasm mushaf ‘Utsmaniy yang menjadi validator atas ragam qira’ah shahihah.
Baca juga: Teori ‘Horizon of Expectation’ Hans Robert Jauss dan Resepsi Terhadap Al-Quran
Dan dari kualifikasi yang ada, hanya tujuh qira’ah saja yang dianggap sesuai. Ketujuh qira’ah ini adalah Abu ‘Amr al-Bashriy (w. 154 H.), Ibn Katsir al-Makky (w. 120 H.), Nafi’ al-Madiniy (w. 169 H.), Ibn ‘Amir al-Syamiy (w. 118 H.), serta Al-Kufiyyun: ‘Ashim (w. 128 H.), Hamzah (w. 156 H.) dan ‘Ali al-Kisa’iy (w. 189 H.).
Melihat ulasan yang ada, dapat dimengerti bahwa kritik Goldziher tidak berdasar pada sejarah tradisi Al-Qur’an, bahwa sunnah muttaba‘ah adalah inti dalam proses transmisi Al-Qur’an. Kritik yang disampaikannya justru menyajikan logika pemikirannya yang terbalik dalam memahami kemunculan teks tertulis Al-Qur’an, yang itu menjadi kesalahannya yang teramat fatal. Wallahu a‘lam bi al-shawab.



![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)









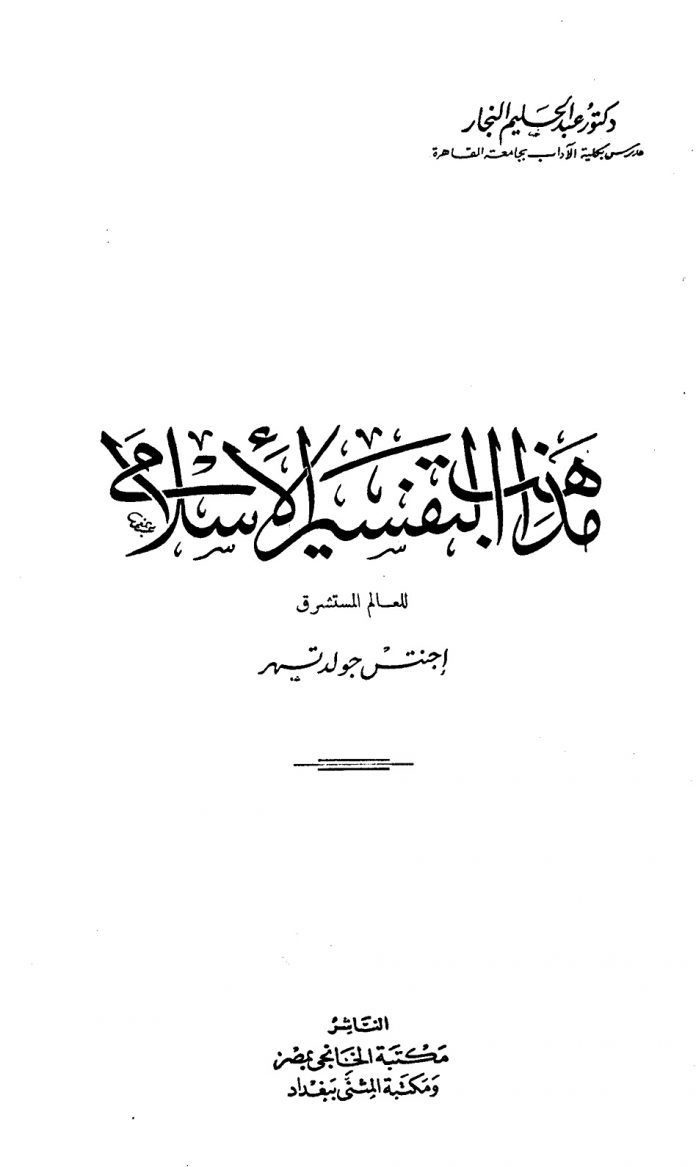



![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-100x70.png)

