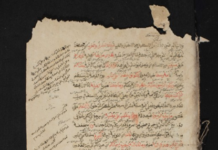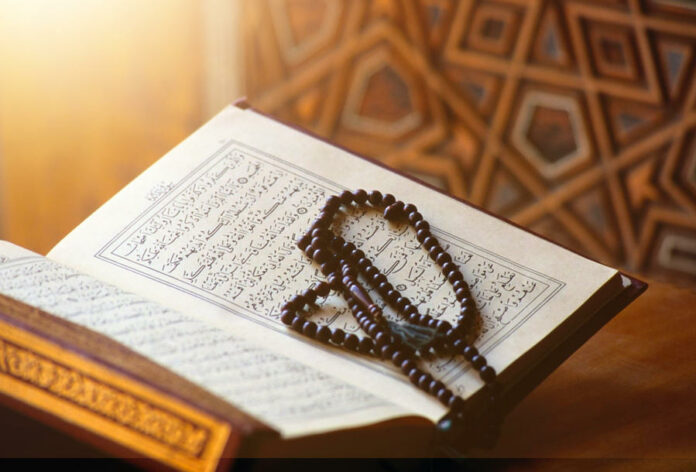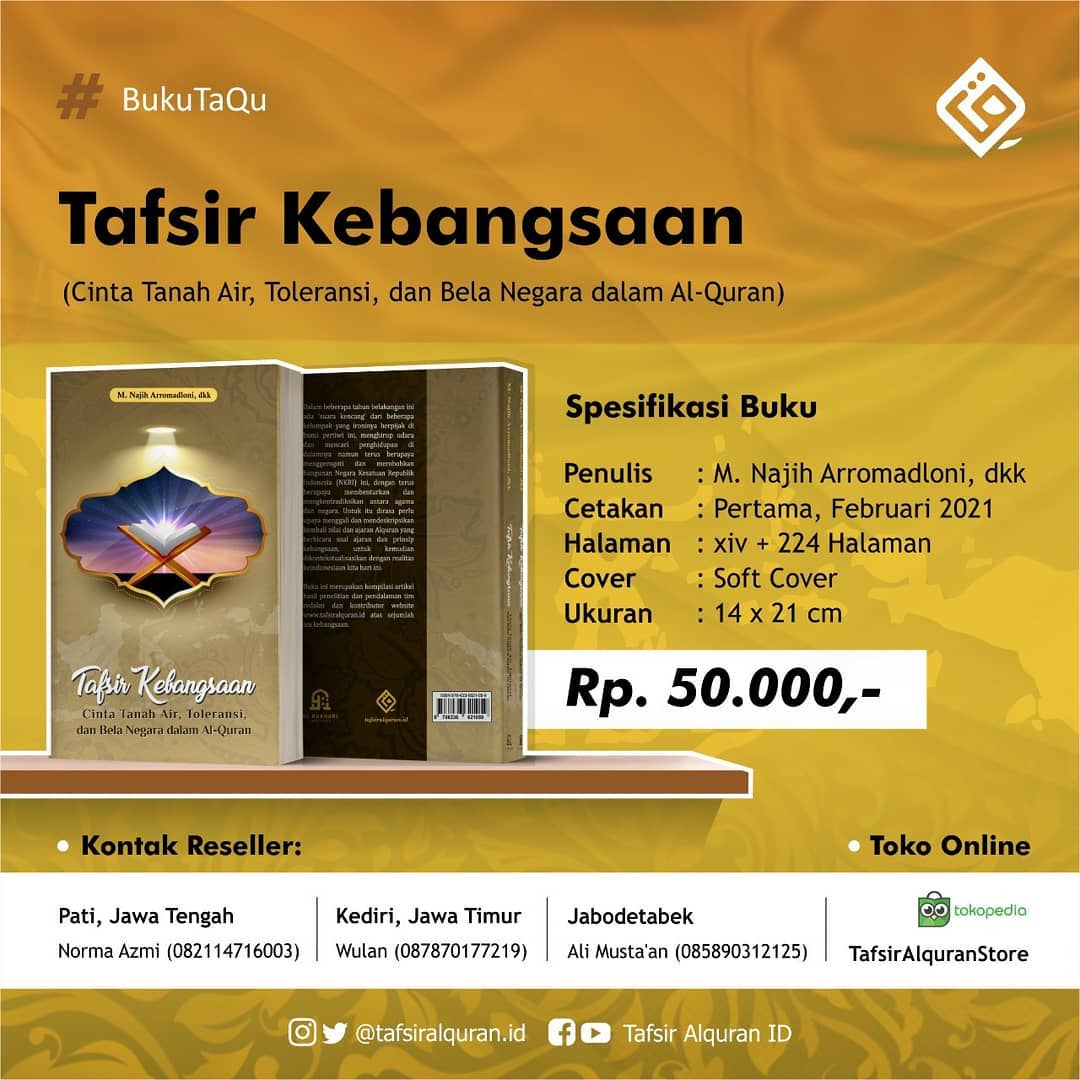Beberapa riwayat menyebutkan hadis yang menjelaskan mengenai penurunan Alquran dengan al-ahruf as-sab’ah. Beberapa pensyarah hadis menjelaskan makna al-ahruf as-sab’ah tersebut dengan tujuh qiraat.
Tujuh qiraat ini banyak yang mengaitkannya dengan dialek di sekitar tempat Alquran diturunkan. Sebagaimana dimaklumi bahwa beragam suku masyarakat Arab ketila itu. Selain suku Quraisy, ada suku Aus dan Khazraj, Bani Nadhir, Bani Qaynuqa’, dan masih banyak lagi. Perbedaan dialek dalam melantunkan ayat-ayat Alquran tersebut antara lain yang menyebabkan beragam qiraat.
Di antara banyak ragam qiraat tersebut, para ahli qiraat membedakannya lagi ke dalam dua kategori; terdapat qiraat yang diterima (qiraat maqbulat) dan qiraat yang tidak diterima (qiraat mardudat). Hal ini berdasarkan pada kajian tentang persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu qiraat.
Fahd al-Rumi dalam Dirasat Fii Ulum Al-Qur’an mengutip syi’ir Tayyibah an-Nasyr dari Ibn Jazari mengenai kajian qiraat,
فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهُ نَحْوِ # وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي
وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ # فَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأرْكَانُ
وَحَيْثُمَا يَخْتَلّ رُكْن أَثْبِتِ # شُذُوْذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِيْ السَّبْعَةِ
Syi’ir tersebut tidak lain adalah tentang syarat-syarat qiraat yang sahih, qiraat yang diterima.
Baca Juga: Mengenal Klasifikasi Qiraat dan Para Imam Madzhabnya
Syarat-syarat qiraat yang diterima
Qiraat yang sahih terdapat pada riwayat dari imam qiraat, baik tujuh imam (qiraat as-sab’ah) maupun sepuluh imam (qiraat al-‘asyrah) yang telah memenuhi syarat-syarat kesahihannya.
Syarat-syarat tersebut adalah; Pertama, sesuai dengan kaidah Bahasa Arab, meski dari satu aspek saja. Artinya, bahwa dalam menentukan bacaan suatu qiraat cukup dengan satu kaidah Bahasa Arab dari banyaknya kaidah Bahasa Arab yang berlaku. Aspek yang dimaksud disini adalah aspek kaidah nahwu.
Namun demikian, menurut Abu ‘Amr ad-Dani dalam kitabnya, Jami’ al-Bayan, para Imam Qiraat tidak mengutamakan kaidah Bahasa Arab dalam menentukan suatu qiraat, melainkan berdasarkan riwayat yang paling sahih. Hal ini karena qiraat adalah sunnah muttaba’ah (mengikuti sunah Nabi SAW) yang harus diterima dan didasarkan kepadanya.
Banyak ulama ahli nahwu mengingkari suatu qiraat disebabkan tidak sesuai dengan kaidah nahwu, tetapi pengingkaran mereka tidak dianggap karena qiraat tersebut disepakati oleh golongan salaf (sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in). Contohnya dapat kita lihat dalam Q.S. ss-Shaffat [37]: 123
وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِيْنَ
Kata الْيَاسَ dibaca washal
Kedua, qiraat harus sesuai dengan salah satu rasm mushaf Utsmani, baik secara sharih (jelas), maupun ihtimal (muatan). Saat proses penulisan Alquran di masa Utsman bin Affan, para sahabat menulis rasm Alquran dengan bentuk yang mencakup seluruh qiraat yang ada pada zaman Rasulullah saw. sehingga muncullah qiraat yang dibaca secara sharih (bacaan dan tulisan sama persis), maupun secara ihtimal atau dikira-kirakan (bacaan dan tulisan berbeda).
Perlu diketahui bahwa beberapa hasil kodifikasi pada masa Utsman bin Affan tersebut disebarkan ke kota-kota metropolitan, di antaranya Madinah, Bashrah, Kufa, Suria/ Syam. Pendapat lain, menambahkan kota Makkah, Yaman, dan Bahrain.
Contohnya terdapat Q.S. al-Fatihah [1]: 4
ملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
Yang bisa dibaca panjang maupun pendek pada mim lafadz ملِكِ.
Ketiga, sahih sanadnya. Menurut Ibnu al-Jauzi, yang dimaksud dari sanad yang sahih adalah qiraat tersebut diriwayatkan oleh orang yang adil, dan dlabith dari awal hingga akhir sanad. Sedangkan sebagian ulama ada yang mensyaratkan diterimanya suatu qiraat bukan hanya dari kualitasnya yang sahih tetapi juga mencapai derajat mutawatir. Ketika suatu qiraat telah mencapai derajat mutawatir, maka kedua syarat di atas tidak diperlukan lagi.
Baca Juga: Makna Tujuh Huruf (Sab’atu Ahruf) dalam Qiraat Al-Quran Menurut Ibn Qutaibah
Kemudian para ulama mengklasifikasi qiraat ke dalam beberapa macam. Menurut ulama ahli ushul fikih, qiraat terbagi menjadi dua macam, yakni qiraat mutawatir dan qiraat syadz atau ahad. Sedangkan menurut al-Bulqini, qiraat terbagi menjadi tiga macam, yakni mutawatir, syadz, dan ahad. Lalu as-Suyuthi menghimpun macam-macam qiraat dengan berdasarkan kepada perkataan Ibnu Jazari, bahwa qiraat terbagi menjadi enam macam.
Pertama, qiraat mutawatir yakni yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan mereka untuk berbohong dari awal hingga akhir sanad, dan diperbolehkan membacanya ketika salat. Contohnya dapat kita lihat dalam Q.S. al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi مَلِكِ يَومِ الدّيِنِ, baik dibaca panjang atau pendek mim dalam kalimat مَلِكِ, keduanya dinilai mutawatir.
Kedua, qiraat masyhur yakni yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai pada tingkatan mutawatir, sesuai dengan rasm mushaf Utsmani, dan sesuai dengan kaidah Bahasa Arab. Qiraat ini masyhur di kalangan para ulama, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan. Para ulama mengatakan qiraat ini boleh diamalkan bacaannya. Contohnya dapat kita lihat dalam qiraat yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far dalam Q.S. al-Kahfi ayat 51 dengan bunyi مَا أَشْهَدْناهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا dimana imam lain membacanya مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
Ketiga, qiraat ahad yakni yang sanadnya sahih, tetapi tidak sesuai dengan rasm mushaf atau kaidah Bahasa Arab atau tidak masyhur sebagaimana dua qiraat di atas. Qiraat ini tidak diperkenankan untuk dibaca dan tidak wajib diyakini.
Contohnya dapat kita lihat dalam qiraat yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadraknya dari jalur ‘Ashim dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi saw. membaca Q.S. ar-Rahman[55]: 76 dengan مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفَارِفَ خُضْرٍ وَعَبَاقَرِي حِسَان
Keempat, qiraat syadz yakni yang sanadnya tidak sahih atau yang tidak diriwayatkan dari rawi yang terpercaya atau dari rawi yang terpercaya tetapi tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Arab. Contohnya terdapat dalam Q.S. Yunus[10]: 92 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ yang dibaca فَالْيَوْمَ نُنَحِّيْكَ بِبَدَنِكَ. Qiraat ini tidak diperkenankan dibaca di dalam dan di luar salat dan tidak dinilai ibadah.
Kelima, qiraat maudu’ yakni yang tidak berdasar dan diriwayatkan tanpa sanad. Ibnu Jazari mengatakan bahwa qiraat ini adalah tertolak meskipun sesuai dengan kaidah Bahasa Arab dan rasm mushaf Utsmani. Contohnya dapat kita lihat pada qiraat yang dinisbatkan oleh al-Khuza’i kepada Abu Hanifah dalam Q.S. Fatir [35]: 28 yang dibaca إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ, padahal Abu Hanifah dinilai tidak pernah meriwayatkan demikian.
Keenam, qiraat mudraj yakni yang di dalamnya disisipi suatu penafsiran, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’[4]: 14 وَلَهُ أَخٌ اَوْ أخْتٌ yang kemudian disisipi dengan kalimat مِنْ أُمٍّ sebagai penjelas. Hukum qiraat ini tidak masuk dalam hitungan bacaan, tidak diperkenankan dibaca di dalam salat dan tidak dinilai ibadah.
Baca Juga: Ragam Qiraat Sebagai Hujah Kebahasaan, Antara Mazhab Basrah dan Kufah
Perlunya memahami qiraat yang diterima dan yang tidak diterima akan berimplikasi terhadap hukum membacanya, baik yang wajib dibaca ketika salat hingga yang tidak boleh dibaca. Pembatasan qiraat dengan syarat-syarat tertentu juga untuk menjaga keotentikan qiraat yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. dari qiraat-qiraat yang salah atau palsu. Wallah a’lam



![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)