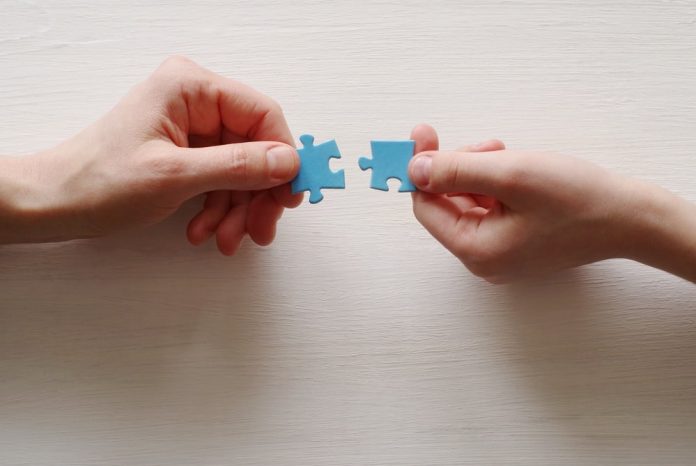Di antara ayat hubungan suami-istri yang familiar menjadi objek penafsiran feminis modern ialah Surah An-Nisa ayat 34 tentang konsep qiwamah (kepemimpinan). Tema ini hampir selalu disinggung mufasir feminis. Sebagian dari mereka yang membahas konsep qiwamah ialah Riffat Hassan (l.1943), Amina Wadud (l. 1952), dan Husein Muhammad (l. 1953). Tiga tokoh ini menekankan relasi kesalingan dalam mengemban peran rumah tangga.
Konteks penurunan ayat
Mengutip Asbab al-Nuzul (151-152) karya al-Wahidi, Q.S. Annisa [4]: 34 turun dalam konteks konflik rumah tangga antara Sa’d bin al-Rabi’ yang memukul istrinya, Habibah bint Zayd, karena telah nushuz. Kemudian, Habibah bersama ayahnya mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi pun memerintahkan untuk meng-qisas (membalas dengan setimpal) kepada suaminya. Tetapi, sebelum mereka pulang, turunlah Q.S. An-Nisa [4]: 34 sebagai ketentuan menghadapi konflik rumah tangga, sekaligus meralat instruksi qisas dari Nabi.
Ayat ini dipahami oleh kebanyakan mufasir klasik sebagai legitimasi kepemimpinan suami atas istrinya secara mutlak. Argumentasi mereka adalah karena terdapat kelebihan-kelebihan khusus yang diasumsikan ada pada laki-laki. Antara lain, potensi akal dan fisik yang lebih tinggi dari perempuan, sehingga menunjukkan kemampuannya untuk mencari kebutuhan finansial. Mufasir yang mengemukakan hal ini antara lain Fakhr al-Din al-Razi (Tafsir al-Kabir, Jilid 10, 88). Pemutlakan kepemimpinan suami dalam rumah tangga dia dasarkan pada kelebihan fisik (al-qudrat) dan intelektual (al-‘ilm), yang dimiliki laki-laki.
Formulasi prinsip kesalingan dalam ayat qiwamah
Para mufasir feminis mengkritik penafsiran klasik dan menawarkan makna baru. Riffat Hassan (l. 1943), teolog dan feminis Muslim asal Pakistan mengambil langkah dekonstruksi terhadap tafsir klasik atas ayat tersebut. Menurutnya, kata qawwam tidak selayaknya dimaknai dengan pemimpin karena berkonsekuensi secara psikologis dan teologis akan adanya superioritas laki-laki. Dia kemudian menawarkan “penopang dan pelindung bagi perempuan” sebagai makna baru dari qawwam. Dua makna itu berada dalam konteks pemenuhan nafkah dan penanggungjawab keluarga. Hassan mempertimbangkan beban biologis perempuan berupa mengandung, melahirkan, dan menyusui, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak dapat mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Karena itu, pemenuhan nafkah tersebut diarahkan kepada laki-laki.
Meski demikian, Hassan tidak berarti mengarahkan ketentuan ini sebagai kemutlakan. Dia berpendapat bahwa penyebutan diksi al-rijal pada pembuka hanya menunjukkan gambaran deskriptif –khabar dalam istilah Usul Fiqh-, sehingga tidak berimplikasi pada perintah. Dengan begitu, subjek yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bersifat fleksibel, sesuai dengan kondisi masing-masing rumah tangga. (Riffat Hassan, Mengungkap Misogini Dalam Islam, 121)
Penafsiran Hassan ini telah menekankan relasi kesalingan dengan pendapatnya bahwa qiwamah tidak mutlak diemban oleh laki-laki, melainkan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan. Dia juga tampak sensitif gender ketika mengarahkan qiwamah kepada laki-laki itu atas dasar pertimbangan beban biologis perempuan yang sifatnya kodrati, alih-alih berorientasi pada pengalaman sosialnya yang bersifat konstruktif. Hanya saja, Dia membatasi ayat ini pada lingkup domestik.
Amina Wadud (l. 1952) sepakat dengan Hassan. Menurutnya, secara prinsip, ayat ini menunjukkan pembagian tanggung jawab dan peran yang timbal-balik antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Wadud mengakui ada kelebihan moral bagi sebagian laki-laki. Dia memaknai qawwam sebagai pelindung, dengan memepertimbangkan keutamaan moral laki-laki dalam mengupayakan kebutuhan spiritual, materiel, psikologis, dan spiritual bagi keluarga, sehingga dalam hal ini suamilah yang bertanggungjawab. Pemaknaan suami sebagai pelindung menurut Wadud tidak berimplikasi pada superioritas laki-laki, karena konsep perlindungan di sini semata sebagai penghargaan atas kelebihan yang dimiliki laki-laki. Di samping itu, konsep perlindungan di sini tidak menunjukkan supremasi terhadap perempuan. Tidak seperti pemaknaan qawwam sebagai ‘pemimpin’. Lagi pula, Wadud juga menempatkan ayat ini sebagai ketentuan yang bersifat fungsional.
Baca juga: Tafsir Ayat Relasional yang Kurang Mencerminkan Kesetaraan
Wadud juga menegaskan bahwa fungsi laki-laki sebagai penopang keluarga harus memenuhi dua kriteria sebagaimana frasa setelah huruf bi, yaitu ma faddala Allahu ba’dahum ‘ala ba’d wa bi ma anfaqu min amwalihim. Dua kriteria itu ialah preferensi yang dimilikinya dan kemampuan finansial untuk menafkahi istri. Selanjutnya, Wadud memperhatikan diksi faddala tidak ditujukan kepada keunggulan sebagian laki-laki atas perempuan saja, tetapi keunggulannya atas sebagian yang lain (manusia secara umum).
Untuk menguatkan argumentasinya ini, Wadud mendiskusikan pemaknaan qawwam dari berbagai ahli. Antara lain, al-Zamakhshari, yang mengartikan qawwam dengan ‘laki-laki bertanggungjawab terhadap kepentingan perempuan’. Terjemahan Pickthall mengartikannya dengan ‘bertanggungjawab’. Azizah al-Hibri berpendapat bahwa diksi itu berarti bahwa laki-laki adalah pengelola dan pelindung bagi perempuan, yang dapat berlaku pada kondisi darurat perempuan atau karena atas dasar kepedulian moral terhadap perempuan (dia mencontohkan dengan gila). Sementara itu, Mawdudi mengartikannya dengan laki-laki sebagai manajer kepentingan perempuan atas dasar kelebihan dari Allah yang diberikan kepadanya. Wadud pun membatasi qiwamah ini pada konteks keluarga (domestik) dengan mempertimbangkan kelanjutan ayat dan ayat setelahnya yang juga berbicara tentang pernikahan. (Amina Wadud, Qur’an and Woman, 73)
Baca juga: Alquran Tidak Melegitimasi Kekerasan dalam Rumah Tangga
Dari berbagai pengertian itu, pada akhirnya Wadud menyimpulkan bahwa qiwamah harus meliputi dimensi psikologis, spiritual, intelektual, dan moral, yang tentu saja dapat dipikul baik oleh suami atau istri, sepanjang mereka memiliki keunggulan dalam aspek tersebut. Tetapi, Wadud pada sebenarnya masih berpihak pada laki-laki sebagai prioritas dalam mengemban tugas tersebut. Hal ini disinyalir dari pendapatnya bahwa laki-laki memiliki keunggulan moral dan sebagaimana yang diulas oleh Etin Anwar tentang penafsiran Wadud terhadap ayat ini. Bahwa dia meyakini qiwamah pada prinsipnya diperuntukkan kepada suami karena keunggulan moralnya dalam mensejahterakan rumah tangga pada segi materiel, spiritual, psikologis, dan intelektual. (Anwar, A Genealogy of Islamic Feminism, 267-268)
Wadud menekankan konsep qiwamah yang demikian sebagai salah satu cara seseorang memenuhi tugas sebagai wakil Tuhan di Bumi (khalifat fi al-ard). Di sisi lain juga mengonter pola pikir yang bersifat kompetitif dan otoriter, sehingga berpotensi menimbulkan konflik alih-alih pemeliharaan dalam keluarga.
Selain soal qiwamah, Wadud juga mengkritisi pemaknaan qanitat pada ayat yang sama sebagai tuntutan kepatuhan sepihak dari istri terhadap suami. Menurutnya, ketaatan harus dilakukan secara timbal-balik. Pendapat ini didasarkan pada berbagai diksi qanitat dan derivasinya dalam Al-Quran yang menunjukkan kesetaraan keduanya dalam hal harus menaati Tuhan. (Amina Wadud, Qur’an and Woman, 74-73)
Penafsiran lebih kontekstual dan jangkauan lebih luas –tidak hanya di lingkup rumah tangga- terhadap Q.S. An-Nisa [4]: 34 datang dari Husein Muhammad (l.1953). Dia tidak saja menempatkan ayat ini dalam konteks khabar, tetapi juga menunjukkan argumentasi-argumentasi pendukung bahwa ayat ini bersifat sosiologis dan kontekstual. Dalam membangun tesis tentang konteks perempuan saat ini sama sekali berbeda dengan apa yang diasumsikan sebagai makhluk terbelakang, lemah fisik dan intelektual, Muhammad mengemukakan pandangan Fakr al-Din al-Razi. Menurut al-Razi, keyakinan atas suatu pemikiran harus berdasarkan fakta empiris, tak terkecuali pemahaman yang bersumber dari teks otoritatif. Pendapat ini yang kemudian menggiring pada kebutuhan untuk interpretasi ulang ayat relasi gender dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa saat ini perempuan jauh lebih beradap daripada mereka di masa lalu. (Muhammad, Fiqh Perempuan, 58)
Baca juga: Benarkah Islam Melarang Kepemimpinan Perempuan? Mari Telisik Lagi Dalilnya
Muhammad kemudian menyatakan bahwa konsep qiwamah baik itu dengan makna pengayom, pelindung, atau pemimpin sekalipun berlaku secara fleksibel, sesuai dengan kondisi keluarga dan sepanjang tetap dalam tujuan kemaslahatan dan kerahmatan. Lebih lanjut, Muhammad juga memberlakukan fleksibilitas qiwamah ini di ranah publik. (Muhammad, Fiqh Perempuan, 72-74)
Husein Muhammad tampak konsisten dengan prinsip kesetaraan dan kesalingan. Analisis konteks yang komprehensif juga kentara dari penafsirannya. Meski dia seorang laki-laki, tetapi pendekatatan feminisnya dalam menafsirkan ayat tersebut dapat mengimbangi mufasir feminis perempuan. Bahkan, di bagian kontekstualisasi, analisisnya tampak lebih dalam.
Relasi kesalingan menjadi tawaran saat pembacaan atas ayat qiwamah (kepemimpinan) tampak bias terhadap laki-laki. Relasi kesalingan semakna dengan konsep resiprokal atau mubaadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Relasi kesalingan dirumuskan tentu saja demi menghasilkan pemahaman terhadap ketentuan hubungan suami-istri dalam Islam secara lebih humanis. Terlebih, jika dihadapkan dengan realitas yang ketimpangan dalam rumah tangga kerap terjadi. Wallahu a’lam[]




![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)