At-Tahrir Fii Ushul At-Tafsir adalah kitab ‘Ulumul Qur’an kontemporer karya seorang ulama terkemuka yaitu Musaid bin Sulaiman bin Nashir at-Thayyar. Kitab ini disebut-sebut dengan kitab ushul at-tafsir yang kompleks, sistematis, dan analitis. dalam salah satu babnya dijelaskan terkait sebab-sebab yang menjadi faktor perbedaan dalam menafsirkan Alquran.
Telah banyak ditemukan perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat Alquran, baik yang bersifat kontradiktif maupun yang bersifat variatif. Pembahasan mengenai perbedaan ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam memahami tafsir dari ayat-ayat Alquran.
Musaid at-Thayyar dalam At-Tahrir Fii Ushul At-Tafsir (229-239) mengatakan bahwa pada dasarnya latar belakang terjadinya perbedaan penafsiran antar ulama adalah bervariasinya makna yang terkandung dalam suatu kata. Perbedaan tersebut ada yang diterima karena sesuai dengan aturan umum penafsiran dan ada yang ditolak karena tidak sesuai dengan aturan umum penafsiran.
Baca Juga: Konsekuensi Perbedaan Qiro’ah pada Penafsiran Al-Quran Menurut Mufassir
Bertambahnya faktor yang memengaruhi perbedaan mufassir dalam menafsirkan ayat Alquran juga dilatarbelakangi oleh munculnya aliran-aliran teologis dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, seperti berkembangnya ilmu fikih yang ditandai dengan munculnya madzhab-madzhab fikih.
Lalu apa saja sebab terjadinya perbedaan dalam menafsirkan Alquran? Berikut penjelasannya.
Pertama, variasi makna yang terjadi akibat perbedaan dasar pengambilan kata. Peristiwa seperti ini seringkali terjadi karena para mufassir berbeda pendapat dalam melihat dari mana suatu kata itu diambil. Sebagai contoh, kata مُسْتَمِرٌّ dalam QS. Al-Qamar[54]:2 ويَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, sebagian ulama berpendapat kata tersebut diambil dari أَمَرَّ-يُمِرُّ yang bermakna kuat, sedangkan ulama lain berpendapat diambil dari kata مَرَّ-يَمُرُّ yang bermakna lenyap atau hilang.
Kedua, tempat kembalinya rujukan dari suatu dlamir (kata ganti). Seringkali ulama merujuk suatu dlamir pada kata yang disebutkan sebelumnya yang terdekat, akan tetapi sebagian ulama merujuk kata ganti tersebut kepada kata yang paling sesuai dengan konteks suatu pembicaraan, sehingga terjadilah perbedaan antara para mufassir. Contohnya dalam QS. Al-Fath[48]:9 وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ , sebagian ulama merujuk dlamir هُ tersebut kepada Allah, dan ulama lain merujuknya kepada Rasul saw.
Baca Juga: Simak Ini untuk Belajar Memaklumi Perbedaan Tafsir Al-Quran!
Ketiga, penyebutan kata sifat yang tidak dijelaskan apa atau siapa yang disifati. Dapat ditemukan dalam QS. Al-Mursalat[77]:1 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا yang tidak dijelaskan siapakah “yang diutus membawa kebaikan” tersebut.
Kemudian, ulama membawa kata sifat tersebut pada sesuatu yang paling pantas untuk disifati dengan اْلمُرْسَلَاتِ. Sehingga, terjadilah perbedaan penafsiran, dimana sebagian ulama mengatakan yang diutus membawa kebaikan adalah angin, dan ulama lain mengatakan yang diutus adalah malaikat.
Keempat, perbedaan disebabkan karena sumber yang digunakan oleh mufassir. Masing-masing mufassir memiliki rujukan utama yang berbeda pada setiap orangnya. Ada yang menggunakan Bahasa, hadis, dan ada pula yang menggunakan selain keduanya. Hal ini biasanya terjadi karena keunggulan latar belakang keilmuan di setiap mufassir itu berbeda-beda.
Sebagai contohnya, dalam QS. Al-Qalam[68]:42 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ . Ada dua penafsiran yang berkaitan dengan ayat ini. Pertama, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hari kiamat itu dibuka dengan peristiwa mengerikan dan memilukan. Penafsiran ini menggunakan bahasa sebagai sumber utamanya, dimana kata سَاقٍ menurut orang Arab adalah peristiwa yang dahsyat.
Kedua, ayat tersebut ditafsirkan menggunakan hadis Nabi saw. sebagai sumber utamanya. Menurut Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah, yang dimaksud dari يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ adalah sebagimana hadis yang tercantum dalam Shahih Bukhari yang berbunyi يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ َفيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرهُ طَبْقًا وَاحِدًا
Baca Juga: Kenapa Hasil Penafsiran itu Berbeda-beda? Ini Salah Satu Alasannya
Kelima, perbedaan dalam mengaitkan suatu ayat dengan ayat lain. Ini berkaitan dengan teori takhsis, taqyid, dan naskh. Contoh yang berkaitan, sebagaimana QS. Al-Baqarah[2]:221 وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata الْمُشْرِكَاتِ adalah mencakup wanita musyrik secara umum, baik wanita musyrik penyembah berhala maupun wanita ahli kitab (Yahudi/Nasrani), kemudian kata ini dikhususkan dengan ayat yang lain yang terdapat dalam QS. Al-Maidah[5]:5 وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذْينَ أُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ yang menyatakan bahwa diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, dan ayat pertama hanya dibatasi dengan wanita musyrik penyembah berhala (tulen).
Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa الْمُشْرِكَاتِ adalah wanita musyrik penyembah berhala, tanpa adanya pembahasan takhsis, taqyid, ataupun selainnya. Sehingga, diputuskan kebolehan menikahi wanita musyrik ahli kitab.
Dan yang terakhir menurut Musaid At-Thayyar, penyebab terjadinya perbedaan antara mufassir dalam menafsirkan Alquran adalah perbedaan dalam mendahulukan atau mengakhirkan urut-urutan kata dalam ayat Alquran. Pada dasarnya, menafsirkan ayat dalam Alquran itu adalah sesuai dengan urutannya. Tetapi, kadangkala terjadi metode mendahulukan dan mengakhirkan penafsiran ayat-ayat. Contohnya pada QS. At-Taubah[9]:62 يَحْلِفُوْنَ باللّٰه لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ
وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ adalah susunan mubtada’ khabar dalam perspektif ilmu nahwu. Sebagian ulama, salah satunya Imam Sibawaih mengatakan bahwa yang dikehendaki dalam ayat tersebut adalah وَاللّٰهُ أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ dan وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ kemudian kalimat أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ dibuang dalam rangkaian kalimat yang kedua. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa dalam ayat tersebut terdapat metode mendahulukan dan mengakhirkan, sehingga yang dikehendaki dalam ayat tersebut adalah وَاللّٰهُ أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ sedangkan kata وَرَسُوْلُهُ tidak berkaitan dengan أَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ.
Sebab-sebab yang telah disebutkan di atas adalah sebab terjadinya perbedaan penafsiran yang terjadi pada masa tafsir era klasik dan generasi setelahnya. Tetapi, ini tidak menutup kemungkinan munculnya sebab-sebab baru yang belum pernah dibahas di era klasik.

![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)
![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)
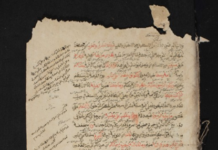







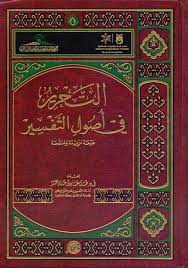
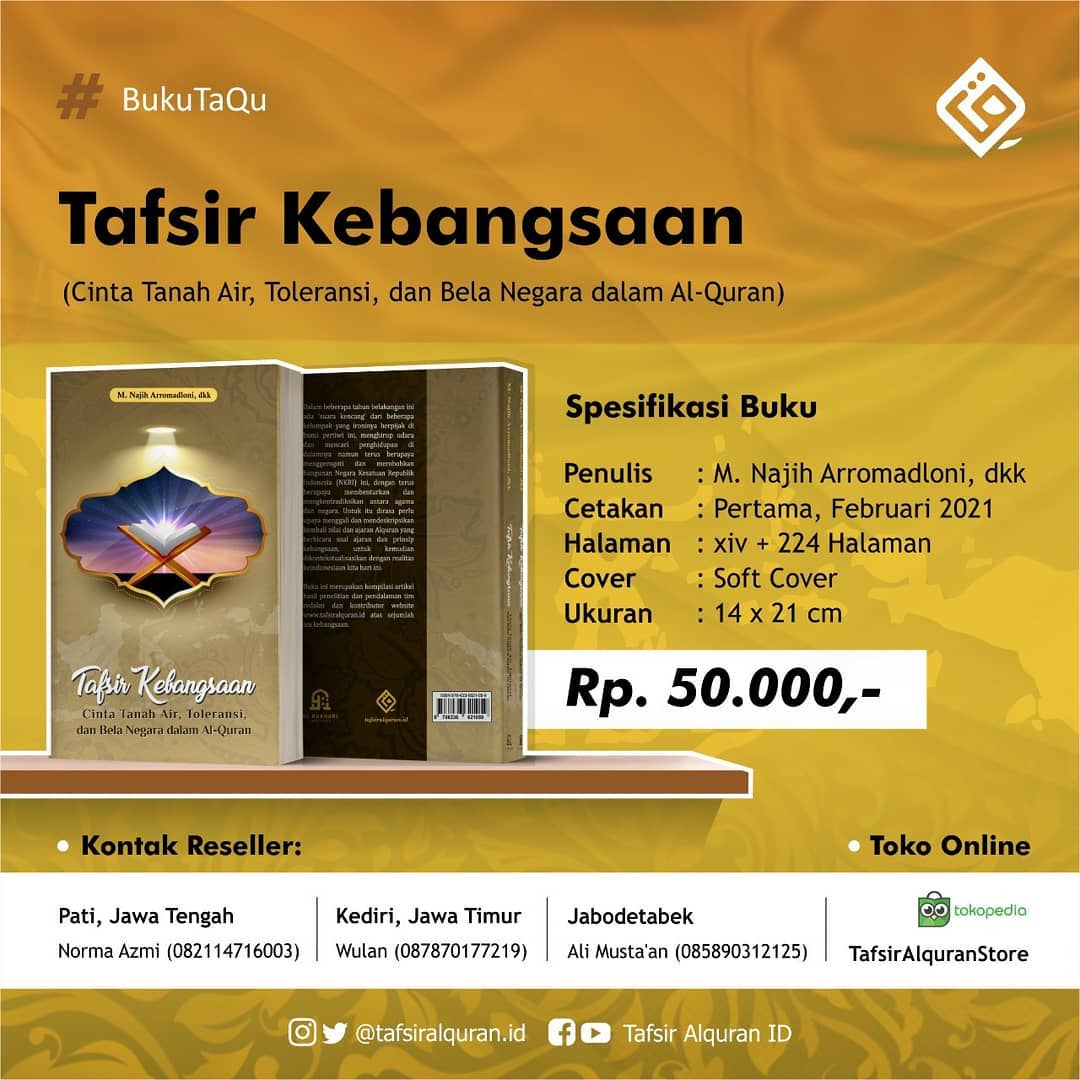


![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)
