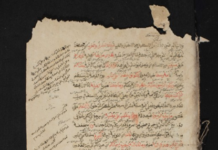Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang diwarnai oleh rangkaian pilihan. Bagi seorang muslim, menavigasi berbagai pilihan ini bukanlah sekadar latihan logika, melainkan sebuah proses spiritual yang menuntut bimbingan.
Al-Qur’an, sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman (w. 1988), adalah sebuah “dokumen yang ditujukan secara langsung kepada manusia” dan menyebut dirinya sebagai “petunjuk bagi umat manusia” (hudan lil-nās) (Major Themes of The Qur’an, hlm. 1). Sebagai petunjuk, ia tidak menawarkan formula instan, tetapi meletakkan fondasi bagi sebuah kerangka berpikir yang utuh. Dari sana, tergali sebuah kurikulum yang menyeimbangkan antara rasionalitas, kearifan sosial, dan kepasrahan spiritual.
Fondasi Pertama: Berpijak pada Ilmu
Fondasi pertama yang ditekankan oleh Al-Qur’an adalah larangan keras untuk bertindak atas dasar kebodohan atau prasangka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36:
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”
Ibn Kathir (w. 774 H) menjelaskan bahwa ayat ini adalah larangan untuk berbicara dan bertindak tanpa ilmu, melainkan hanya berdasarkan prasangka (zhan) dan imajinasi (Tafsir al-Qur’an al-’Azhim Vol. 5, hlm. 69). Ibn ‘Ashur (w. 1393 H) bahkan menyebut ayat ini sebagai sebuah “pelajaran etika yang agung” dan “reformasi intelektual yang mendalam”. Ia mengajarkan umat untuk mampu membedakan antara informasi yang valid, yang masih dugaan, dan yang sekadar angan-angan (al-Tahrir wa Al-Tanwir Vol. 15, hlm. 100).
Baca juga: Mempertimbangkan Akibat dari Suatu Keputusan Hukum dalam Memahami Alquran
Prinsip superioritas ilmu ini ditegaskan kembali dalam surah Az-Zumar ayat 9: “…Katakanlah, ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”. Ibn ‘Ashur menguraikan bahwa “orang yang mengetahui” adalah mereka yang memahami hakikat sesuatu dan perbuatannya selaras dengan ilmunya. Beliau menegaskan bahwa iman adalah saudara kembar dari ilmu (al-Tahrir wa Al-Tanwir Vol. 23, hlm. 348).
Pada era ketika hoaks dan opini tanpa data menyebar dengan cepat, fondasi ‘ilmu’ ini menjadi sangat krusial. Ia mendidik seorang muslim untuk menjadi “skeptis yang bertanggung jawab”, yakni tidak mudah percaya pada judul berita, tidak gegabah mengambil keputusan investasi berdasarkan “kata orang”, dan selalu melakukan verifikasi. Sebagaimana ditekankan oleh Fazlur Rahman (w. 1988), pengetahuan dalam Al-Qur’an bukan sekadar data empiris yang ditangkap “mata dan telinga”, tetapi haruslah pengetahuan yang pada akhirnya “mengetuk hati” (strike the heart) dan menyalakan sebuah persepsi moral. Tanpa persepsi ini, seseorang bisa saja mengetahui “eksternalitas kehidupan duniawi”, tetapi tetap “lalai akan konsekuensi akhirnya” (Major Themes of The Qur’an, hlm. 23).
Fondasi Kedua: Berbagi Beban dengan Musyawarah
Setelah landasan ilmu individu terpenuhi, Islam mengangkat proses ini ke level sosial. Bahkan kepada Rasulullah saw, yang dibimbing oleh wahyu, Allah memerintahkan dalam surah Ali ‘Imran ayat 159: “…dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…”
Ibn Kathir menjelaskan bahwa perintah ini bertujuan untuk “menenangkan dan memenangkan hati para sahabat” agar mereka lebih bersemangat dalam menjalankan keputusan bersama. Beliau mencatat bahwa Rasulullah saw. senantiasa bermusyawarah dalam banyak urusan penting, seperti saat Perang Badar, Uhud, dan Khandaq (Tafsir al-Qur’an al-’Azhim vol 2, hlm. 130).
Lebih dari sekadar perintah, musyawarah dipuji sebagai ciri khas sebuah komunitas beriman yang sehat, sebagaimana disinggung dalam surah Asy-Syura ayat 38: “…sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…”. Fazlur Rahman menyoroti bahwa melalui ayat ini, Al-Qur’an mengkonfirmasi dan melembagakan syūrā, yakni institusi demokrasi Arab pra-Islam, sebagai sarana bagi umat untuk menjalankan urusan kolektif mereka, di mana kehendak umat dapat diekspresikan (Major Themes of The Qur’an, hlm. 29).
Baca juga: Pelajaran dari Perang Khandaq
Pandangan ini diperluas oleh Sayyid Qutb (w. 1966), yang menyatakan bahwa lingkup musyawarah mencakup semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam bidang pemerintahan. Menurutnya, ini termasuk masalah keduniaan dan bahkan masalah keagamaan yang belum memiliki ketentuan hukum yang pasti (Fi Zilal al-Qur’an Vol. 8, hlm. 48).
Prinsip musyawarah adalah antitesis dari budaya “hero” individualistis yang seringkali diagungkan di zaman modern. Ia mengajarkan sebuah kerendahan hati intelektual, bahwa secerdas apapun seseorang, ia pasti memiliki “titik buta”. Dengan bermusyawarah, seseorang tidak hanya mendapatkan perspektif baru, tetapi juga berbagi beban psikologis dari sebuah keputusan, sehingga apa pun hasilnya, ia tidak ditanggung sendirian.
Fondasi Ketiga: Menyerahkan Hasil pada Istikharah
Puncak dari kerangka ini adalah sebuah pengakuan akan keterbatasan absolut manusia di hadapan ilmu Allah. Setelah akal dan ikhtiar sosial dimaksimalkan, seorang hamba diajarkan untuk menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta. Prinsip di balik penyerahan diri ini terangkum dalam surah Al-Baqarah ayat 216:
“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
Ibn Kathir menegaskan bahwa ayat ini berlaku umum untuk semua urusan (Tafsir al-Qur’an al-’Azhim vol. 1, hlm. 428). ‘Ashur menambahkan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penenang jiwa. Allah seolah-olah berkata, “Kami wajibkan atasmu suatu perkara yang berat, dan Kami tahu itu tidak kamu sukai, tetapi Kami juga tahu bahwa di baliknya ada kebaikan yang lebih besar untukmu” (al-Tahrir wa Al-Tanwir Vol. 2, hlm. 319).
Baca juga: Keserasian Nilai-Nilai Pancasila dengan Alquran
Manifestasi praktis dari prinsip ini adalah salat istikharah. Istikharah adalah sebuah deklarasi bahwa “saya telah melakukan bagian saya, dan kini saya serahkan hasilnya kepada-Mu, ya Allah”, yang membebaskan jiwa dari beban kecemasan akan hasil akhir.
Istikharah adalah jawaban Islam untuk “kecemasan akan hasil akhir” (outcome anxiety) yang melanda banyak profesional modern. Setelah riset (‘ilmu) dan konsultasi (musyawarah) dilakukan, istikharah memberikan sebuah “strategi penutup” yang menenangkan. Ia adalah sebuah deklarasi spiritual seolah “Tugas saya sebagai manusia telah selesai, sisanya adalah urusan-Mu, ya Allah”. Ini membebaskan jiwa dari beban untuk harus mengontrol segala sesuatu yang pada dasarnya berada di luar kendalinya.
Penutup
Kerangka pengambilan keputusan dalam Islam bukanlah sebuah formula kaku. Ia adalah sebuah kurikulum yang dinamis, yang mengalir dari penguatan akal individu (Ilmu), menuju kearifan komunal (Musyawarah), dan bermuara pada kepasrahan spiritual (Istikharah). Dengan menapaki tiga fondasi ini, proses membuat keputusan tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan berubah menjadi sebuah bentuk ibadah yang mendatangkan ketenangan, apapun hasil akhirnya. Wallahu ‘alam.




![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)