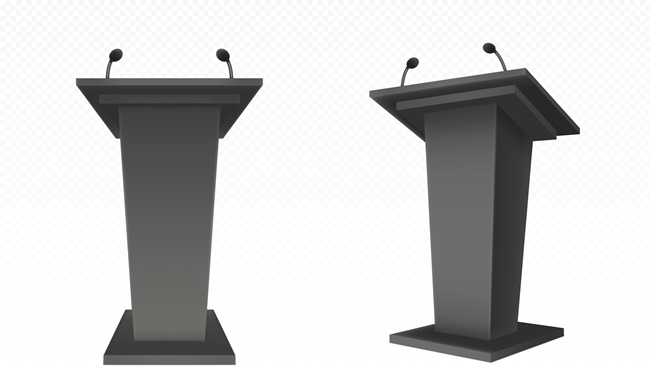Sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat adanya cacian, gunjingan dan kekerasan antar sesama manusia, bahkan seagama (Islam). Lebih-lebih di era Medsos seperti sekarang, semua informasi dapat mudah tersebar, dan menjadi riskan apabila yang tersebar adalah adalah ujaran kebencian antar individu atau kelompok. Apakah Islam tidak mengajarkan cinta dan damai?, lalu bagaimana cinta dapat tumbuh?
Pada dasarnya Islam adalah agama perdamaian yang tumbuh dari kasih sayang dan cinta kepada sesama. Menjalankan Islam dengan tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah Swt. dengan mematuhi perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”.
Sesama mukmin adalah saudara, dan hendaknya saling menjaga perdamaian serta kehormatan orang lain dengan tidak melakukan praktik-praktik yang mengarah kepada kebencian dan kejahatan.
az-Zuhaili di dalam karyanya (Tafsir al-Munir,juz 26 hal.235) memaparkan secara jelas maksud ayat di atas:
والمعنى: فأصلحوا بينهما، وليكن رائدكم في هذا الإصلاح وفي كل أموركم تقوى اللَّه وخشيته والخوف منه، بأن تلتزموا الحق والعدل، ولا تحيفوا ولا تميلوا لأحد الأخوين، فإنهم إخوانكم، والإسلام سوّى بين الجميع، فلا تفاضل بينهم ولا فوارق، ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي.
Artinya: “maka damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu, dan jadikan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah pemandu kalian dalam mendamaikan dan segala urusan kalian. Dengan melaksanakan yang hak dan adil, tidak curang dan berpihak ke salah satu saudara, karena mereka adalah saudara kalian dan Islam menyama-ratakan semuanya, tidak membanding dan membedakan antara mereka, supaya kalian mendapat rahmat sebab bertakwa kepada Allah yaitu dengan melaksanakan peprintah-perintah dan larangan-laranganNya”.
Damai merupakan representasi dari cinta dan kasih sayang antara sesama manusia. Sehingga kemudian akan berdampak banyak pada hal-hal positif, seperti saling tolong-menolong, perhatian, menjaga perasaan dsb. Dengan terbangunnya cinta antar sesama maka akan secara otomatis terwujud ketentraman dan kedamaian.
Lalu bagaimana cinta antar sesama dapat tumbuh?
Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menukil dari kitab karya al-Buthi (al-Hubbu fi al-Quran: 77-78). Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kecintaan manusia kepada sesama (selain karena Allah mencintainya) adalah buah dari kecintaannya Kepada Allah Swt. semakin seseorang cinta kepada Allah, maka semakin tumbuh pula kecintaan manusia kepada sesama. Halini tidak bisa dipungkiri karena dengan tertanamnya kecintaan kepada Allah yang ditandai kepatuhan terhadap perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya maka seseorang cinta kepada sesama, sebab cinta dan damai merupakan bagian dari ketakwaan.
Disebutkan dalam hadits qudsi yang diriwayatkan sahabat Ubadah bin Shamit ra.
( حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِين فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِيْنَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي للمتزاورين في وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم.
Pasti mendapat kecintaanKu bagi orang-orang yang saling mencintai karenaKu, pasti mendapaat kecintaanKu bagi orang-orang yang menyambung kekerabatan karenaKu, pasti mendapat kecintaanKu bagi orang-orang yang saling menasehati karenaKu, pasti mendapat kecintaanKu bagi orang-orang yang saling berkunjung karenaKu, dan pasti mendapat kecintaanKu bagi orang-orang yang saling berkorban karenaKu. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim).
Al-Buthi juga menyebutkan bahwa seseorang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti dia mencintai sesama manusia. Sebab (tanpa pandang bulu) manusia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Swt. dengan diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepada manusia (Adam ra.) dan kemuliaan dinisbatkannya ruh (manusia) kepadaNya.
Wallahu A’lam
Oleh : M. Ali Mustaan