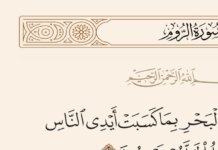Setelah sebelumnya dinyatakan bahwa Hari Pengadilan itu ada, pada tafsir Surah Yasin Ayat 55-57 ini akan diuraikan bagaimana gambaran kenikmatan yang dirasakan penduduk surga. Berikut tafsir surah Yasin ayat 55-57:
إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ
Artinya:
(55) Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
(56) Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
(57) Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Pada Hari Kiamat, para penduduk surga sibuk dengan kesenangan mereka. Maksud dari sibuk dengan kesenangan atau bersenang-senang dalam kesibukan ini para ulama berbeda pendapat. Ar-Razi mengemukakan tiga penafsirannya. Yang pertama, bahwa para penghuni surga disibukkan dengan berbagai kenikmatan surga, sehingga tidak merasakan huru-hara kiamat berupa hisab maupun azab.
Kedua, bahwa mereka sibuk beraktivitas, namun bukan aktivitas yang menyusahkan, melainkan aktivitas yang disukai lagi menyenangkan. Ketiga, bisa jadi mereka sibuk menerka-nerka kenikmatan seperti apa lagi yang akan mereka dapatkan, sebab kenikmatan surgawi yang datang selalu melebihi gambaran imajinasi mereka.
Selain tiga penafsiran tersebut, Nawawi al-Bantani menyebutkan dua penafsiran lain. Menurutnya, kenikmatan yang menyibukkan itu ialah saling berkunjung antarsesama penghuni surga. Bisa pula berarti mereka sibuk bertamu kepada Allah Swt. Melihat Allah Swt bagi ahlus sunnah wal jama’ah merupakan kenikmatan terbesar di akhirat kelak.
Para penduduk surga itu bersama pasangannya berada di tempat yang teduh sambil bertelekan di atas dipan-dipan. Hamka menjelaskan, mereka nyaman, aman dan tentram di sana, tidak terkena terik panasnya matahari. Sebagai catatan, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim no. 5108, pada hari kiamat kelak matahari hanya berjarak satu mil dari kepala manusia.
Ilustrasi ini dipilih bisa jadi dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Arab abad 7 ketika ayat al-Qur’an ini turun. Dahulu kondisi Arabia identik dengan gurun pasir yang panas lagi gersang. Ketika sedang dalam perjalanan di gurun pasir, tempat berteduh tentu merupakan suatu kenikmatan tersendiri.
Adapun yang dimaksud dengan azwajuhum (pasangan-pasangan mereka) menurut At-Thabathaba’i adalah istri atau suami mereka ketika di kehidupan dunia. Mereka yang diperkenankan menyertai pasangannya di surga tentulah yang juga sama-sama beriman dan ikut masuk surga. Sementara bagi yang pasangannya tidak senasib dengan mereka, para bidadarilah yang menggantikannya.
Baca Juga: Sayyid Muhammad Husain Al-Thabathaba’i: Arsitek Tafsir Al-Mizan
Di surga kelak, mereka memperoleh berbagai buah-buahan dan memperoleh apa pun yang mereka minta. Al-Bantani menjelaskan, Segala macam buah-buahan tersedia di surga. Al-Bantani juga mengutip az-Zajaj yang mengatakan bahwa apa yang penghuni surga inginkan akan langsung datang menghampiri mereka, tanpa perlu usaha dan menunggu lagi.
Terkait redaksi ayat, At-Thabari meriwayatkan perbedaan bacaan pada kata شغل di bagian akhir QS. Yasin: 55 di atas. Mayoritas qurra (ahli qiraat) membaca fi syughulin. Sedangkan sebagian ulama qiraat Basrah membaca fi syughlin.
Demikian pula pada kata فاكهون (fakihun). Ada yang membaca pendek fa’-nya, yaitu riwayat dari Abu Ja’far. Ada pula yang memanjangkannya, yaitu bacaan mayoritas ulama qiraat dan yang tepat menurut at-Tabari.
Demikianlah penjelasan singkat dari tafsir surat Yasin ayat 55-57 mengenai gambaran kenikmatan yang dirasakan penduduk surga. Tentunya ini hanya sebagian gambaran yang diilustrasikan Allah Swt melalui al-Qur’an untuk kita renungi bersama. Semoga kita termasuk dalam kelompok yang beruntung ini. Amin ya mujibas sailin. Sekian, Wallahu a’lam.