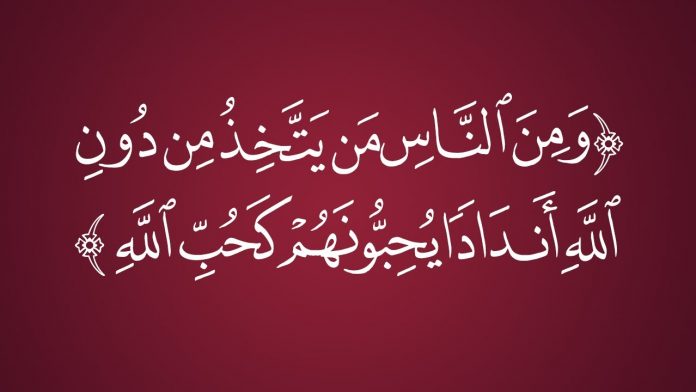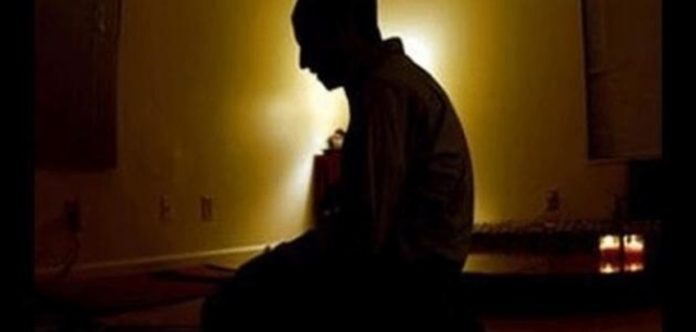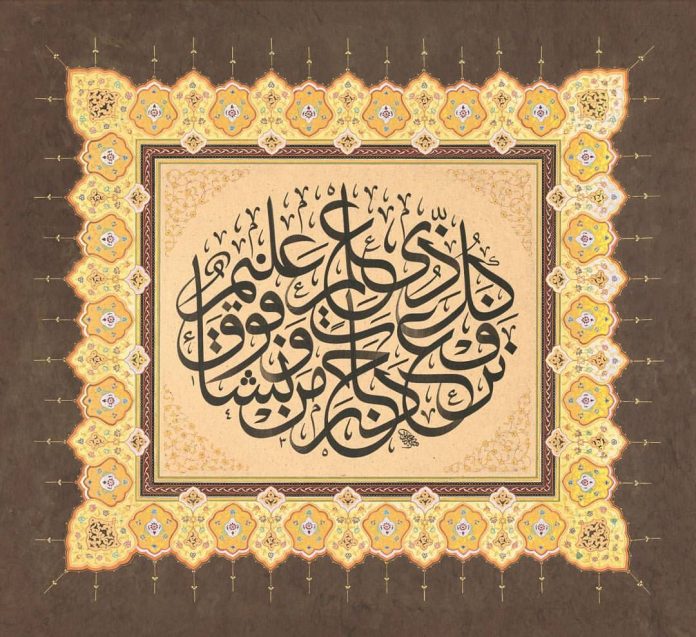Saling memaafkan dan kasih sayang adalah dambaan setiap umat manusia. Tidak peduli darimana ia berasal, latar belakang kesukuannya apa, bahasa, etnis dan budayanya bagaimana, sepanjang ia disebut sebagai manusia dan makhluk hidup pasti membutuhkan dua hal itu. Dengan begitu, ada ayat al-quran yang menyebutkan doa kasih sayang dan pengampunan.
Tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu lalu (28/3/2021) sangat kontradiktif terhadap ajaran agama Islam yang notabene mengedepankan kasih sayang dan melepas dengki serta dendam dari hati manusia. Islam mengajarkan salah satu doa kasih sayang dan pengampunan sebagaimana termaktub dalam firman-Nya di bawah ini,
وَالَّذِيْنَ جَاۤءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ࣖ
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (Q.S. al-Hasyr [59]: 10)
Baca juga: Kajian Semantik Andad Allah (Tandingan Allah) dalam Al-Quran
Tafsir Surat al-Hasyr Ayat 10
Dalam Jami’ al-Bayan, al-Tabari menyampaikan bahwa ayat di atas menyatakan bahwa generasi umat Islam yang datang sesudahnya (setelah kaum Muhajirin dan Ansar), mereka nanti akan berdoa memohonkan ampun kepada generasi terdahulunya, serta berdoa agar diri mereka dilepaskan dari dendam dan iri hati atau dengki.
Hal senada juga disampaikan al-Suyuthi dalam al-Dur al-Mantsur, ia menukil salah satu riwayat yang berasal dari ‘Abd bin Hamid dari Mujahid r.a. bahwa maksud redaksi walladzina ja-uu min ba’dihim adalah mereka orang-orang yang masuk Islam setelah generasi terdahulu (Muhajirin dan Ansar). Sedang dalam riwayat yang lain, sebut saja al-Dhahhak, ia menafsirkannya bahwa doa di atas memerintahkan untuk memohon ampun kepada mereka (kaum muhajirin dan Ansar).
Lebih jauh, al-Qurtuby memaknai redaksi rabbana ighfirlana wa li ikhwanina, sebagai suatu bentuk rasa cinta kepada sahabat Nabi saw (dalil ‘ala wujub mahabbah al-shahabah) di mana telah menjadikan mereka bernasib baik (memeluk Islam) sehingga patut baginya untuk mencintai para sahabat dan memohonkan ampunan kepada Allah swt. Al-Qurtuby juga menyitir perkataan Malik, “
من كان يُبْغِض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غِلٌّ، فليس له حق في فَيْء المسلمين ثم قرأ { وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ } الآية
“Barang siapa yang membenci salah satu dari sahabat Nabi Muhammad saw, atau di dalam hatinya terdapat rasa dendam, dengki dan benci, maka ia tidak termasuk dalam golongan muslimin sebagaimana difirmankan ayat di atas”
Pernyataan Malik di atas menunjukkan bahwa mencintai para sahabat Nabi saw dan “memaklumi” atas kekhilafan serta mau memohonkan ampunan atasnya, maka ia termasuk salah satu apa yang disebut dalam ayat di atas, yakni termasuk generasi sesudah kaum Muhajirin dan Ansar, generasi penerus panji Islam.
Baca juga: Bom Bunuh Diri Bukan Jihad! Inilah Makna Jihad Dalam Al-Qur’an
Penafsiran selanjutnya diungkap al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib bahwa sejatinya ayat di atas telah melingkupi semua umat muslimin yang ada baik Muhajirin, Ansar maupun generasi setelahnya bahkan generasi muslim masa kini. Lebih dari itu, al-Razi juga menyatakan ayat di atas merupakan bentuk doa dan rahmat bagi seluruh umat muslim tanpa terkecuali. Bentuk doa dan rahmat kasih sayang itu diejawantahkan dalam doa di atas dengan makna, agar Allah swt melepaskan darinya sifat dengki, iri hati, mengadu domba, dendam, dan sejenisnya.
Tidak cukup itu, penafsiran sufistik juga dituturkan al-Qusyairi dalam Lathaif al-Isyarat bahwa generasi yang datang sesudah Muhajirin dan Anshar maupun sezamannya seluruhnya dalam naungan kasih sayang-Nya, mereka saling mengasihi (tarahum), saling memintakan ampunan, memaafkan (istighfar) dan saling memintakan perlindungan (istijaran). Barang siapa yang tidak menaruh rasa belas kasih (syafaqah) kepada semua umat muslim, maka ia bukanlah termasuk bagian dari agama Islam. Demikian al-Qusyairi memungkasi pernyataanya.
Doa Kasih Sayang
Dengki, iri hati, dendam, provokasi, politisasi ayat, dan semacamnya merupakan sumber kejahatan dan maksiat yang mendorong seseorang ke dalam nestapa kehinaan. Allah swt melalui firman-Nya di atas memerintahkan kepada kita, sebagai umat muslim sesudah Muhajirin dan Ansar untuk senantiasa berdoa memohon ampunan dan melepas segala angkara murka dalam hati dan tubuh manusia.
Ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah dari ayat di atas, di antaranya pertama, tatkala seseorang berdoa, hendaknya diawali dari diri sendiri kemudian untuk orang lain. Rasionalisasinya adalah bagaimana mungkin seseorang mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, sementara dirinya enggan memohon ampunan untuk ia sendiri. Jadi, ibda’ binafsik (mulailah dari dirimu sendiri).
Selanjutnya, umat Islam yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan (al-muslimu lil muslim kal-bunyani yasyuddu ba’dhuhu ba’dhan). Artinya, saling bertalian erat karenanya satu sama lain mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, mengasihi, tolong-menolong, bukan malah sebaliknya.
Baca juga: Tafsir Ahkam: Beda Pendapat Hukum Salat Malam bagi Nabi Muhammad Saw
Tidak kalah pentingnya, saling memaafkan dan saling mengasihi merupakan modal utama dalam membina kerukunan antar umat beragama sebagaimana disitir doa di atas. Imam Turmudzi dalam Sunan Turmudzi mengutip hadis Nabi saw,
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ
“Orang-orang yang memiliki sifat penyayang akan disayang oleh-Nya. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka langit pun akan menyayangi dan mengasihimu. Sebab kasih sayang itu bagian daripada rahmat Allah swt. Barang siapa yang menyayanginya, maka Allah sayang kepadanya. Demikian pula, siapa yang memutuskannya, Allah akan memutuskannya”. (H.R. Tumudzi).
Wallahu A’lam.