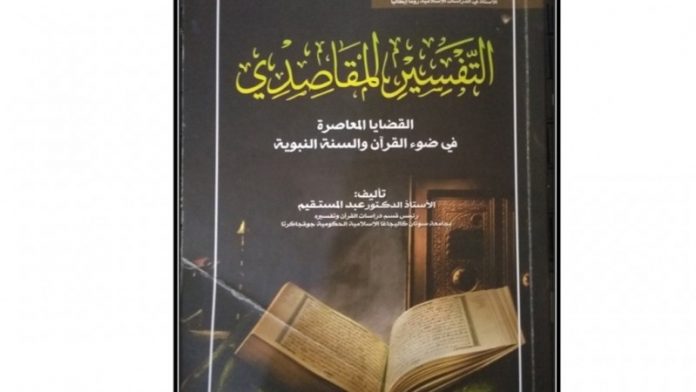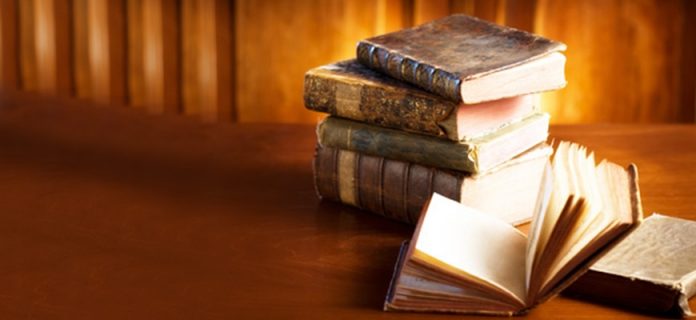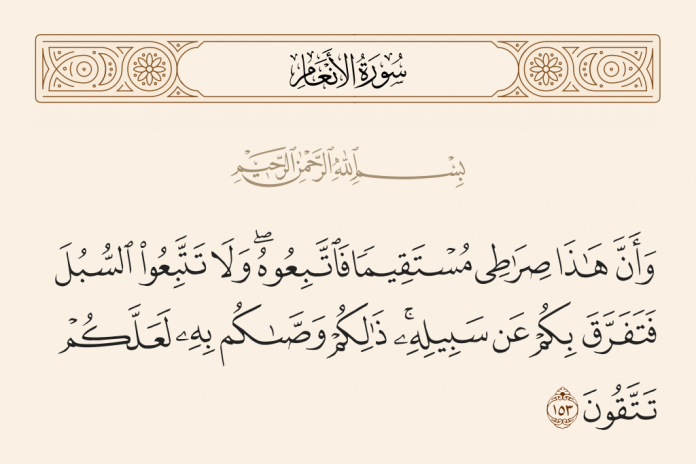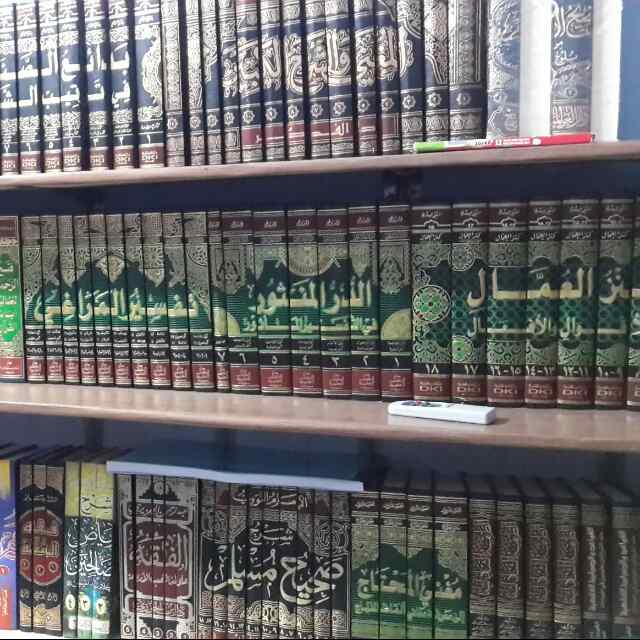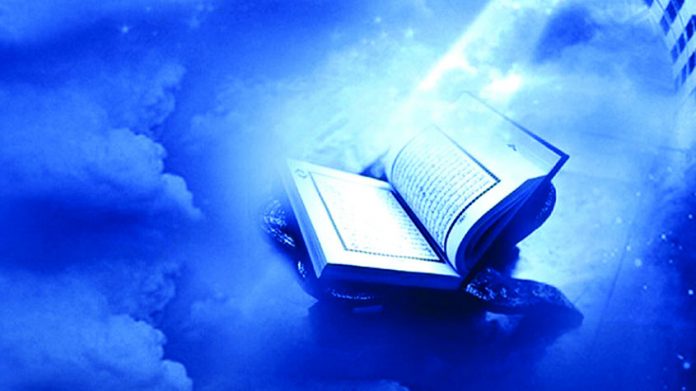Abdul Mustaqim merupakan salah satu guru besar Tafsir al-Qur’an kenamaan di Indonesia. Ia juga salah satu sarjanawan al-Qur’an yang aktif menyuarakan moderasi dan perdamaian sebagai karakteristik Islam sebagai agama. Dalam salah satu karya terbarunya, al-Tafsir al-Maqashidi, ia menuliskan satu bagian pembahasan khusus yang menguraikan penafsiran ideal dari salah satu maqashid al-syari’ah yakni hifz al-din dalam kehidupan keberagamaan yang multikultural.
Mengawali pembahasan ini, Mustaqim menegaskan bahwa hifz al-din atau menjaga eksistensi Islam sebagai agama, salah satunya diwujudkan memperlihatkan Islam sebagai agama yang pro-aktif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang damai. Serta bukan malah memperlihatkan Islam sebagai dalang dari terjadinya konflik kehidupan beragama di tengah masyarakat.
Baca juga: Merawat Nilai-nilai Kebangsaan dalam Tafsir Lisan M. Quraish Shihab
Maka menurutnya, kedua hal tersebut hanya akan diperoleh jika berpedoman pada perintah Allah bahwa umat Islam harus menjunjung toleransi dan menjalin interaksi yang baik kepada non-muslim. Hal ini sebagaimana tertuang dan diisyaratkan dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 8:
لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Selanjutnya, Mustaqim menjelaskan bahwa umat Islam juga harus menyadari dan memahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Pemahaman ini akan memudahkan umat Islam dalam menerapkan toleransi dan menjalin interaksi yang baik kepada kawan yang berbeda. Selain itu, pemahaman ini juga akan membimbing umat Islam untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mencederai kehidupan beragama seperti memaksakan agama pada orang lain maupun menghina agama lain.
Sebab dalam al-Qur’an, Allah sendiri telah menegaskan bahwa Dia-lah yang mentakdirkan adanya perbedaan. Maka memaksa orang lain memeluk Islam maupun menghina agama lain bukanlah ajaran Islam. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah: 256; Q.S. Yunus: 99; Q.S. Hud: 118: Q.S. al-An’am: 108.
لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?
وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَۙ
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat)
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
Mustaqim pun memberikan penafsiran lanjutan, bahwa maknanya ialah Islam merupakan ajaran agama yang menjunjung kebebasan beragama dan menghormati ajaran agama lainnya. Sebab keberagamaan yang hakiki ialah keberagamaan yang dihasilkan oleh kesadaran batin yang murni dan tidak melalui paksaan. Menurutnya, pemaksaan dalam beragama justru akan menimbulkan kebencian (al-ikrah tatawaladu minhu al-karahiyah).
Baca juga: Bismillāhirrahmānirrahīm, Belajar Cinta dan Kasih dari Basmalah
Oleh sebab itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk memaksakan kepercayaan kepada orang lain melalui cara apapun. Umat Islam hanya diperkenankan mengajak dan mengenalkan Islam dengan cara yang baik dan santun sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Nahl: 125. Selanjutnya, umat Islam juga tidak memiliki alasan untuk menghina agama lain. Sebab realita kehidupan umat manusia tidak hanya heterogen dari sisi warna kulit, bahasa dan ras/ bangsa namun juga agama.
3 model interaksi ideal sebagai bentuk Hifz al-din di tengah kehidupan beragama yang multikultural
Abdul Mustaqim juga memberikan model interaksi ideal yang harus diterapkan umat Islam sebagai bentuk hifz al-din di tengah kehidupan beragama yang multikultural, yang penulis klasifikasikan kepada tiga poin penting. Pertama, memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan untuk menyikapi perbedaan agama dengan akhlak yang mulia, penghormatan serta toleransi dan tidak mencampuri dalam urusan akidah. Hal ini penting sebagai bentuk representasi kualitas keagamaan seseorang, sebab tidak ada agama bagi yang orang yang tidak berakhlak.
Baca juga: Surah Al-Anam Ayat 153, Menyusuri Jalan Menuju Kebahagiaan
Kedua, membawa masyarakat dari perbedaan kepada keselarasan (min al-ikhtilaf ila al-i’tilaf), dari perpecahan menuju persatuan (min al-furqah ila al-wahdah) dan dari permusuhan menjadi persaudaraan (min al-‘adawah ila al-ukhuwah). Artinya umat Islam dituntut untuk mampu menemukan kalimatun sawa’ (common platform) yang mampu menjadi benang pengikat hubungan kemanusiaan di tengah keniscayaan perbedaan, sehingga mampu menjadi penjaga bagi keberlangsungan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat.
Ketiga, mengkoversi dan memperbaharui pemahaman beragama dari “din al-la’nah” menjadi “din al-samahah”, dari “din al-irhab” menjadi “din al-rahmah”. Maknanya, umat Islam harus segera membenahi pemahaman beragamanya menuju pemahaman yang ideal. Sebab penyakit radikalisme telah menggiring umat memahami Islam sebagai din al-la’nah atau agama yang senang mengutuk dan mendiskreditkan agama lain. Serta bahkan dapat bertransformasi menjadi din al-irhab atau agama yang seakan merestui aksi-aksi kekerasan dan teror terhadap yang berbeda secara keyakinan.
Pemahaman semacam itu harus diubah menjadi din al-samahah dan din al-rahmah. Maknanya umat Islam harus memahami ajaran fundamental Islam yang menjunjung tinggi toleransi serta kasih sayang sebab hal itu justru menjadi salah satu faktor yang menjaga eksistensi Islam sebagai agama.
Terakhir tema pembahasan semacam ini, menurut hemat penulis, sangat perlu diangkat sebagai respon terhadap fenomena radikalisme dan terorisme yang kembali eksis di Indonesia. Sebab fenomena tersebut seakan menjadi bukti bahwa masih banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang telah terpapar dan terjangkit virus pemahaman agama yang ekstrem. Mereka yang telah tercuci otaknya bahkan tidak segan untuk merusak tatanan perdamaian dan mencoreng citra serta meruntuhkan eksistensi Islam sebagai agama yang menjunjung perdamaian. Wallahu a’lam.