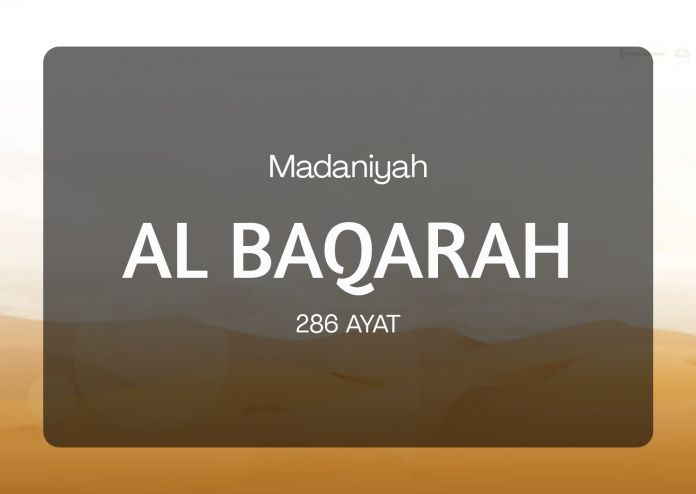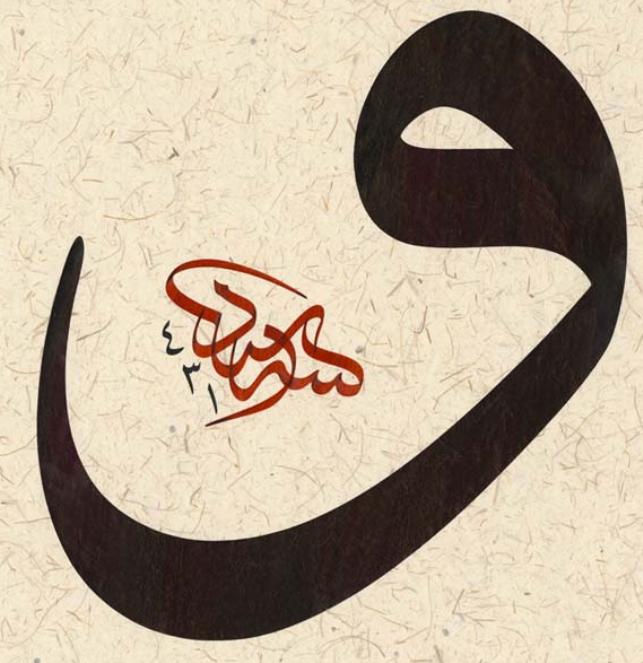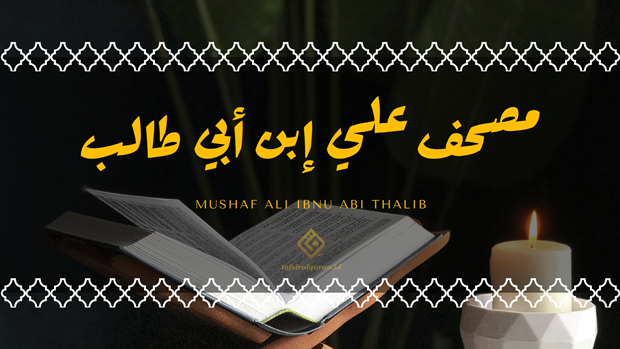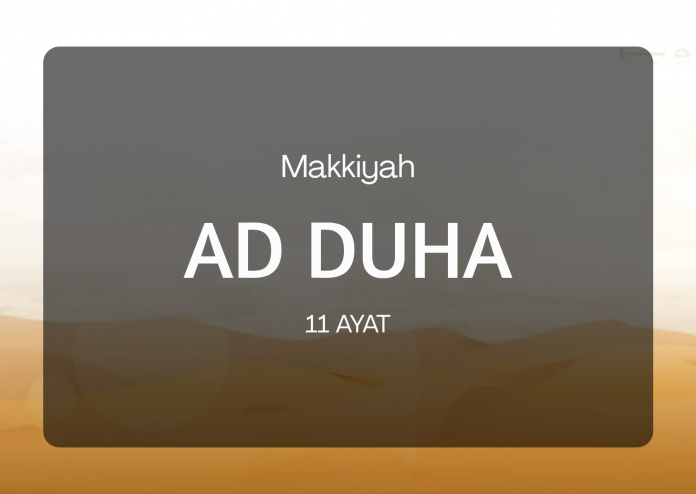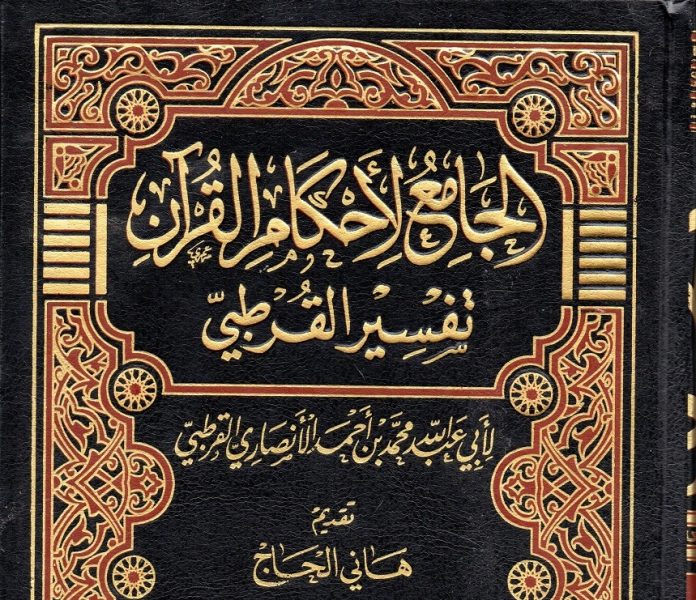Salah satu misi besar dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak untuk berserah pada agama Islam dan mengesakan Allah. Hal ini misalnya ada pada firman Allah dalam Surat Fushilat ayat 37, yang berisi larangan untuk bersujud sembah pada selain-Nya dan perintah untuk mengesakan-Nya. Akan tetapi, kepada lintas agama, Allah tidak lantas menyeru untuk menistakan. Justru, Ia melarang untuk menghina dan pilih kasih terhadap non Muslim, Sebagaimana yang tertera pada Surat Al-An’am ayat 108:
وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”
Baca juga: Tafsir Ahkam: Bolehkah Non-Muslim Masuk ke Masjidil Haram?
Larangan menistakan non Muslim
Fakhruddin ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib menyebutkan bahwa ayat ini berisi larangan untuk menghina orang yang tak sekeyakinan dengan Islam. Ia selanjutnya berpendapat bahwa di balik larangan ini, Allah memberi alarm untuk memperingatkan umat Islam sekalian agar dalam berdakwah tidak terjerembab dalam perbuatan tidak bermanfaat. Juga, ajakan agar umat Islam tidak bertindak seperti orang bodoh, melalui penghinaan terhadap non Muslim.
Adalah tidak pada tempatnya bila menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk menghinakan non Muslim. ‘Abdurrahman as-Sa’di dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman pun memaknai ayat ini sebagai pengakuan Islam atas keberadaan agama lain dengan segala ajarannya. Hal ini lantaran Allah telah menghiasai tiap amal masing-masing agama, sehingga tiap penganutnya pun menganggap apa yang ia lakukan itu adalah hal terpuji.
Baca juga: Makna Kebebasan Beragama dan Toleransi dalam Al-Quran
Adanya perbedaan ini harusnya menumbuhkan sikap tenggang rasa dan keinginan untuk saling memahami. Sebagaimana yang tertera dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang secara eksplisit menginformasikan keberagaman sebagai sunnatullah (ketetapan Allah). Dan juga, ini yang paling penting ada pada frasa li ta’arafu (saling mengenal), yang merupakan tujuan dari penciptaan keberagaman itu sendiri. Tentu saja, mengenal disini demi menumbuhkan rasa ingin saling memahami, sehingga dapat bersikap toleran, alih-alih menistakan terhadap yang tidak seiman.
Perbedaan juga bukan alasan untuk pilih kasih
Selain larangan menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk menghina, Allah juga melarang menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk pilih kasih. Yakni ada pada surat Al-Baqarah ayat 272:
لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ
“Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan).”
Ayat ini turun berkenaan dengan himbauan Nabi kepada umat Islam untuk tidak memberi sedekah kepada non Muslim. Dalam Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, terlampir satu hadis riwayat Sa’id bin Jubair yang menjadi latar turunnya ayat ini, Rasulullah bersabda:
لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ
“Janganlah kalian bersedekah kecuali kepada yang seagama denganmu!”
Baca juga: Larangan Memaki Sesembahan Non-Muslim: Salah Satu Ajaran Toleransi Dalam al-Quran
Lalu turunlah ayat ini, hingga kemudian Nabi meralat larangannya:
تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ
“Bersedekahlah kalian semua kepada umat beragama”
Sebenarnya, motif Nabi bukan lantaran rasa egois sehingga antipati pada agama lain. Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan Nabi untuk bersedekah pada non Muslim merupakan strategi dakwah terhadap non Muslim agar mengikuti Islam. Tetapi, karena cara itu dinilai kurang tepat, ayat tersebut turun untuk mengingatkan bahwa hidayah itu urusan Allah, dan tugas manusia adalah untuk menebar kebaikan tanpa paksaan.
Perintah untuk sedekah tidak hanya pada sesama Muslim dapat diartikan dengan perintah untuk tetap menjalin relasi baik kepada non Muslim dengan tidak pilih kasih. Sehingga, seorang Muslim tidak boleh apatis ketika non Muslim butuh bantuan.
Demikianlah agama Islam, agama yang rahmah mengajarkan umat manusia untuk menjunjung toleransi. Jangan pilih kasih dalam membantu apalagi seenaknya menghinadinakan sesama manusia. Sebagaimana petuah Gus Dur, “Sikap toleransi tumbuh dari masing-masing individu untuk memberikan nilai di masyarakat”
“Wallahu a’lam[]