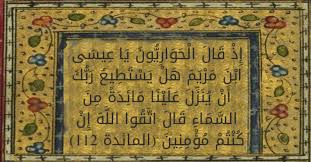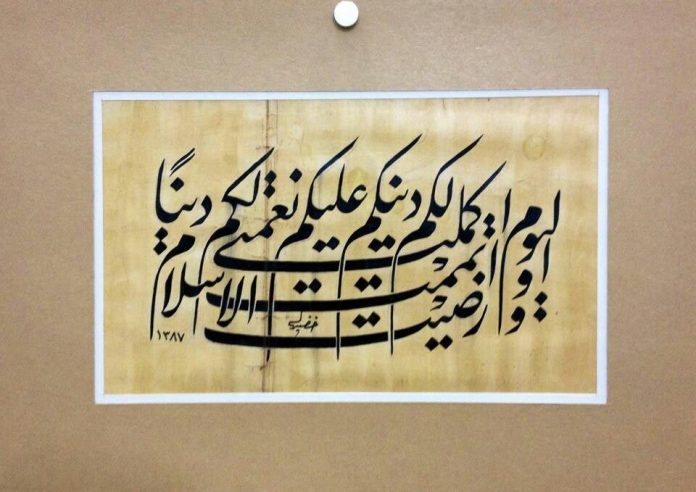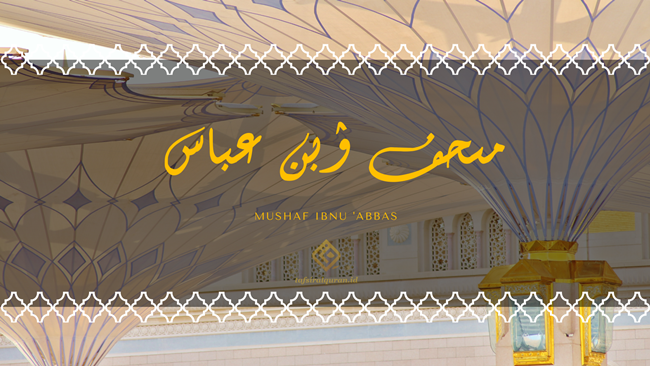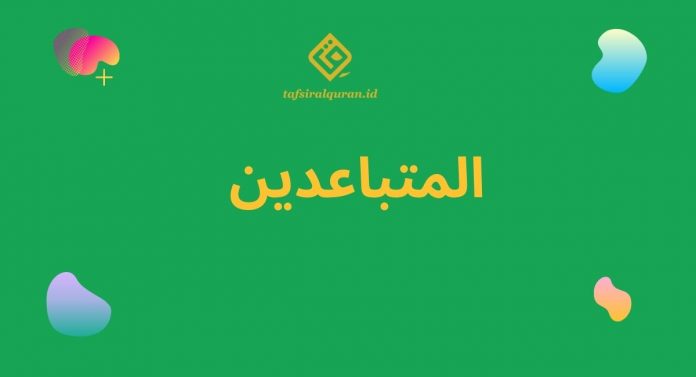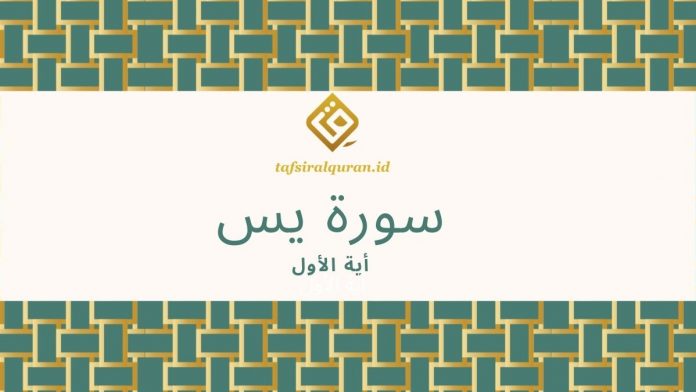Kata Al-Hawariyyun dalam Al-Quran disebut sebanyak empat kali. Penyebutan ini ditujukan untuk sekelompok atau segolongan orang karena sifat lafadz tersebut adalah jamak. Namun Al-Quran sendiri tidak memperinci jumlah, nama-nama atau siapa saja yang masuk dalam kelompok Al-Hawariyyun. Lalu siapakah Al-Hawariyyun itu?
Sebelum membahas definisi, berikut ayat-ayat yang menyebut Al-Hawariyyun. Pertama ada dalam surah Ali ‘Imran ayat 52:
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
Ketika Isa merasakan kekufuran mereka (Bani Israil), dia berkata, “Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawari (sahabat setianya) menjawab, “Kamilah penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.
Kemudian surah Al-Maidah ayat 111-112:
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ ب بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku.” Mereka menjawab, “Kami telah beriman, dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslim)”
“(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, “Wahai Isa putra Maryam! Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?” Isa menjawab, “Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”
Baca juga: Ikrar Setia Kaum Hawariyyun: Refleksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Dan yang terakhir dalam surah As-Shaf ayat 14:
يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah,” lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan kekuatan ke-pada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.”
Julukan untuk pengikut setia Nabi Isa
Secara harfiyah Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan lafadz Al-Hawariyyun adalah bentuk jamak dari Al-Hawariyyun. Asal katanya adalah Al-Hawar yang berarti putih bersih. Mereka dinamai demikian karena putih dan sucinya hari mereka dari dari berbagai noda serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa.
Quraish Shihab juga menyatakan pendapat ulama lain bahwa Al-Hawariyyun berasal dari bahasa Habasyah (Ethiopia) yaitu Hawariya yang berarti sahabat yang sangat tulus. Darimanapun asal katanya, yang jelas Al-Quran menggunakan istilah Al-Hawariyyun untuk para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa as. Jumlahnya adalah 12 orang.
Sebenarnya secara munasabah ayat-ayat tentang Al-Hawariyyun berkorelasi dengan ingkarnya kaum Nabi Isa. Penolakan dari kaumnya begitu besar. Alih-alih mau menerima dakwahnya, sekedar membenarkan kerasulan Nabi Isa pun mereka tidak sudi. Bahkan mengolok-olok, memfitnah, bahkan merencanakan pembunuhan terhadapanya. Namun ada sedikit orang dari kaum Nabi Isa tersebut yang mau mengimani.
Baca juga: Pengertian Kata Taubat dan Perintah Bertaubat dalam Al-Quran
Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim juga menjelaskan bahwa Al-Hawariyyun ini adalah pengikut setia Nabi Isa. Ketika kuatnya penolakan dan hampir tidak ada mau beriman, Nabi Isa menanyakan kepada kaumnya siapa yang akan menjadi penolong agama Allah. Siap berkorban secara lisan, perbuatan, dan bersedia mengorbankan jiwa dan harta benda. Lalu mereka menjawab seruan Nabi Isa bahwa mereka siap menjadi para penolong agama Allah. Membenarkan kerasulan dan mukjizat Nabi Isa dan bersaksi atas nama Allah. Kesaksian atas iman mereka difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Ali ‘Imran ayat 52, surah Al-Maidah ayat 111-115, dan surah Shaf ayat 14.
Atas tulusnya persahabatan Al-Hawariyyun ini terhadap Nabi Isa maka Allah mengabadikan nama mereka dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran julukan ini hanya khusus diberikan kepada pengikut nabi Isa saja, sedang bagi pengikut rasul yang lain tidak diberikan.
Setiap nabi punya Hawary
Al-Quran memang memberikan julukan Al-Hawariyyun kepada pengikut Nabi Isa. Namun, secara konteks kerasulan dan sifat-sifat setia yang dimiliki Al-Hawariyyun ini, rasul-rasul yang lain pun sebenarnya juga memiliki. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:
لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ
“Setiap Nabi itu punya hawary (pembela), dan hawaryku adalah Zubair.” (Muttafaqun ‘Alaih)
Dalam hadis tersebut Rasulullah juga menyebutkan bahwa beliau juga mempunyai hawary. Dan hawary beliau adalah Zubair. Dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair yang dimaksud di sini adalah Zubair bin Awwam, suami dari Asma’ dan menantu Abu Bakar.
Baca juga: Kosa Kata Bahasa Asing dalam Al-Quran
Sama seperti Abu Bakar, Zubair pun juga seorang pebisnis sukses dan sangat kaya raya. Masih menurut hadis riwayat Bukhari bahwa kekayaan Zubair mencapai lima puluh juta dua ratus ribu dirham. Dan semua kekayaan yang dimilikinya tersebut ia gunakan untuk berkorban membela Rasulullah SAW.
Menurut Ibnu ‘Arabi dalam kitab Karamatul Auliya, hawary tidak berhenti pada masa ketika Rasulullah hidup saja. Melainkan pada generasi setelah Rasulullah pun hawary ini masih ada, karena hawary ini adalah pembela agama Rasulullah dengan hati yang sangat tulus. Menurut Ibnu ‘Arabi, hawary setelah generasi Rasulullah adalah para wali. Wallahu a’lam[]