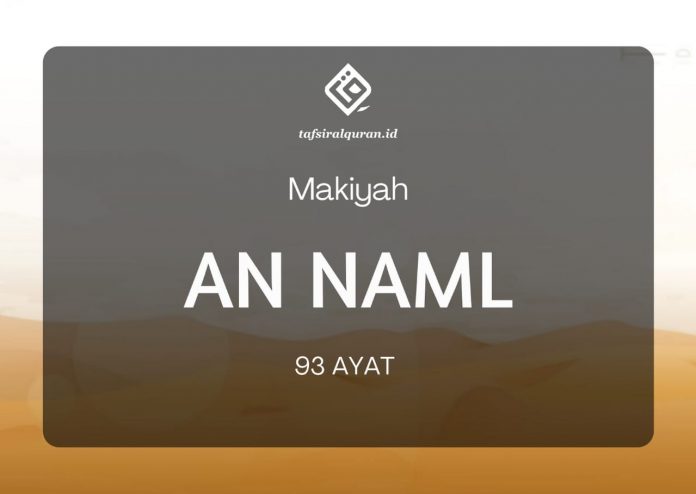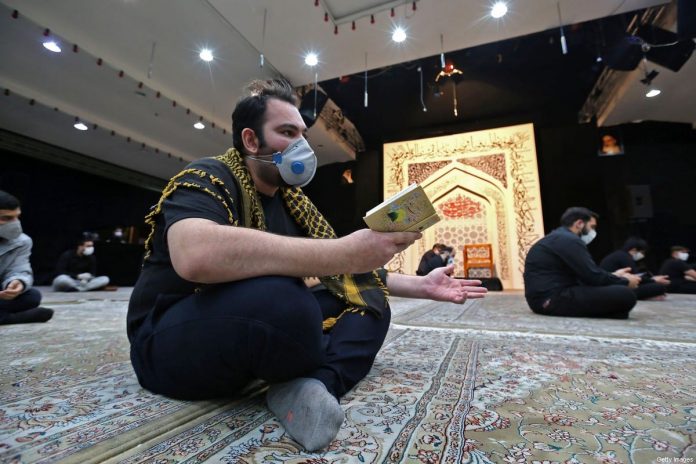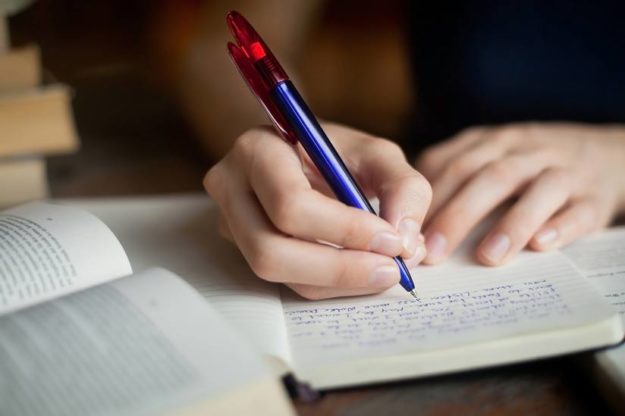Tafsir Surah An-Naml ayat 18-19 mengisahkan percakapan Nabi Sulaiman dengan Raja Semut. Menurut Qatadah dalam Tafsir Surah An-Naml ayat 18-19 ini terjadi ketika Sulaiman berjalan dengan tentaranya di lembah Syam.
Selanjutnya Baca Tafsir Surah An-Naml ayat 18-19 di bawah ini…..
Baca Sebelumnya: Tafsir Surah An-Naml Ayat 16-17
Ayat 18
Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah, yang menurut Qatadah, merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara raja semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil, sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya.
Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial yang sangat terorganisasi ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual.
Otaknya terdiri atas sekitar setengah juta simpul syaraf, mempunyai mata yang berfungsi baik, dan sungut yang berfungsi sebagai hidung untuk mencium atau ujung jari untuk meraba. Tonjolan-tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap. Sedang rambut-rambut yang ada di tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan.
Walaupun banyak organ yang dimiliki semut untuk berkomunikasi, namun komunikasi utama yang dilakukan adalah komunikasi kimiawi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan feromon, suatu senyawa kimia seperti hormon yang mengeluarkan bau dan dihasilkan oleh salah satu kelenjar di dalam tubuh semut itu.
Dengan menggunakan hormon inilah semut berkomunikasi. Apabila seekor semut mengeluarkan feromon, maka semut lainnya akan menerimanya dengan cara mencium baunya atau menyentuhnya, dan bereaksi terhadapnya.
Baca Juga: Kisah Nabi Sulaiman Dalam Al-Quran: Kepribadiannya Sebelum Menjadi Raja
Ayat 19
Mendengar perkataan raja semut bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka, karena tubuh mereka amat kecil.
Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman berupa kemampuan memahami percakapan raja semut itu, dan adanya semacam anggapan baik dari raja semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya, maka Sulaiman berdoa kepada Allah,
“Wahai Tuhanku Yang Pemberi Rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu-bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal saleh yang Engkau ridai, dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal saleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang saleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu.”
Dari doa Nabi Sulaiman itu dipahami bahwa yang diminta oleh Sulaiman kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal.
Sikap Nabi Sulaiman pada waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum Muslimin. Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmat-Nya, dan tidak bersikap mengingkari nikmat-Nya.
(Tafsir Kemenag)
Baca Setelahnya: Tafsir Surah An-Naml ayat 20-22