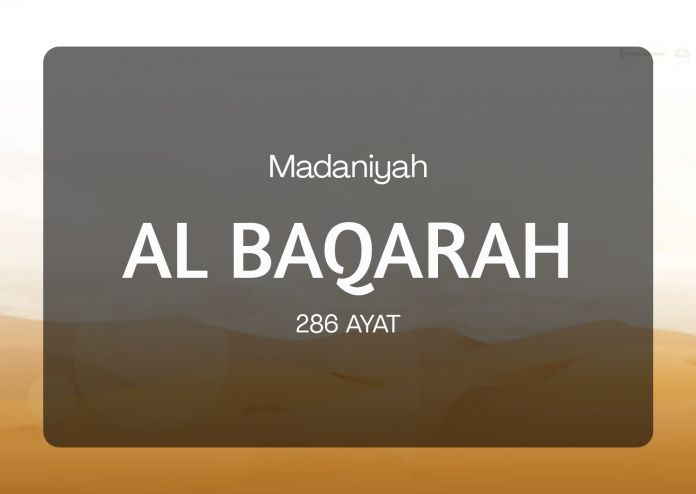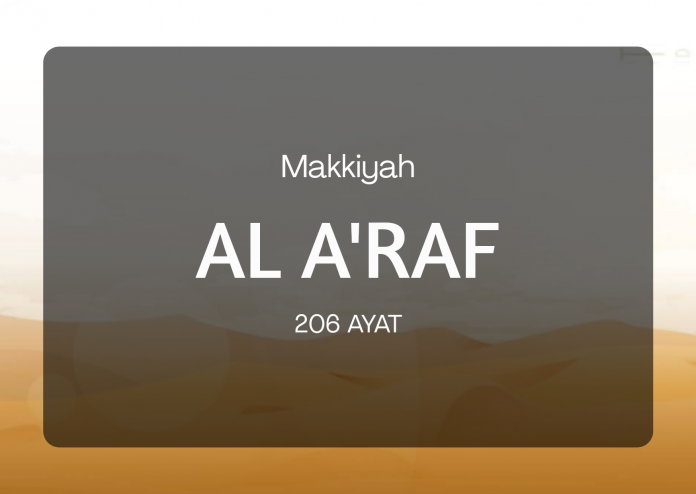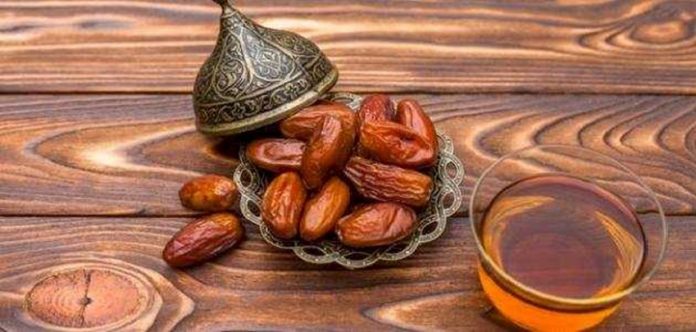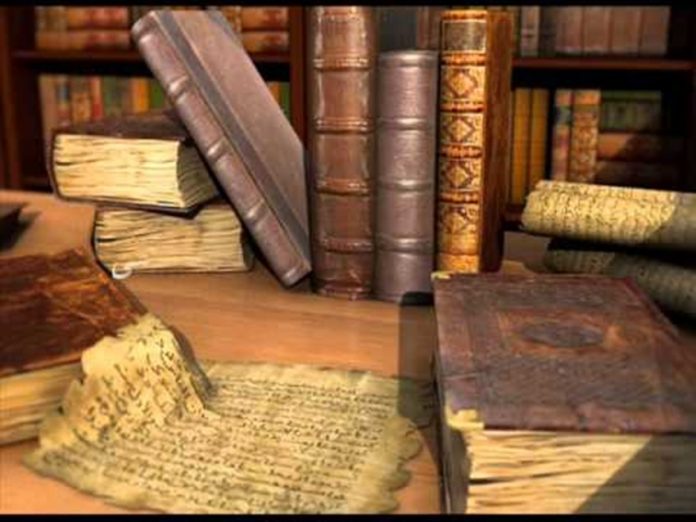Istilah Husn Al-zhann dan Su’ Al-zhann adalah dua istilah yang bertolak belakang, yang satu merupakan bagian dari akhlak muila, sementara satu yang lain adalah sebaliknya. Meskipun demikian, dua-duanya sangat dekat dengan keseharian kita. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran sendiri menyinggung keduanya meski hanya dengan menggunakan kata Al-zhann. Dari situ kemudian ada yang memahami zhann dengan husn al-zhann ada pula yang su’ al-zhann. Bagaimana sebenarnya makna Al-zhann tersebut? Berikut penjelasannya
Al-zhann yaitu pengetahuan yang tidak meyakinkan tentang sesuatu. Hal ini dikaitkan dengan sebuah pengetahuan atau berita yang belum dapat dipercaya kebenarannya. Kata ini juga dikaitkan dengan sebuah pengetahuan yang meyakinkan yang diperoleh melalui pengamatan (tadabbur), bukan melalui pancaindera.
Baca Juga: Jangan Berprasangka Buruk! Renungkanlah Pesan Surat Al-Hujurat Ayat 12
Tiga makna al-zhann dalam Al-Quran
Menurut Ibn al-Jauzy, pada dasarnya makna al-zhann itu ialah keyakinan terhadap salah satu dari dua hal yang berlawanan di dalam diri manusia. Lawannya adalah al-syakk, yang berarti keraguan. Keraguan yaitu ketidakyakinan terhadap dua hal berlawanan di dalam jiwa.
Al-zhann di dalam Al-Qur’an mengandung 3 makna, yaitu
- Al-zhann berarti al-Syakk. Makna al-Zhann yang pertama yaitu ragu-ragu atau keraguan, yang terkandung di dalam QS. Al-Jatsiyah [45]: 24.
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
“Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.”
Kata al-zhann dalam ayat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diragukan atau sesuatu yang diduga-duga kebenarannya. Sebab, manusia tidak memiliki penetahuan yang pasti tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Mereka hanya menduga-duga belaka.
- Al-zhann berarti al-Yaqīn. Makna al-Zhann yang kedua adalah keyakinan, seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 46, Berikut terjemahan ayatnya,
“(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.”
Kata al-zhann yang digunakan di dalam ayat ini menujukkan suatu kepastian. Orang-orang yang berima memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada-Nya.
- Al-zhann berarti al-Kadzib, Makna al-Zhann yangketiga yaitu kedustaan, yang terdapat di dalam QS. Al-Najm [53]: 28, Berikut terjemahan ayatnya,
Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
Kata al-zhann dalam ayat ini menunjukkan makna persangkaan. Manusia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kepastian sesuatu yang akan terjadi pada mereka. Mereka hanya mengikuti sangkaan mereka belaka.
Baca Juga: Pentingnya Berprasangka Baik Dalam Rangka Toleransi Beragama dalam Al-Quran
Perbedaan makna al-zhann di dalam ayat-ayat di atas hanya disebabkan karena perbedaan konteks yang dibicarakan dalam setiap kalimat. Semua kata ini menunjukkan makna yang positif. Lalu kata ini disandarkan dengan kata yang lain, su’u dan husn, sehingga artinya menjadi berbeda. Su’u al-zhann berarti buruk sangka dan husnu al-zhann berarti baik sangka.
Dua makna Al-Zhann menurut Imam Al-Zarkasy
Imam al-Zarkasy, yang dikutip oleh Mahmud al-Mishri, menyatakan bahwa al-zhann mengandung dua makna, yaitu al-yaqin yang bermakna keyakinan, dan al-syakk yang berarti keraguan. Penggunaan kedua makna itu dapat dilihat dari cirinya, yaitu sebagai berikut:
- Al-zhann bermakna yakin apabila sifatnya terpuji, dan dalam hal ini pelaku mendapat pahala, dan al-zhann bermakna ragu apabila sifatnya tidak terpuji, dan palakunya mendapat dosa.
- Apabila kata zhann beriringan dengan kata أن yang tidak bertasydid, maka makna adalah al-syakk (keraguan), seperti di dalam QS. Al-Fath [48]: 12. Apabila zhann beriringan dengan أن yang bertasydid, maka maknanya adalah yakin.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata الظن mengandung tiga makna, yaitu al-syakk (ragu, keraguan), al-yaqiin (yakin, keyakinan), dan al-kadzib (dusat, kedusataan). Ketiga makna itu dapat dipastikan dilihat dari konteks penggunaannya. Kita dapat memastikan perbedaan makna di dalam penggunaan kata al-zhann itu apabila dihubungkan dengan dua kata yang berbeda, yaitu su‘ (سوء) sehingga menjadi سوء الظن yang berarti “berburuk sangka,” dan husn (حسن) sehingga menjadi حسن الظن yang berarti “berbaik sangka”.
Baca Juga: Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 12: Larangan Berprasangka Buruk
Jenis dan hukuman prasangka
Mahmud al-Mishri membagi prasangka itu atas 5 macam dan diakitkan dengan hukumnya masing-masing, yaitu:
- Prasangka yang diharamkan, yaitu prasangka buruk terhadap Allah. Prasangka beuruk terhadap Allah, misalnya, karena Allah menetapkan sebuah kewajiban yang terasa sangat berat dilakukan oleh manusia. Termasuk prasangka buruk terhadap Allah, kalau Allah memberikan ujian, cobaan kepada manusia.
- Prasangka yang diharamkan, yaitu prasangka buruk terhadap kaum muslimin, seperti prasangka terhadap sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mislanya, ia melihat seorang muslim, yang kaya raya, lalu dalam pikirannya dia berkata, bahwa kekayaannya itu adalah diperoleh dengan jalan yang haram. Padahal orang itu mendapatkannya dengan jalan yang halal.
- Prasangka yang diperbolehkan, yaitu prasangka yang terlintas di dalam hati seorang muslim kepada saudaranya karena ada hal yang mencurikan. Boleh berprasangka kepada seseorang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita agar kita berjaga-jaga dan waspada dari hal itu.
- Prasangka yang dianjurkan adalah prasangka baik terhadap sesama muslim. Misalnya, ada seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang baik, lalu kita menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Berprasangka baik terhadap sesuatu yang kurang baik yang dilakukan oleh seseorang kepada diri kita. Lalu kita berkata, bahwa dia sebenarnya tidak memiliki tujuan yang tidak baik terhadap kita.
- Prasangka yang diperintahkan adalah prasangka dalam ibadah dan hukum yang belum ada nashnya. Prasangka itu adalah prasangka yang berkaitan dengan upaya untuk mengeluarkan suatu hukum yang belum ada nashnya di dalam Al-Qur’an dan al-Hadis. Ijtihad yang dilakukan oleh ulama terhadap suatu yang hukum yang belum ada nashnya di dalam Al-Qur’an maupun hadis adalah prasangka yang diperintahkan.
Penjelasan tentang makna al-zhann di atas menginformasikan bahwa makna al-zhann itu tidak satu, tetapi banyak, bahkan ada yang sampai kontradiktif, sesuai konteks ayatnya. Wallahu a’lam