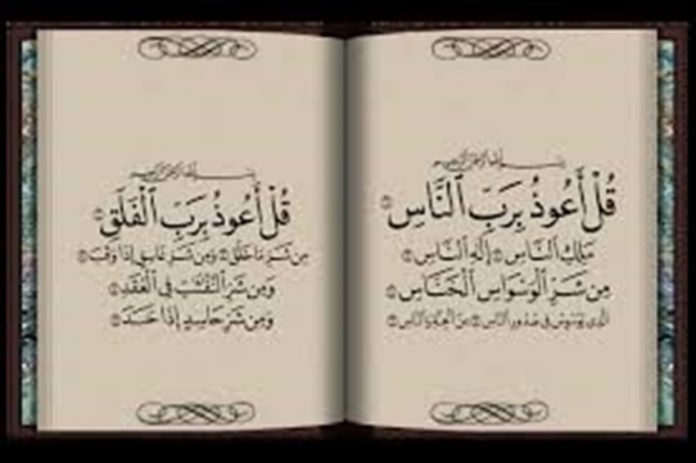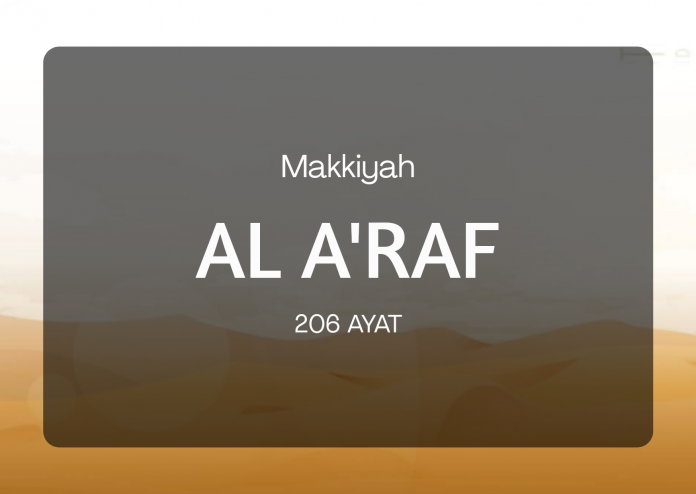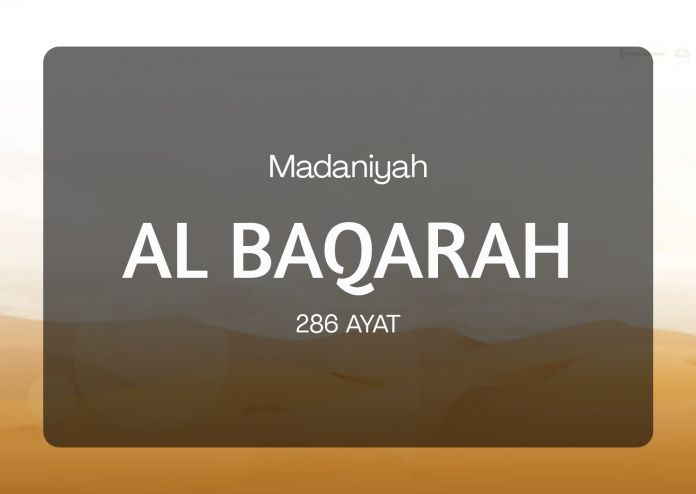Salat Witir menjadi salah satu ritual yang sering dilakukan umat Islam selepas Salat Tarawih di Bulan Ramadan. Biasanya, salat Witir di Bulan Ramadan, dilakukan secara berjamaah sebanyak 3 rakaat. Di Tiap rakaat itu, orang yang salat Witir juga dianjurkan untuk membaca surah-surah pendek tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.
Salat Witir
Salat Witir merupakan salat sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Mengutip ‘Ianah at-Thalibin karya Sayyid al-Bakri, di antara hadis yang menjadi dalil kesunnahan Salat Witir ialah hadis sahih yang ditakhrij oleh Abu Daud:
الوترُ حقٌ على كلِ مسلمٍ فمن أحبَ أن يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ أو بثلاثً فليفعل أو بواحدةٍ فليفعل
“Salat Witir sunnah muakkad bagi tiap muslim. Barangsiapa senang menunaikan 5 rakaat Witir maka lakukanlah! Atau 3 rakaan, maka lakukanlah! Atau satu rakaat, maka lakukanlah!”
Baca Juga: Sejarah Puasa dan Rahasia Dipilihnya Bulan Ramadhan Menurut Para Tokoh Tafsir
Sementara itu, ada pula pendapat yang mewajibkan Salat Witir. Pendapat ini datang dari Imam Abu Hanifah. Ia berlandaskan pada hadis Nabi:
أوتروا فإن الله وترٌ يحِبُ الوترَ
“Salat Witirlah! Karena sesungguhnya Allah itu ganjil. Ia menyukai Witir”
Meski demikian, tampaknya, pendapat kesunnahan Witir lebih unggul, karena dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 terdapat diksi salatil wustha (salat yang tengah), yang merupakan istilah untuk salat paling utama. Meski terdapat banyak pendapat soal salat apa yang dimaksud salat wustha, apakah salat ‘Ashar, Subuh, Maghrib, atau sengaja disamarkan, sebagaimana penjelasan Al-Baghawi dalam Ma’alimut Tanzil, tidak ada satu pun yang mengarah pada Salat Witir.
Ditambah pendapat sementara Fuqaha, bila Salat Witir wajib, maka tidak ada salat wustha, dan saat Nabi mendelegasikan Muadz bin Jabal ke Yaman, ia menegaskan bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam, tidak enam waktu.
Tetapi, untuk menghormati perbedaan itu dan berdasar hadis Nabi di atas, Salat Witir sangat dianjurkan (Sunnah Muakkad), bahkan menjadi salat sunnah paling utama dibanding Salat Rawatib. (Sayyid Bakri, ‘Ianatut Thalibin, 249)
Baca Juga: Tafsir Ahkam: Beda Pendapat tentang Salat Fardu yang Paling Utama
Seperti namanya, Salat Witir memiliki rakaat ganjil. Mulai dari satu rakaat, sampai 11 rakaat. Sedangkan, batas minimum sempurnanya salat witir ialah sejumlah 3 rekaat. Ketentuan ini bukan berarti menimbulkan konsekuensi hukum makruh bagi yang menunaikan Witir satu rakaat. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam Nihayatuz Zayn, yang demikian itu sebatas kurang utama saja, atau dalam istilah fikih disebut khilaful awla.
Pada dasarnya, salat sunnah ini tidak sekedar dianjurkan ketika Ramadan tiba, melainkan setiap hari, seusai menunaikan salat Isya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, salat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan berjamaah, kecuali saat Ramadan.
Surah-surah yang sunnah dibaca
Menurut Fuqaha, pada Salat Witir 1 rakaat, disunnahkan untuk membaca Surah Al-Ikhas dan Al-Muawwidzatayn. Sedangkan, pada salat Witir 3 rakaat, terdapat lima surah yang sunnah dibaca. Lima surah-surah pendek itu ialah Al-A’la; Al-Kafirun; Al-Ikhlash; Al-Falaq, dan An-Nas (Al-Mu’awidzatayn. Menurut Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam Al-Adzkar, pada rakaat pertama, disunnahkan membaca Al-A’la, disusul rakaat kedua sunnah membaca Al-Kafirun, dan yang terakhir membaca surah Al-Ikhlash dan Al-Mu’awidzatayn.
Pendapat Imam Nawawi senada dengan Sayyid Bakri. Pendapat ini didukung oleh hadis dalam Sunan An-Nasa’i dan Ibnu Majah:
سئِلتْ عائشةُ رضي الله عنها بأي شيءٍ كان يوتِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرَأُ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانيةِ بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد والمعوذتَينِ
‘Aisyah ra. ditanyai perihal surah apa yang dibaca Nabi saw. tatkala menunaikan Salat Witir. ‘Aisyah ra. menjawab: “ Nabi saw. membaca sabbihisma rabbikal a’la (surah Al-A’la) pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun (Surah Al-Kafirun) pada rakaat kedua, dan qul huwa Allahu ahad serta al-mu’awwidzatayn (Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas) pada rakaat ketiga”
Baca Juga: Alasan Mengapa Surat Al-Ikhlas Sebanding Sepertiga Al-Quran Menurut Imam Ghazali
Bila Salat Witir dilakukan melebihi 3 rakaat, maka pada selain 3 rakaat terakhir, disunnahkan untuk membaca Surah Al-Qadr pada rakaat ganjil dan Surah Al-Kafirun. Adapun, tiga rakaat terakhir disunnahkan membaca 5 surah-surah pendek sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. (Syeikh Nawawi al-Bantani, Nihayatuz Zayn, 102).
Kesunnahan lain dalam pelaksanaan Salat Witir ialah dengan menjadikannya pemungkas salat-salat sunnah, terlebih bila seseorang terbiasa bangun malam. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan melaksanakan Salat Witir 2 kali. Jika kita sudah menunaikan Witir, lalu bangun dan salat Tahajjud atau salat sunnah lain, kita tidak sah untuk mengulang Salat Witir kembali. Hal ini berdasarkan hadis yang disitir Imam Nawawi dalam Nihayatuz Zayn, “laa witraani fi laylatin” (tidak ada dua witir dalam satu malam).
Wallahu a’lam