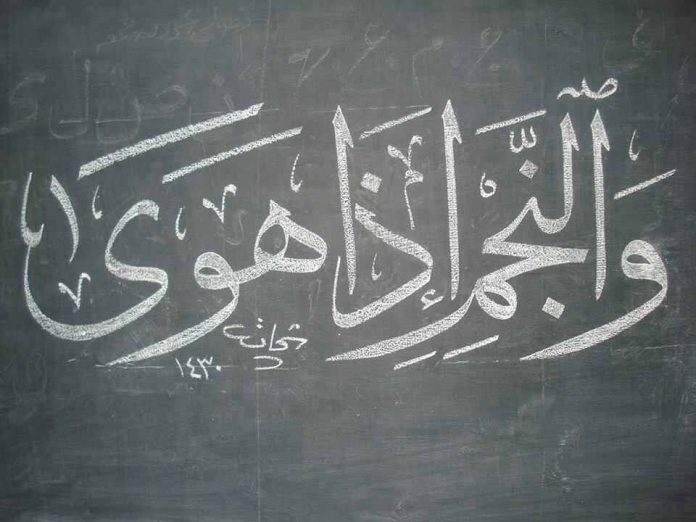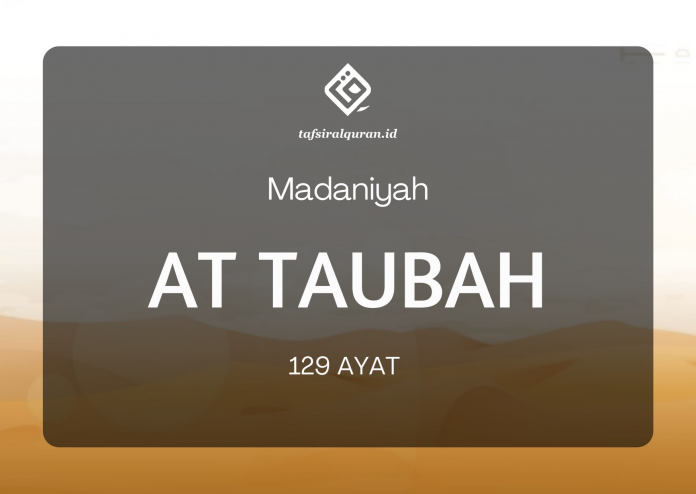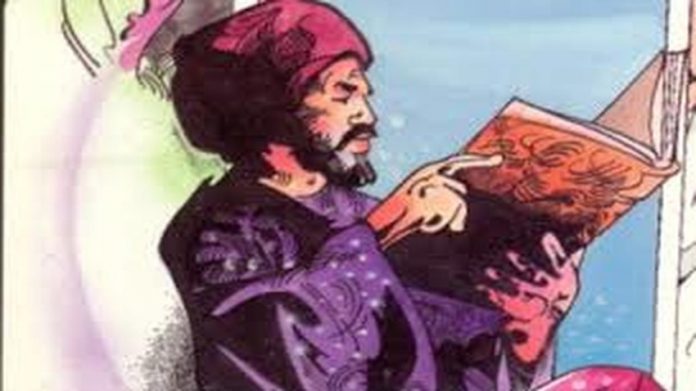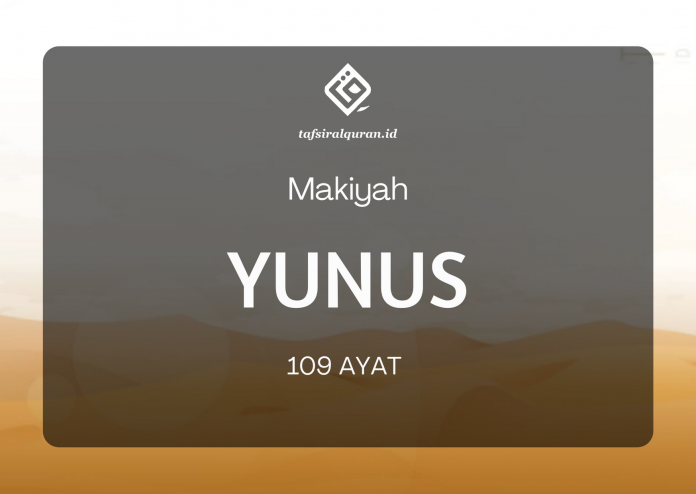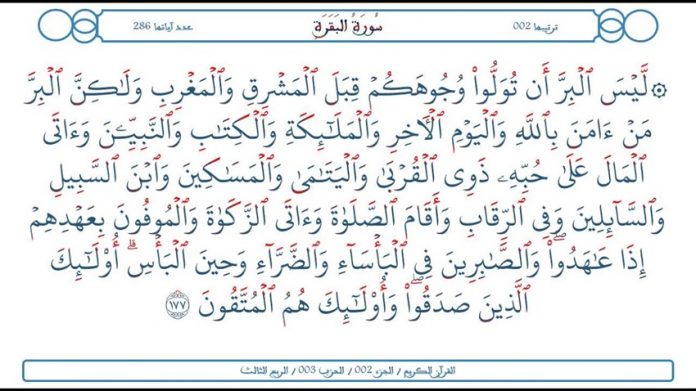Pada risalah ini, gagasan utama yang akan saya perkuat adalah argumentasi tentang pemaknaan teks-teks wahyu Al-Quran dalam khazanah intelektual Islam awal yang tidak bermakna tunggal, statis, dan pasti, tetapi sebaliknya, plural, dinamis, dan kontradiktif. Satu lagi contoh aspek pluralisme dan kontradiksi makna teks Al-Qur’an tang terefleksikan dalam tradisi penafsiran awal adalah pemaknaan atas surah An-Najm [53]: 1 yang berbunyi wa an-najm idha hawa. What exactly was the meaning of this divine oath in early Islam?
Hingga saat ini, makna atas ayat sumpah di atas telah dibentuk dan dipengaruhi oleh paham ortodoksi Islam yang mengambil konsensus bahwa Tuhan bersumpah demi bintang ketika ia terbenam/terjatuh.
Selama ini, An-Najm ditafsirkan sebagai bintang secara umum. Ada juga beberapa penafsir awal menafsirkannya lebih spesifik. Al-Suddi (w. 128/745), misalnya, menafsirkan An-Najm sebagai venus (Az-Zuharā) karena “sekelompok manusia diantara orang-orang Arab menyembah Venus”. Berbeda dengan Al-Suddī, Mujāhid b. Jabr (w. 102/720) menafsirkannya sebagai bintang Ath-Thurayya (the Pleiades) ketika mereka menghilang di waktu fajar.
Baca Juga: Makna Wahyu dalam Penafsiran Muqatil bin Sulayman
Wa an-najm idha hawa: demi bintang, demi Nabi Muhammad
Penafsiran An-Najm sebagai bintang, itu berarti bahwa Tuhan bersumpah secara impersonal demi bintang ketika ia terbenam, baik itu sebagai bintang pada umumnya atau bintang secara khusus, yakni Venus, Ath-Thurayya, dan Sirius. Penafsiran ini merepresentasikan konsensus mayoritas ulama tentang pemaknaan An-Najm sebagai bintang. Proses penafsiran ini sudah menghasilkan makna yang stabil dan tetap dan hampir tertutup kemungkinan untuk mengeksplorasi makna-makna lain yang tak terpikirkan (unthinkable meanings).
Namun, ketika saya membaca kembali khazanah intelektual Islam awal yang terabaikan dalam diskursus pemikiran Islam modern, dan mengeksplorasi kemungkinan makna-makna lain atas sumpah Tuhan secara impersonal itu, saya menemukan kemungkinan makna lain dari sumpah tersebut yang terekam dalam tradisi awal penafsiran Al-Qur’an yang berorientasi sufistik.
Di kalangan sufi, pemaknaan ayat pembuka di surah An-Najm itu tidak terkait dengan sumpah Tuhan atas nama bintang, tetapi justru sepenuhnya tentang Muhammad. Dalam tafsir sufistiknya, Kāmil al-Tafsīr al-Sūfi al-‘Irfāni li Al-Qur’ān (2002:159), Ja‘far Al-Sadiq (w. 148/765), figur sentral dalam tradisi Shi’ah dan penafsir wahyu yang otoritatif di awal Islam, menafsirkan sumpah Tuhan—wa an-najm idha hawa—dengan makna yang bercorak sufistik.
Pertama, “An-najm berarti Muhammad; ketika dia turun, [maka] cahaya-cahaya terpancar darinya”; Kedua, “An-Najm adalah hati Muhammad ketika terputus dari apa pun kecuali Tuhan.” Penafsiran Al-Qur’an yang bercorak sufistik ini juga dapat ditemukan pada pemikiran teolog Islam Sunnī dan penafsir sufistik, Sahl ‘Abd Allāh Al-Tustari (w. 283/896). Dalam karyanya, Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm (1908:145), At-Tustari menafsirkan sumpah Tuhan—wa an-najm idha hawa—dengan makna yang sufistik: “Demi Muhammad ketika ia kembali dari langit.”
Meskipun Ja‘far Al-Sadiq dan Al-Tustari berasal dari dua tradisi Islam yang berbeda, keduanya sama-sama memproduksi makna esoterik dan mistik atas sumpah Tuhan itu, yang ditafsirkan sebagai referensi kepada Muhammad yang baru saja kembali dari pengalaman spiritual di malam mi‘raj.
Pada momen pengalaman spiritual yang berharga itulah hati Muhammad terputus dari segala bentuk keterikatan pada apa pun, kecuali hanya pada Tuhan. Untuk itu, Tuhan bersumpah bukan secara impersonal atas nama bintang, tetapi justru secara personal atas nama Muhammad yang baru saja kembali dari perjumpaan spiritual dengan the heavenly figure.
Berbeda dengan pemaknaan sumpah Allah di atas yang statis, mengenai pertanyaan, siapakah figur yang dijumpai dan bahkan dilihat oleh Muhammad dalam perjalanan spiritualnya di ufuk yang tinggi (the highest horizon) dan di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ataukah Tuhan itu sendiri, telah menjadi perdebatan intelektual yang produktif sejak awal Islam.
Penafsiran sufistik atas sumpah Tuhan secara personal itu tetap dipandang absah dan legitimitatif dalam khazanah intelektual Islam, terutama karena konteks pewahyuan surah An-Najm terkait langsung dengan proses mi‘raj Muhammad ke langit, sehingga sumpah Tuhan—wa an-najm idha hawa—merujuk pada momen peristiwa kembalinya Nabi Muhammad dari langit.
Baca Juga: Siapa Saja Mufassir di Era Sahabat? Edisi Abdullah Ibn Abbas
Wa an-najm idha hawa: demi Al-Quran
Selain makna “demi bintang ketika ia terbenam” dan “demi Muhammad ketika ia kembali dari langit,” sejumlah penafsir Al-Qur’an pada fase awal Islam juga berikhtiar untuk mengeksplorasi makna lain atas sumpah Tuhan—wa an-najm idha hawa. Hasilnya adalah makna “demi Al-Qur’an ketika ia turun [secara gradual, sedikit demi sedikit].” Pemaknaan wahyu yang kreatif dan inovatif ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada pemikiran sejumlah penafsir Al-Qur’an, mulai dari ‘Abd Allah b. ‘Abbas (w. 68/688), Mujahid b. Jabr (w. 102/720), Zayd b. ‘Ali (w. 120/738); Muqatil b. Sulayman (w. 150/767), sampai Abu Zakariyya’ Yahya b. Ziyad Al- Farra’ (w. 207/822).
Bahkan, Ibn ‘Abbas lah penafsir otoritatif yang pertama kali menafsirkan wa an-najm idha hawa sebagai referensi pada pewahyuan Al-Qur’an secara gradual: “Saya bersumpahdemi Al-Qur’an ketika ia turun secara gradual, sedikit demi sedikit: tiga atau empat ayat dan surah. Jarak interval antara wahyu pertama dan terakhir adalah dua puluh tahun.” Pendapat Ibn ‘Abbās ini terekam dalam al-Tafsīr al-Basīt yang terdiri atas 25 volume (Mesir:2013) karya penafsir masyhur Al-Wāhidi (w. 486/1076).
Baca Juga: Tafsir Ibnu Abbas: Mengenal Dua Kitab yang Menghimpun Penafsiran Ibnu Abbas
Sebagai otoritas penting dalam tafsīr, Ibn ‘Abbas mempunyai pengaruh yang besar pada penafsiran Al-Qur’an di awal Islam dan abad pertengahan. Hal ini terbukti pada sejumlah penafsir yang terafiliasi pada dirinya. Mujāhid b. Jabr adalah salah satunya, yang juga menafsirkan sumpah itu dengan proses pewahyuan Al-Qur’an yang tidak terjadi sekaligus (all at once), tetapi secara gradual, tahap demi tahap.
Proses wahyu yang gradual itu dideskripsikan secara tepat oleh penafsir Shi’ah, Zayd b. ‘Alī dalam Tafsīr Gharīb Al-Qur’ān (Cairo: 1992, 191), yang berkomentar bahwa “wa an-najm idha hawa merujuk pada proses turunnya Al-Qur’an secara gradual. Jibril terbiasa menurunkan Al-Qur’an kepada Muhammad sedikit demi sedikit, yakni lima āyāt, kurang atau lebih.”
Penafsiran atas wahyu yang gradual ini juga diperkuat oleh penafsir Muqātil b. Sulaymān dalam Tafsīr Muqātil b. Sulaymān, yang terdiri atas 5 volume (Cairo: 2002, vol. 4:159): “Tuhan bersumpah demi Al-Qur’ān. Wa an-najm idha hawa berarti turunnya Al-Qur’an dari langit ke Muhammad secara gradual, yang maknanya sesuai firman-Nya: “[Tidak!] saya bersumpah demi turunnya Al-Qur’an secara berangsur-angsur” (fala uqsimu bi almawāqi’i an-nujūm, al-Wāqi‘ah/ 56:75). Ketika Al-Qur’an turun, maka ia turun sedikit demi sedikit: tiga atau empat ayat,atau sesuatu yang serupa, dan satu atau dua surah.”
Akhirnya, penafsiran Al-Qur’an—wa an-najm idha hawa—tidak pernah bermakna satu dan sama, tetapi plural dan kontradiktif. Hal ini terekam secara eksplisit dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an yang bersifat multivokal. Para penafsir wahyu di fase awal Islam terbiasa dengan multivokalitas penafsiran atas makna Al-Qur’an.
Terkait dengan pluralisme dan kontradiksi makna Al-Qur’an ini, para intelektual kemudian terinspirasi untuk mengajukan pertanyaan yang terabaikan dalam tradisi pemikiran Islam: di mana kah sebenarnya letak lokus makna atas teks-teks Al-Qur’an? Apakah lokus makna itu terletak pada otoritas teks (the authority of text) ataukah pada otoritas penafsir (the authority of interpreters)?