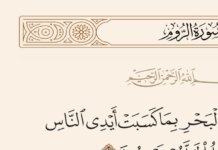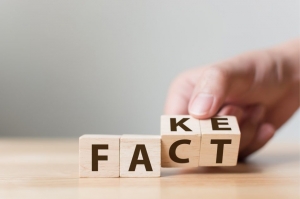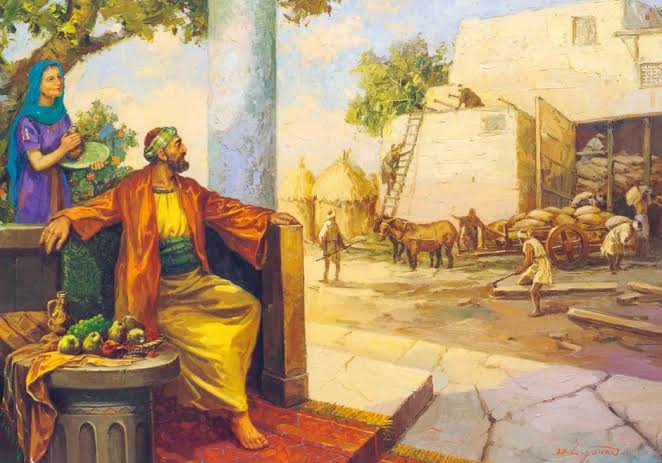Di tengah derasnya arus digitalisasi, pertanyaan mendasar yang menggelitik para pemikir muslim adalah bagaimana Alquran, kitab suci yang diturunkan 14 abad lalu bisa tetap menjadi panduan yang relevan. Tantangan ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi para mufasir muda yang hidup di era ketika artificial intelligence, media sosial, dan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dan memahami realitas. Alquran dengan tegas menyatakan posisi Islam sebagai agama yang mendapat perkenan Allah:
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗوَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ( اٰل عمران/3: 19)
Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya) (Q.S. Ali ‘Imran/3: 19).
Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib (vol. 7/hlm. 172) menggarisbawahi bahwa perbedaan di kalangan ahli kitab yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah akibat ketidaktahuan. Akan tetapi, lebih kepada kedengkian dan kesombongan, meskipun ilmu telah diberikan kepada mereka. Ia mengidentifikasi tiga kelompok perbedaan di antara ahli kitab:
- Kaum Yahudi: Mereka berselisih setelah wafatnya Nabi Musa a.s., ketika 70 pemimpin agama yang diberi amanah atas Taurat gagal menjaga keutuhannya. Generasi selanjutnya saling berselisih karena hasad dan perebutan kepentingan duniawi.
- Kaum Nasrani: Mereka berbeda pendapat tentang status Nabi Isa a.s., sebagian menganggapnya sebagai nabi, anak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri.
- Gabungan Yahudi dan Nasrani: Mereka berselisih dalam menolak kenabian Nabi Muhammad saw. karena alasan rasial, menganggap kaum Quraisy yang “ummiyyin” (tidak memiliki kitab sebelumnya) tidak layak menerima wahyu.
Ar-Razi menunjukkan bahwa meskipun ilmu telah datang kepada mereka, perbedaan masih bisa muncul karena hasad dan keinginan untuk saling mendominasi (بَغْيًا بَيْنَهُمْ). Ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam di era modern, bahwa ilmu agama seharusnya menjadi alat untuk menyatukan, bukan memecah belah.
Baca juga: Grand Syekh Al-Azhar Kunjungi Indonesia, Quraish Shihab Tegaskan Komitmen Wasathiyyah
Namun, bagaimana Islam memandu umatnya untuk tetap relevan di tengah perkembangan zaman? Tantangan ini tidak hanya melibatkan pemahaman yang statis terhadap teks-teks suci, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam konteks modern. Ayat berikut memberikan isyarat tentang peran strategis umat Islam sebagai pembawa kebaikan dan pembela keadilan.
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ( اٰل عمران/3: 110)
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (Q.S. Ali ‘Imran/3: 110).
Konsep Ummah
Quraish Shihab, dalam tafsirnya (vol. 2/hlm. 232) memberikan pemahaman mendalam tentang konsep “ummah” yang menjadi kunci penting dalam memahami peran umat Islam di era modern. Menurutnya, ummah bukan sekadar kumpulan individu yang statis, melainkan representasi dari kesatuan yang bergerak dinamis, dengan arah dan tujuan yang jelas di bawah satu kepemimpinan. Pemahaman ini menjadi sangat relevan di era digital, ketika komunitas tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis.
Yusuf Qardhawi memperkuat perspektif ini dengan menegaskan bahwa Alquran adalah kitab yang abadi, yang hukum-hukum dan tuntunannya tidak terbatas oleh waktu atau generasi tertentu. Alquran, menurutnya, dijaga oleh Allah Swt. karena fungsinya sebagai pedoman hingga akhir zaman, bukan hanya untuk satu kelompok atau periode tertentu (Yusuf Qardhawi, 1999, hlm. 93). Pandangan ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk upaya membumikan Alquran di era digital.
Baca juga: Solusi Alquran dalam Pencegahan Stunting
Dalam konteks kekinian, tantangan untuk menghadirkan Alquran sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi manusia) menjadi semakin kompleks. Prof. Syahrin Harahap mengidentifikasi nilai-nilai universal Alquran yang perlu digali untuk menjaga relevansinya dalam kehidupan modern. Menurutnya, nilai-nilai seperti ketundukan kepada Tuhan, persamaan derajat manusia, toleransi, pembebasan, dan keadilan menjadi sangat penting untuk direvitalisasi dalam konteks kontemporer (Syahrin Harahap, 2017, hlm. 15). Di era digital, nilai-nilai ini mendapatkan momentum baru untuk diaktualisasikan dalam berbagai dimensi kehidupan.
Lebih jauh, Prof. Harahap mengajukan empat argumentasi penting tentang urgensi memahami Alquran dalam konteks modern. Pertama, modernisasi dalam Islam harus tetap berlandaskan ajaran Alquran yang memberikan panduan tentang dinamika kehidupan. Kedua, para pembaru muslim perlu terus menghindari stagnasi dengan merujuk pada Alquran sebagai sumber utama. Ketiga, kebutuhan akan penafsiran mendalam mendorong pemikiran yang lebih progresif. Keempat, modernisasi dalam Islam pada dasarnya adalah upaya kembali kepada inti ajaran Alquran dan hadis (Syahrin Harahap, 2017, hlm. 15).
Peran Mufasir
Pernyataan Muhammad Abduh yang dikutip oleh Jansen menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Ia mengingatkan bahwa pada hari akhir nanti, Allah tidak akan menanyakan pendapat para mufasir tentang Alquran, melainkan bagaimana kita memahami dan mengamalkan kitab-Nya yang diturunkan sebagai petunjuk (J. J. G. Jansen, 1997, hlm. 28). Peringatan ini menjadi semakin bermakna di era digital, ketika tantangan untuk membumikan Alquran atau menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks.
Para mufasir muda kini dihadapkan pada tugas untuk melakukan tiga hal penting: memahami teks, membaca konteks, dan menghadirkan makna. Memahami teks berarti menguasai ilmu-ilmu tradisional yang diperlukan dalam penafsiran. Membaca konteks artinya memiliki kepekaan terhadap isu-isu kontemporer, dari artificial intelligence hingga krisis iklim. Menghadirkan makna berarti mampu menerjemahkan nilai-nilai universal Alquran ke dalam bahasa dan realitas kekinian.
Baca juga: Tafaqquh Fi Digital dan Pedoman Bermedia Sosial dalam Alquran
Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang bagi para mufasir muda. Mereka perlu mengembangkan metodologi tafsir yang tidak hanya setia pada tradisi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman. Seperti ditegaskan Qardhawi, Alquran diturunkan sebagai pedoman hingga akhir (Yusuf Qardhawi, 1999, hlm. 93). Ini mengisyaratkan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk membumikan Alquran dengan menemukan relevansinya dalam konteks zamannya.
Penutup
Sebagai penutup, tantangan untuk membumikan Alquran di era digital bukanlah tugas yang ringan. Namun, justru di sinilah peran strategis para mufasir muda. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami teks dan konteks, tetapi juga harus mampu menghadirkan Alquran sebagai solusi atas problematika kontemporer.
Jika kita hanya berpegang pada penafsiran klasik tanpa menggali lebih dalam atau menyesuaikan dengan konteks zaman, Alquran bisa terlihat jauh dari kehidupan manusia modern. Dengan kata lain, jika kita tidak mampu menghadirkan Alquran secara relevan, jangan heran jika generasi mendatang mencari petunjuk di tempat lain. Wallahu a’lam.


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)