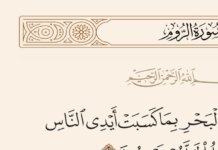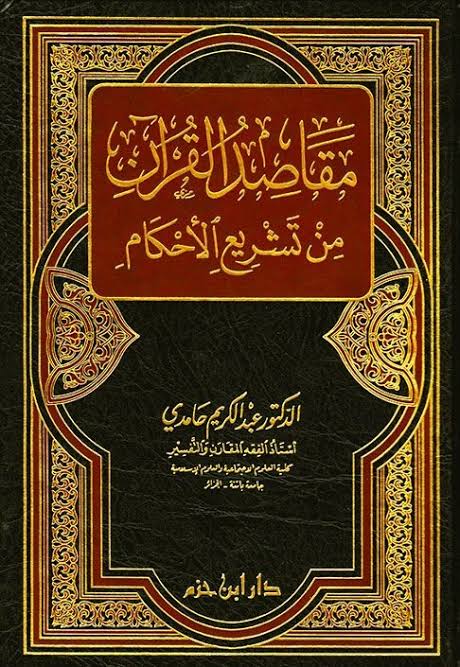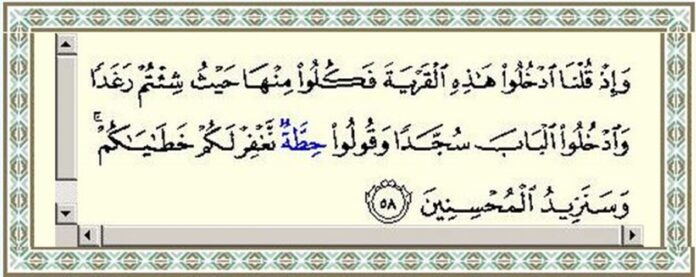Bagaimana memahami definisi manusia dalam konteks perkembangan zaman saat ini? Salah satu sumber yang memberikan panduan mendalam tentang esensi manusia adalah Alquran. Alquran memberikan arahan spiritual, yang juga mencakup nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Alquran mendefinisikan manusia dan relevansi definisi ini dalam konteks dunia modern.
Alquran menyebutkan dengan jelas martabat dan kehormatan yang diberikan kepada manusia. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ” yang artinya, “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam.” (Q.S. Al-Isra [17]: 70). Penegasan ini menunjukkan bahwa manusia, sebagai ciptaan Allah, diberikan martabat dan kehormatan yang tinggi. Martabat ini mencakup dimensi moral dan spiritual.
Jadi nilai manusia tidak hanya terletak pada kemampuan intelektual atau pencapaian material. Akan tetapi, juga pada kapasitas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks manusia modern, peringatan ini relevan sebagai pengingat bahwa meskipun kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan material, nilai-nilai kemanusiaan dan etika harus tetap menjadi pusat perhatian.
Baca juga: Penafsiran Strukturalis Semiotik Surah Al-Kahfi: Lima Model Manusia
Lebih jauh lagi, Alquran menggambarkan manusia sebagai khalifah di bumi. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً “Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ‘Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” Definisi ini menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memelihara bumi dengan bijaksana.
Di tengah isu lingkungan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya, tanggung jawab ini semakin relevan. Manusia modern dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan. Sebagai khalifah, manusia diharapkan untuk bertindak dengan tanggung jawab, tidak hanya demi kepentingan saat ini, tetapi juga untuk kesejahteraan generasi mendatang.
Alquran juga menekankan pentingnya akal sebagai alat untuk membuat keputusan moral yang baik. Dalam surah Al-Mulk (67: 2), Allah berfirman, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا “(Dia) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Q.S. Al-Mulk [67]: 2). Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan adalah ujian dan manusia diberikan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Baca juga: Alquran dan Problem Sosial Kemanusiaan Perspektif Cendekiawan Muslim Kontemporer
Dalam dunia modern yang kompleks, kemampuan untuk menggunakan akal secara bijaksana sangat penting. Ini mencakup pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab di berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga hubungan sosial. Dalam konteks ini, Alquran mengajarkan bahwa kecerdasan harus diarahkan untuk kebaikan bersama dan tidak hanya untuk keuntungan pribadi.
Selain itu, Alquran mengakui kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Dalam surah Al-Kahf ayat 29 diوَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artinya, “Dan katakanlah, ‘Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia kafir.” (Q.S. al-Kahf [18]: 29). Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam memilih adalah hak setiap individu. Namun, dengan kebebasan tersebut datanglah tanggung jawab untuk memilih jalan yang benar.
Dalam konteks manusia saat ini, kebebasan ini mencakup hak untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keyakinan pribadi. Dan harus diimbangi dengan kesadaran akan dampak dari keputusan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain.
Baca juga: Karya-karya Tafsir Bercorak Sosial di Era Modern
Dari perspektif ulama dan literatur Islam, kitab-kitab seperti Tafsir Al-Jalalain dan Fath al-Bari memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat-ayat ini. Misalnya, dalam Tafsir Al-Jalalayn, penjelasan mengenai martabat manusia sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan etika yang harus dipenuhi.
Kemudian dalam Fath al-Bari dijelaskan bahwa sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara bumi serta mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana. Buku-buku ini menggarisbawahi bahwa meskipun manusia diberikan kebebasan, kebebasan tersebut harus digunakan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh akan implikasinya.
Secara keseluruhan, definisi manusia menurut Alquran memberikan panduan yang relevan bagi kita di era modern. Dengan menekankan martabat, tanggung jawab, penggunaan akal, dan kebebasan dengan tanggung jawab, Alquran menawarkan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan zaman modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Panduan ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan material tidak mengabaikan prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari keberadaan manusia.


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)