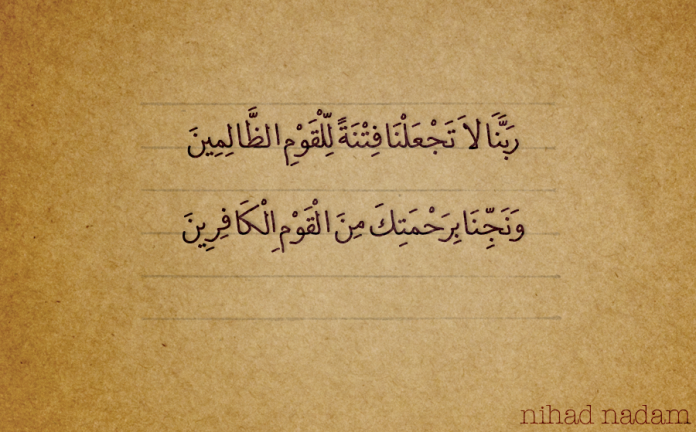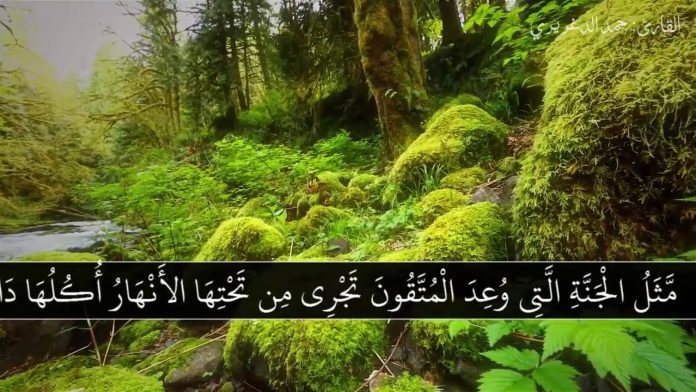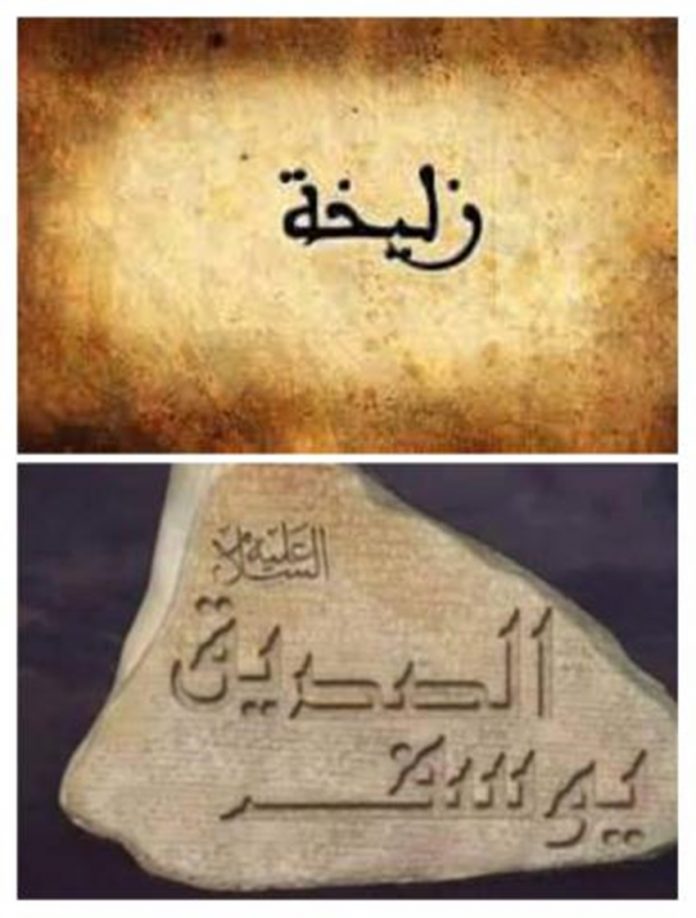Segala bentuk pemanfaatan teknologi jejaring sosial atau telekomunikasi, menimbulkan dua implikasi yaitu positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya tentu kita semua sudah merasakannya yaitu mempererat tali saliturrahim dan membuat yang jauh seakan menjadi dekat. Namun disisi lain ada dampak negatif karena penggunaan yang kurang tepat, salah satunya yaitu ujaran kebencian (Hate Speech). Apakah hate speech itu?
Hate Speech adalah sebuah Tindakan yang dalam koridor agama perbuatan yang sangat tidak terpuji, dalam hal ini bisa digambarkan dengan upaya individu atau sekelompok orang yang menyerang individu atau kelompok pihak lain dengan nada kebencian, dan sesungguhnya hal itu menjadikan sebuah luka yang dalam dan susah untuk diobati, dan apabila bisa di obatipun juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dalam kondisi hati dan pikiran serta perasaan tersakiti maka akan sangat sulit menemukan jalan harmoni. setidaknya itulah gambaran kerusakan yang ditimbulkan oleh Hate Speech.
Baca juga: Mari Amalkan Doa Agar Terhindar dari Kezaliman dan Fitnah dalam Al-Quran
Dalam kehidupan sehari-hari pernahkah kita membayangkan betapa dahsyatnya sebuah ujaran kebencian? Tentu dalam hal ini sebagian besar sepakat bahwa ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech akan sangat berdampak buruk dalam hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Bahkan dalam skala yang lebih luas implikasi dari ujaran kebencian (Hate speech) dapat mengoyak belah serta memecah belah keutuhan sebuah bangsa.
Al-Qur’an menyampaikan pelajaran yang sangat berharga mengenai bahaya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech), yaitu kisah Raja fir’aun yang hancur karena ucapannya sendiri. Sang fir’aun harus mengalami kehancuran karena selalu melontarkan ujaran kebencian (hate speech) kepada nabi Musa. Namun pada akhirnya bukan nabi Musa yang hancur justru ujaran kebencian itu berbalik kepada fir’aun sendiri. Oleh karenanya pesan-pesan dalam Al-Qur’an selalu mengajarkan kepada kita agar tidak mudah membenci orang lain. Seperti yang telah di firmankan dalam surat al Hujurat ayat 12:
يأيها ٱلذين ءامنوا ٱجتنبوا كثيرا من ٱلظن إن بعض ٱلظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وٱتقوا ٱلله إن ٱلله تواب رحيم
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Baca juga: Kajian Semantik Kata Jannah dalam Al-Quran dan Korelasi Maknanya
Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 12
Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan, Telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mu’minin Umar ibnul Khattab r.a., bahwa ia pernah berkata, “Jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin melainkan hanya kebaikan belaka, sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik.”
قَالَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا”.
Malik r.a. telah meriwayatkan dari Abuz Zanad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta; janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling berbuat makar, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ القِرْمِطي الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: “ثلاث لازمات لِأُمَّتِي: الطِّيَرَةُ، وَالْحَسَدُ وَسُوءُ الظَّنِّ”. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنْ هُنَّ فِيهِ؟ قَالَ: “إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأمض “
Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurmuti Al-Adawi, telah menceritakan kepada kami Bakr ibnu Abdul Wahhab Al-Madani, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Qais Al-Ansari, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu Muhammad ibnu Abur Rijal, dari ayahnya, dari kakeknya Harisah ibnun Nu’man r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Ada tiga perkara yang ketiganya memastikan bagi umatku, yaitu tiyarah, dengki, dan buruk prasangka.
Seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara melenyapkannya bagi seseorang yang ketiga-tiganya ada pada dirinya?” Rasulullah Saw. menjawab: Apabila kamu dengki, mohonlah ampunan kepada Allah; dan apabila kamu buruk prasangka, maka janganlah kamu nyatakan; dan apabila kamu mempunyai tiyarah (pertanda kemalangan), maka teruskanlah niatmu.
Baca juga: Surah An-Nur [24] Ayat 27: Anjuran Mengucap Salam Ketika Bertamu
Tegasnya, apabila kita ingin meraih ketenangan dan ketentraman maka jauhilah hate speech. Implikasi dari hate speech tidak hanya mengoyak kesatuan suatu bangsa melainkan juga ketentraman harmonisasi intern. Cara yang bisa kita tempuh dalam hal ini ialah dengan membumikan pesan-pesan langit, sebuah istilah untuk menggambarkan luasnya wahyu yang telah diturunkan kepada manusia untuk dipedomani. Membumikan pesan langit bagian dari jihad, ijtihad, dan mujahadah. Kita tak dapat menginkari bahwa Al-Qur’an merupakan serangkaian pesan yang kaya dengan ajaran moral-spiritual, dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya.