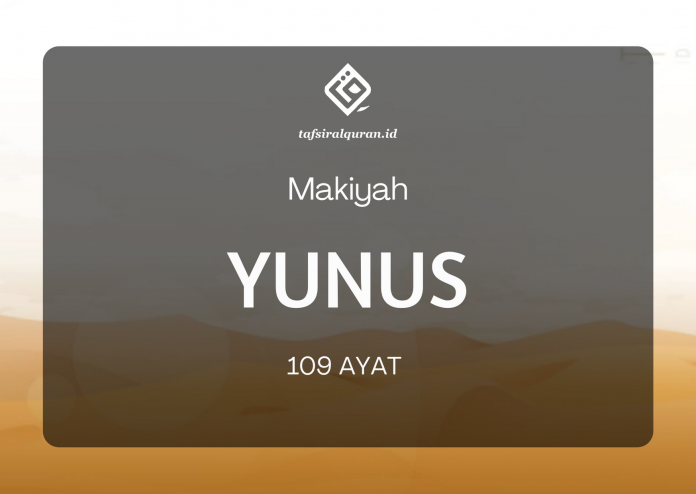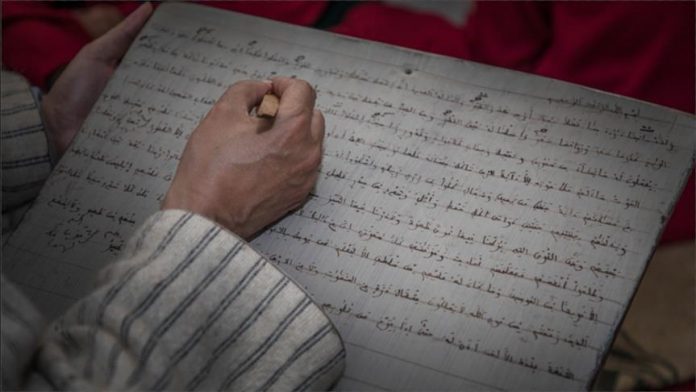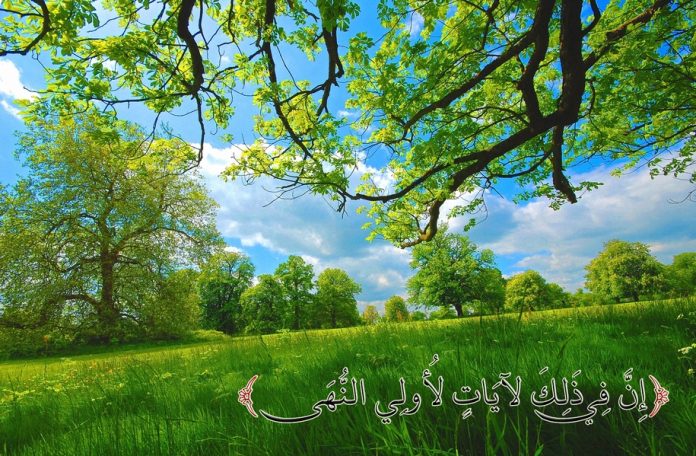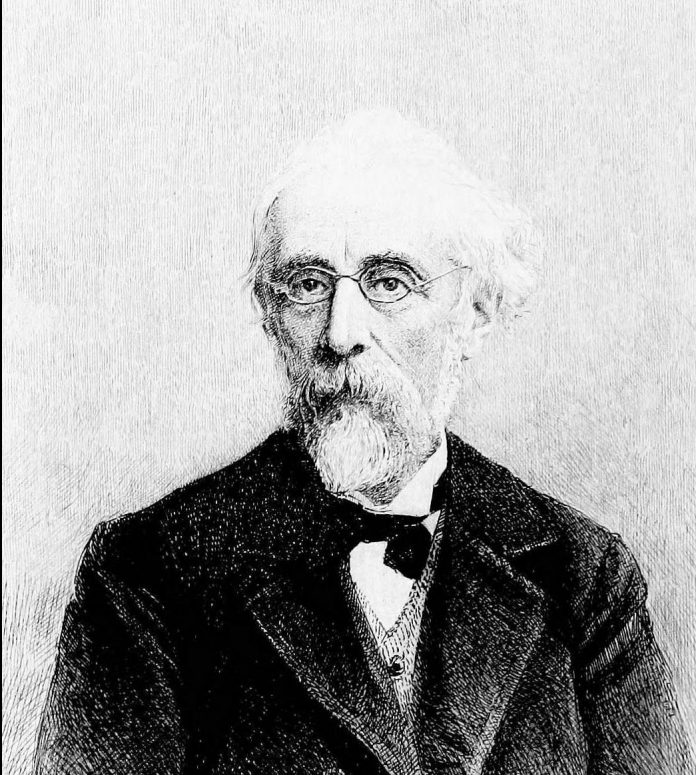Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah lewat diciptakannya hewan adalah keberadaan jenis minuman berupa susu. Susu adalah cairan yang secara alami dikeluarkan oleh hewan. Susu amat berbeda dengan darah serta kotoran yang sama-sama juga dikeluarkan oleh hewan. Susu hewan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Lalu bagaimana ulama’ memperoleh kesimpulan hukum halalnya susu, padahal darah dan kotoran dihukumi haram? Berikut penjelasannya:
Perihal Susu Hewan Di Dalam Al-Qur’an
Kehalalan susu hewan di dalam Al-Qur’an merujuk pada dua firman Allah. Pertama, Surat An-Nahl ayat 66:
وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ٦٦
Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya (QS. An-Nahl [16] 66).
Kedua, firman Allah dalam Surat Al-Mu’minun ayat 21:
وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةًۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۙ ٢١
Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan (QS. Al-Mu’minun [23] 21).
Imam Ibn Katsir tatkala menafsiri Surat Al-Mu’minun ayat 21 menyatakan, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari hewan ternak. Diantaranya adalah dapat diminum susunya, dapat dimakan dagingnya, dapat dipakai bulunya dan dapat ditunggangi punggungnya. Susu tersendiri memiliki keunikan. Sebab meski bersanding dengan darah dan kotoran, Allah telah mengatur jalur keluarnya susu tersendiri sehingga tidak bercampur dengan yang lain (Tafsir Ibn Katsir/3/197).
Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami’ Liahkamil Qur’an menyatakan, dalam ayat di atas terdapat dasar bolehnya mengambil manfaat dengan susu hewan. Baik pengambilan manfaat itu dengan cara meminum maupun selainnya. Namun ini berlaku pada susu dari hewan yang hidup. Sedang dari hewan yang mati atau bangkai, maka tidak boleh dimanfaatkan. Dikarenakan susu adalah sesuatu yang cair, dan keberadaannya di dalam bangkai menyebabkan susu itu berasal dari wadah yang najis sehingga otomatis susu itu menjadi najis (Tafsir Al-Jami’ Liahkamil Qur’an/10/126).
Di dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah dinyatakan, ulama’ mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali bersepakat bahwa apabila susu hewan tersebut keluar dari hewan yang hidup, maka hukum susu tersebut mengikuti hukum mengkonsumsi daging hewan tersebut. Apabila daging hewan tersebut haram atau makruh dikonsumsi maka hukum mengkonsumsi susunya adalah haram atau makruh juga. Apabila halal, maka hukum susunya juga halal (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah/2/1628).
Penutup
Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abi Hurairah dinyatakan, tatkala Isra’ Mi’raj, Nabi Muhammad pernah diberi dua pilihan. Yaitu antara susu dan khamr. Lalu Nabi pun memilih susu. Lalu ada yang berkata kepada Nabi Muhammad “Engkau telah mendapatkan fitrah manusia. Andai engkau memilih khamr, pastilah umatmu tersesat” (Sahih Bukhari/3/1243).
Di dalam hadis lain yang diriwayatkan Abi Dawud, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, diajarkan sebuah doa tatkala minum susu. Doa tersebut berbunyi:
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
Allaahumma baarik lanaa fiihi wazidnaa minhu
Ya allah, berilah keberkahan pada susu ini dan berilah kami tambahan darinya (Sunan Abi Dawud/11/157).
Berbagai uraian di atas menunjukkan kepada kita tentang dalil kehalalan susu hewan. Tidak hanya halal, tapi juga merupakan nikmat yang besar sebab mengandung berbagai manfaat. Susu juga merupakan rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Nabi sendiri juga mengajarkan doa sebelum meminum susu. Kesemuanya menunjukkan keistimewaan susu. Wallahu a’lam bishshowab