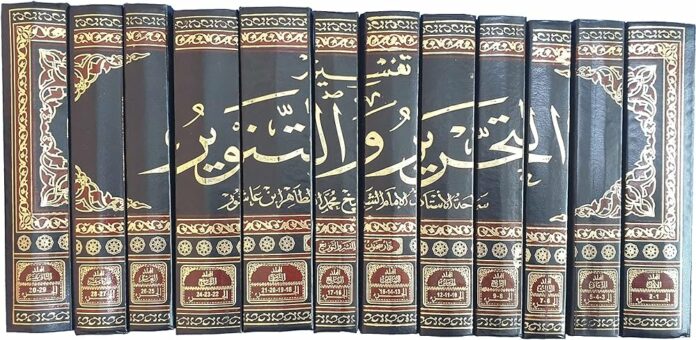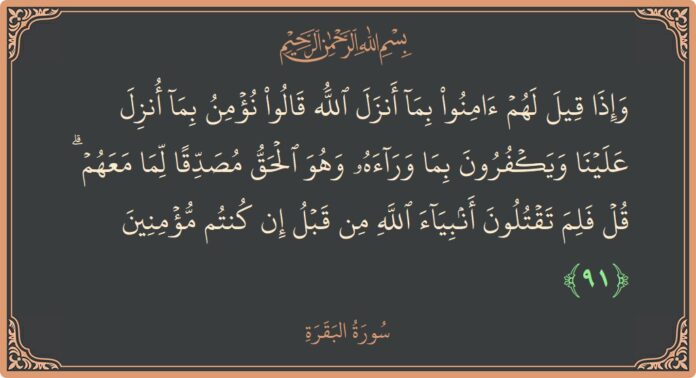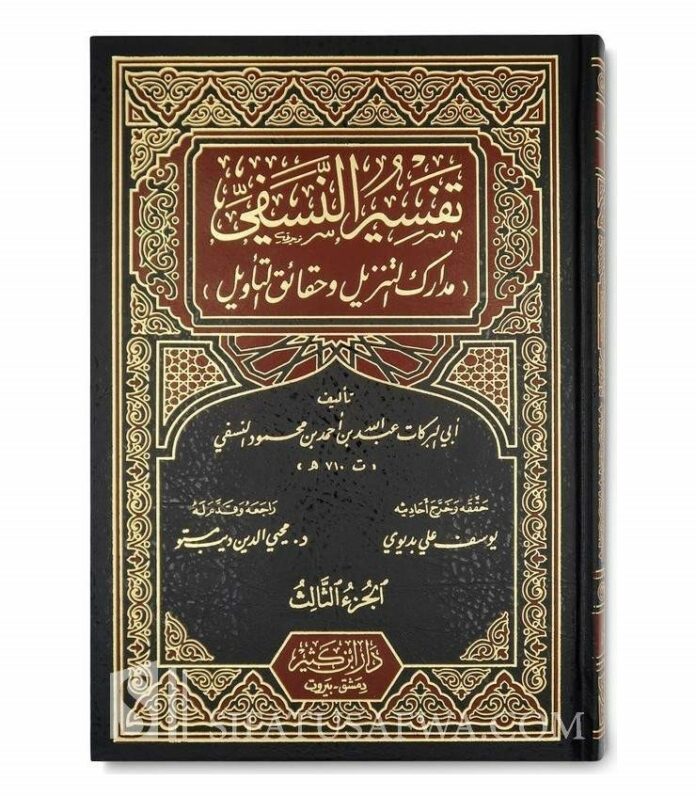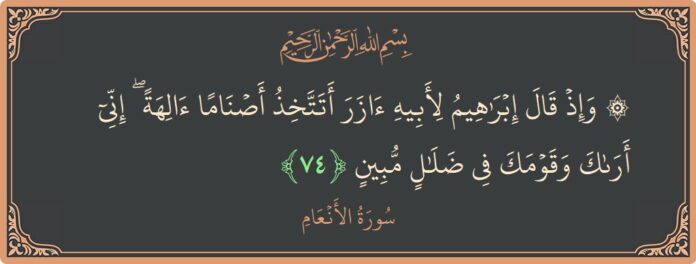Dalam tulisan ‘Izz al-Din Kashnit yang tertulis dalam karyanya yang berjudul Ummahat Maqasid al-Qur’an menyebutkan salah satu tokoh yang mempunyai kiprah dalam dunia maqashid ialah Ibnu Ashur (Kashnit, Ummahat Maqasid al-Qur’an, 363). Pernyataan Kashnit memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Ibn Āshūr merupakan tokoh dalam tafsir maqashidi, akan tetapi penyebutan Kashnit tersebut secara tidak langsung memasukkan Ibnu Ashur dalam ruang lingkup tokoh tafsir maqashidi.
Karya tafsir Ibnu Ashur yang terkenal dan banyak dikaji serta mempunyai banyak sumbangsih dalam dunia keilmuan tafsir ialah tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas terkait Ibn Āshūr dan seputar tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir.
Baca Juga: Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur dan Empat Prinsip Penafsirannya
Biografi Ibn Āshūr
Ibnu Ashur mempunyai nama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadzili bin ‘Abd Qadir bin Muhammad bin Ashur. Ia dilahirkan tahun 1296 H/1879 M di sebuah desa yang bernama Marsi, yang berada di Tunisia bagian Utara. Beliau juga terkenal dari keluarga yang religius dan cendekiawan. Rata-rata keluarganya mempunyai kiprah agama yang baik.
Oleh sebab itu, Ibn Āshūr juga tumbuh sebagai tokoh yang mempunyai banyak sumbangsih dalam dunia keilmuan. Sejak kecil, dia memang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sehingga dari didikan yang diterapkan oleh keluarganya mendapatkan pengaruh yang besar dan membentuk pola pikirnya (Al-Khaijah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar, jilid 1, hal. 154)
Sejak umur 6 tahun, Ibn Āshūr sudah dikenalkan dengan ilmu seputar al-Qur’an dan juga beberapa kitab turats lainnya. Umur 14 tahun beliau sudah menginjakkan karir intelektualnya di Universitas al-Zaitunah. Beliau mempelajari beberapa disiplin ilmu, mulai dari fikih, usul fikih, Bahasa Arab, hadis, tarikh dan beberapa bidang keilmuan lainnya (Al-Khaijah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar, jilid 1, hal. 154).
Pengembaraan keilmuan yang dilalui oleh Ibn Āshūr berhasil membuahkan hasil yang berupa karya-karya yang mengisi peradaban keilmuan. Ibn Āshūr menorehkan beberapa karyanya yaitu tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir, Maqashid al-Syariah al-Islamiyah, Kashf al-Mughtha min al-Ma’ani wa al-Fadz al-Waqi’ah fi al-Muwaththa’, al-waqfu wa Atsruhu dan beberapa karya di bidang keilmuan lainnya.
Baca Juga: Mengenal 8 Maqasid Al Quran Versi Ibnu ‘Asyur
Seputar Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir
Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir diawali dengan pengantar dan juga motivasi Ibn Āshūr dalam menulis tafsir tersebut. Pernyataan latar belakang penulisan tafsir tersebut dapat diketahui melalui muqaddimah tersebut. Dia menyatakan bahwa dorongan tersebut karena cita-cita ia yang memang sedari awal ingin menuangkan pengetahuannya dalam bentuk tafsir.
Dalam catatan al-Hamid, tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir menorehkan catatan waktu yang cukup lama, bahkan hampir memasuki separuh abad, karena tafsir tersebut ditulis dalam kurun waktu 39 tahun dalam hitungan Hijriyah dan 38 dalam hitungan Masehi. Mulai ditulis pada tahun 1341 H/1922 M dan selesai pada tahun 1380 H/1960 M (Al-Hamid, al-Taqrib li Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir, jilid 1, hal. 35).
Ibn Āshūr menjadikan tafsirnya sebagai bentuk refleksi untuk mencurahkan hasil pemikirannya yang belum tersentuh dalam diskursus keilmuan sebelumnya. Akan tetapi, beliau juga secara jelas menyatakan bahwa tafsirnya tersebut merupakan hasil analisis dari tafsir-tafsir sebelumnya. Sang pengarang menjadikan tafsir-tafsir tersebut sebagai rujukan dan tidak melakukan kritik terhadap penukilan yang dilakukan (Ibn Āshūr, at-Tahrir wa at-Tanwir, jilid 1, hal. 7).
Dari pernyataan Ibn Āshūr dapat dipahami bahwa motivasi penulisan tafsir karena adanya rasa cinta, baik kepada Islam atau umat Islam itu sendiri. Dorongan dan motivasi tersebut tentunya tidak terlepas dari lingkungan yang sudah membentuk pola pemikirannya untuk mencintai dunia keilmuan. Sehingga dari itu, beliau berniat untuk terus melanjutkan peradaban keilmuan dengan karya-karya yang beliau tulis.
Baca Juga: Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi: Inspirasi Metode Ishlah dari Ibn ‘Asyur
Metode dan Sumber Penafsiran
Untuk mempermudah kategorisasi ini, perlu adanya pemetaan metode dan sumber yang digunakan untuk memberikan analisis pada satu tafsir. Oleh karena itu, sesuai dengan pemetaan Nashruddin Baidan, corak yang ada dalam tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir masuk dalam kategori corak kebahasaan, karena penjelasan dominan yang ada dalam tafsir tersebut lebih banyak menggunakan analisis kebahasaan. Hal tersebut dapat dilihat ketika Ibn Āshūr menafsirkan surah al-Fatihah.
Ketika Ibn Āshūr menafsirkan surah al-Fatihah, beliau banyak menggunakan analisis kebahasaan nahwu dengan menampilkan struktur kalimat. Berikut potongan penafsiran yang dilakukan Ibnu Ashur:
وَيَصِحُّ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ إِضَافَةُ السُّورَةِ إِلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ
Menurut saya boleh menyandarkan surah ke pembuka surah seperti menyandarkan mausuf kepada sifat. (Ibnu Ashur, at-Tahrir wa at-Tanwir, jilid 1, hal. 132).
Meskipun corak kebahasaan yang menjadi dominasi dalam tafsir ini, pernyataan ‘Izz al-Din Kashnit tentang ketokohan maqaashid juga terdapat dalam analisis surah ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan pernyataannya:
أَنَّهَا تَشْتَمِلُ مُحْتَوَيَاتُهَا عَلَى أَنْوَاعِ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ…
Sesungguhnya surah al-Fatihah kandungannya memuat beberapa macam maqashid al-qur’an… (Ibnu Ashur, at-Tahrir wa at-Tanwir, jilid 1, hal. 133).
Sedangkan sumber yang digunakan oleh Ibn Āshūr, juga bisa dilihat ketika ia menafsirkan surah al-Fatihah, yaitu ia menggunakan Alquran dan hadis sebagai bahan analisis dan tambahan. Contoh penafsiran dengan hadis ketika Ibn Āshūr menjelaskan penamaan al-Fatihah dengan sebutan umm al-qur’an atau umm al-kitab. Wallah a’lam