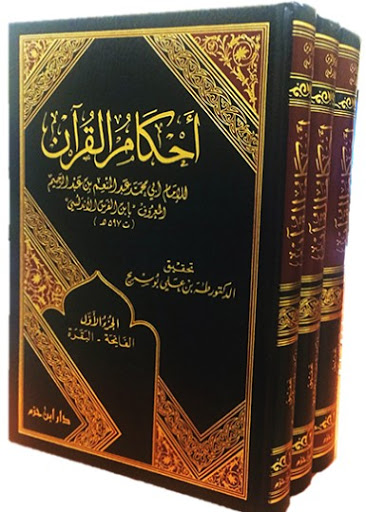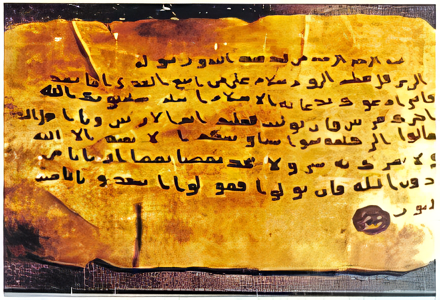Pada dasarnya, setiap orang berhak atas dirinya sendiri serta memiliki kendali penuh terkait apa dan bagaimana ia mengaktualisasikan dirinya. Ia bebas menentukan apa saja yang akan dilakukan, dengan siapa ia menjalin interaksi dan berkomunikasi serta kepada siapa ia akan membagikan informasi pribadinya untuk sekedar curhat, misalnya. Tidak ada yang berhak mengintervensi apalagi mendikte kehidupan pribadi orang lain.
Dengan kata lain, setiap manusia memiliki sisi-sisi privasi yang tidak layak diketahui orang banyak. Secara substantif, hak privasi dapat diartikan sebagai batasan atas diri atau informasi diri dari jangkauan publik. Dalam UU ITE, disebutkan bahwa hak pribadi yang tidak boleh terekspos dengan bebas itu meliputi; hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan; hak untuk berkomunukasi dengan orang lain; hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi.
Namun, sebelum masyarakat modern mengakui eksistensi hak privasi, Islam telah lebih dulu mengakui bahkan berupaya melindungi hak privasi. Hal ini terlihat misalnya dalam Q.S. An-Nur ayat 27-28, Allah Swt. berfirman:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) } [النور: 27]
{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) } [النور: 28، 29]
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Nur [24]: 27-28).
Baca juga: Surah An-Nur [24] Ayat 27: Anjuran Mengucap Salam Ketika Bertamu
Menurut Imam al-Thabari, ayat di atas turun lantaran ada seorang perempuan Ansar yang mengadu kepada Rasulullah. Perempuan tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, di dalam rumah, aku sering ada dalam kondisi yang aku tidak ingin seorangpun melihatnya; tidak orang tua, tidak juga anak. Namun, seringkali seorang anggota keluargaku memasuki rumah sedangkan aku dalam kondisi tersebut.” Lantas, turunlah ayat tersebut menjelaskan mengenai ketentuan memasuki rumah orang lain [Jami’ al-Bayan, juz 18, hal. 147].
Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Islam bukan hanya mengakui hak privasi, tetapi lebih dari itu, berupaya untuk melindungi hak privasi seseorang. Dalam ayat di atas, ditegaskan adanya perintah untuk tidak sembarangan memasuki rumah seseorang sebelum mendapatkan izin dari pemilik rumah yang bersangkutan.
Pasalnya, rumah merupakan tempat paling privasi yang dimiliki oleh seseorang. Di dalamnya ada banyak hal-hal privasi yang tidak selayaknya diketahui orang lain. Maka dari itu, sebelum memasuki rumah orang lain harus terlebih dahulu meminta izin pemilik rumah bersangkutan agar tidak mengganggu hak privasi pemilik rumah tersebut [Tafsir al-Maraghi, juz 18, hal. 95].
Baca juga: Tafsir Surah An-Nur Ayat 58-59: Etika Anak Ketika Ingin Masuk Kamar Orang Tua
Larangan untuk memasuki rumah orang tanpa izin dikarenakan rumah merupakan tempat paling privasi bagi seseorang. Imam al-Mawardi menandaskan bahwa rumah adalah pelindung bagi penghuninya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin masuk ke rumah orang lain harus mendapatkan izin dari pemilik rumah. Hal tersebut, menurut Imam al-Mawardi, disebabkan oleh dua faktor.
Pertama, hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap penghuni rumah untuk menggunakan rumah sesuai kehendaknya sendiri, termasuk menerima atau tidak izin dari orang yang mau memasuki rumah tersebut. Kedua, rumah berperan sebagai pelindung hal-hal sensitif dan privasi pemilik rumah beserta keluarganya [Al-Hawi al-Kabir, juz 13, hal. 463].
Dalam satu peristiwa, Rasulullah saw. pernah menegur dengan keras orang mengintip melalui celah-celah tembok rumah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih-nya meriwayatkan hadis sebagai berikut:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ»
Dari Sahl ibn Sa’d: Sesungguhnya seorang laki-laki mengintip dari celah rumah Nabi saw., sedangkan Nabi saw. pada waktu itu sedang menyisir rambutnya dengan sebuah sisir. Kemudian Nabi saw. bersabda, “ Andai aku tahu kamu mengintip niscaya aku akan mencolok matamu dengan sisir itu. Sungguh, minta izin itu di proyeksikan untuk menjaga mata (H.R. Bukhari).
Baca juga: Walimatul Urs, Kesunnahan dan Etika Menghadirinya
Tindakan mengintip rumah merupakan perilaku menyimpang yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena di dalam rumah terdapat banyak hal-hal privat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hadis di atas menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang mengintip rumah orang lain karena itu membuka peluang tersebarnya hal-hal privasi yang tidak sepantasnya diketahui orang banyak.
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sesungguhnya bukan hanya mengakui keberadaan hak privasi, tetapi juga berusaha melindungi hak privasi. Aturan mengenai pembatasan kebebasan terhadap hak privasi orang lain ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta menjaga keharmonisan hubungan antara satu individu dengan individu lain. hal ini sejalan dengan salah satu tujuan asasi hukum Islam (al-maqashid al-syariah al-dharuriyah), yaitu menjaga kehormatan (hifdz al-‘irdh).