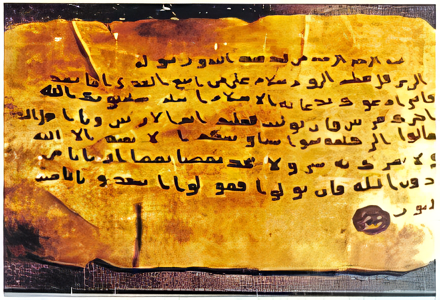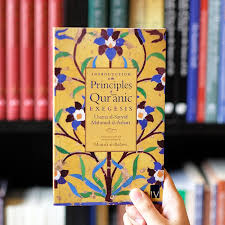Kajian terhadap maqasid asy-syari’ah dinilai muncul lebih awal daripada maqasid al-Qur’an. Dalam fase-fase geneologisnya, maqasid al-Qur’an tidak hanya muncul dari pemikiran para pakar Al-Qur’an. Ada beberapa tokoh besar di bidang maqasid asy-syari’ah yang telah menuliskan gagasannya tentang maqasid al-Qur’an, misalnya Izzuddin bin Abdussalam dan Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur. Selain kedua nama besar tersebut, nama Ahmad ar-Raisuni, ulama besar maqasid asy-syari’ah asal Maroko juga memiliki konsep maqasid al-Qur’an.
Baca Juga: Mengenal 8 Maqasid Al Quran Versi Ibnu ‘Asyur
Biografi Ahmad ar-Raisuni
Ahmad bin Abdus Salam bin Muhammad ar-Raisuni yang lebih dikenal Ahmad ar-Raisuni lahir pada tahun 1372 H./1953 M. di Aulad Sulton, Qashr al-Kabir, Provinsi Ara’isy, Maroko. Pendidikan dasar dan menengah ar-Raisuni dihabiskan di kampung halamannya, Qashr al-Kabir. Setelahnya, ar-Raisuni meneruskan ke Universitas Al-Qarawiyyin dengan mengambil konsentrasi kajian syari’at dan lulus sebagai sarjana di tahun 1398 H./1978 M. Studi pascasarjana ar-Raisuni diteruskan di Universitas Muhammad V, Rabat. Ar-Raisuni meraih gelar magister dalam kajian maqasid asy-syari’ah pada tahun 1409 H./1989 M. dan gelar doktor dalam kajian usul al-fiqh 1412 H./1994 M. (Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi, hal. 3)
Karir intelektual ar-Raisuni sudah dimulai sejak beliau menjadi mahasiswa pascasarjana dengan mengajar sebagai dosen pada program studi usul al-fiqh dan maqasid al-syari’ah, Fakultas Sastra dan Humaniora, Universitas Muhammad V, Rabat (1986-2006). Di level global, ar-Raisuni menjadi Penasihat Akademis di Institut Pemikiran Islam Internasional (The International Institute of Islamic Thought) yang berdiri sejak 1981 dan berbasis di Virginia, Amerika Serikat.
Pada bulan November, 2018 ar-Raisuni menggantikan Yusuf al-Qaradhawi menjadi Pemimpin Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (The International Union of Muslim Scholars) yang berakhir di tahun 2022. (“Ahmed al-Raissouni: President of Muslim Scholars’ Union”, Anadolu Agency, Ankara, 2018)
Baca Juga: Maqasid al-Qur’an Perspektif ‘Abd al-Karim Hamidi
Kontribusi Intelektual ar-Raisuni
Pemikiran ar-Raisuni dalam bidang maqasid tertuang pada karya-karyanya, di antaranya, penerbitan karya akademik tesis berjudul Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi (1411 H./1990 M.) dan disertasi berjudul Nazariyyat al-Taqrib wa al-Taglib wa Tatbiqatuha fi al-‘Ulum al-Islamiyyah (1995 M.). Khusus di bidang maqasid al-Qur’an, ar-Raisuni menulis jurnal ilmiah berjudul Juhud al-Ummah fi Maqasid al-Qur’an al-Karim yang ia presentasikan dalam Muktamar Internasional Pengkaji Al-Qur’an dan terkompilasi dalam sebuah kitab berjudul Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur’an al-Karim wa ‘Ulumuhu
Konsep maqasid al-Qur’an ar-Raisuni kemudian lebih disempurnakan pada kitab Maqasid al-Maqasid: al-Ghayat al-‘Ilmiyah wa al-‘Amaliyah li Maqasid al-Shari’ah yang membahas definisi, klasifikasi, metode ekstraksi, hingga urgensi maqasid al-Qur’an terhadap kehidupan beragama. Kitab Maqasid al-Maqasid adalah sumber otoritatif pemikiran maqasid al-Qur’an ar-Raisuni, meski isi kitab tersebut terdiri dari ragam maqasid lain seperti maqasid al-sunnah dan al-syari’ah. (Maqasid al-Maqasid, 3-10)
Baca Juga: Diskursus Maqashid Al-Quran di Kalangan Ulama Klasik
Konsep Maqasid al-Qur’an ar-Raisuni
Ar-Raisuni membagi maqasid al-Qur’an menjadi tiga bagian, maqasid ayat, maqasid surah, dan maqasid universal Al-Qur’an. (Juhud al-Ummah fi Maqasid al-Qur’an al-Karim, 1965-1966). Klasifikasi maqasid al-Qur’an ar-Raisuni mengindikasikan dua hal. Pertama, similaritas konsep maqasid al-Qur’an ar-Raisuni dengan konsep maqasid asy-syari’ah yang dirumuskannya. Pada aspek klasifikasi misalnya, ar-Raisuni membagi maqasid asy-syari’ah menjadi tiga, maqasid juz’iyyah, maqasid khashshah, dan maqasid ‘ammah. Indikasi kedua adalah menampilkan secara eksplisit proses ekstraksi maqasid al-Qur’an versi ar-Raisuni menggunakan metode induksi dan konklusi. (Muhadarat fi Maqasid al-Syari’ah, 26-30).
Secara hirarkis, maqasid universal adalah bagian maqasid tertinggi dan memiliki cangkupan terbesar. Ar-Raisuni menyebut maqasid universal Al-Qur’an terdiri dari lima maqasid yang dapat dicermati secara tekstual dalam ayat-ayat Alquran, antara lain, pertama, tauhid dan ibadah. Kedua, pedoman hidup dan beragam bagi hamba. Ketiga, penyucian diri dan pengajaran hikmah. Keempat, kasih sayang dan kebahagiaan, dan kelima, menegakkan kebenaran dan keadilan. (Maqasid al-Maqasid, 10-12)
Baca Juga: Alquran dan Ilmu Ushul Fikih
Ekstraksi Maqasid al-Qur’an ar-Raisuni
Dalam proses ekstraksi maqasid universal Alquran, ar-Raisuni telah menyusun dua metode, yaitu metode tekstual dan metode induksi-konklusi. Metode pertama berfokus pada telaah maqasid al-Qur’an yang dinarasikan ayat-ayat Alquran secara eksplisit, misalnya Q.S. Al-Isra’ [17]: 82 menarasikan salah satu maqasid universal yaitu kasih sayang dan kebahagiaan.
Metode kedua mengintegrasikan proses induktif dan konklusif. Kompilasi maqasid parsial pada ayat dan surat disusun berdasarkan kesamaan tematik untuk kemudiaan ditarik kesimpulan beberapa maqasid universal Alquran. Pada pembahasan metode induksi-konklusi, ar-Raisuni juga menyebutkan maqasid universal Alquran perspektif al-Ghazali, Izzuddin bin Abdussalaam, al-Biqa’i, Rasyid Ridha, dan Ibnu ‘Asyur. (Maqasid al-Maqasid, 12-15)
Ahmad ar-Raisuni lebih familiar sebagai tokoh maqasid al-syari’ah kontemporer yang masih eksis menyampaikan pemikiran maqasid-nya melalui berbagai forum ilmiah dan media digital. Namun gagasannya tentang maqasid al-Qur’an dapat menjadi warna baru yang harus terus dikaji, dikritisi, dan dikembangkan sebagai salah satu perspektif untuk melihat fenomena kekinian dan memberikan tawaran jawaban yang relevan dengan visi utama Alquran. Wallah a’lam