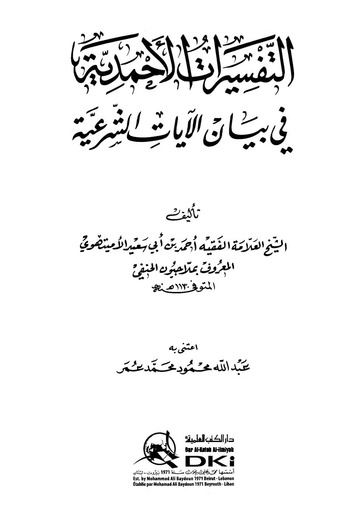Di era yang dipenuhi dengan notifikasi, target, dan tuntutan produktivitas, seseorang didorong untuk terus bergerak, berlari, bahkan berkompetisi setiap hari. Budaya ini sering disebut dengan hustle culture, yakni ketika nilai seseorang ditentukan dari seberapa sibuk dan sibuknya dia.
Baca Juga: Antara Impian dan Keluarga: Refleksi Qur’ani Film Home Sweet Loan
Apa Itu Hustle Culture?
Hustle culture merupakan pola hidup yang menuntut individu untuk terus bekerja dengan tempo cepat dan intens, sering kali tanpa jeda bak kerja rodi. Budaya ini kerap membuat seseorang mengesampingkan waktu istirahat dan mengorbankan kehidupan pribadinya demi produktivitas yang berlebihan.
Pola hidup seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya tekanan sosial, ambisi untuk meraih kesuksesan, pengaruh media sosial yang memamerkan pencapaian seperti yang banyak terlihat di Instagram, hingga perubahan dunia digital yang serba cepat dan instan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang jika terjadi secara terus menerus.
Namun, apakah benar hidup harus secepat itu? Apakah Islam mengajarkan hambanya untuk berlomba-lomba dalam kesibukan?
Slow Living dalam Alquran
Di era modern saat ini muncul trend gaya hidup baru, yakni slow living (hal. 10) yang mulanya berakar dari gerakan slow food di Italia sekitar tahun 1980-an. Gerakan ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran restoran cepat saji di kota Roma. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk kembali menghargai makanan lokal dan menikmati proses makan dengan perlahan. Seiring waktu, gagasan ini berkembang luas dan tidak lagi terbatas pada urusan makanan saja, melainkan merambah ke berbagai aspek kehidupan yang kemudian dikenal sebagai slow living.
Slow living mengajak manusia untuk lebih hadir dan sadar dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dengan cara mengurangi kesibukan yang tidak perlu serta menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan sosial. Gaya hidup ini menekankan pentingnya menikmati setiap momen dengan tenang, tanpa terburu-buru. Fokusnya bukan pada kecepatan, melainkan pada kualitas dalam menyelesaikan sesuatu. Dengan begitu, seseorang akan lebih bijak dalam memanfaatkan waktu, mengelola stres, dan membuat keputusan.
Menariknya, jauh sebelum munculnya trend tersebut, agama Islam telah memiliki prinsip yang selaras dengan gaya hidup slow living, salah satunya disebutkan dalam Q.S Al-Asr: 1-3
وَالْعَصْرِۙ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ࣖ
Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.
Dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan menggunakan kata “masa/waktu” yang mengandung makna tersirat tentng peringatan betapa pentingnya menghargai waktu agar tidak menjadi orang yang merugi, Allah Swt bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa yang telah diberikan-Nya dan memanfaatkannya dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip slow living yakni menghargai waktu.
Namun, perlu digaris bawahi bahwa gaya hidup slow living bukan berarti justru bermalas-malasan, dalam Q.S Al-Insyirah: 7 juga telah disebutkan:
فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Ayat tersebut mengandung nilai semangat produktivitas, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menafsirkan dalam Tafsir Al-Wajiz (hal. 598) “Maka ketika kalian lengang wahai Rasulallah setelah melaksanakan dan menyampaikan risalah itu kepada manusia, maka beristirahatlah dengan berdoa dan ibadah, dan tetaplah melakukan keduanya”
Baca Juga: Keseimbangan Hidup Manusia Menurut Al-Quran: Tafsir QS. Al-Qasas Ayat 77
Dari penjelasan tafsir tersebut terlihat bahwasanya maksud Allah Swt adalah tetap menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat, tanpa mengesampingkan salah satunya. Ketika seseorang telah menyelesaikan satu kewajibannya di dunia, maka jangan lupa untuk beristirahat dengan kembali pada Rabb-nya. Untuk hidup yang singkat ini jangan sampai disia-siakan hanya dengan mengejar kesibukan dunia, mengejar validasi manusia yang tak pernah ada ujungnya, sisakan waktu untuk beristirahat sejenak untuk mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah: 152,
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.
Penutup
Melalui ayat diatas Allah Swt mengingatkan hamba-Nya agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal tersebut selaras dengan prinsip gaya hidup slow living yang kini digencari banyak orang. Terlalu berlebihan dalam urusan dunia juga tidak baik, apalagi di tengah kehidupan modern yang serba instan, justru hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi lalai dalam menjaga hubungan spiritual dengan Allah Swt.
Baca Juga: 3 Pola Hidup Minimalis Yang Bernilai Qur’ani
Dalam konteks ini, gaya hidup slow living dapat membantu mengurangi sikap tergesa-gesa, serta mengajak manusia untuk kembali menikmati hidup lebih tenang, dengan tetap produktif, dan menyeimbangkan antara urusan dunia dengan akhirat, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Swt melalui Alquran.