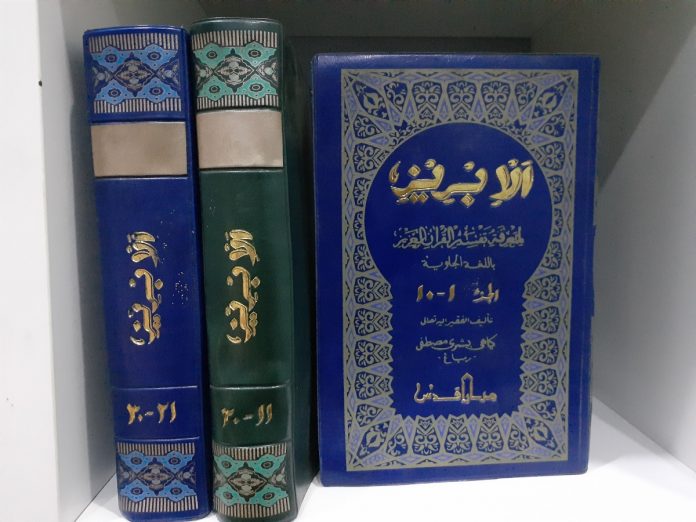Narasi Alquran tentang Firaun menawarkan pandangan yang mengerikan tentang jiwa seorang autokrat. Melalui tindakan dan pernyataannya, kita dapat melihat ciri-ciri kepribadian yang autokrat; haus akan kekuasaan absolut, meremehkan orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya, dan penolakan yang mendalam terhadap setiap tantangan terhadap otoritasnya.
Firaun memang dikenal dengan sikap diktatornya. Alquran menggambarkan sosok Firaun dengan pemimpin yang mengaku dirinya sendiri—dan harus diakui pula oleh para rakyat, tidak terkecuali keluarganya sendiri—sebagai Tuhan atau dewa. Dalam hal ini, Firaun yang digambarkan di dalam Alquran memiliki kepribadian histrionik, yaitu suatu gangguan kejiwaan yang melibatkan emosi yang berlebihan dan kebutuhan yang sangat kuat untuk menjadi pusat perhatian. (Novel Naga Hong Kong Karya Naning Pranoto: Tinjauan Psikologi Sastra the Histrionic Personality Disorders of the Main Characters in Naga Hong Kong Novel Written By Naning Pranoto : a Review of Literature Psychology. E-Journal Student: Sastra Indonesia, Vol. 8 No. 1 Desember 2019, 73)
Pernyataan di atas secara sederhana ingin mengatakan bahwa Firaun di samping memiliki karakter kepemimpinan yang didaktor dan haus akan kekuasaan, di sisi lain, jika ditelaah dari pespektif psikologi, Firaun juga memiliki gangguan psikis. Gangguan psikis ini berupa terus menerus mencari kegairahan (excitement) dan penghargaan (appreciation) dari orang lain, serta kurangnya rasa empati karena berkurangnya aktivitas di wilayah otak yang terkait dengan kasih sayang.
Kompleksitas Firaun dalam Alquran
Dr. John Ng, seorang spesialis neurologi di Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapura, mengenalkan istilah The Pharaoh Complex (Kompleksitas Firaun). The Pharaoh Complex yang dikemukakan oleh Dr. John Ng “terilhami” dari peristiwa dan kisah-kisah di dalam Kitab Keluaran (Book of Exodus) yang terjadi antara Musa dan Harun dengan Firaun, terlebih sikap Firaun yang menjadikan orang Israel sebagai budak.
Dari pembacaannya atas Kitab Keluaran tentang Firaun, Dr. John Ng memetakan tujuh hal utama yang menandakan seorang pemimpin menderita The Pharaoh Complex atau Kompleksitas Firaun, yaitu: Pertama, berpikir dan berperilaku seperti dewa. Kedua, akan melakukan apa saja untuk mencegah hilangnya kekuasaan. Ketiga, menggunakan penipuan untuk membuat citra dan melindungi statusnya.
Baca juga: Menelusuri Aspek Historis Firaun dalam Alquran
Keempat, membuat kompromi untuk tetap berkuasa. Kelima, berbicara secara lembut/manis, membujuk, dan menipu untuk melanggengkan kekuasaannya. Keenam, memanjakan dan membagi hasil rampasannya dengan rekan konspiratornya. Ketujuh, menggunakan ancaman, intimidasi, dan genosida untuk menghancurkan lawan mereka.
Demikian, beberapa ayat Alquran seperti Q.S. Al-Baqarah [2]: 49 dan Q.S. Al- A’râf [7]: 141 yang mengabarkan akan ketiadaan empati Firaun; Q.S. Al- A’râf [7]: 103 dan Q.S. Yûnus [10]: 88 tentang kesombongan serta penolakan Firaun akan tanda-tanda ilahi, dan eksploitasi kekuasaan; Q.S. Al-A’râf [7]: 123-124, Q.S. Thâhâ [20]: 71, dan Q.S. Asy-Syu’arâ` [26]: 49 terkait penindasan dan ketidakadilan yang dilakukannya, serta ayat-ayat lainnya mengonfirmasi akan The Pharaoh Complex yang termaktub dalam Alquran.
Kompleksitas Firaun: Tiadanya Rasa Empati
Q.S. Al-Baqarah [2]: 49 yang berbunyi:
وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۤءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ
(Ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir‘aun dan) pengikut-pengikut Fir‘aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu.
dan Q.S. Al- A’râf [7]: 141 yang berbunyi:
وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۤءَ الْعَذَابِۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌࣖ
(Ingatlah wahai Bani Israil) ketika Kami menyelamatkan kamu dari para pengikut Fir‘aun yang menyiksa kamu dengan siksaan yang paling buruk. Mereka membunuh anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu.
memiliki redaksi yang sama persis, kecuali pada kata yudzabbihûna dan yuqattilûna. Secara eksplisit-tekstual, kedua ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israil dari kekejaman pengikut atau rezim Firaun yang dengan entengnya menyembelih serta membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan.
At-Thabarî mencoba menjelaskan akan perintah Firaun kepada pengikutnya untuk menyiksa dan membunuh anak laki-laki Bani Israil. Meskipun Firaun tidak melakukan praktik kekejaman tersebut secara langsung. Akan tetapi, Firaun sebagai orang yang memerintah dan penguasa, juga dianggap sebagai “pelaku utama” yang memiliki andil cukup besar (Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Âyi al-Qur’ân, jilid 01, 203-204).
Baca juga: Meski di Bawah Pimpinan Firaun, Allah Tak Perintahkan Nabi Musa Untuk Berontak
Selaras dengan At-Thabari, Quraish Shihab menukil pendapat Al-Biqâ’î bahwa kata âl pada awalnya bermakna fatamorgana. Ia menampakkan suatu yang tidak ada, dalam arti jika fatamorgana itu tidak ada, maka sesuatu tersebut juga tidak akan nampak. Dengan demikian, di kala ayat tersebut menyatakan âl-fir’aun, maka ini mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga, pengikut, dan rezim Firaun itu menampakkan kepribadian Firaun.
Di saat Bani Israil mendapatkan perlakuan yang kejam oleh para pengikut Firaun, maka di saat itu pula yang nampak di pelupuk mata mereka adalah Firaun dengan segala keadaan dan keburukannya. Sehingga, walaupun ketika itu ia tidak ada atau tidak ikut serta dalam penyiksaan, tetapi ia seakan nampak terlihat oleh mereka yang disiksa. (Tafsir Al-Mishbah, jilid 01, 190)
Lebih lanjut, Buya Hamka menerangkan bahwa salah satu dari bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Firaun adalah memusnahkan anak laki-laki. Sehingga Firaun memerintahkan para bidan untuk segera membunuh anak laki-laki yang baru lahir dengan tujuan agar Bani Israil musnah. (Tafsir al-Azhar, jilid 01, 188)
Quraish Shihab menambahkan, konon, Firaun selama setahun memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu, dan membiarkan hidup yang lahir pada tahun berikutnya, demikian seterusnya silih berganti. Nabi Harun lahir pada tahun penyelamatan, sedangkan Nabi Musa lahir pada tahun pembunuhan anak laki-laki. (Tafsir al-Mishbah, jilid 01, 190)
Baca juga: Kisah Perjuangan Ibu Nabi Musa a.s.
Menurut Wahbah Zuhaili, di balik pembunuhan serta penyiksaan anak laki-laki oleh Firaun, ada suatu kekhawatiran dan rasa takut yang membayangi pikirannya. Suatu waktu ia bermimpi ada kobaran api mengerikan yang membuatnya ketakutan. Kobaran api tersebut keluar dari Bayt al-Muqaddas (Yerussalem) masuk menuju rumah-rumah suku Qibti di Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israil yang tidak dimasukinya. Dari mimpi tersebut, muncul dugaan dari tafsir mimpi itu bahwa kekuasaan Firaun akan runtuh di tangan seorang lelaki dari Bani Israil. (al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wa al-Manhaj, jilid 01, 174-175)
Narasi Alquran tersebut menggambarkan tentang kebrutalan Firaun di Mesir yang sering digunakan oleh para autokrat untuk mempertahankan kendali. Dalam cerita dua surah di atas, Firaun memberikan siksaan berat kepada Bani Israel; membunuh anak laki-laki dan membiarkan perempuan mereka hidup. V.A. Mohamad Ashrof mencoba membandingkan tindakan genosida dan penindasan berbasis gender ini dengan karya Ervin Staub tentang psikologi kekerasan.
Penelitiannya menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan dan dehumanisasi dapat membuat para pemimpin tidak peka, sehingga tindakan kekejaman lebih mudah dibenarkan. Dari perspektif neurologis (diagnosis dan penanganan gangguan pada sistem saraf), hal ini dapat dijelaskan oleh berkurangnya empati karena berkurangnya aktivitas di wilayah otak yang terkait dengan kasih sayang. (Cultural-societal roots of violence: The examples of genocidal violence and of contemporary youth violence in the United States. American Psychologist, 51 (2), 117–132)