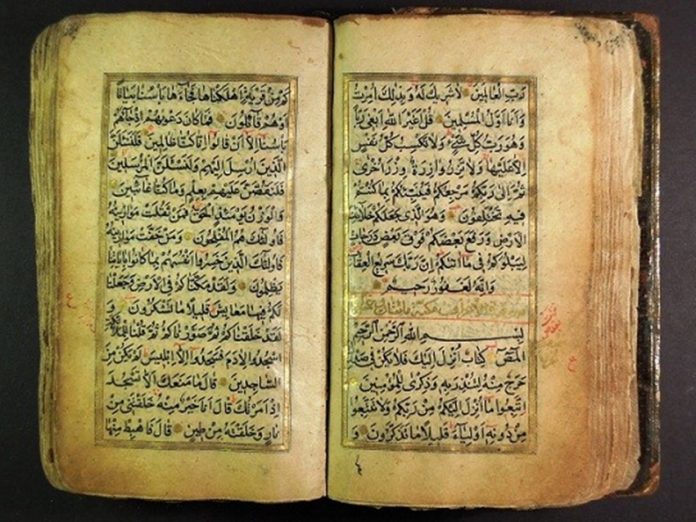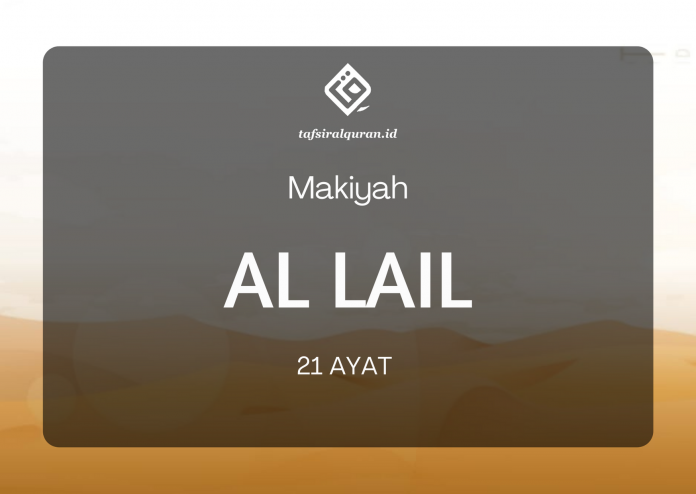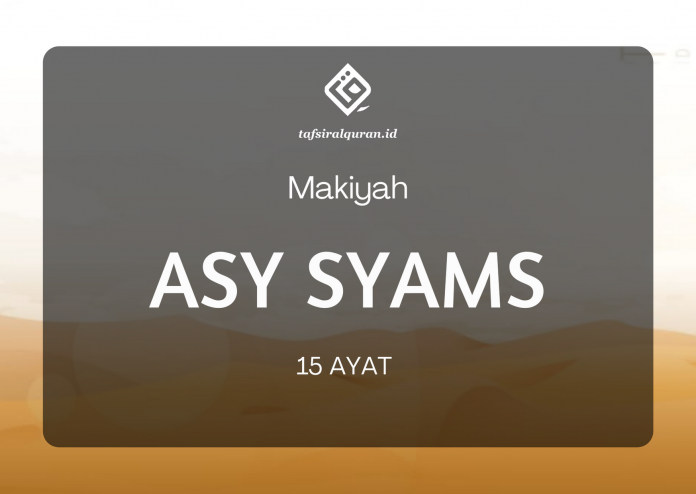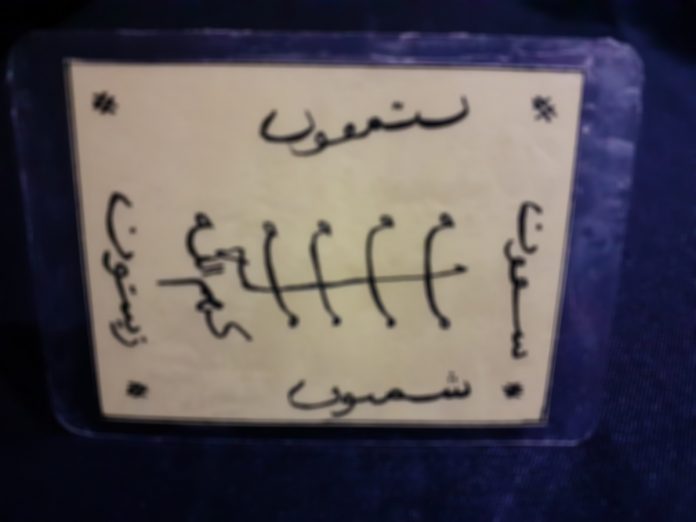Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat nabi Muhammad saw yang paling setia. Ia merupakan tokoh garda terdepan dalam membela kaum muslimin setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Umar dikenal sebagai sahabat yang cerdas, tegas, bijaksana dan visioner dalam menyelesaikan permasalahan umat. Bahkan disebutkan bahwa ada banyak ayat Al-Qur’an yang turun karenanya seperti ayat pengharaman khamar.
Jika ada suatu permasalahan yang dianggap Umar penting untuk diperbincangkan, maka ia akan langsung menyampaikannya kepada sahabat lain dan nabi Muhammad saw. Misalnya, ketika Umar melihat bahwa nabi saw dan istrinya sering dikunjungi tamu, ia lalu berinisiatif menyarankan kepada beliau agar memerintahkan istrinya menggunakan hijab untuk berjaga-jaga, karena tidak semua tamu berniat baik (al-Tafsir al-Munir).
Umar berkata, “Wahai Rasulullah, yang datang kepada Anda ada orang yang baik, ada yang jahat. Sebaiknya para Ummul Mukminin (Ibu orang-orang beriman) disuruh memakai hijab.” Meskipun awalnya saran ini tidak dilakukan nabi saw, namun pada akhirnya saran tersebut direspons oleh Allah swt dengan menurunkan surah al-Ahzab [33] ayat 32-33 yang memerintahkan istri nabi dan wanita muslimah untuk menggunakan hijab.
Baca Juga: Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar
Sedangkan menurut Ibnu Jarir al-Thabari – sebagaimana dikutip Ibnu al-Arabi dalam Ahkam al-Qur-an (jilid 3: 587) – ayat ini adalah larangan terhadap perempuan-perempuan merdeka untuk menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak ataupun perempuan non-muslim. Hijab berfungsi sebagai cover atau pelindung bagi perempuan sekaligus simbol identitas seorang muslimah.
Tidak hanya sampai di situ, Umar bin Khattab juga berperan dalam sebab-sebab pewahyuan ayat penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, ayat teguran terhadap kecemburuan istri nabi saw dan ayat pengharaman khamar. Karena kecakapannya dalam membedakan hal yang benar dan yang batil ini, Umar dijuluki oleh nabi saw dengan gelar al-faruq (The Life of Muhammad).
Kebiasaan Bangsa Arab dan Ayat Pengharaman Khamar
Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau biasa disebut khamar. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi – saking akrabnya mereka dengan khamar – dalam bahasa Arab ada sekitar 100 kosa kata berbeda yang merujuk kepada makna minuman beralkohol tersebut. Selain itu, juga terdapat banyak syair Arab yang berisi tentang kecintaan terhadap khamar (History of The Arabs).
Bisa dikatakan bahwa khamar adalah konsumsi utama bangsa Arab. Mereka menjadikannya sebagai minuman harian yang dianggap bermanfaat dan berfaedah bagi badan. Minum khamar bagi orang-orang Arab itu – kurang lebih – seperti minum kopi bagi orang-orang Aceh di zaman ini. Dalam setiap rumah mereka – hampir selalu – tersedia khamar untuk dinikmati atau disajikan bagi para tamu yang berkunjung.
Ketika Islam datang, kebiasaan bangsa Arab tidak serta-merta hilang. Kita dapat menemukan banyak riwayat pada periode awal Mekah di mana bangsa Arab – termasuk sebagian sahabat – masih menikmati khamar sebagai minuman harian. Hal ini dikarenakan ayat pengharaman khamar belum turun dan tidak ada perintah secara langsung dari nabi Muhammad saw untuk meninggalkannya.
Muhammad Husein Haekal, cendekiawan asal Mesir, menyebutkan dalam Biografi Umar bin Khattab bahwa masyarakat Mekah sangat gemar minum khamar kala itu, dan Umar – sebelum masuk Islam – adalah orang yang sangat kecanduan khamar. Namun kebiasaannya tersebut lambat laun berubah dan hilang tak tersisa sehingga ia sepenuhnya terbebas dari khamar.
Kendati demikian, sebagian kaum muslimin masih gemar meminum khamar. Disebutkan bahwa kebiasaan ini berlangsung hingga periode awal di Madinah. Ketika sebagian kaum muslimin minum khamar, tak jarang terjadi permasalahan atau pertikaian di antara mereka. Singkatnya, kebiasaan meminum khamar kala itu sering menimbulkan kekacauan.
Melihat situasi kaum muslimin sedemikian rupa, tak jarang pula rang-orang Yahudi dan kaum munafik memanfaatkan situasi serta menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara bani Aus dengan bani Khazraj. Sehubungan dengan itu Umar kemudian menanyakan soal minuman keras ini kepada nabi Muhammad saw — ketika itu Al-Qur’an belum menyinggungnya (Biografi Umar bin Khattab).
Nabi Muhammad saw lalu berkata, “Allahumma ya Allah, jelaskanlah soal ini kepada kami.” Setelah itu turunlah surah al-Baqarah [2] ayat 219, “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya….” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 219).
Karena dalam ayat ini khamar belum dilarang, maka kaum Muslimin tetap saja menghabiskan malam dengan meminum khamar. Lama-kelamaan, kegelisahan Umar bin Khattab justru semakin menjadi-jadi karena khawatir akan imbas buruk jangka panjang khamar. Sebagai contoh, sebagian sahabat kerap lalai dalam shalatnya – baik lupa rakaat ataupun salah bacaan – karena mereka beribadah dalam keadaan mabuk.
Umar bin Khattab lantas bertanya lagi kepada nabi Muhammad saw tentang kepastian pelarangan khamar. Beliau bersabda, “Allahumma ya Allah, jelaskanlah tentang khamar itu kepada kami. Minuman ini merusak pikiran dan harta! Kemudian turunlah surah an-Nisa [3] ayat 43: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan…”
Sejak saat itu muazin sering menambahkan seruan, “orang yang mabuk jangan mendekati shalat.” Pada tahap ini, kaum Muslimin sudah mulai mengurangi minum khamar meskipun belum berhenti seutuhnya. Namun, efek buruk khamar rupanya masih sangat terasa. Sebagian kaum muslimin yang tetap meminum khamar di luar shalat kerap bertikai. Bahkan dikisahkan bahwa ada dua suku yang saling tikam akibat pengaruh alkohol (Sejarah Hidup Muhammad).
Baca Juga: Tafsir Ahkam: Khamar itu Haram! Fase Terakhir Pengharaman Khamar
Kegelisahan Umar bin Khattab akhirnya memuncak. Ia lantas bertanya lagi kepada Rasulullah kapankah khamar mutlak diharamkan dan kapan ayat pengharaman khamar akan turun. Beliau berkata, “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar ini dengan tegas, sebab ini telah merusak pikiran dan harta.” Kemudian turunlah surah al-Maidah [5] ayat 90 sebagai ayat pengharaman khamar secara mutlak.
Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, Fi Zhilalil Qur’an, ketika ayat ini turun para sahabat langsung menumpahkan gelas-gelas yang masih berisi khamar tanpa tersisa. Mereka menuju tempat penyimpanan khamar yang terdiri dari gentong-gentong dan seketika itu menghancurkan semuanya. Dikisahkan bahwa kala itu jalanan Madinah berwarna merah akibat tumpahan zat haram tersebut. Wallahu a’lam.