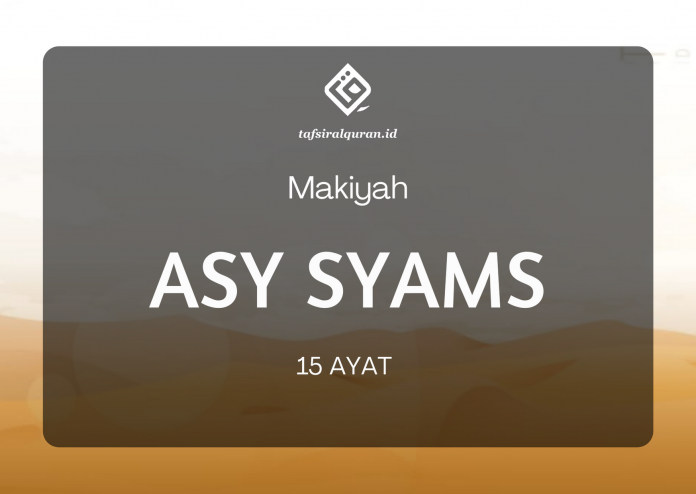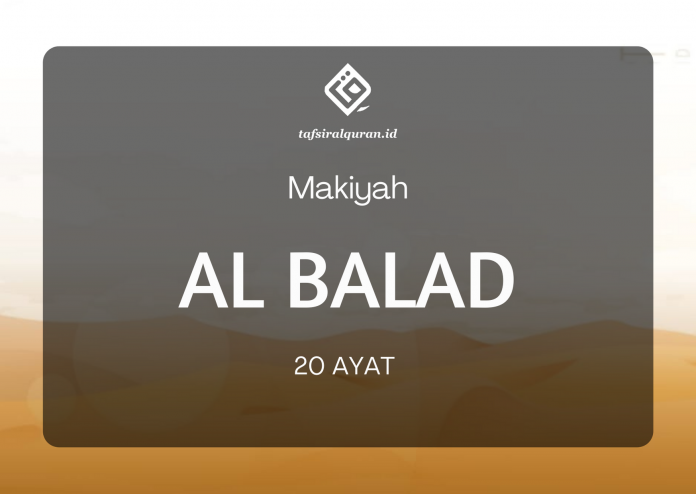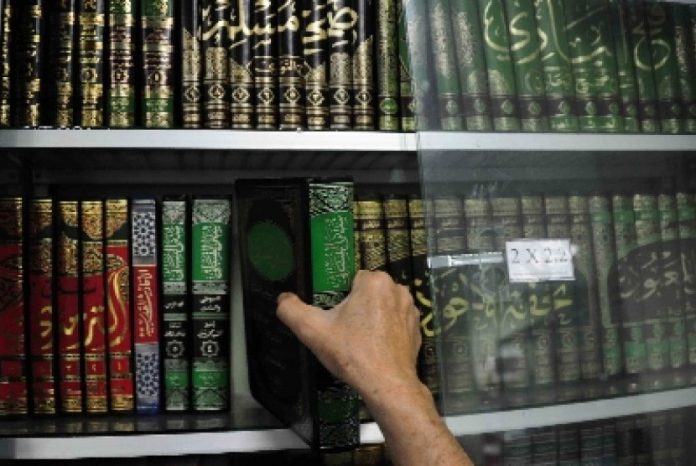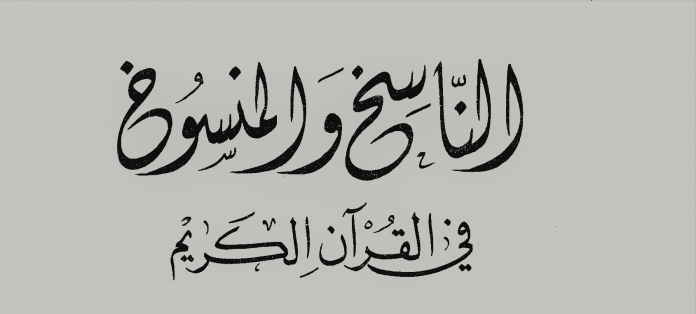Secara kebahasaan, kata “moderasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung dua makna, pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Sedang Moderasi dalam Al-Quran, salah satunya dapat kita ambil petunjuknya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, tepatnya dalam frasa ummatan wasatan.
Berbicara tentang moderasi dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat al-Baqarah [2]: 143 :
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqoroh [2]: 143)
Baca Juga: Menilik Makna Ummatan Wasatha dalam Surat Al-Baqarah Ayat 143 Dari Berbagai penafsiran
Ummatan wasatan, simbol moderasi dalam Al-Quran
Penyelaman tafsir wasatan akan ditemukan kata kuncinya ketika melihat definisi yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata washat mempunyai arti sesuatu yang berada diantara kedua kutub yang saling berlawanan. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kata wasat untuk menyifati sikap orang-orang muslim yang moderat dalam beragama, yaitu golongan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak ceroboh dalam beragama.
Makna ummatan wasatan adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, bisa melihat ke dan dilihat oleh semua pihak dari segala penjuru. Dengan menempatkan Islam di posisi tengah, diharapkan umat Islam tidak seperti umat yang hanyut oleh materialisme, tidak pula mengantarnya membumbung tinggi ke alam ruhani. Posisi tengah adalah memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas.
Menurut al-Qurtubi dalam kitabnya al-Jami’ al-ahkam, Makna al-wast adalah adil. Asal dari kata ini adalah bahwa sesuatu yang paling terpuji adalah yang pertengahan. Sebagaimana ka’bah yang terletak di tengah-tengah bumi, maka demikian pula ‘kami menjadikan kalian umat yang pertengahan’, yakni kami jadikan kalian di bawah para Nabi tapi di atas umat-umat yang lain.
Quraish Shihab memberi penjelasan terkait QS. Al-Baqarah [3]: 143, bahwa ayat ini telah memberi petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat mengantar seseorang berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dari penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak.
Baca Juga: Inilah 3 Syarat Utama Implementasi Islam Wasathiyah Menurut Quraish Shihab
Kenapa moderasi beragama di Indonesia itu penting?
Penguatan moderasi, khususnya moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan. Ini karena fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara agama.
Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama, sampai-sampai yang bukan urusan agama pun dibawa-bawa untuk ‘beragama’, dan ketika sudah menyangkut agama maka itu akan menjadi isu yang sangat sensitif. Selain itu moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat.
Moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat.
Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman.
Kita semua tahu bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami ini, bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrem yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan.
Satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri tanpa melihat konteks dari teks tersebut sehingga memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif. Sementara kutub lainnya terlalu bertumpu pada otak dan nalar sehingga dalam memahami teks selalu mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultra liberal.
Dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban yang baik. Karena itulah moderasi dalam beragama juga harus dinamis dengan terus memposisikan diri di tengah.
Baca Juga: Ayat-Ayat Wasathiyah: Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 143 Menurut Hasbi al-Shiddiqie
Konsep moderasi dalam Al-Quran seperti dalam QS. al-Baqarah [3]: 143 disebut dengan konsep al-wasathiyah. Umat yang moderat (Ummatan wasathan) merupakan prototipe umat yang memiliki dan memegang teguh prinsip prinsip tidak melampaui batas (ghuluww), baik dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, termasuk beribadah. Dalam hal ini Allah berfirman:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
“Katakanlah, hai Ahli kitab janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam beragama … (Q.S. al-Ma’idah [5]: 77).
Ummatan wasathan adalah khaira ummah, umat terbaik yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemunkaran, dan selalu menjadikan hidupnya penuh keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadikan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam