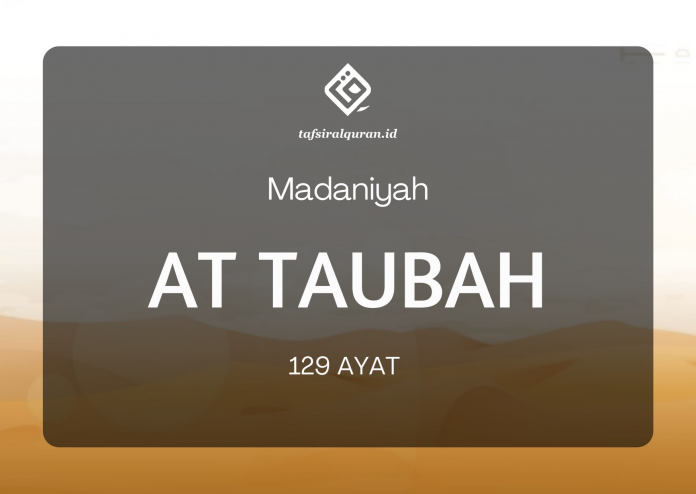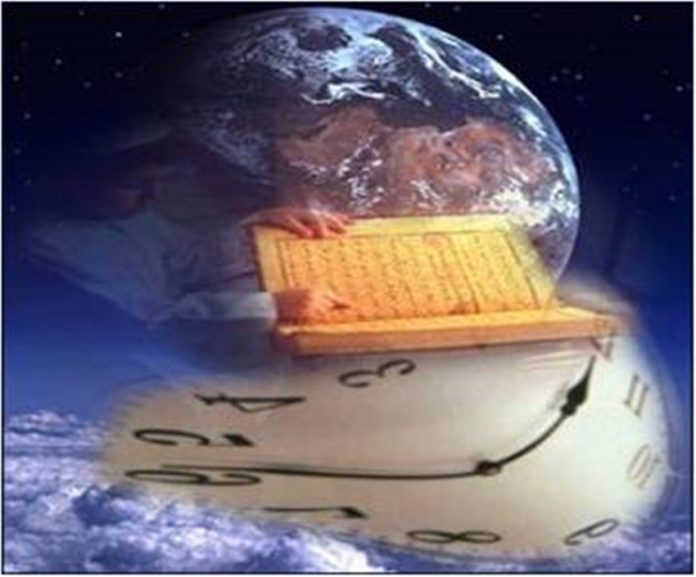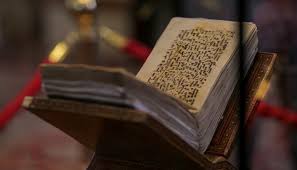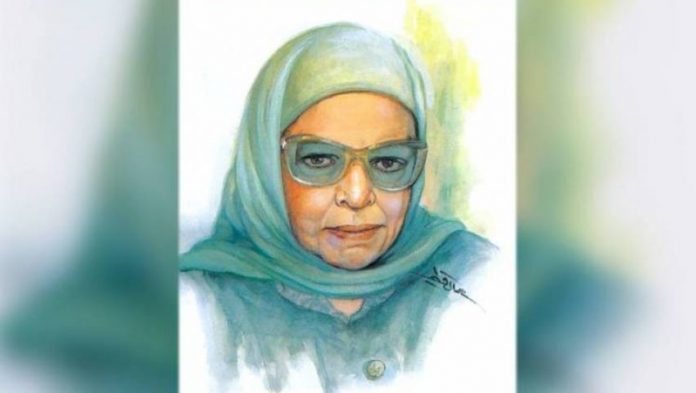Keterangan dalam Tafsir Surah At Taubah Ayat 62-64 masih berbicara perihal sikap buruk orang munafik. Ternyata, mereka menyadari bahwa kedustaan itu dapat memacu turunnya ayat, rasa khawatir pun muncul dalam benak mereka. Mereka takut apabila keburukan mereka selama ini diketahui oleh Rasul dan orang-orang Mukmin.
Baca Sebelumnya : Tafsir Surah At Taubah Ayat 61
Tentu Allah mengetahui hal tersebut, dan nyatanya menurunkan ayat-ayat terkait sikap mereka. Alih-alih berubah menjadi baik, mereka justru semakin terang-terangan dan tidak tahu malu untuk berlaku buruk.
Ayat 62
Sabab Nuzul: Diriwayatkan Ibnu Munzir dari Qatadah tentang sebab nuzul ayat ini, Qatadah berkata, “Kepada kami diberitahukan bahwa seorang lelaki dari kalangan munafik berkata tentang golongan yang tidak turut Perang Tabuk dimana turun ayat khusus mengenai mereka.
Lelaki itu berkata, “Demi Allah bahwa sesungguhnya mereka yang tidak ikut berperang itu adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang mulia. Jika sekiranya benar apa yang dikatakan Muhammad tentulah mereka lebih jahat daripada keledai.”
Ucapan lelaki itu didengar oleh seorang lelaki dari kalangan muslim, lalu ia berkata (sebagai jawaban terhadap orang-orang munafik itu), “Demi Allah, bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah benar dan engkau adalah lebih jelek daripada himar (keledai).
”Orang muslim itu pergi kepada Rasulullah untuk menceritakan kejadian itu maka orang-orang munafik itu didatangkan menghadap Nabi dan Nabi berkata, “Apakah yang mendorong engkau berkata demikian?”
Orang munafik itu mengingkari ucapannya dan melaknati dirinya dengan bersumpah bahwa ia tidak pernah berkata demikian. Orang muslim itu berkata, “Hai Tuhanku benarkanlah orang yang benar dan dustakanlah orang yang dusta,” maka turunlah ayat ini.
Ayat ini menerangkan tentang kebiasaan orang-orang munafik sebagaimana halnya dengan orang-orang yang berbuat suatu kesalahan, seperti: mencuri, dan membunuh.
Mereka selalu merasa dalam kesulitan karena mereka selalu dibayang-bayangi oleh akibat perbuatan mereka yang buruk yang mereka lakukan, dan mereka takut kebohongan mereka diketahui oleh orang-orang muslim. Mereka sering bersumpah sebagai cara untuk menutupi kejahatan dan kebohongan mereka.
Demikian perbuatan orang munafik, mereka bersumpah untuk meyakinkan orang-orang mukmin bahwa apa yang disampaikannya tentang kelakuan buruk mereka baik menentang maupun memburukkan Rasulullah adalah tidak benar.
Hal ini dimaksudkan agar orang mukmin mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih dari segala tuduhan.
Mereka sering bersumpah dengan maksud menyenangkan Rasul dan mendapat kepercayaan dari orang-orang mukmin sehingga mereka mendapat perlindungan dari orang-orang mukmin; semestinya mereka berusaha mendapat keridaan Tuhan dan Rasul-Nya dengan iman yang sungguh-sungguh yang jauh dari kemunafikan dan keraguan jika benar-benar mereka ingin menjadi orang mukmin.
Meskipun orang-orang mukmin dapat diyakinkan dengan jalan bersumpah, dan kebohongan mereka tidak terungkap, namun Allah swt, tetap mengetahui segala sesuatu yang mereka perbuat dan sesuatu yang masih tersimpan di hati mereka. Ketika kemaslahatan menghendaki, Allah menurunkan kepada Rasul wahyu yang menjelaskan tentang semua yang mereka lakukan.
Baca Juga : Tafsir Surat Al-Mulk Ayat 12-14: Allah Maha Mengetahui Sesuatu, Sekalipun Isi Hati Manusia
Ayat 63
Semestinya orang munafik segera sadar karena tidak mungkin mereka tidak mengetahui bahwa membuat-buat tuduhan terhadap Rasul seperti tuduhan berlaku curang dalam membagi zakat atau menuduh Rasul dengan sifat senang mendengar laporan tanpa meneliti kebenarannya adalah termasuk perbuatan menentang Allah dan Rasul-Nya.
Orang yang demikian halnya akan mendapat ganjaran api neraka, kekal di dalamnya. Azab seperti ini adalah suatu kehinaan yang besar yang tentunya harus ditakuti dan dijauhi.
Ayat 64
Ayat ini menggambarkan tentang tingkah laku orang-orang munafik yang pernah diungkapkan dalam Perang Tabuk. Mereka merasa khawatir seandainya diturunkan ayat atau surah yang menerangkan segala sesuatu yang mereka lakukan.
Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada mereka agar meneruskan ejekan-ejekan yang mereka lakukan. Orang-orang munafik adalah manusia yang tidak mempunyai pendirian, mereka berada di antara iman dan kufur, mereka tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul, mereka berada di antara cemas dan harap.
Andaikata mereka mengingkari Rasul secara tegas tentulah mereka tidak akan cemas. Demikian pula jika mereka beriman kepada Rasul secara tegas.
Karena posisi mereka di antara iman dan kufur, selalu mencela, mengejek Nabi dan orang-orang mukmin, timbullah kekhawatiran dan kecemasan mereka kalau-kalau Allah menurunkan lagi ayat-ayat yang mengungkap keaiban mereka dan menerangkan segala sesuatu yang ada pada mereka meskipun mereka menyimpannya dalam hati mereka.
(Tafsir Kemenag)
Baca Setelahnya : Tafsir Surah At Taubah 65-67