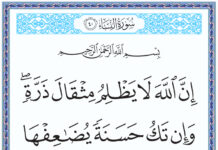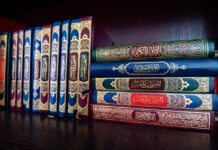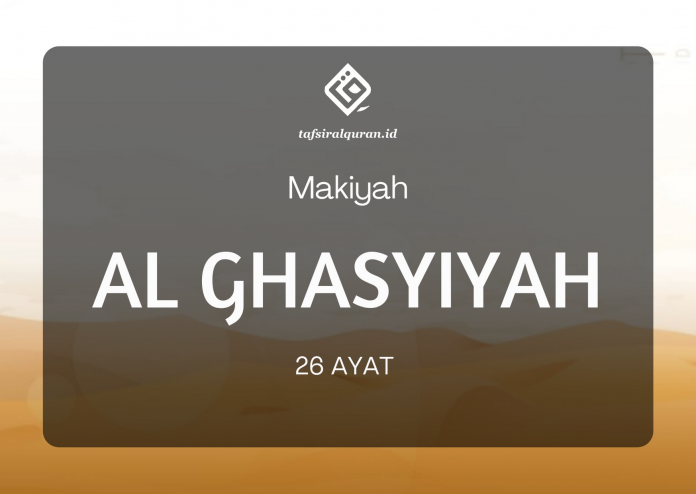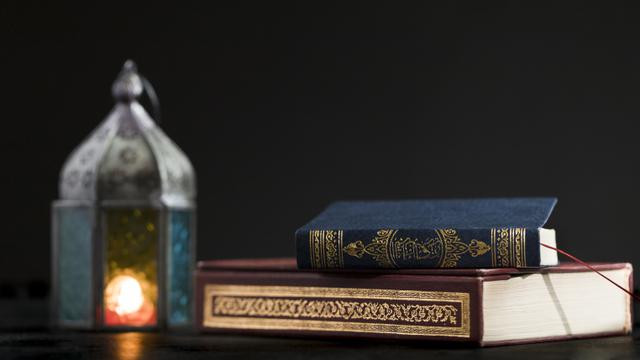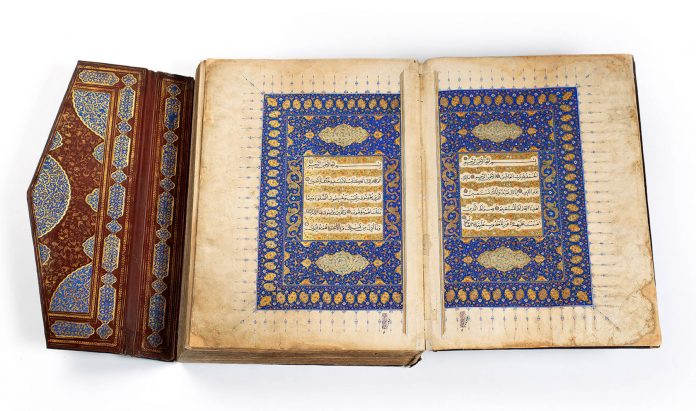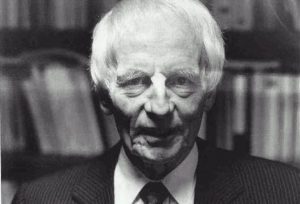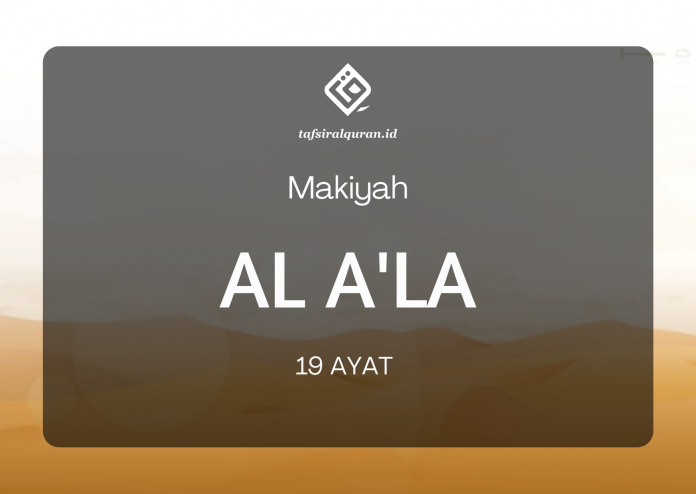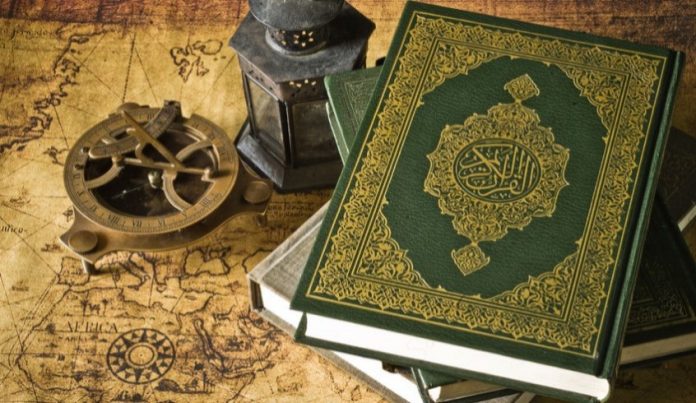Tafsir Surah Al Ghasyiyah Ayat 17-26 mula-mula berbicara mengenai segala nikmat yang ada di dunia agar manusia dapat memanfaatkannya. Dengan itu manusia menjadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan penting sehingga manusia lebih bijak dalam pilihannya.
Baca sebelumnya: Tafsir Surah Al Ghasyiyah Ayat 1-16
Setelah itu, Tafsir Surah Al Ghasyiyah Ayat 17-26 ini berbicara mengenai tugas kenabian Nabi Muhammad Saw, yaitu menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah tegaskan pula bahwa Nabi Muhammad hanya bertugas menyampaikan, bukan menjadikannya beriman. Karena sejatinya iman hanyalah dari Allah Swt. Manusia hanya berusaha sedangkan hasil Allah yang kuasa.
Ayat 17-20
Dalam ayat-ayat ini, Allah mempertanyakan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta, yang ada di depan mata mereka dan dipergunakan setiap waktu, diciptakan. Bagaimana pula langit yang berada di tempat yang tinggi tanpa tiang. Bagaimana gunung-gunung dipancangkan dengan kukuh, tidak bergoyang dan dijadikan petunjuk bagi orang yang dalam perjalanan.
Di atasnya terdapat danau dan mata air yang dapat dipergunakan untuk keperluan manusia, mengairi tumbuh-tumbuhan, dan memberi minum binatang ternak. Bagaimana pula bumi dihamparkan sebagai tempat tinggal bagi manusia.
Apabila mereka telah memperhatikan semua itu dengan seksama, tentu mereka akan mengakui bahwa penciptanya dapat membangkitkan manusia kembali pada hari Kiamat.
Ayat 21
Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agama-Nya kepada umat manusia, karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan.
Ayat 22-24
Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak berkuasa menjadikan seseorang beriman. Akan tetapi, Allah-lah yang berkuasa menjadikan manusia beriman. Sementara itu, barang siapa yang berpaling dengan mengingkari kebenaran petunjuk Nabi-Nya, niscaya Allah menghukumnya.
Allah berfirman:
وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ٩٩
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yµnus/10: 99)
Dan Allah berfirman:
نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍۗ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ࣖ ٤٥
Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur’an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman-Ku. (Qaf/50: 45)
Baca juga: Meneladani Rasa Cinta Tanah Air dari Nabi Muhammad SAW. dan Nabi Ibrahim AS.
Berkaitan dengan hal itu, para juru dakwah cukup menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an dan hadis Nabi sambil mengajak setiap manusia untuk beriman dan beramal saleh, serta masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan (kaffah).
Penampilan dan metode dakwah perlu dengan cara yang baik dan tidak boleh bersikap memaksa, sebagaimana firman Allah:
لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqarah/2: 256)
Dan Allah berfirman:
اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ١٢٥
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)
Ayat 25-26
Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari daripada-Nya.
Dialah yang akan menghisab mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia dan kemudian menjatuhkan hukuman-Nya. Ayat-ayat ini adalah penghibur hati bagi Nabi Muhammad dan sebagai obat bagi kesedihan dan kepedihan hatinya atas keingkaran orang-orang kafir itu.
Baca setelahnya: Tafsir Surah Al Fajr Ayat 1-8
(Tafsir Kemenag)