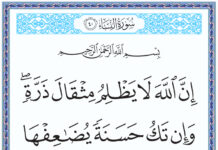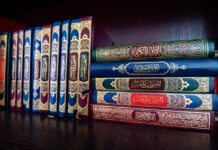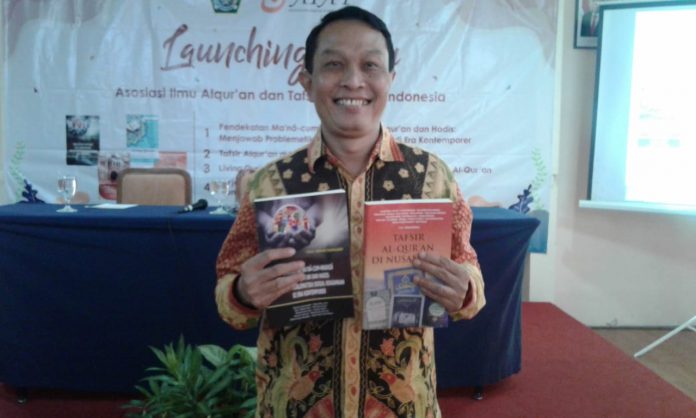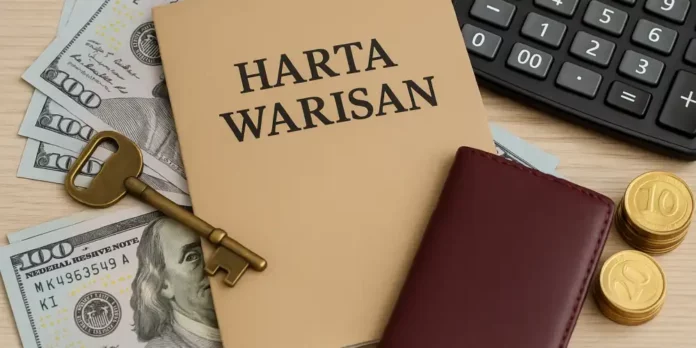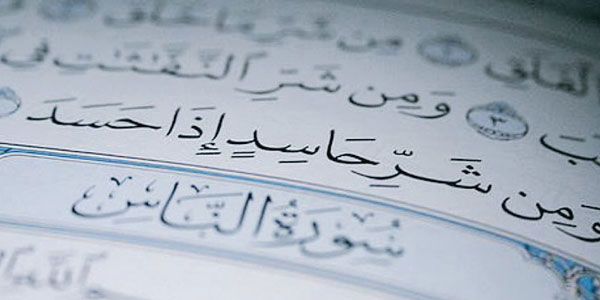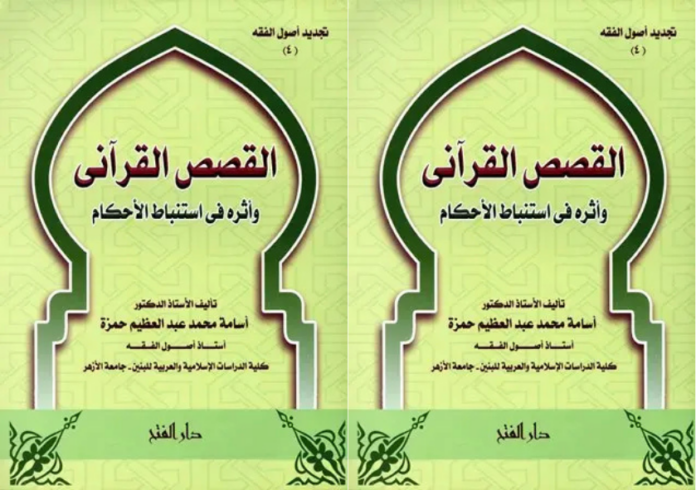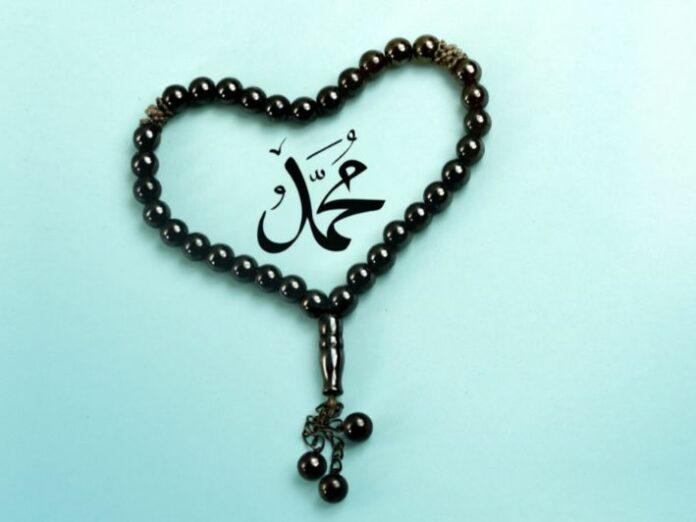Pada 2022 lalu, Ahmad Muttaqin dalam artikelnya, From Contextual to Actual Approach: Towards a Paradigm Shift in Interpreting the Qur’an, memasukkan lima figur kontekstualis terkait pergeseran paradigma pendekatan penafsiran Al-Qur’an, salah satunya Sahiron Syamsuddin. Sahiron, yang menginjak usia 55 tahun pada 11 Agustus kemarin, menjadi satu dari sekian cendikiawan yang dipertimbangkan dalam diskursus studi Al-Qur’an di Indonesia. Ia dikenal dengan pendekatannya yang diberi nama Ma’na-Cum-Maghza.
Pendekatan ini, diasumsikan mampu untuk menggali dan merekonstruksi makna dan pesan utama historis teks Al-Qur’an, yaitu makna (ma’na) dan signifikansi (maghza), untuk kemudian dikembangkan signifikansi teks itu kepada konteks kekinian dan kesinian, persis seperti yang ia sampaikan dalam artikelnya, Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza, dalam buku antologi Pendekatan Makna Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer (2020).
Pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron ini, tentu tidak luput dari kritik dari beberapa peneliti lainnya sebagai respons yang biasa terjadi dalam tradisi percaturan pemikiran. Nurmahni dan Irsyadunnas dalam artikelnya, meski hanya sentilan sekilas, memberi sebuah pernyataan kritis terhadap pendekatan Sahiron yang kemudian memunculkan counter-counter dari peneliti lain setelahnya. Mari saya kutipkan kritik itu, “Di samping itu ada artikel yang ditulis oleh Asep Setiawan yang berjudul “Studi Kritis atas Teori Ma’na-cum-Maghza dalam Penafsiran al-Qur’an” yang fokus pada kajian kritis terhadap teori hermeneutika Ma’na-cum-Maghza dengan menilai bahwa teori tersebut belum dapat memberikan sumbangsih secara signifikan terhadap perkembangan metodologi tafsir, sebab hanya melakukan elaborasi dari berbagai teori.” (Nurmahni, Irsyadunnas, 2020)
Meskipun pernyataan di atas disandarkan terhadap penelitian Asep Setiawan, namun Umi menyebut pernyataan dari Nurmani dan sejawatnya itu tidak berdasar dan perlu dikaji ulang. Sebab, menurutnya, kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama yang ditangani oleh Sahiron menjadi satu bukti kontribusi itu (Umi Wasilatul Furdausiyah, 2021). Lalu bagaimana sebenarnya tarik ulur pendekatan ini beserta kritik-kritik terhadapnya?
Beberapa Kritik
Kritik yang cukup komprehensif pada mula-mula metode ini ditawarkan, dilakukan oleh Asep Setiawan dalam artikelnya, Hermeneutika Al-Qur’an “Mazhab Yogya”: Telaah atas Teori Ma’na-Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Qur’an (2016). Asep mengawali kritiknya pada klasifikasi Sahiron terhadap tipologi penafsiran yang simplistik. Menurutnya, klasifikasi tersebut terlalu general. Sebab, meskipun tampak rasional dan objektif, tetapi secara konsep tipologi Sahiron terkesan mengikuti kacamata orientalis yang dikotomis dan parsial. Hal itu, dibuktikan dengan dimasukkannya beberapa ulama yang dikategorikan sebagai aliran quasi-objektif tradisionalis dengan anggapan bahwa mereka tidak memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syari’ah dan literal murni tidak berdasar dan kering data.
Apa yang dituduhkan Asep memang diungkapkan oleh Sahiron. Sahiron menyebut kategori pertama dalam tiga tipologinya itu diisi oleh kelompok konservatif yang tidak memperatikan tujuan hukum secara prinsipil, melainkan hanya menunjukkan rasionalitas hukum itu sendiri dan keharusan aplikasinya sepanjang masa. Asep menganggap klaim itu keliru, sebab maqashid syariah bukanlah hal baru dan sudah dibahas oleh ulama-ulama klasik dimulai dari Imam Tirmizi.
Baca juga: Mengenal Ma’na Cum Maghza sebagai Pendekatan Tafsir Ala Sahiron Syamsuddin
Alasan yang dijadikan dasar counter Asep ini, bagi saya, kurang menjawab kritikannya sendiri secara substansial. Sebenarnya, Sahiron tidak ingin mengatakan bahwa mufasir klasik melupakan maqashid, tapi lebih kepada pengabaian prinsip. Namun, kata pengabaian di sini juga menjadi problem, seperti yang dirasakan Asep. Ikhawanul Muslimin yang dijadikan satu contoh dari kelompok itu, juga tidak dijelaskan di mana letak kekeliruannya oleh Asep. Hanya saja, untuk mengatakan bahwa tipologi yang digagas Sahiron terlalu menggeneralisasi, saya setuju. Dan untuk mengklaim bahwa mufasir klasik, mengabaikan maqashid, bisa jadi konteks hukumnya masih relevan kala itu.
Ikhwanul Muslimin sebagai tamsil penafsiran quasi-objektivis konservatif menjadi penekanan tersendiri oleh Sahiron. Ini bisa dilihat dari salah satu alasan yang diajukannya terkait kelemahan kelompok yang dimaksud. Ia menyebut, “…mereka yang memiliki pandangan ini tidak tertarik untuk melakukan pembaharuan pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan modern dengan cara mempertimbangkan adanya perbedaan yang sangat menyolok antara situasi pada saat diturunkannya wahyu dan situasi yang ada pada masa kini.” Atas dasar inilah, kemudian ia lebih memilih pandangan kelompok quasi-objektivis progresif yang memberi perhatian yang seimbang terhadap makna asal (ma’na) dan pesan utama (maghza) di baliknya.
Signifikansi dan kontekstualisasi
Terkait kelompok yang dipandang Sahiron dapat diterima untuk saat ini, ia menunjukkan satu kelemahan, yaitu pemahaman akan signifikansi. Maka kemudian ia menjelaskan apa saja bentuk signifikasnsi itu: Pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis sejak masa Nabi hingga penafsirannya pada periode tertentu. Siginifikansi ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis; Kedua, signifikansi ideal yang berarti akumulasi ideal pemahaman terhadap signifikansi ayat.
Adapun metode dari pendekatan Ma’na-Cum-Maghza itu sendiri, setelah mengetahui hakikat signifikansi dan macam-macamnya, terdapat tiga hal penting yang harus dijalankan seorang penafsir: Pertama, mencari makna historis (al-ma’na al-tarikhi); Kedua, mencari signifikansi fenomenal historis (al-maghza al-tarikhi); dan Terakhir, mencari signifikansi fenomenal dinamis (al-maghza al-mutaharrik) konteks ketika teks Al-Qur’an ditafsirkan.
Baca juga: Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia
Untuk menelusuri dua tahap pertama, Sahiron memberikan langkah-langkah berikut: a) analisa bahasa; b) intratekstualitas (membandingkan dengan ayat lain); c) analisa intertekstualitas (membandingkan dengan teks lain); d) konteks historis wahyu; dan e) analisa tujuan (maqshad) ayat. Sedang untuk langkah-langkah tahap terakhir berikut: a) kategorisasi ayat; b) pengembangan definitive; c) menangkap makna simbolik ayat; dan d) perspektif yang lebih luas.
Semua langkah-langkah di atas dilakukan tiada lain hanya untuk mengontekstualisasikan ayat yang ditafsirkan. Penafsir kontemporer, yang notabene terpaut jauh dari waktu Al-Qur’an diturunkan, meniscayakan penangkapan pesan moral dari kandungan teks agar sesuai dengan konteksnya di masa kini. Sebagaimana pandangan tokoh yang juga menjadi inspirasi pemikiran Sahiron, J.E. Gracia, bahwa teks menjadi entitas historis yang hadir pada kondisi tertentu dan berada dalam ruang tertentu (Umi Wasilatul Firdausiyah, 2021).