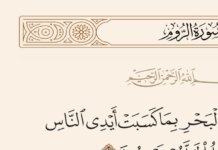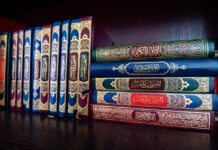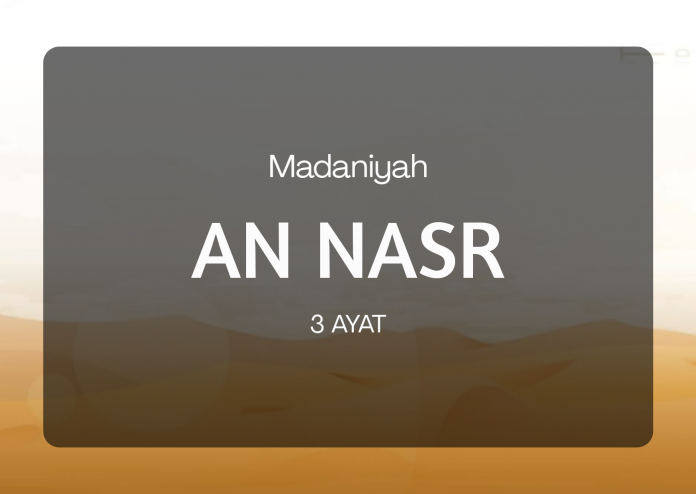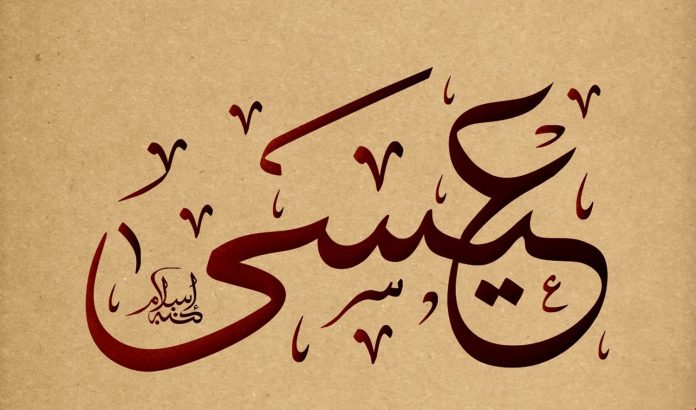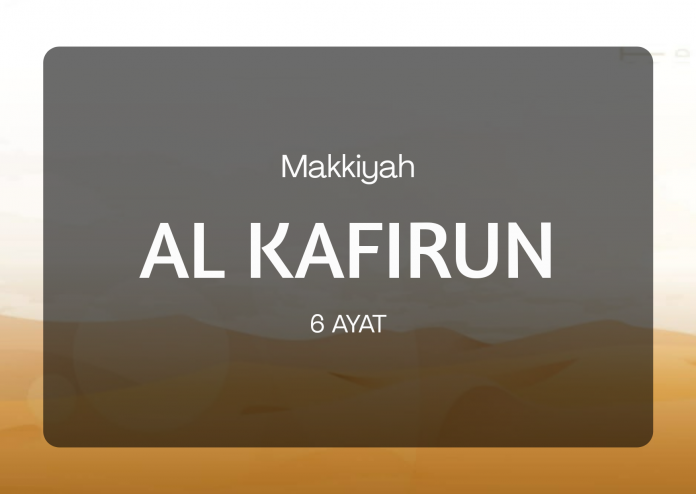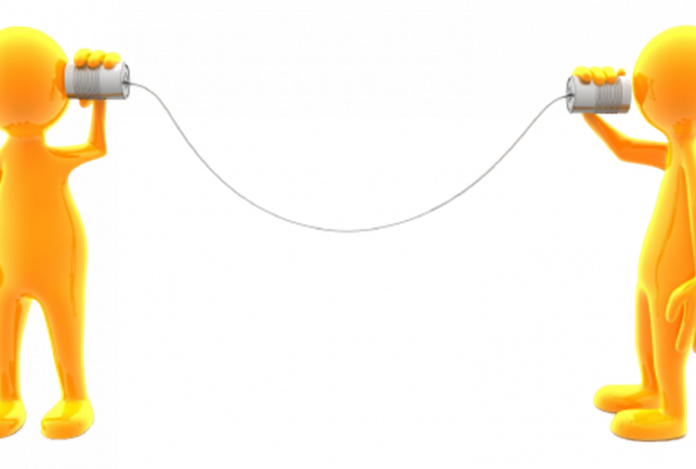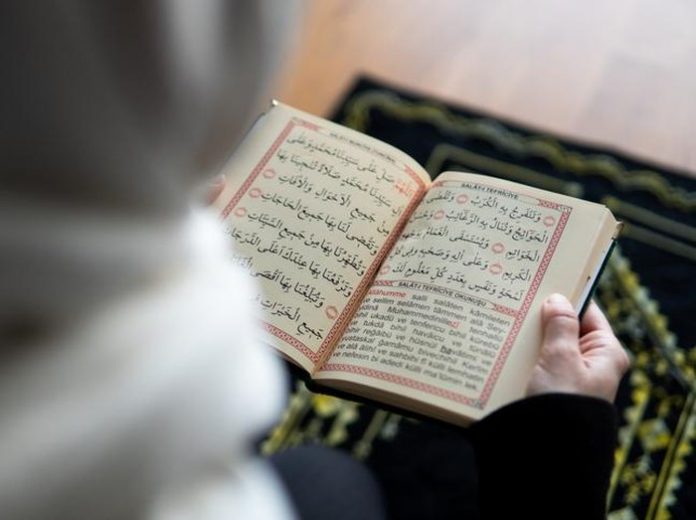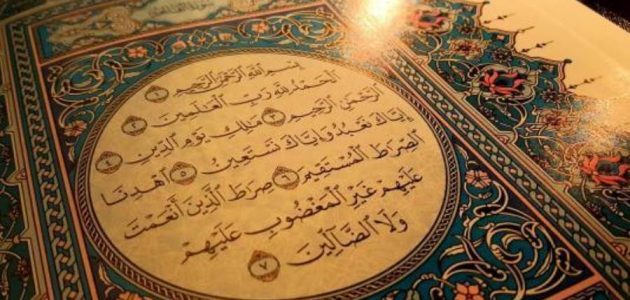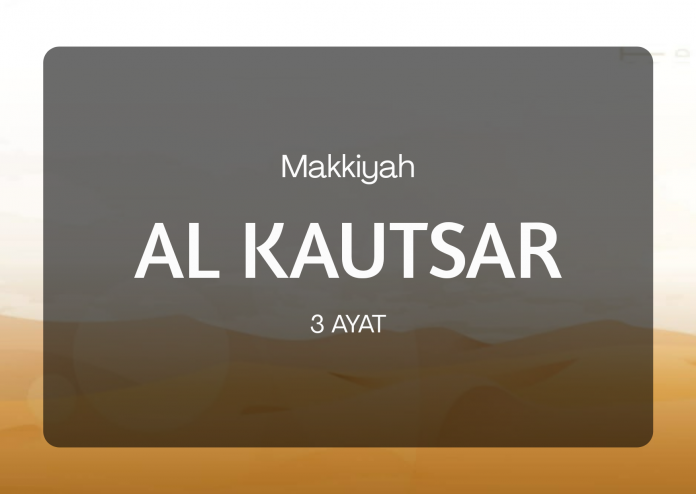Pembahasan qiraat Al-Quran selalu menarik untuk dikaji. Ilmu qiraat sendiri terklasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu qiraat sab’ah, qiraat ‘asyrah, dan qiraat arba’ah asyrah. Di antara ketiganya yang paling populer adalah qiraat sab’ah. Sebab qiraat sab’ah memiliki cara bacaan masing-masing sesuai tujuh imam masyhur. Salah satu ulama yang menaruh perhatian dan kontribusi besar dalam bidang ilmu qiraat adalah Ibnu Mujahid (245 H-324 H).
Biografi Ibnu Mujahid
Ibnu Mujahid bernama lengkap, Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid al-Tamimi al-Baghdadi. Ibn al-Jazary al-Dimasyqi al-Syafi’i dalam Ghayatun Nihayah fi Thabaqat al-Qurra menerangkan bahwa Ibnu Mujahid lahir di Suq al-‘Atthasy di Kota Bagdad, tahun 245 H dan wafat pada hari Rabu 11 Sya’ban 324 H. Ia mulai menghafalkan Al-Quran serta belajar ilmu agama dan bahasa di usia muda.
Ia juga banyak menimba ilmu kepada ulama nahwu di Kufah di antaranya adalah Abdurrahman bin Abdus, murid daripada Abi Umar al-Duri yang sanad qiraahnya muttashil kepada Imam Nafi’. Di antara guru qiraatnya, Aburrahman bin Abdus inilah yang terkenal akan ketsiqahan dan kedhabitannya. Maka tak heran di dalam kitabnya Al-Sab’ah terdapat beragam istilah ilmu nahwu mazhab Kuffah.
Di samping itu, ia menekuni bidang ke-qiraat-an Al-Quran, tafsir, i’rab, riwayah, dan thuruq huruf-hurufnya. Horizon qiraat beserta riwayat dan thuruq-nya bak full record (rekaman lengkap) atau dhabit tamm. Tak puas nyantri kepada Abdurrahman bin Abdus, ia berkelana untuk belajar qiraat kepada Hamzah, Kisa’i, Nafi’ dan Abu ‘Amr dengan sanad-sanadnya dari Ibnu Abdus serta qiraat Ibnu Katsir dengan sanadnya dari Qunbul.
Kehausannya akan ilmu qiraatnya terus memandunya hingga ke beberapa kota, Madinah, Kuffah, Basrah, dan Damaskus sebagaimana penjelasan Ibnu Mujahid sendiri dalam kitabnya, Kitab al-Sab’ah fi al-Qiraat. Ia belajar kepada guru-guru qiraat yang lain seperti Isma’il bin Ishaq, Ibn Syazzan al-Razi, Al-Asyanu bin Ali bin Malik, Qunbul al-Makki, Ishaq bin Ahmad al-Khuzai, Muhammad al-Asfahani, Muhammad bin Yahya al-Kisa’i, al-Marwazi, dan sebagainya.
Baca juga: Qiraat Al-Quran (1): Sejarah dan Perkembangannya di Era Islam Awal
Seiring dengan kesibukannya mendalami ilmu qiraat dengan cara talaqqi kepada beberapa ulama qiraat, tercatat banyak sekali perbedaan bacaan di antara guru-gurunya. Oleh karena itu, kemudian Ibnu Mujahid memutuskan menghafalkan ragam bacaan tersebut. Misalnya, dari Abdurrahan bin Abdus, salah seorang gurunya, ia menerima sanad qiraat darinya menurut riwayat Imam Nafi’ dan disetorkan dengan metode musyafahah lebih dari 20 kali khatam.
Tidak hanya qiraat dari riwayat Imam Nafi’ saja, beliau juga khatam beberapa kali qiraat menurut riwayat Hamzah, al-Kisa’i, dan Abu ‘Amr. Dikisahkan dalam Kitab al-Sab’’ah fi al-Qiraat bahwasannya Ibnu Mujahid mengambil sanad qiraat riwayat Ibnu Katsir kepada Imam Qunbul yang merupakan salah seorang imam qiraat terkemuka di Makkah. Dari rihlah ilmiah yang beliau tempuh guna mendapatkan sanad qiraat, Ibnu Mujahid telah berhasil meriwayatkan berbagai macam qiraat tidak kurang dari 40 orang guru.
Kepakarannya dalam bidang qiraat membuatnya dikenal sebagai ulama yang ‘alim di bidang qiraat. Reputasinya di bidang qiraat telah mengantarkannya kepada pemahaman yang mendalam tentang qiraat sehingga banyak orang yang “nyantri” kepadanya. Bahkan, ia tercatat memiliki murid yang banyak di bidang qiraat. Dalam setiap halaqah, misalnya, setidaknya tidak kurang terdapat 84 asisten sehingga tak terhitung lagi jumlah murid yang ikut halaqah. Kegiatan halaqah ini berlangsung selama 40 tahun sampai beliau wafat.
Pada tahun 286 H, Ibnu Mujahid diangkat sebagai imam qiraat di Baghdad dan menduduki jabatan tertinggi di birokrat. Namun demikian, ia tidak terlena dengan kedudukannya. Beliau termasuk ulama yang zahid dan sama sekali tidak terpaku pada kehidupan hedonisme. Baginya, semua hanyalah titipan Allah swt semata.
Dalam konteks ini, Tsa’lab menuturkan, “Tiada orang yang pada masa kami yang lebih mengetahui kitabullah selain daripada Ibnu Mujahid”. Sedangkan Abu Amr al-Dani, imam qiraat di Andalusia, Spanyol yang hidup setelah masa Ibnu Mujahid mengatakan, “Ibnu Mujahid melebihi semua ahli pikir pada masanya karena keluasan ilmunya, kecakapan pemahamannya, ketekunan ibadahnya, kewira’iannya serta kebenaran lahjah-nya.”
Baca juga: Qiraat Al-Quran (2) : Sejarah dan Perkembangan Qiraat di Era Sahabat
Kontribusi di Bidang Qiraat
Pada permulaan tahun 300 H di Baghdad, Ibnu Mujahid menyusun kitab qiraat yang dinamakan Kitab al-Sab’ah fi al-Qiraat. Beliau mengumpulkan tujuh sistem qiraat dari tujuh Imam qurra’ yang berasal dari Makkah, Madinah, Syam, Kuffah, dan Bashrah. Semuanya dikenal sebagai qiraat yang tsiqah, dan dhabit di bidangnya. Tentunya Ibnu Mujahid bukanlah orang pertama yang melakukan kodifikasi qiraat. Meskipun demikian harus diakui bahwa kontribusinya di bidang qiraat telah dapat kita rasakan hingga saat ini. Istilah qiraat sab’ah, asyrah, bahkan arba’a asyrah adalah buktinya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Mujahid telah melakukan “bid’ah” keragaman mutu bacaan Alquran. Ia berjuang berjuang untuk melakukan penilaian terhadap qiraat-qiraat yang ada dengan tiga syarat penerimaan qiraat; sanad, rasm, dan bahasa Arab. Penilaian juga dilakukan terhadap kredibilitas dan kapabilitas para Imam qira’at.
Perjuangan Ibn Mujāhid tidak sia-sia, beliau berhasil menginventarisir tujuh Imam qira’at dari lima kota dan menghasilkan konsep qiraat sab’ah (tujuh) yang valid dan diakui oleh jumhur ulama serta disepakati qiraat sab’ah ini sebagai qiraat yang mutawatir. Wallahu A’lam.


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)