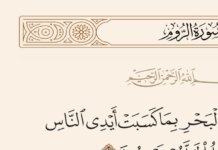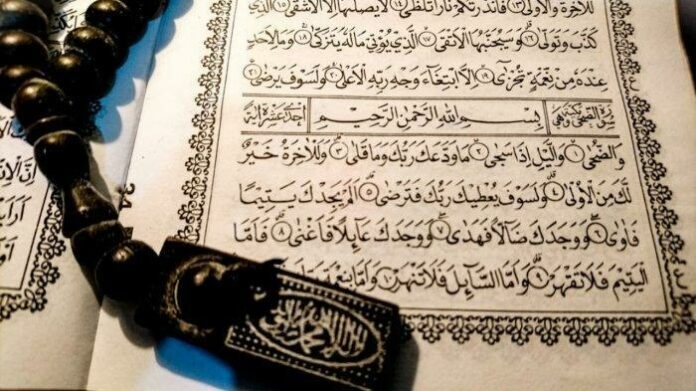Alquran memberikan petunjuk dan panduan bagi seseorang dalam menyikapi keburukan atau kejahatan orang lain. Solusi yang ditawarkan Alquran bersifat kondisional dan bijak, tidak serta merta mewajibkan mereka untuk memaafkan semata, justru kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah kepiawaian membaca situasi. Karena terkadang, dalam beberapa keadaan bisa jadi sekadar memaafkan saja bukan solusi terbaik.
Cukup banyak ayat Alquran yang subtansinya sama, yakni tidak dilarangnya membalas keburukan orang lain sesuai kadarnya, tetapi closing-nya selalu berujung pada rekomendasi untuk memaafkan. Di antaranya adalah firman Allah Swt. berikut.
وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ . وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ
“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. asy-Syura [42]: 39-40).
Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas dengan ulasan yang ringkas dan komprehensif. Beliau mengatakan,
فشرع العدل وهو القصاص ، وندب إلى الفضل وهو العفو
“Maka disyariatkan untuk berbuat adil, yaitu qishash. Dan disunahkan berbuat yang fadhl (utama), yaitu memaafkan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 7/212).
Prinsip ‘adl dan fadhl yang dikemukakan Ibnu Katsir di atas mewakili pilihan sikap yang bisa diambil seorang muslim.
Prinsip ‘Adl
Berdasarkan prinsip ‘adl, Ibnu Katsir mengatakan bahwa pilihan sikap yang disyariatkan adalah qishash, yakni membalas dengan yang setimpal. Tentunya persyaratan membalas ini adalah benar-benar dengan kadar yang sesuai dan tidak melampaui batas. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, disebutkan tentang bolehnya membalas cacian selama tidak melampaui batas. Adapun dosanya ditanggung oleh ia yang memulai cacian (H.R. Muslim no. 2587). Berdasarkan hadis tersebut, Islam membolehkan umatnya untuk membela apa yang menjadi haknya dengan catatan takaran yang sesuai atau membalas secukupnya.
Baca juga: Hukum Mendoakan Jelek Orang yang Zalim
Dalam surah asy-Syura di atas, kata maaf digandengkan dengan islah. Menurut ulama, hal itu sebagai isyarat bahwa permaafan terkadang tidak memberi dampak perbaikan. Dengan kata lain, memaafkan saja terkadang menjadi tidak utama ketika kondisi mengharuskan seseorang untuk membalas demi terjadinya perbaikan.
Al-Absyihi memberikan beberapa catatan, bahwa kebolehan membalas keburukan orang lain bukan berarti menjadikan sifat suka membalas sebagai tabiat. Dan membalas ini pun tidak berlaku pada perbuatan yang terdapat hukuman had-nya (Al-Mustshraf, 197). Misalnya pencurian dan pembunuhan, yang hendaknya diserahkan kepada ulil amri atau pihak berwenang terkait untuk mengeksekusinya.
Prinsip Fadhl
Berdasarkan prinsip fadhl, Ibnu Katsir menyebut sikap yang disunahkan adalah memaafkan. Dengan kata lain, memaafkan tidak wajib, tetapi utama. Rasulullah saw. bersabda; “Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab; ‘tentu’. Rasul pun bersabda; ‘Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu.” (H.R. Thabrani).
Baca juga: Tidak Sama yang Buruk dengan yang Baik, Jangan Terjebak Keburukan yang Melenakan!
Memaafkan tidaklah mudah. Quraish Shihab mengatakan, al-afwu berarti menghapus. Tidak disebut memaafkan apabila masih tersisa luka dan dendam di hati. Itu hanya sampai pada tahap menahan amarah (Fathoni, 2022).
Saking beratnya memaafkan, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim melarang bertengkar dan mendiamkan seseorang lebih dari tiga hari. Yang menjadi penekanan di sini, bukanlah tenggang waktu kebolehannya. Tetapi syariat memahami psikis manusia yang tidak mudah begitu saja memaafkan. Bahkan lanjutan hadis itu adalah bahwa yang terbaik adalah yang memulai dengan memberi salam (menyapa). Bahwa memaafkan dan berlapang dada, sekalipun hukumnya sunah, tetapi merupakan sikap afdhal (paling utama) yang direkomendsikan syariat.
Sebuah Pertimbangan
Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan seorang muslim sebelum menentukan sikap. Pertama, terkait motif kejahatan. Apabila motifnya bersifat duniawi, sebaiknya diupayakan untuk memaafkan. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf a.s. Ketika beliau tengah di puncak karir, beliau sebenarnya memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Akan tetapi, beliau justru berlapang dada memaafkan sembari berucap,
لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
“Tak ada celaan bagi kalian di hari ini, semoga Allah mengampuni kalian.” (Q.S. Yusuf: 92).
Pilihan sikap Nabi Yusuf di atas tidak hanya memaafkan, tapi juga membalas dengan kebaikan berupa dimohonkan ampunan. Motif kejahatan saudaranya bersifat duniawi, yakni iri dengki, karena mereka termasuk orang yang beriman. Itulah mengapa kisah Nabi Yusuf tidak diulang dalam Alquran, karena permasalahannya lingkup duniawi dan bukan agama seperti pergulatan hak dan batil yang dialami Nabi Musa.
Hikmahnya, jika ada yang berbuat kejahatan dengan motif duniawi, sebaiknya dimaafkan. Membalas dengan kebaikan juga dianjurkan Allah dalam surah Fushilat ayat 34, dengan harapan kebaikan dapat meluluhkan hati.
Baca juga: Beberapa Hal tentang Ghibah yang Dibolehkan
Kedua, terkait memaafkan yang sulit dan dilematis. Pahala memaafkan sangat bisa diperhitungkan untuk kemaslahatan seseorang di dunia dan akhirat. Bahwa memaafkan adalah sedekah. “Tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain, kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya (tidak menuntut diyat), kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan” (H.R. Ahmad no. 22701).
Dan bahwa memaafkan adalah penebus dosa. Allah ﷻ berfirman,
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ
“Maafkan dan ampuni (lapangkan dada), apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah?” (Q.S. An-Nur: 22).
Namun tetap, pada akhirnya agama tidak memaksa, apalagi mewajibkan untuk memaafkan. Hanya saja, memilih tidak memaafkan berarti telah melewatkan banyak keutamaan sebagaimana telah dipaparkan di atas.
Baca juga: Keteladanan Nabi Ibrahim Menyikapi Sensitivitas Orang Tua
Ketiga, terkait karakteristik orang yang telah berbuat zalim. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a., Rasulullah saw. bersabda:
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ
“Maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik” (H.R. Ibnu Hibban no. 94).
Menurut Imam Asy Syaukani, haiah adalah orang yang yang baik agamanya (Nailul Authar, 7/163). Jika kejahatan bukan dilakukan oleh orang yang dikenal melakukan keburukan dan gemar melakukan kerusakan, maka berlapang dada memaafkannya lebih baik. Wallah a’lam