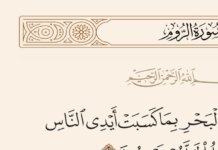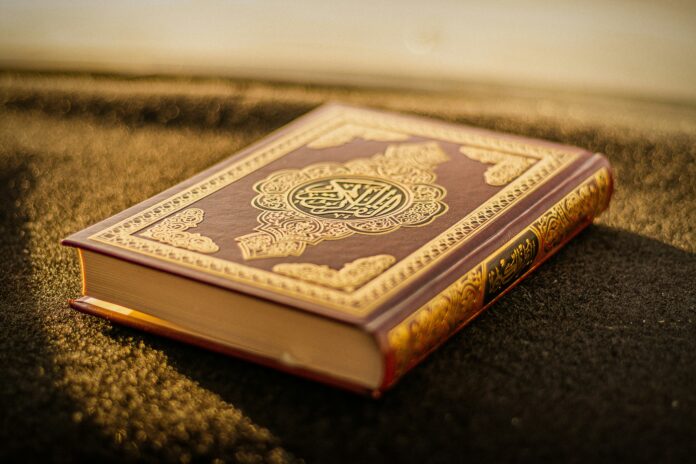Dalam sebuah artikel berjudul “Conveying Meaning in Legal Language: Why the Language of Legislation Needs to Be More Explicit than Ordinary Language”, Roberta Colonna Dahlman (2022) menegaskan bahwa undang-undang perlu disampaikan dalam bahasa tersurat.
Dalam artikel yang dimuat di Journal of Pragmatics, peraih dua gelar doktor yakni doktor di bidang hukum dan doktor di bidang linguistik Italia itu menjelaskan, pembuat undang-undang dapat saja menyampaikan undang-undang secara tersirat. Namun, tidak ada jaminan bahwa hakim akan menafsirkan teks undang-undang tersebut sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.
Hampir sama dengan undang-undang, Alquran juga berisi peraturan dan pedoman hidup untuk umat manusia. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 2 Allah berfirman, “Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.”
Sebagai pedoman hidup, Alquran perlu disampaikan melalui bahasa tersurat sehingga maksud Alquran dapat dipahami secara jelas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir. Pemahaman akan maksud Alquran membuat pedoman Alquran dapat diterapkan secara benar.
Alquran terkadang memang menggunakan bahasa tersirat. Namun, hal tersebut bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu seperti memperbagus ujaran, memperhalus bahasa serta menarik perhatian. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan membahas penggunaan bahasa tersurat di dalam Alquran.
Peran Bahasa Arab
Salah satu cara menyampaikan sesuatu secara tersurat dan jelas adalah dengan memanfaatkan kata yang memiliki makna khusus, tidak bermakna ambigu, dan tidak multitafsir.
Sebagai contoh, dalam Bahasa Indonesia, kata “alis” bermakna lebih khusus dan lebih jelas dibandingkan kata “bulu”. Hal tersebut karena kata “alis” berarti bulu yang tumbuh di dahi di atas mata, sementara kata “bulu” berarti berbagai bulu yang tumbuh di permukaan tubuh. Oleh karena itu, untuk merujuk kepada bulu yang tumbuh di dahi di atas mata, penggunaan kata “alis” tentu lebih tepat dibandingkan kata “bulu”.
Alquran telah memilih sebuah bahasa yang memungkinkan dan memenuhi kriteria penyampaian sesuatu secara tersurat dan jelas. Bahasa tersebut adalah Bahasa Arab. Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf [12]: 2, “Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Alquran berbahasa Arab agar kamu mengerti.”
Baca juga: Pandangan Ulama Tentang Konsep Sinonimitas dalam Alquran
Bahasa Arab merupakan sebuah bahasa yang perbendaharaan katanya memiliki makna khusus. Untuk makna yang sama tetapi memiliki perbedaan sedikit saja, bahasa Arab akan menyebutnya dengan sebutan yang berbeda. Meski makna masing-masing kata tersebut mirip, setiap kata memiliki makna sendiri dan bukan sinonim.
Ali Karimpoor Qaramaleki (2022) menerbitkan sebuah artikel berjudul “Analysis of the Challenges of Synonymization in Quran” dan diterbitkan oleh Biannual Journal of Research in the Interpretation of the Quran.
Dalam artikel tersebut, Qaramalek menyatakan bahwa sinonim dalam Alquran tidak dapat diterima bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya pemikiran dangkal dan sederhana dalam memahami makna ayat-ayat Alquran, keyakinan akan redundansi kata-kata Alquran, serta distorsi mukjizat Alquran dalam berbagai bentuknya.
Baca juga: Keindahan Konsep Sinonim dan Antonim dalam Alquran
Karena setiap kata memiliki makna khusus, bahasa Arab sangat kaya dan memiliki banyak perbendaharaan kata. Dalam sebuah artikel berjudul “Arabic as a Language between Qur‘anic (Sacred) and Historical Designations” dan diterbitkan di Millah: Journal of Religious Studies, Kamarudin Salleh (2007) menyatakan, jauh sebelum Islam datang, suku-suku Arab telah mempunyai penyair-penyair yang menulis dalam bahasa yang canggih dengan kosakata yang kaya.
Karena bahasa Arab memiliki banyak kata dan setiap kata bermakna khusus, kata-kata dalam bahasa Arab bermakna jelas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir. Uraian berikut akan memberikan beberapa contoh penggunaan kata tersebut di dalam Alquran.
Bahasa Tersurat dalam Alquran
Dalam Alquran, penggunaan bahasa tersurat dapat ditemui dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 27, misalnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, “Dan serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”
Ayat ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia sepanjang mereka mampu melaksanakannya. Untuk melaksanakan ibadah haji, mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju Makkah, Arab Saudi. Saat ayat ini turun, kendaraan darat lintas negara yang tersedia hanyalah unta.
Dalam ayat ini, unta disebut sebagai ضَامِرٍ. Dalam Tafsir Al-Munir, Syeh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, ضَامِرٍ adalah unta jantan atau betina yang kurus dan kelelahan karena melakukan perjalanan jauh. Unta tersebut menghabiskan banyak waktu untuk berjalan sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk makan dan beristirahat. Pemilihan kata ضَامِرٍ menjadi tepat karena menunjukkan unta khusus serta mampu menggambarkan alat transportasi jarak jauh kala itu.
Baca juga: Memaknai Istilah-Istilah Manusia dalam Alquran Perspektif Bintu Syathi
Penggunaan bahasa tersurat juga dapat ditemui dalam Q.S. Al-Waqi’ah [56]: 55. Dalam ayat ini Allah berfirman, “Maka, kamu minum bagaikan unta yang sangat haus”. Dalam ayat ini, unta disebut sebagai الْهِيمِ. Dalam Tafsir Al-Munir, Syeh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, الْهِيمِ adalah unta yang sangat haus dan menderita penyakit الهيام, sebuah penyakit yang membuat mereka minum sampai mati. Pemilihan kata الْهِيمِ di sini tepat karena الْهِيمِ bermakna khusus dan mampu menggambarkan rasa haus yang luar biasa.
Pemilihan kata الْهِيمِ di sini juga tepat karena ayat ini menceritakan manusia penghuni neraka. Menurut ayat ini, manusia penghuni neraka tidak minum seperti manusia. Mereka minum seperti الْهِيمِ. Meskipun sudah minum, mereka tetap kehausan. Untuk selanjutnya mereka akan minum kembali dan hal tersebut terus berulang sampai mereka mati.
Penggunaan bahasa tersurat juga dapat ditemui dalam Q.S. At-Takwir [81]: 3. Dalam ayat ini Allah berfirman, “Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus).”
Baca juga: Wa An-Najm Idha Hawa: Demi Bintang, Demi Muhammad, Demi Alquran
Ayat ini mendeskripsikan kekacauan dahsyat yang terjadi menjelang hari kiamat. Dalam ayat ini, unta disebut sebagai الْعِشارُ. Dalam Tafsir Al-Munir, Syeh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, الْعِشارُ adalah unta yang sudah bunting melebihi sepuluh bulan, hampir melahirkan sekaligus menjadi harta paling berharga bagi masyarakat Arab.
Pemilihan kata الْعِشارُ di sini tepat sebab الْعِشارُ memiliki makna khusus dan menunjukkan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat Arab. Menjelang hari kiamat, الْعِشارُ dibiarkan terbengkalai dan sang pemilik memilih fokus pada keselamatan dirinya. Hal tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat sehingga orang lupa kepada harta berharga miliknya.
Itulah beberapa contoh penggunaan bahasa tersurat dalam Alquran. Sebenarnya, terdapat begitu banyak contoh serupa dan menunjukkan betapa Alquran menggambarkan sesuatu secara jelas dan tepat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alquran merupakan kitab suci yang jelas, tidak ambigu dan tidak mengandung pertentangan di antara setiap bagian. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa Alquran layak dan tepat menjadi pedoman dan panduan hidup manusia. Wallahu a’lam.