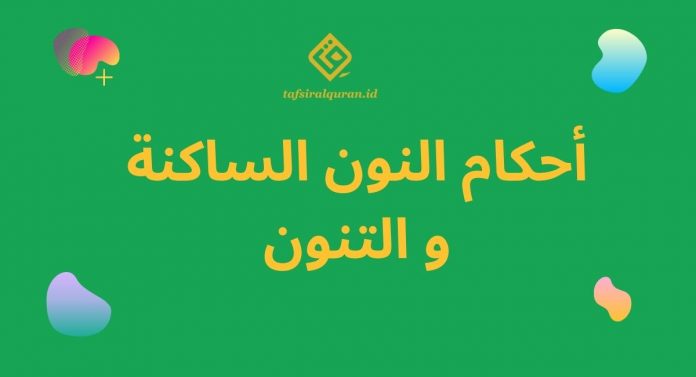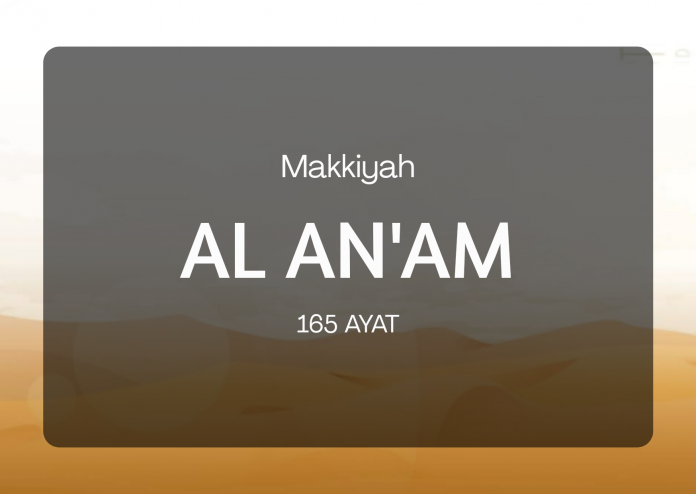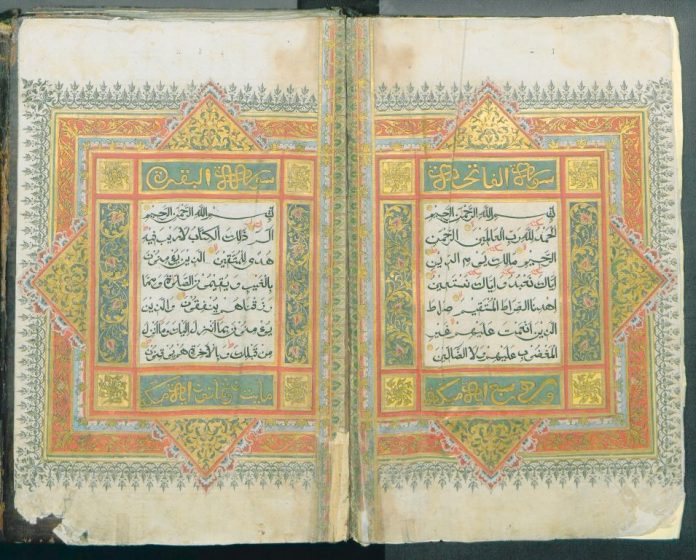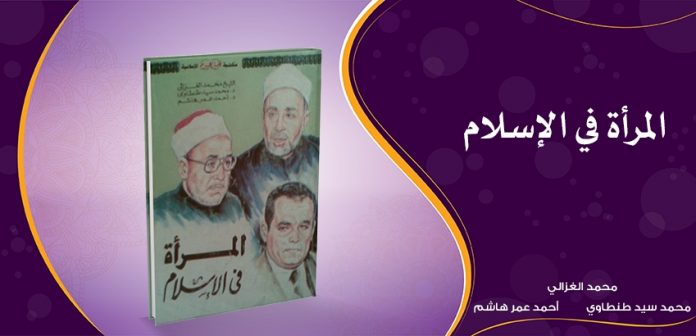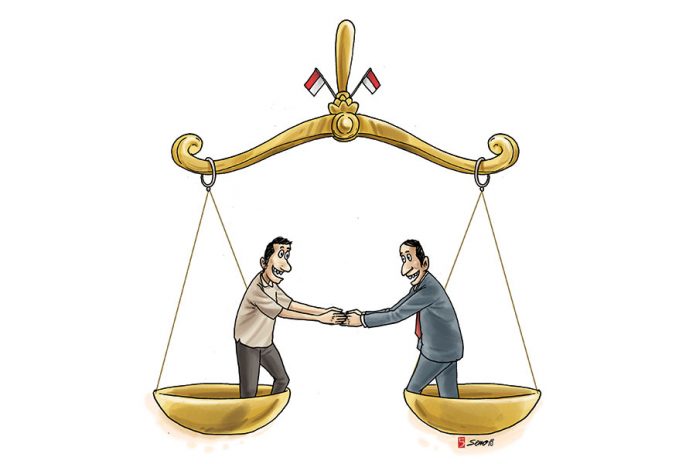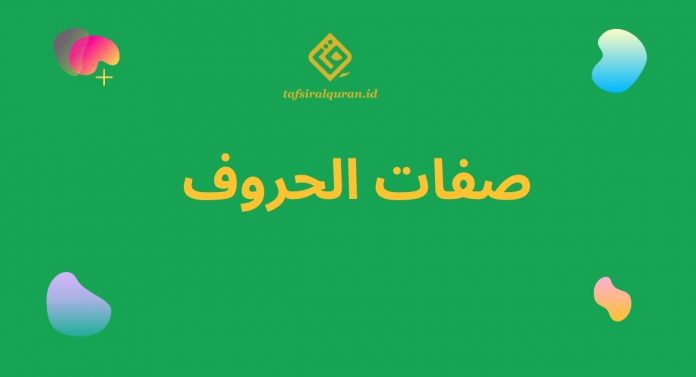Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, para pengkaji tidak luput pandangannya dari segi historis yang terdapat pada Al-Quran. Mereka berusaha mencari dan meneliti kebeneran sejarah atau kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak sedikit sekali dari mereka membanding-bandingkan kisah-kisah tersebut dengan kitab-kitab suci sebelumnya.
Salah satunya adalah kisah Maryam yang paling popular di kalangan ahli al-Kitab, dan kemudian ditulis oleh Suleiman Ali Mourad. Suleiman Ali Mourad adalah Associate Professor Bidang Agama di Smith College. Dia saat ini sedang mengerjakan studi tentang Tahdhib fi tafsir al-Qur’an dari al-Hakim al-Jishumi.
Profil Suleiman Ali Mourad
Mourad lahir dan dibesarkan di Beirut, Lebanon. Dia berasal dari keluarga di desa kecil Benwati daerah Jizzin di Lebanon selatan. Kemudian dia menikahi seorang wanita yang benaman Rana knio dan karuniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang diberi nama Jude dan Alya Jasmine.
Perjalana pendidikan Ali Mourad dimulai ketika tinggal di Lebanon, dia masuk pada salah satu universitas yang ada di Libanon yaitu American University of Beirut. Pada saat itu A. Mourad mengambil jurusan matematika. Setelah tiga tahun berkeliaran di padang gurun yaitu jurusan Matematika, kemudian dia memutuskan untuk bergabung dengan departemen sejarah guna mempelajari Sejarah Timur Tengah.
Mourad kemudian datang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya di Yale University, dan di tempat itulah dia mempelajari kurikulum dasar dalam Bahasa Arab dan Studi Islam dan pada akhirnya dia mendapatkan gelar Ph.D. nya.
Baca juga: Tayyar Altikulac: Filolog Muslim Pengkaji Manuskrip Al-Qur’an Kuno
Profesor dan teman sekelas Ali Mourad di AUB dan Yale merupakan instrumental dalam pendidikannya. Sehingga A. Mourad berkata: “Saya sangat berhutang kepada mereka yang telah menanamkan dalam diri saya hasrat keingintahuan serta pengetahuan intelektual, dan membantu saya menjadi sarjana beserta menjadi guru yang lebih baik”.
Menurut Suleiman Ali Mourad sendiri, Hal yang paling menarik tentang perjalanan pendidikannya adalah perjalanannya yang terus berlanjut dan bermanfaat dari banyak teman dan rekannya serta menemukan inspirasi dari karya-karya mereka. Serta dengan murah hati berbagi komentar dan saran mereka tentang tulisan dan penelitiannya.
Adapun guru-guru yang membentuk pemikiran Suleiman Ali Mourad ada banyak sekali diantaranya: 1. Kamal Salibi, padanya dia mempelajari sejarah Abad Pertengahan, Pra-Modern dan Modern Timur Tengah. 2. Tarif Khalidi; Budaya Islam, Sejarah dan Pemikiran Agama. 3. Samir Seikaly; Sejarah Sosial dan Intelektual, dan disiplin Sejarah. 4. Abdul Rahim Abu-Husayn; Sejarah Usmani dan Sejarah Pra-Masa Lebanon Modern. 5. Dan mempelajari Syriac pada Paul-Alain Beaulieu, dll.
Penelitiannya berfokus pada hermeneutika Al-Quran, Islam abad pertengahan, Yerusalem, dan masa Perang Salib. Penelitian A. Mourad sangat bervariasi dan mencerminkan formasi pendidikan yang luas dan keingintahuan intelektual. Sebagai seorang sejarawan Islam, dia sangat tertarik untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang bagaimana umat Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga hari ini, memahami tradisi masa lalu dan agama mereka sendiri serta cara mereka menyesuaikannya untuk menghadapi tantangan di lingkungan mereka masingmasing.
Dengan kata lain, yang merupakan daya tarik Mourad untuk mempelajari sejarah dan pemikiran Islam adalah dinamika kehidupan yang dialami umat islam sejak zaman nabi Muhammad sampai saat ini. Tetapi sayangnya sedikit sekali dihargai oleh kebanyakan Muslim dan non-Muslim masa ini. Padahal dari sebuah tradisi besar kita bisa menemukan makna dan interpretasi, dan bahkan untuk menemukan kembali dirinya sendiri.
Baca juga: Massimo Campanini; Pengkaji Al-Quran Kontemporer dari Italia
Pemikiran Suleiman Ali Mourad Tentang Al-Quran
Mourad telah banyak menulis tentang Al-Quran dan sejarah penafsirannya, radikalisasi ideologi Jihad pada periode Perang Salib dan dampaknya pada pemikiran Sunni dan jalannya sejarah Timur Tengah, tulisan sejarah Arab / Islam awal, Yesus dan Maria dalam Al Quran dan sastra Islam, dan Yerusalem dan literatur Fadaʾil (kebajikan agama)
Mengidentifikasi Maria
Menurut A. Mourad, salah satu yang sering diperdebatkan adalah masalah garis keturunan dari Maryam. Ayat-ayat yang relevan yang berkaitan dengan masalah ini adalah Surat Ali Imran Ayat 35, yang artinya:
(ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Imran: 35)
Menurut Surat Ali Imran ayat 35 diatas menunjuk bahwa ibu Maryam adalah istri Imran, dan juga pada Surat At-Tahrim ayat 12 menunjukan bahwa maryam sebagai anak perempuan Imran. Sedangkan di dalam surat Maryam ayat28 menunjukan bahwa dia sebagai saudara perempuannya Harun.
Dari ketiga ayat di atas, banyak para ulama modern menganggap bahwa Al-Quran telah mengidentifikasi Maryam sebagai putri Imran dan saudara perempuannya Harun, serta menyebabkan banyak orang berpendapat bahwa Muhammad itu bingung dalam mebedakan apakah Maryam itu ibu Yesus atau saudara perempuan Harun dan Musa, yang ayahnya adalah Imran. A. Mourad juga mengutip dari pendapat at-Thabari yang mengatakan bahwa dalam konteks ayat 35, wanita yang diidentifikasi sebagai istri Imran tidak lain adalah ibu Maryam, Hanna (Anna).
Kemudian A. Mourad menjelaskan dari sumber-sumber Kristen seperti Protevangelium dari James bahwa ayah Maria bernama Joachim. Meskipun laporan-laporan tentang keluarga Maria ini tidak memiliki nilai sejarah yang nyata, begitu mereka diperkenalkan, mereka diterima dari cara orang Kristen dan orang lain mengidentifikasi dirinya.
Baca juga: Pesan Az-Zarkasyi bagi Para Pengkaji Ilmu Al Quran
Kabar dan kelahiran Yesus
Dibagian ini Suleiman Ali Mourad mengakat tentang berita tentang sebelum dan sesudah lahirnya seorang nabi atau utusan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam dan Injil Lukas, malaikat memberi tahu Maryam bahwa dia akan mengandung anak laki-laki. Sedangkan di surah al -Imran dan Protevangelium dari James, Mary mengatakan bahwa dia akan mengandung firman Allah.
Kesamaan yang dekat ini adalah bukti bahwa di sini Al-Quran meminjam materi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang digunakan oleh orang Kristen terutama dalam Protevangelium dari James yang banyak digunakan di Timur dalam kekristenan Barat, meskipun teks itu dilarang.
Di dalam Al-Quran menceritakan tentang mengandungnya Maria dalam surat Maryam mencakup ayat 22-6 ini dianggap sebagai satu-satunya bagian dari konsep dan cerita yang tidak memiliki Kristenisasi yang diketahui. Kemudian kisah pada waktu Maryam melahirkan menurut A. Murad, kisah seperti yang muncul dalam surat Maryam jelas jauh lebih pendek daripada yang ada di Pseudo Matthew ditambah lagi dalam surat Maryam, cerita ketika Maria sedang dalam proses persalinan, tidak ceritakan tempatnya hanya diidentifikasikan sebagai tempat yang terpencil. Dalam Pseudo-Matius, Yesus telah dilahirkan, dan insiden itu terjadi selama Perjalanan menuju ke Mesir. Wallahu A’lam.