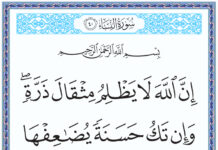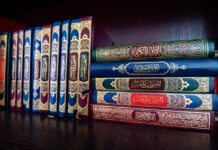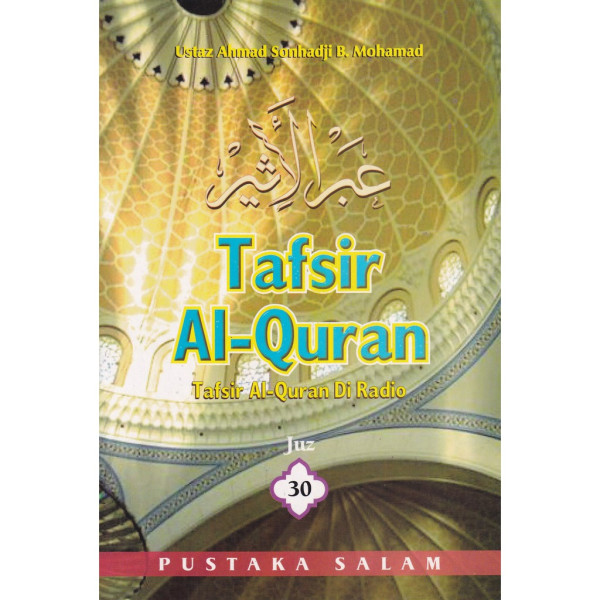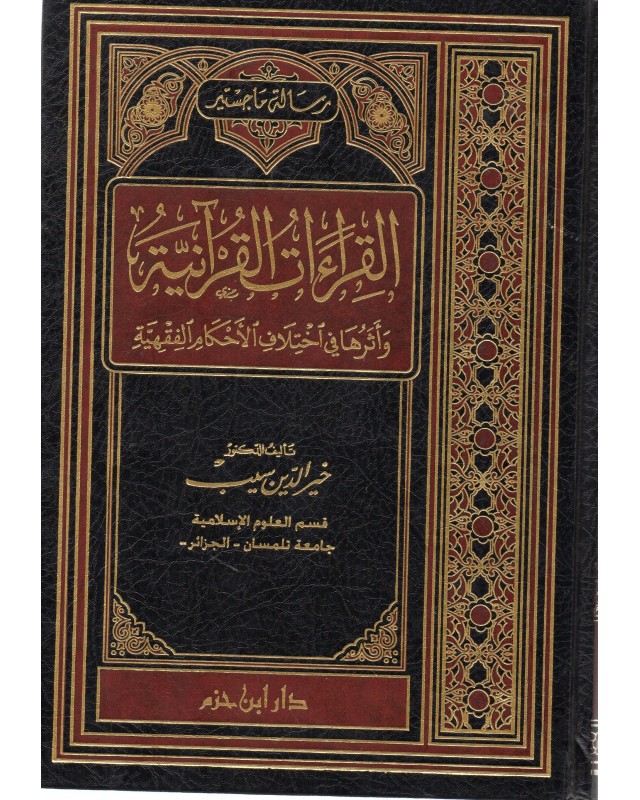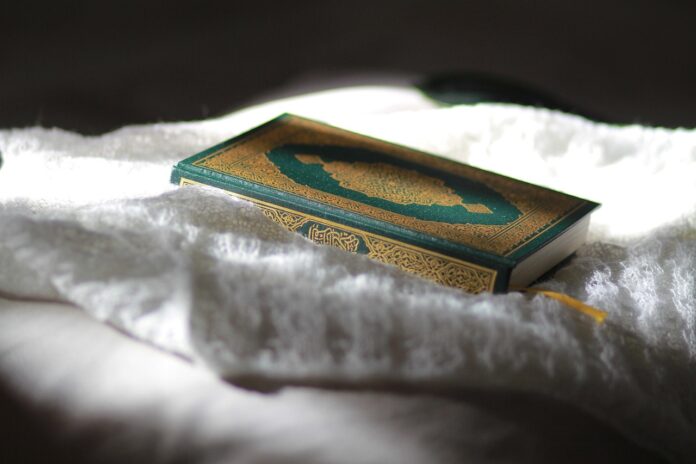Kisah Nabi Musa adalah salah satu kisah paling lengkap yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Bukan hanya karena keluasan peristiwa yang dialami beliau, tetapi juga karena setiap tahap hidupnya memuat pelajaran tentang bagaimana karakter seorang nabi dibentuk sedikit demi sedikit hingga siap memikul amanah besar. Melalui surah al-Qaṣaṣ dan Ṭāhā, kita dapat melihat empat fase pembentukan karakter Nabi Musa: perlindungan ilahi sejak bayi, pendidikan sosial di masa muda, panggilan kenabian, dan ujian kepemimpinan dalam menghadapi umat.
Melalui keempat fase dalam hidup Nabi Musa, Al-Qur’an mengajarkan bahwa manusia tidak dilahirkan langsung menjadi tokoh besar. Akan tetapi, ia ditempa oleh pengalaman, ujian, dan bimbingan Tuhan. Dengan bahasa yang lembut namun kuat, Al-Qur’an mengajak pembaca meresapi perjalanan panjang ini sebagai cermin pembentukan diri.
Perlindungan Ilahi: Fondasi Emosional dan Spiritualitas Nabi Musa
Kisah Nabi Musa dimulai dari situasi paling menegangkan, yaitu ketika Fir‘aun membantai setiap bayi laki-laki pada masa itu. Di tengah bahaya itu, Allah menenangkan hati ibu beliau melalui firman-Nya:
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚاِنَّا رَاۤدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ
Artinya: “Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, ‘Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul.” (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 7).
Baca juga: Religious Hate Speech dan Perlunya Model Dakwah Qaulan Layyina Nabi Musa
Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah menanamkan fondasi ketenangan dan keamanan sejak awal kehidupan Nabi Musa. Muhammad Ridwan dalam Karakter Nabi Musa dalam Menjalankan Misi Dakwah dan Relevansinya dengan Era Kontemporer (2023) menyebut bahwa perlindungan ilahi ini adalah dasar pembentukan karakter spiritual yang penuh kepercayaan kepada Allah. Yang menunjukkan bahwa janji ilahi bukan sekadar kata-kata, tetapi menjadi pengalaman langsung yang mewarnai perjalanan hidup seterusnya.
Di sinilah kita belajar bahwa karakter seseorang tidak dimulai dari panggung besar, tetapi dari pengalaman batin yang menghadirkan rasa aman, kedekatan dengan Tuhan, dan ketenangan emosional.
Fase Muda: Pendidikan Sosial dan Latihan Kepedulian
Setelah dewasa, Nabi Musa memasuki fase kedua, yaitu: ujian sosial dan spiritual yang membentuk kedewasaannya. Al-Qur’an menceritakan bahwa beliau terlibat dalam sebuah perkelahian yang tidak disengaja hingga membuatnya harus meninggalkan Mesir (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 15–22). Pelarian ini mengantarkan beliau ke kota Madyan.
Baca juga: Kisah Kedurhakaan Bani Israel Kepada Nabi Musa dalam Pembebasan Palestina
Di Madyan, Nabi Musa hidup sederhana, bekerja keras, menolong orang-orang lemah, dan menggembala ternak. Pengalaman ini melatih empati, kemandirian, dan kesabaran. Khairul Hidayat dalam Kisah Nabi Musa di Kota Madyan dalam Q.S. Al-Qashash Ayat 23-28 Menurut Tafsir Ibnu Katsir (Studi tentang Kisah Nabi Musa dan Ibrah di Dalamnya) (2024) menekankan bahwa di kota Madyan inilah “pendidikan sosial” yang membentuk karakter rendah hati dan kepekaan sosial Nabi Musa terjadi.
Di tengah kehidupan yang jauh dari keluarga dan istana, Nabi Musa belajar memahami kerasnya hidup, jatuh bangun pekerjaan, serta dinamika masyarakat kecil. Nilai-nilai itu membentuk kepribadian beliau seperti: tidak sombong, tidak terbiasa hidup nyaman, dan dekat dengan rakyat kecil.
Panggilan Kenabian: Pembentukan Mentalitas Kepemimpinan
Tahap ketiga adalah peristiwa paling besar bagi Nabi Musa, yaitu ketika beliau menerima wahyu sebagaimana yang tergambar dalam Q.S. Ṭāhā ayat 9 sampai 36. ketika beliau melihat cahaya di Bukit Ṭūr dan menghampirinya, Allah berfirman:
اِنِّيْٓ اَنَا۠ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ
“Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa.” (Q.S. Ṭāhā [20]: 12).
Ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas besar membutuhkan kesiapan spiritual. Perintah melepas kedua terompah (alas kaki) adalah simbol penyucian diri dan penyerahan total. Taufiq dkk. dalam Internalisasi Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an: Kajian Atas Surat Al-Qashash Ayat 7 (2021) menjelaskan bahwa dialog panjang antara Allah dengan Nabi Musa pada momen ini merupakan proses pembentukan mentalitas kenabian Nabi Musa.
Baca juga: Penafsiran Esoterik Peristiwa Eksodus Nabi Musa as. dalam Tafsir al-Alusi
Manik dalam The Preaching of Prophet Musa in Improving the Integrity of the Nation’s Children in the Era of Society 5.0 (2023) menggambarkan fase ini sebagai transformasi yang membawa Nabi Musa dari seorang pelarian menjadi pembawa risalah besar. Ia dididik untuk menghadapi Fir‘aun bukan dengan kemarahan, tetapi dengan lemah lembut dan argumentasi yang kuat.
Menghadapi Bani Israil: Ujian Kepemimpinan yang Sesungguhnya
Setelah menyelamatkan Bani Israil, Nabi Musa memasuki tahap paling rumit dalam pembentukan karakternya: memimpin umat yang sering berubah-ubah, mudah kecewa, dan tidak jarang melanggar aturan. Peristiwa penyembahan anak sapi menjadi contoh bagaimana umat bisa goyah meski telah menyaksikan mukjizat besar.
Ridwan mencatat bahwa pada tahap ini, kesabaran Nabi Musa ditempa melalui dinamika umat yang ruwet. Beliau harus menghadapi sikap keras kepala, protes, dan perdebatan internal. Afiati menunjukkan bahwa kemampuan sosial yang dipelajari Nabi Musa di Madyan sangat berperan dalam menghadapi karakter sulit Bani Israil.
Di sinilah terlihat bahwa pemimpin tidak hanya diuji oleh musuh, tetapi oleh orang-orang yang dipimpinnya sendiri. Nabi Musa mengajarkan bahwa ketegasan harus berjalan seimbang dengan empati. Beliau tidak membiarkan penyimpangan, tetapi juga tidak memimpin dengan kemarahan. Keseimbangan inilah yang membuat kepemimpinan beliau bertahan di tengah badai ujian.
Penutup
Kisah Nabi Musa bukan sekadar rangkaian peristiwa besar dalam sejarah kenabian. Ia adalah gambaran tentang bagaimana seorang manusia ditempa sedikit demi sedikit oleh pengalaman hidup, ujian batin, dan bimbingan langsung dari Allah. Melalui surah al-Qaṣaṣ dan Ṭāhā, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah membentuk karakter Nabi Musa melalui empat fase: perlindungan ilahi sejak beliau masih bayi, pendidikan sosial di masa mudanya, panggilan kenabian yang menguatkan mentalitas beliau, hingga ujian kepemimpinan ketika menghadapi karakter sulit Bani Israil.
Setiap fase menghadirkan pelajaran yang sangat manusiawi. Bahwa seorang pemimpin, sebelum memikul amanah besar, lebih dulu melewati masa-masa sunyi, kesederhanaan, kegelisahan, bahkan kesalahan yang membentuk kedewasaan. Dalam perjalanan Nabi Musa itu, Al-Qur’an seakan mengajak pembaca untuk merenung: bahwa tidak ada karakter mulia yang lahir dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang yang penuh arahan dan kasih sayang Tuhan. Dengan memahami kisah ini, kita belajar melihat kehidupan bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai rangkaian pendidikan yang halus dan terus menerus. Wallāhu a‘lam.