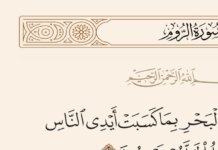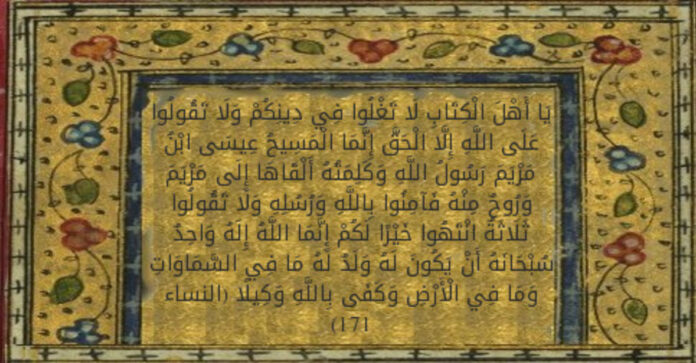Akhir-akhir ini, tengah ramai diperbincangkan mengenai halal-haramnya musik. Hal ini bermula dari penjelasan ust. Adi Hidayat mengenai asy-Syu’ara yang dimaknai sebagai para pemusik, yang kemudian diklaim oleh sebagian kalangan bahwa beliau menghalalkan musik.
Penulis tidak akan mengkaji lebih lanjut mengenai pro-kontra apakah benar asy-Syu’ara dapat diterjemahkan sebagai para pemusik. Melihat berbagai narasi yang mengecam ust. Adi Hidayat karena diduga telah menghalalkan musik, memberikan indikasi bahwa ternyata tidak sedikit kalangan yang menganggap musik sebagai hal yang harus dihindari karena merupakan perkara haram yang dapat mendatangkan dosa.
Oleh karena itu, sebagai narasi pembanding, penulis sedikit akan mengulas penjelasan dari Imam al-Ghazali mengenai hukum musik yang beliau paparkan secara panjang lebar dalam kitab Ihya Ulum ad–Din.
Baca Juga: Tafsir Surah asy-Syu’ara dan Polemik Hukum Musik
Islam dan Keindahan
Islam merupakan agama yang paripurna. Tidak hanya meliputi masalah ritual peribadatan, ajaran dan tuntunanya masuk ke dalam sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Hal-hal yang menyangkut relasi antar sesama, politik bahkan seni menjadi hal-yang kerap kali diperbincangkan dalam diskursus hukum Islam.
Terkait masalah seni, ada berbagai isu yang menjadi ranah perdebatan ulama terkait bagaimana perspektif Islam terhadapnya. Sebut saja misalnya masalah seni ukir, seni pahat dan seni suara atau musik.
Secara umum, Islam merupakan agama yang mengapresiasi keindahan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi:
إن الله جميل يحب الجمال
Sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha indah dan menyenangi keindahan.
Baca Juga: Syair Jahili dalam Penafsiran Al-Quran
Musik Menurut al-Ghazali
Terkait status hukum musik dan nyanyian, sejatinya sejak dulu ulama telah berdiskusi panjang lebar dan menghasilkan pandangan yang pro-kontra. Sebagai ranah ijtihadi, tidak heran jika ada yang melegalkan, ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan beberapa catatan.
Dalam hal ini, Imam al-Ghazali memosisikan dirinya sebagai pihak yang tidak setuju musik dianggap haram. Beliau menegaskan bahwa menilai haram sebuah perkara berarti memvonis pelakunya melakukan dosa dan akan mendapat siksa. Menurut beliau, dalam masalah ini, tidak ada dalil yang secara tegas mengindikasikan keharaman musik. Jikapun ada beberapa ayat atau hadis yang menjadi argumentasi keharaman musik, itu diperoleh dari penafsiran subjektif yang sudah barang tentu dapat ditafsirkan dengan pemahaman yang lain.
Salah satu ayat Alquran yang sering dijadikan dalil oleh para pendukung keharaman musik atau nyanyian adalah surah Luqman ayat 6.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Q.S. Luqman [31]: 06
Tidak sedikit ulama baik dari kalangan sahabat maupun generasi berikutnya yang menafsiri kata لهو الحديث pada ayat di atas sebagai penyanyi. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari Sahabat Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat tersebut turun menyangkut seorang laki-laki yang membeli budak perempuan untuk bernyanyi. (Zad al-Masir fi ‘Ilm al-Tafsir, juz 3, hal. 429).
menurut Imam al-Ghazali, mempekerjakan budak perempuan dalam dunia hiburan –dalam hal ini menjadi penyanyi- merupakan tindakan tercela. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa hukum haram tersebut lahir karena nyanyian yang didendangkan. Hal ini terbukti ketika budak tersebut dipekerjakan khusus untuk menghibur majikannya sendiri, tentu hal tersebut tidak dilarang dalam agama.
Hal yang perlu diperhatikan adalah alasan mengapa لهو الحديث yang ditafsiri sebagai (membeli) budak penyanyi, dikecam dalam ayat tersebut. menurut al-Ghazali, titik tekan dalam ayat tersebut adalah bukan pada musiknya, melainkan karena ia dijadikan sebab untuk jauh dari jalan Allah. Melihat alasan ini, jangankan nyanyian, membaca Alquran saja bisa dihukumi haram ketika ia menjadi faktor seseorang jauh dari jalan Allah. (Ihya’ Ulum al-Din, juz 2, hal. 310)
Dari sini, Imam al-Ghazali mengajak kita untuk melihat sebuah perkara tidak hanya dari luarnya saja agar tidak terjebak pada pemahaman tekstualis yang biasanya kaku dan rigid. Terkait masalah musik dan nyanyian, kita harus dapat memisahkan antara yang substansi dan tidak.
Musik atau nyanyian sebagai lantunan suara indah dan berirama merupakan keindahan yang pada dasarnya tidak dilarang dalam agama. Sebab, akan terjadi paradoks jika Islam sebagai agama fitrah melarang keindahan lantunan suara yang juga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang menyukai keindahan. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan sebuah pernyataan,
من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاح ليس له علاج
Barang siapa yang tidak bergetar hatinya oleh musim semi, bunga-bunga, pepohonan dan suara petikan senar musim semi maka ia telah mati rasa. Dan tidak ada obat baginya. (Ihya’ Ulum al-Din, juz 2, hal. 299)
Baca Juga: Hukum Mengidolakan Artis Nonmuslim
Imam al-Ghazali memandang perlu ada pemisahan terkait musik atau nyanyian sebagai sebuah manifestasi dari keindahan dengan hal-hal eksternal yang mengitarinya. Menurut beliau, musik atau seni suara hukumnya boleh. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi haram disebabkan faktor lain yang ada dalam musik itu sendiri.
Ia dapat dihukumi haram apabila penyanyinya adalah seorang perempuan yang disinyalir dapat mengundang syahwat dan menimbulkan fitnah. Demikian pula, musik hukumnya haram ketika lirik-liriknya mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
Bahkan, Imam al-Ghazali juga memahami hadis yang melarang penggunaan alat musik seperti seruling dan gitar dengan pendekatan kontekstual. Menurut beliau, pada waktu itu, alat-alat musik tersebut memang menjadi ciri khas para pemabuk dan karap kali dimainkan di bar-bar dan tempat-tempat minuman keras lainnya. Karena ia identik dengan kemaksiatan maka sebagai langkah antisipasi alat musik tersebut juga dilarang.
Namun, seiring perkembangan zaman, alasan-alasan tersebut tentu mengalami perubahan dan pergeseran. Ini artinya, tidak selamanya musik atau alat musik yang dulu diharamkan masih tetap haram sampai sekarang. Begitu pula musik atau alat musik yang dulunya dilegalkan bisa jadi sekarang dilarang. Ini tergantung alasan hukum serta situasi dan kondisi yang mengitarinya.
Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menyikapi masalah musik dan nyanyian, imam al-Ghazali tidak memahami dalil-dalil yang ada secara tekstual. Beliau menekankan pentingnya melihat persoalan secara komprehensif dan mendalam serta melakukan penafsiran secara maqhasidi. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum islam yang mengatakan bahwa الحكم يدور مع علته وجودا و عدما (ada dan tidak adanya hukum bergantung pada ada dan tidak adanya alasan hukum tersebut). wallahu a’lam.


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)