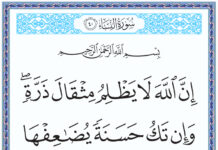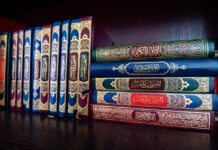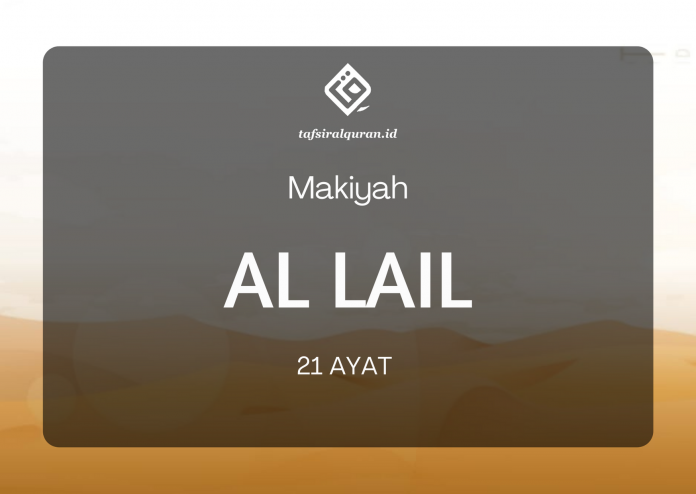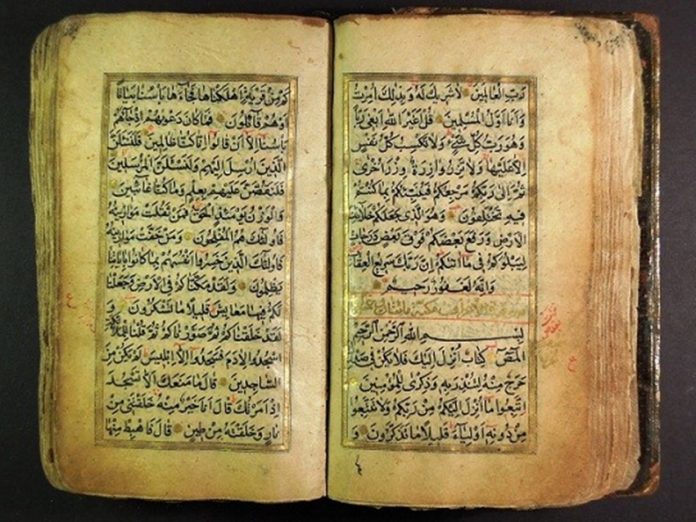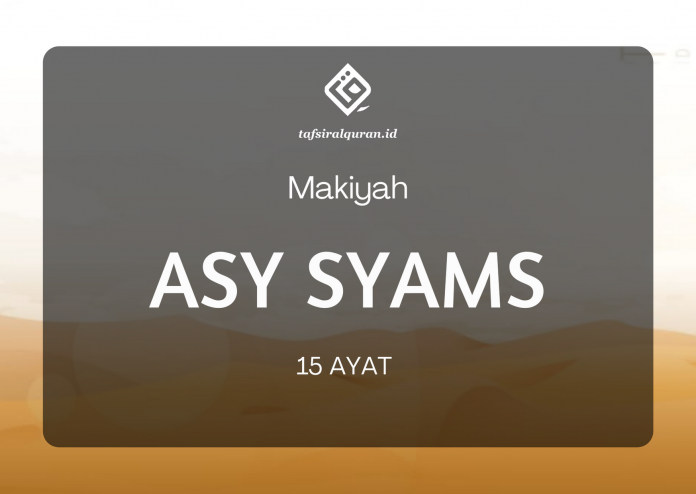Pada tahun 2019, sempat viral sebuah tehnik persalinan Siti Maryam di media sosial. Tehnik tersebut diklaim mampu mengurangi cidera dan minim sobekan, dilansir dari laman detikHealtcom. Lantas bagaimana sebenarnya masa mengandung hingga proses bersalin Siti Maryam dalam Al-Quran?
Siti Maryam dikenal dengan sebutan perempuan suci, karena penjagaan atas dirinya, dan penghambaannya pada Allah SWT., yang penuh kekhusyukan. Kesucian Siti Maryam tercatat dalam QS. Maryam (19): 18-19, ketika Allah mengutus Jibril untuk menganugerahkan seorang anak laki-laki suci yang kelak akan menjadi seorang Nabi. Telah banyak diketahui, bahwa Siti Maryam mengandung tanpa tersentuh seorang laki-laki, hingga siti Maryam bertanya pada malaikat Jibril yang diutus oleh Allah saat itu, “bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki -laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) pezina!” Demikianlah, hal mudah bagi Allah untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kisah Siti Maryam yang mengandung tanpa berhubungan badan, adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa.
Bahkan kuasa Allah bukan hanya berhenti pada itu saja, masa kehamilan hingga masa kelahiran seorang bayi ke muka bumi adalah kuasa-Nya. Proses persalinan, menjadi proses yang singkat, namun juga panjang. Proses dimana seorang bernama ibu menjalani syahidnya, hingga Nabi menyebutnya tiga kali diatas penyebutan seorang ayah.
Baca juga: Banyak Bertanya itu Tidak Baik, Simak Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 101-102
Mengandung hingga Melahirkan Nabi Isa as.
فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا
“Maka, dia mengandungnya, lalu menyisihkan diri dengannya ke tempat yang jauh. Maka, rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia kepangkal pohon kurma, ia berkata, “aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini,dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti.”
Ketika Malaikat Jibril as., meniupkan ruh ke tubuh Maryam as., maka saat itu pula Siti Maryam mengandung anak laki-laki, yakni Nabi Isa as., sebagaimana yang putuskan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bahwa Malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam baju kurung Siti Maryam hingga masuk pada farji nya, dengan atas izin Allah ia mengandung. Saat itu, siti Maryam merasa kebingungan, dan menemui istri Nabi Zakariya, yang juga kebetulan mengandung Nabi Yahya sebagaimana yang dikatakan Imam Malik rahimahumullah, bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya dikandung dalam masa bersamaan.
Dalam masa mengandungnya, Ibnu Katsir menegaskan bahwa menurut jumhur Ulama, Siti Maryam mengandung Nabi Isa selama sembilan bulan sebagaimana yang lumrah terjadi pada masa kehamilan seorang perempuan. Namun, ada juga yang mengatakan, masa kehamilan Siti Maryam terbilang singkat, akan tetapi menurut Ibnu Katsir hal ini terlihat aneh, karena menurut para jumhur ulama fa dalam ayat tersebut bermakna ta’qib (urutan) sebagaimana dalam surat al-Mu’minun ayat 12-14 yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia dari saripati, mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian janin. Dari bagian-bagiannya, ditetapkan 40 hari pembentukan. Tentu jika melihat dari proses penciptaan manusia ini, para jumhur ulama sepakat mengatakan masa kehamilan Siti Maryam sebagaimana wanita pada umumnya -sembilan bulan masa kehamilan.
Baca juga: Tafsir Surat Yasin Ayat 74-75; Celaan Pada Mereka yang Menuhankan Selain Allah
Ketika masa melahirkan akan tiba, Siti Maryam sebagaimana wanita pada umunya juga merasakan sakit akibat kontraksi. Kata al-makhadh, dalam Tafsir Al Misbah dimaknai gerak yang sangat keras. Hal ini disebabkan karena desakan janin yang ingin keluar dari rahim. Gerakan inilah yang mengakibatkan sakit -kontraksi rahim.
Dalam masa-masa ini, perasaan seorang wanita yang hendak melahirkan berkecamuk. Jika yang terjadi pada Siti Maryam adalah perasaan sedih hati karena kaum bani Israil yang mengolok dan menfitnahnya hingga Siti Maryam berputus asa dan berkata,“aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini,dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti.” Biasanya, para wanita pada masa kontraksi yang sakit ini, merasa cemas akan diri dan anaknya. Maka, dalam masa-masa ini, butuh adanya sebuah dukungan, support dari pasangan, dan keluarga wanita yang akan melahirkan atau telah melahirkan ini. Sebagaimana malaikat Jibril yang pada ayat selanjutnya oleh Allah disebutkan.
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
“maka dia menyerunya dari tempat yang rendah (di bawahnya): ‘Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon karma itu ke arahmu, niscaya ia akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu.’
Kataمن تحتها menurut Quraish Shihab ada yang membacanya min tahtiha –dari tempat rendah (di bawahnya) dan man tahtiha – siapa yang rendah (dibawahnya). Mayoritas ulama memahami ayat tersebut, bahwa yang menyeru adalah Malaikat Jibril. Namun, juga ada sebagian kecil ulama mengatakan Nabi Isa yang baru lahir. Salah satunya yang mengatakan bahwa Nabi Isa menyerukan pada Siti Maryam adalah Ibn Jarir Ath-Thabari, hal ini disebabkan karena adanya pengganti nama yang paling dekat disebut dalam redaksi tersebut adalah anak Maryam.
Terlepas dari perbedaan pendapat siapa yang dimaksud, ayat 24-25 ini memiliki pesan untuk para ibu hamil akan kasiat buah kurma di masa kehamilan, proses persalinannya, hingga pasca melahirkan (nifas). Di website alodokter.com disebutkan bahwa terdapat penelitian yang dilakukan untuk mempelajari manfaat buah kurma pada proses persalinan. Hal tersebut dilakukan pada 69 ibu hamil, ditemukan hal baik dalam pengonsumsian buah kurma tersebut, seperti; ketuban tidak mudah pecah, angka persalinan normal lebih tinggi, dan kebutuhan oksitosin lebih rendah.
Jangan Bersedih Hati ketika Masa Kehamilan
Kembali pada tafsiran Quraish Shihab, bahwa ayat di atas terlihat bagaimana Siti Maryam sangat lemah setelah melahirkan, diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma untuk memperoleh rezeki. Hal ini mengisyaratkan kepada semua makhluknya agar senantiasa tidak berpangku tangan menanti rezeki, akan tetapi harus tetap berusaha dengan kemampuan yang dimiliki.
Terakhir, kesimpulann penulis dan pesan yang ingin disampaikan, terutama umtuk para perempuan yang sedang dalam masa mengandung, atau menunggu proses bersalin, bahwa proses ini harus dijalani dengan sabar, penuh kesadaran, dan senatiasa terus dipenuhi rasa ikhlas. Jangan bersedih hati, karena pertolongan Allah itu nyata sebagaimana Ia melancarkan proses persalinan Siti Maryam. Yakinlah, sakit akibat kontraksi, akan terbayar dengan lahirnya buah hati.
Semoga untuk para perempuan yang sedang mengandung, Allah lancarkan hingga proses persalinannya. Dan untuk para perempuan yang sedang ikhtiar untuk hamil, Allah segera berikan amanah. Aamiin.
Wawwahu a’lam bissowab.