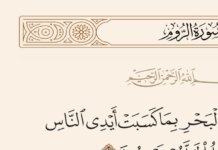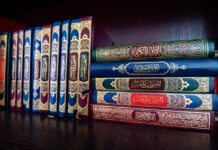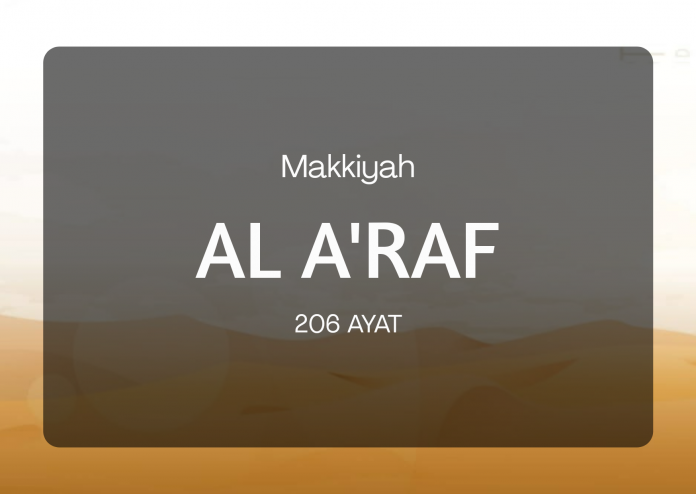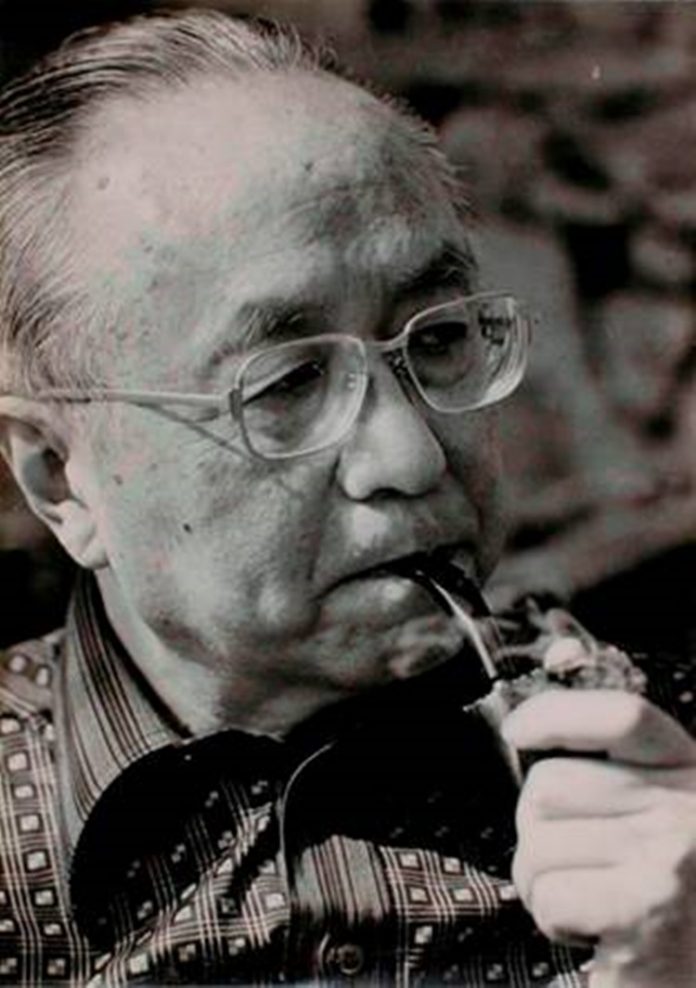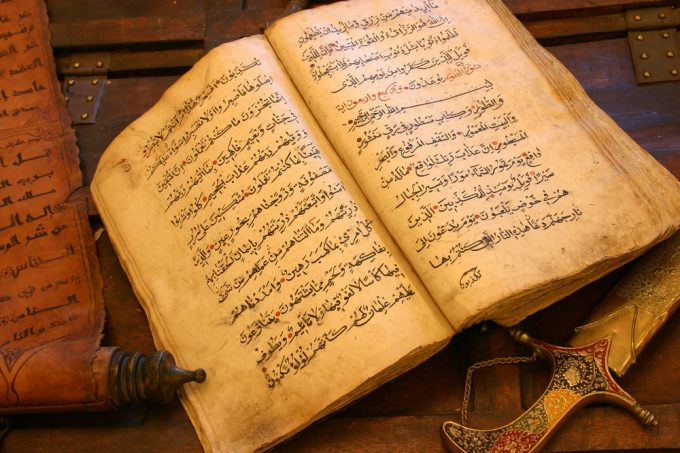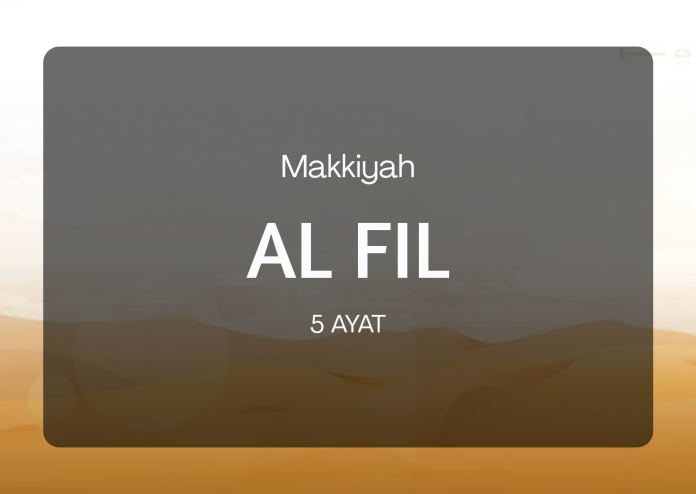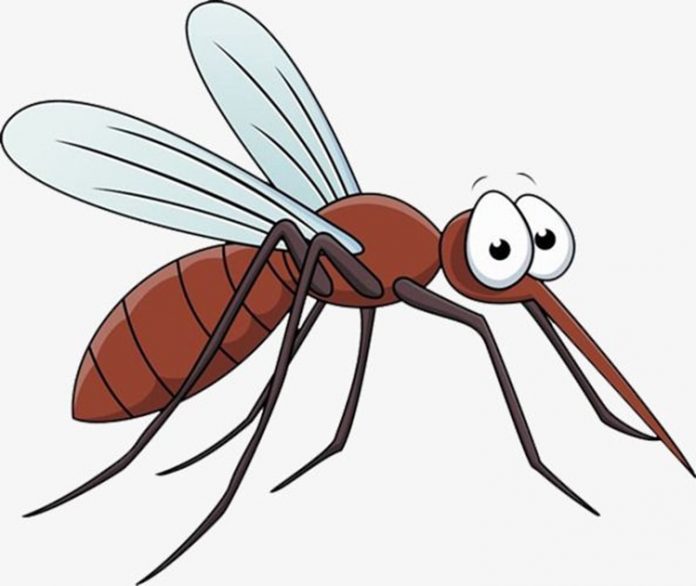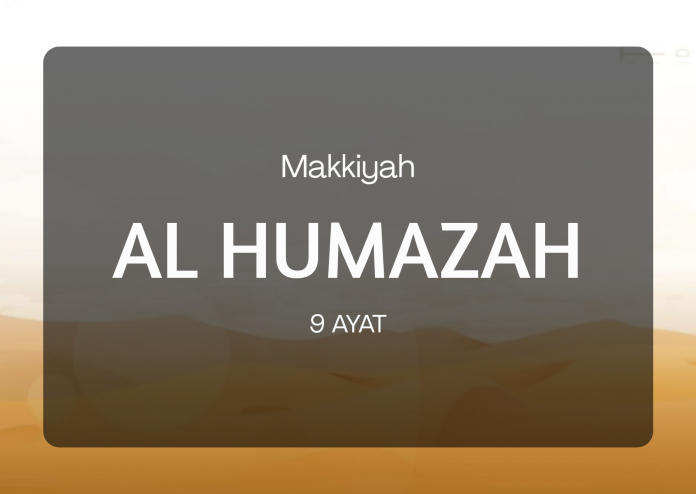Tafsir surat Al A’raf ayat 46-47 ini menjelaskan tentang batas bagi penghuni neraka dan surga. Batas tersebut berupa tembok yang sangat kokoh dan juga tinggi. Selain itu dalam tafsir surat Al A’raf ayat 46-47 ini, khususnya di ayat 47 menyinggung orang-orang yang melihat ke neraka akan timbul rasa takut di dadanya.
Baca Juga: Mengenal Kuliner Neraka dalam Al-Quran, dari Buah Zaqqum hingga Shadid
Ayat 46
Ayat ini menerangkan bahwa antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas yang sangat kokoh. Batas itu berupa pagar tembok yang tidak memungkinkan masing-masing mereka untuk keluar dan untuk berpindah tempat. Di atas pagar tembok itu ada suatu tempat yang tertinggi, tempat orang-orang yang belum dimasukkan ke dalam surga. Mereka bertahan di sana menunggu keputusan dari Allah. Dari tempat yang tinggi itu mereka bisa melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka. Kedua penghuni itu kenal dengan tanda yang ada pada mereka masing-masing. Seperti mengenal mukanya yang telah disifatkan Allah dalam Al-Qur′an. Firman Allah:
وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةٌۙ ٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ ٣٩ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌۙ ٤٠ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۗ ٤١ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ࣖ ٤٢
Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. (‘Abasa/80: 38-42)
Mereka yang tinggal di tempat yang tinggi di atas pagar batas itu mempunyai kebaikan yang seimbang dengan kejahatannya, belum bisa dimasukkan ke dalam surga, tetapi tidak menjadi penghuni neraka. Mereka untuk sementara ditempatkan di sana, sambil menunggu rahmat dan karunia Allah untuk dapat masuk ke dalam surga.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud, bahwa Rasulullah bersabda:
تُوْضَعُ الْمَوَازِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوْزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ دَخَلَ النَّارَ. قِيْلَ وَمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، قَالَ: أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ اْلأَعْرَافِ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ (رواه ابن جرير عن ابن مسعود
“Diletakkan timbangan pada hari Kiamat lalu ditimbanglah semua kebaikan dan kejahatan. Maka orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya dari pada timbangan kejahatannya meskipun sebesar biji sawi/atom dia akan masuk surga”. Dan orang yang lebih berat timbangan kejahatannya dari pada timbangan kebaikannya meskipun sebesar biji sawi/atom, ia akan masuk neraka. Dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana orang yang sama timbangan kebaikannya dengan timbangan kejahatannya? Rasulullah menjawab: mereka itulah penghuni A‘raf, mereka itu belum memasuki surga tetapi mereka sangat ingin memasukinya.” (Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Mas‘ud)
Sesudah itu Ibnu Mas‘ud berkata, “sesungguhnya timbangan itu bisa berat dan bisa ringan oleh sebuah biji yang kecil saja. Siapa yang timbangan kebaikan dan kejahatannya sama-sama berat, mereka penghuni A‘raf, mereka berdiri menunggu di atas jembatan.
Kemudian mereka dipalingkan melihat penghuni surga dan neraka. Apabila mereka melihat penghuni surga, mereka mengucapkan: “Keselamatan dan kesejahteraaan bagimu. Apabila pandangan mereka dipalingkan ke kiri, mereka melihat penghuni neraka, seraya berkata, “Ya Tuhan kami janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang zalim”. Mereka sama-sama berlindung diri kepada Allah dari tempat mereka.
Ibnu Mas‘ud berkata, “Orang yang mempunyai kebaikan, mereka diberi cahaya yang menerangi bagian depan dan kanan mereka. Tiap-tiap orang dan tiap-tiap umat diberi cahaya setibanya mereka di atas jembatan, Allah padamkan cahaya orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Tatkala penghuni surga melihat apa yang di hadapan orang-orang munafik, mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami.” Adapun penghuni A’raf, cahaya mereka ada di tangan mereka, tidak akan tanggal. Pada waktu itu Allah berfirman :
لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ
Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera (masuk). (al-A‘raf/7: 46);Yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa penghuni A‘raf itu menyeru penghuni surga, mengucapkan selamat sejahtera, karena kerinduan mereka atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada penghuni surga. Mereka belum juga dapat masuk ke dalamnya, sedang hati mereka sudah sangat rindu untuk masuk.
Ayat 47
Ayat ini menerangkan, bila penghuni A‘raf ini mengalihkan pandangannya ke arah penghuni neraka, timbullah ketakutan mereka, lalu memohon kepada Allah agar mereka jangan dimasukkan bersama orang-orang yang zalim itu ke dalam neraka. Sedangkan melihat penghuni surga adalah kesenangan dan kesukaan mereka. Karena itu ketika mereka melihat surga mengucapkan salam sejahtera, karena kerinduan hati mereka melihat kesenangan yang ada di dalamnya. Jadi maksud ayat ini adalah menumbuhkan rasa takut dan gentar kepada penghuni A‘raf itu, agar dapat dijadikan pelajaran bagi manusia untuk berhati-hati agar jangan mengerjakan pekerjaan yang dapat mendatangkan dosa.


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)